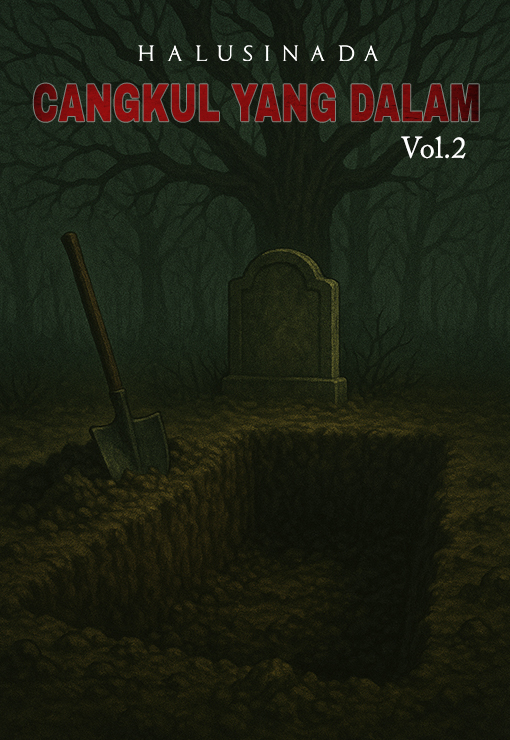BAB IV: LELAH YANG TAK TERLIHAT
Hari-Hari yang Terhenti
Setelah pengumuman kelulusan SNMPTN, waktu seolah berhenti bagi Arunika.
Bukan hanya karena gagal masuk kuliah. Bukan hanya karena ekonomi keluarga yang tak mampu. Tapi karena segala sesuatu yang selama ini menjadi identitasnya, tiba-tiba runtuh.
Ia bukan lagi “anak pintar”.
Ia bukan lagi “harapan keluarga”.
Ia bukan lagi “juara kelas”.
Ia hanya… Arunika yang gagal.
Hari pertama setelah pengumuman, ia tidak keluar kamar. Ia mematikan ponsel. Menarik selimut hingga menutupi kepala. Udara di kamar terasa pengap, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menghilang.
Ibunya mengetuk pintu pelan.
“Arun? Makan dulu, Nak.”
Tidak ada jawaban.
“Kita nggak apa-apa. Masih ada waktu.”
Masih diam.
Di luar, ayahnya duduk di teras, merokok dengan tatapan kosong. Ia tidak marah. Ia tidak menyalahkan. Tapi Arunika tahu: di matanya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah karena tidak bisa memberi lebih.
“Harusnya aku bisa nabung lebih,” gumam Pak Darmo suatu malam, tanpa menyadari Arunika mendengar dari balik dinding.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arunika menangis bukan karena dirinya.
Tapi karena orang tuanya.
Dua minggu berlalu. Arunika mulai membuka ponselnya lagi. Dan yang pertama ia lihat adalah dunia yang terus berjalan tanpa dirinya.
Teman-temannya memposting foto di kampus baru.
Ada yang di Bandung, memakai jaket almamater, tersenyum di depan gerbang universitas.
Ada yang di Jogja, duduk di kafe sambil membaca buku tebal.
Ada yang di Jakarta, berdiri di depan gedung pencakar langit, dengan tulisan: “Akhirnya, mimpi jadi nyata.”
Setiap notifikasi adalah paku kecil yang menusuk hati.
Ia membuka profil mantan teman sekelasnya, Dinda, yang dulu selalu kalah dalam lomba sains. Kini, Dinda memposting foto dirinya memakai jas lab, dengan keterangan:
“Hari pertama praktikum di Fakultas Kedokteran. Terima kasih Tuhan, aku nggak menyerah.”
Arunika menutup ponselnya. Dadanya sesak.
“Kalau aku yang menulis itu, mungkin akan jadi: ‘Hari pertama tidak punya tujuan. Aku menyerah.’”
Ia merasa seperti penonton dalam film kehidupan orang lain. Ia bisa melihat, tapi tidak bisa masuk. Ia terkunci di luar.
Percakapan yang Tidak Pernah Terjadi
Suatu malam, Arunika duduk di lantai kamarnya, memandang langit-langit. Ia membayangkan percakapan yang ingin ia ucapkan, tapi tidak pernah berani:
“Bu, aku nggak mau jadi apoteker. Aku nggak pernah mau. Aku cuma takut kamu kecewa.”
“Ayah, aku bukan Raka. Aku nggak kuat jadi satu-satunya harapan. Aku cuma ingin jadi… aku.”
“Teman-teman, aku nggak kalah karena bodoh. Aku kalah karena lelah. Karena aku hidup bukan untuk aku.”
Tapi semua itu hanya tinggal di dalam kepala. Di mulut, hanya keluar:
“Nggak apa-apa, Bu.”
“Iya, Ayah.”
“Selamat ya, Dinda.”
Laut sebagai Saksi Bisu
Pada hari ke-17 setelah pengumuman, Arunika kembali ke pantai.
Bukan karena ingin sembuh.
Tapi karena ia butuh tempat di mana ia tidak harus berpura-pura.
Ia duduk di batu karang favoritnya, tempat ia biasa menulis di jurnal kecil. Angin malam bertiup kencang, membawa bau garam dan rumput laut. Ombak datang, memecah, lalu surut—seperti napas yang tak pernah berhenti.
Ia mengeluarkan jurnalnya. Halaman-halaman terakhir kosong. Ia menulis:
“Hari ini, aku merasa seperti ikan mati yang hanyut. Tidak punya arah. Tidak punya oksigen. Hanya terbawa arus.”
Ia menutup jurnal. Lalu berbisik:
“Laut, kamu pernah merasa lelah nggak? Kamu selalu bergerak. Kamu nggak pernah berhenti. Kamu nggak pernah menyerah. Tapi aku… aku lelah.”
Ombak datang, membasahi ujung kakinya. Seperti menjawab:
"Aku juga lelah. Tapi aku tetap bergerak. Karena kalau aku berhenti, dunia akan mati."
Arunika menangis. Tidak keras. Hanya air mata yang mengalir diam-diam, larut dalam suara laut malam.
Beberapa hari kemudian, Arunika bermimpi.
Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi laut, memakai jas laboratorium putih. Ia memegang botol obat, tapi saat dibuka, isinya adalah pasir. Ia mencoba membacanya, tapi huruf-hurufnya berubah jadi gelombang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar.
Lalu muncul bayangan ibunya.
“Kenapa kamu gagal, Arun?”
“Kamu anak pintar!”
“Kamu anak terakhir!”
“Kamu harapan kami!”
Arunika mundur. Ia terus mundur sampai jatuh ke laut.
Airnya dingin. Gelap. Ia tidak bisa bernapas.
Ia melihat ikan-ikan kecil berenang melewatinya, seolah berkata:
“Kamu bukan dari sini.”
Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi punggungnya.
Ia menyalakan lampu. Menatap jurnalnya. Lalu menulis:
“Aku bukan dari sana. Aku bukan dari dunia itu. Tapi aku juga belum tahu dari mana aku sebenarnya.”
Pagi harinya, Pak Darmo duduk di samping Arunika di teras.
Tidak bicara. Hanya menawarkan secangkir kopi pahit—yang biasanya ia minum sebelum pergi melaut.
Setelah beberapa menit, ia berkata pelan:
“Kamu tahu, Nak, setiap kali aku pergi melaut, aku nggak tahu ikan apa yang akan aku dapat. Kadang dapat banyak. Kadang kosong. Tapi aku tetap pergi.”
Arunika menatap ayahnya.
“Kenapa, Yah?”
“Karena kalau aku berhenti, aku bukan nelayan lagi. Aku cuma orang yang takut laut.”
Ia menatap anaknya.
“Kamu gagal masuk kuliah. Tapi kamu belum berhenti jadi Arunika. Selama kamu masih bernapas, kamu masih punya waktu.”
Arunika menunduk. Air matanya jatuh ke cangkir.
“Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana, Yah.”
Pak Darmo tersenyum tipis.
“Mulai dari yang kecil. Seperti aku. Hari ini, aku cuma bawa jaring kecil. Kalau dapat ikan, syukur. Kalau nggak, besok aku coba lagi.”
Arunika mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa ayahnya benar-benar mengerti.
Hari-Hari Tanpa Nama
Beberapa minggu berlalu. Arunika mulai keluar kamar lebih sering. Tapi belum ada semangat. Belum ada tujuan.
Ia mulai membantu ibunya menjual jamu. Duduk di pasar, menawarkan ramuan jahe dan temulawak. Ia tidak pandai bicara, tapi orang-orang suka karena senyumnya tulus.
Suatu hari, seorang nenek tua berkata:
“Kamu mirip ibumu dulu. Tapi matamu… matamu seperti orang yang sedang mencari sesuatu.”
Arunika terdiam.
Ia mulai menulis lagi. Tidak di jurnal. Tapi di kertas bekas bungkus ikan, di balik nota penjualan jamu, di buku tulis bekas SMK.
Tulisan-tulisannya pendek:
“Iya aku sedang mencari sesuatu, yang bahkan aku sendiri ngga tau keberadaannya”
“Hari ini, aku keluar rumah. Itu kemenangan.”
“Aku belum tahu harus jadi apa. Tapi aku masih bernapas. Itu cukup untuk hari ini.”
“Laut tadi malam tenang. Seperti pikiranku yang mulai menemukan damai.”
Pertemuan dengan Nenek Laut
Di ujung pantai, tinggal seorang perempuan tua yang dipanggil Nenek Laut. Konon, ia pernah menjadi nelayan perempuan pertama di desa—sesuatu yang sangat langka di masanya. Kini, ia tinggal sendiri di gubuk kecil, membuat jaring dan menjual kerajinan dari cangkang laut.
Suatu sore, Arunika melihatnya duduk di depan gubuk, menatap laut.
“Nek, kenapa Ibu bisa bertahan jadi nelayan? Padahal perempuan jarang melaut,” tanya Arunika.
Nenek Laut tertawa kecil.
“Karena laut nggak peduli kamu perempuan atau laki-laki. Laut hanya peduli: kamu berani atau tidak.”
Ia menatap Arunika.
“Kamu sedang lelah, ya?”
Arunika mengangguk.
“Lelah itu wajar. Tapi jangan sampai jadi alasan untuk berhenti. Aku dulu pernah tenggelam. Dua jam hanyut. Tapi aku bertahan karena satu hal: aku masih ingin melihat matahari besok.”
Ia memberi Arunika kalung kecil dari kerang.
“Ini jangkar kecil. Kalau kamu merasa hanyut, pegang ini. Ingat: kamu punya tempat pulang.”
Arunika memegang kalung itu erat.
Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang melihatnya, bukan karena prestasinya, tapi karena jiwanya.
Titik Balik yang Sunyi
Malam itu, Arunika kembali ke pantai.
Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya duduk, memandang laut, memegang kalung dari kerang.
Ia membuka jurnalnya. Menulis:
“Aku lelah. Aku sedih. Aku bingung. Tapi aku belum selesai.
Aku bukan apoteker. Tapi mungkin aku bisa jadi sesuatu yang lain.
Aku bukan harapan keluarga. Tapi aku bisa jadi harapan untuk diriku sendiri.
Aku belum tahu jalan selanjutnya. Tapi aku tahu: aku harus terus berjalan.
Terima kasih, Laut. Karena kamu selalu ada. Karena kamu tidak pernah menyerah. Karena kamu mengajariku bahwa pasang pasti datang setelah surut.
Aku belum kuat. Tapi aku mulai percaya: aku akan kuat.”
Ia menutup jurnal. Angin berhembus pelan. Ombak datang, membasahi kakinya, lalu surut.
Seperti sebuah janji.
Setelah pengumuman kelulusan SNMPTN, waktu seolah berhenti bagi Arunika.
Bukan hanya karena gagal masuk kuliah. Bukan hanya karena ekonomi keluarga yang tak mampu. Tapi karena segala sesuatu yang selama ini menjadi identitasnya, tiba-tiba runtuh.
Ia bukan lagi “anak pintar”.
Ia bukan lagi “harapan keluarga”.
Ia bukan lagi “juara kelas”.
Ia hanya… Arunika yang gagal.
Hari pertama setelah pengumuman, ia tidak keluar kamar. Ia mematikan ponsel. Menarik selimut hingga menutupi kepala. Udara di kamar terasa pengap, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menghilang.
Ibunya mengetuk pintu pelan.
“Arun? Makan dulu, Nak.”
Tidak ada jawaban.
“Kita nggak apa-apa. Masih ada waktu.”
Masih diam.
Di luar, ayahnya duduk di teras, merokok dengan tatapan kosong. Ia tidak marah. Ia tidak menyalahkan. Tapi Arunika tahu: di matanya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah karena tidak bisa memberi lebih.
“Harusnya aku bisa nabung lebih,” gumam Pak Darmo suatu malam, tanpa menyadari Arunika mendengar dari balik dinding.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arunika menangis bukan karena dirinya.
Tapi karena orang tuanya.
Dua minggu berlalu. Arunika mulai membuka ponselnya lagi. Dan yang pertama ia lihat adalah dunia yang terus berjalan tanpa dirinya.
Teman-temannya memposting foto di kampus baru.
Ada yang di Bandung, memakai jaket almamater, tersenyum di depan gerbang universitas.
Ada yang di Jogja, duduk di kafe sambil membaca buku tebal.
Ada yang di Jakarta, berdiri di depan gedung pencakar langit, dengan tulisan: “Akhirnya, mimpi jadi nyata.”
Setiap notifikasi adalah paku kecil yang menusuk hati.
Ia membuka profil mantan teman sekelasnya, Dinda, yang dulu selalu kalah dalam lomba sains. Kini, Dinda memposting foto dirinya memakai jas lab, dengan keterangan:
“Hari pertama praktikum di Fakultas Kedokteran. Terima kasih Tuhan, aku nggak menyerah.”
Arunika menutup ponselnya. Dadanya sesak.
“Kalau aku yang menulis itu, mungkin akan jadi: ‘Hari pertama tidak punya tujuan. Aku menyerah.’”
Ia merasa seperti penonton dalam film kehidupan orang lain. Ia bisa melihat, tapi tidak bisa masuk. Ia terkunci di luar.
Percakapan yang Tidak Pernah Terjadi
Suatu malam, Arunika duduk di lantai kamarnya, memandang langit-langit. Ia membayangkan percakapan yang ingin ia ucapkan, tapi tidak pernah berani:
“Bu, aku nggak mau jadi apoteker. Aku nggak pernah mau. Aku cuma takut kamu kecewa.”
“Ayah, aku bukan Raka. Aku nggak kuat jadi satu-satunya harapan. Aku cuma ingin jadi… aku.”
“Teman-teman, aku nggak kalah karena bodoh. Aku kalah karena lelah. Karena aku hidup bukan untuk aku.”
Tapi semua itu hanya tinggal di dalam kepala. Di mulut, hanya keluar:
“Nggak apa-apa, Bu.”
“Iya, Ayah.”
“Selamat ya, Dinda.”
Laut sebagai Saksi Bisu
Pada hari ke-17 setelah pengumuman, Arunika kembali ke pantai.
Bukan karena ingin sembuh.
Tapi karena ia butuh tempat di mana ia tidak harus berpura-pura.
Ia duduk di batu karang favoritnya, tempat ia biasa menulis di jurnal kecil. Angin malam bertiup kencang, membawa bau garam dan rumput laut. Ombak datang, memecah, lalu surut—seperti napas yang tak pernah berhenti.
Ia mengeluarkan jurnalnya. Halaman-halaman terakhir kosong. Ia menulis:
“Hari ini, aku merasa seperti ikan mati yang hanyut. Tidak punya arah. Tidak punya oksigen. Hanya terbawa arus.”
Ia menutup jurnal. Lalu berbisik:
“Laut, kamu pernah merasa lelah nggak? Kamu selalu bergerak. Kamu nggak pernah berhenti. Kamu nggak pernah menyerah. Tapi aku… aku lelah.”
Ombak datang, membasahi ujung kakinya. Seperti menjawab:
"Aku juga lelah. Tapi aku tetap bergerak. Karena kalau aku berhenti, dunia akan mati."
Arunika menangis. Tidak keras. Hanya air mata yang mengalir diam-diam, larut dalam suara laut malam.
Beberapa hari kemudian, Arunika bermimpi.
Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi laut, memakai jas laboratorium putih. Ia memegang botol obat, tapi saat dibuka, isinya adalah pasir. Ia mencoba membacanya, tapi huruf-hurufnya berubah jadi gelombang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar.
Lalu muncul bayangan ibunya.
“Kenapa kamu gagal, Arun?”
“Kamu anak pintar!”
“Kamu anak terakhir!”
“Kamu harapan kami!”
Arunika mundur. Ia terus mundur sampai jatuh ke laut.
Airnya dingin. Gelap. Ia tidak bisa bernapas.
Ia melihat ikan-ikan kecil berenang melewatinya, seolah berkata:
“Kamu bukan dari sini.”
Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi punggungnya.
Ia menyalakan lampu. Menatap jurnalnya. Lalu menulis:
“Aku bukan dari sana. Aku bukan dari dunia itu. Tapi aku juga belum tahu dari mana aku sebenarnya.”
Pagi harinya, Pak Darmo duduk di samping Arunika di teras.
Tidak bicara. Hanya menawarkan secangkir kopi pahit—yang biasanya ia minum sebelum pergi melaut.
Setelah beberapa menit, ia berkata pelan:
“Kamu tahu, Nak, setiap kali aku pergi melaut, aku nggak tahu ikan apa yang akan aku dapat. Kadang dapat banyak. Kadang kosong. Tapi aku tetap pergi.”
Arunika menatap ayahnya.
“Kenapa, Yah?”
“Karena kalau aku berhenti, aku bukan nelayan lagi. Aku cuma orang yang takut laut.”
Ia menatap anaknya.
“Kamu gagal masuk kuliah. Tapi kamu belum berhenti jadi Arunika. Selama kamu masih bernapas, kamu masih punya waktu.”
Arunika menunduk. Air matanya jatuh ke cangkir.
“Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana, Yah.”
Pak Darmo tersenyum tipis.
“Mulai dari yang kecil. Seperti aku. Hari ini, aku cuma bawa jaring kecil. Kalau dapat ikan, syukur. Kalau nggak, besok aku coba lagi.”
Arunika mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa ayahnya benar-benar mengerti.
Hari-Hari Tanpa Nama
Beberapa minggu berlalu. Arunika mulai keluar kamar lebih sering. Tapi belum ada semangat. Belum ada tujuan.
Ia mulai membantu ibunya menjual jamu. Duduk di pasar, menawarkan ramuan jahe dan temulawak. Ia tidak pandai bicara, tapi orang-orang suka karena senyumnya tulus.
Suatu hari, seorang nenek tua berkata:
“Kamu mirip ibumu dulu. Tapi matamu… matamu seperti orang yang sedang mencari sesuatu.”
Arunika terdiam.
Ia mulai menulis lagi. Tidak di jurnal. Tapi di kertas bekas bungkus ikan, di balik nota penjualan jamu, di buku tulis bekas SMK.
Tulisan-tulisannya pendek:
“Iya aku sedang mencari sesuatu, yang bahkan aku sendiri ngga tau keberadaannya”
“Hari ini, aku keluar rumah. Itu kemenangan.”
“Aku belum tahu harus jadi apa. Tapi aku masih bernapas. Itu cukup untuk hari ini.”
“Laut tadi malam tenang. Seperti pikiranku yang mulai menemukan damai.”
Pertemuan dengan Nenek Laut
Di ujung pantai, tinggal seorang perempuan tua yang dipanggil Nenek Laut. Konon, ia pernah menjadi nelayan perempuan pertama di desa—sesuatu yang sangat langka di masanya. Kini, ia tinggal sendiri di gubuk kecil, membuat jaring dan menjual kerajinan dari cangkang laut.
Suatu sore, Arunika melihatnya duduk di depan gubuk, menatap laut.
“Nek, kenapa Ibu bisa bertahan jadi nelayan? Padahal perempuan jarang melaut,” tanya Arunika.
Nenek Laut tertawa kecil.
“Karena laut nggak peduli kamu perempuan atau laki-laki. Laut hanya peduli: kamu berani atau tidak.”
Ia menatap Arunika.
“Kamu sedang lelah, ya?”
Arunika mengangguk.
“Lelah itu wajar. Tapi jangan sampai jadi alasan untuk berhenti. Aku dulu pernah tenggelam. Dua jam hanyut. Tapi aku bertahan karena satu hal: aku masih ingin melihat matahari besok.”
Ia memberi Arunika kalung kecil dari kerang.
“Ini jangkar kecil. Kalau kamu merasa hanyut, pegang ini. Ingat: kamu punya tempat pulang.”
Arunika memegang kalung itu erat.
Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang melihatnya, bukan karena prestasinya, tapi karena jiwanya.
Titik Balik yang Sunyi
Malam itu, Arunika kembali ke pantai.
Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya duduk, memandang laut, memegang kalung dari kerang.
Ia membuka jurnalnya. Menulis:
“Aku lelah. Aku sedih. Aku bingung. Tapi aku belum selesai.
Aku bukan apoteker. Tapi mungkin aku bisa jadi sesuatu yang lain.
Aku bukan harapan keluarga. Tapi aku bisa jadi harapan untuk diriku sendiri.
Aku belum tahu jalan selanjutnya. Tapi aku tahu: aku harus terus berjalan.
Terima kasih, Laut. Karena kamu selalu ada. Karena kamu tidak pernah menyerah. Karena kamu mengajariku bahwa pasang pasti datang setelah surut.
Aku belum kuat. Tapi aku mulai percaya: aku akan kuat.”
Ia menutup jurnal. Angin berhembus pelan. Ombak datang, membasahi kakinya, lalu surut.
Seperti sebuah janji.
Other Stories
Yang Dekat Itu Belum Tentu Lekat
Dua puluh tahun sudah aku berkarya disini. Di setiap sudut tempat ini begitu hangat, penuh ...
Cangkul Yang Dalam ( Halusinada )
Alya sendirian di dapur. Dia terlihat masih kesal. Matanya tertuju ke satu set pisau yang ...
Hidup Sebatang Rokok
Suratemu tumbuh dalam belenggu cinta Ibu yang otoriter, nyaris menjadi kelinci percobaan d ...
Cinta Dibalik Rasa
Cukup lama menunggu, akhirnya pramusaji kekar itu datang mengantar kopi pesananku tadi. A ...
Love Of The Death
Segala sumpah serapah memenuhi isi hati Gina. Tatapan matanya penuh dendam. Bisikan-bisika ...
Queen, The Last Dance
Di panggung megah, di tengah sorak sorai penonton yang mengelu-elukan namanya, ada air mat ...