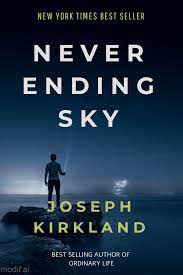BAB VI: PERJALANAN KE JOGJA — MEMULAI DARI NOL
Dari Laut ke Kota
Pagi itu, Arunika berdiri di dermaga, koper kecil di tangan. Ayah, ibu, dan Raka mengantarnya.
Bus antarkota datang. Ia menatap keluarganya. Tidak ada kata-kata besar. Hanya pelukan, doa, dan air mata yang ditahan.
“Hati-hati di jalan,” kata Pak Darmo. “Kalau kamu rindu laut, lihat langit. Kita lihat langit yang sama.”
Arunika mengangguk. Ia naik bus. Duduk di jendela. Melihat Tirtamulya perlahan menghilang di kejauhan.
Ia menatap laut terakhir kali.
Lalu menutup mata.
Kota yang Asing
Jogja ternyata tidak seperti yang ia bayangkan.
Tidak ada gedung tinggi, tapi ada riuhnya pasar, deru sepeda motor, dan aroma kopi dari warung pinggir jalan. Udara terasa lebih kering. Angin tidak membawa garam, tapi debu dan asap.
Dengan alamat yang telah Raka beritahu, ia berjalan ke gang kecil di dekat Pasar Beringharjo. Di ujung gang, ada rumah tua dengan papan kayu:
“Baca Bersama – Perpustakaan & Ruang Belajar Anak”
Pintunya terbuka. Di dalam, seorang pemuda menyambutnya dengan senyum hangat.
“Kamu Arunika? Aku Langit, koordinator relawan di sini. Selamat datang.”
Arunika tersenyum, tapi hatinya berdebar.
Ia merasa seperti ikan yang tiba-tiba dilempar ke darat.
Komunitas “Baca Bersama” bukan tempat mewah. Lantainya dari semen, rak bukunya dari kayu bekas, dan AC-nya hanya kipas angin tua. Tapi di sana, ada sesuatu yang langka: semangat.
Anak-anak datang dari keluarga buruh, pedagang kaki lima, bahkan tunawisma. Mereka tidak punya banyak, tapi punya rasa ingin tahu yang besar.
Langit memperkenalkan Arunika:
“Ini Kak Arunika. Ia dari desa pesisir. Ia akan bantu kita ngajar membaca dan menulis.”
Seorang anak kecil, Dina, langsung bertanya:
“Kak, lautnya besar nggak?”
Arunika tertawa. “Sangat besar. Dan sangat indah.”
“Nanti kamu cerita, ya?” ujar Dina, penuh antusias.
“Iya, janji.”
Untuk pertama kalinya, Arunika merasa dibutuhkan bukan karena prestasinya, tapi karena dirinya.
Mengajar ternyata tidak mudah.
Arunika tidak tahu cara menjelaskan huruf “A” agar menyenangkan. Ia salah mengucapkan kata. Ia kaku saat bercerita. Anak-anak tertawa — bukan karena menghina, tapi karena lucu.
Tapi ia tidak marah. Ia ikut tertawa.
“Kak Arun lucu kalau salah baca,” kata Dina.
“Ya, karena aku masih belajar,” jawab Arunika. “Kita semua sedang belajar.”
Malam itu, ia menulis di jurnal:
“Aku pikir, mengajar itu tentang tahu segalanya. Tapi ternyata, mengajar itu tentang mau belajar bersama.”
Laut dalam Cerita
Suatu hari, Arunika membawa cerita dari rumah. Ia menceritakan tentang Tirtamulya — tentang ombak, tentang nelayan, tentang ikan teri yang muncul saat bulan purnama.
Anak-anak terpukau.
“Kak, lautnya biru banget ya?”
“Ada hiu nggak?”
“Kamu pernah lihat lumba-lumba?”
Arunika tersenyum. Ia mulai menggambar laut di papan tulis. Ia menyanyikan lagu nelayan. Ia membuat drama kecil tentang perahu yang melawan ombak.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lautnya tidak jauh.
Lautnya ada di sini — dalam suara anak-anak yang tertawa.
Di sore hari, Dina datang dengan buku kecil.
“Kak, aku sudah bisa baca satu paragraf sendiri!”
Arunika membacanya. Itu tentang laut. Tentang perempuan yang melaut. Tentang harapan.
Air mata Arunika mengalir.
“Kamu hebat, Dina,” bisiknya. “Kamu hebat sekali.”
Malam itu, ia menulis:
“Aku datang ke sini karena ingin menemukan diriku. Tapi ternyata, aku menemukan sesuatu yang lebih besar: arti dari memberi.”
Mimpi Baru yang Perlahan Tumbuh
Lama-kelamaan, Arunika mulai menikmati hari-harinya. Ia membuat metode belajar dengan lagu, gambar, dan permainan. Ia mulai menulis blog kecil: “Catatan dari Gang Kecil”.
Salah satu tulisannya viral:
Komentar masuk berbondong-bondong.
“Kamu inspiratif.”
“Aku dulu juga merasa gagal, tapi baca tulisanmu bikin aku semangat lagi.”
Arunika menangis. Bukan karena sedih.
Tapi karena ia merasa berguna.
Di malam hari, pada hari yang sama— Arunika duduk di atap rumah komunitas. Ia menatap langit. Bintang-bintang bersinar.
Ia membayangkan laut Tirtamulya. Ombak yang memecah. Angin yang menyapa. Suara ayah yang memanggil dari dermaga.
Ia membuka jurnal:
“Aku merindukan laut. Tapi aku sadar: laut bukan hanya tempat. Laut adalah perasaan. Laut adalah keberanian. Laut adalah terus bergerak meski tidak tahu arah. Aku tidak perlu kembali ke pantai untuk merasa dekat dengan laut. Karena laut sekarang ada di dalam hatiku.”
Ia menutup jurnal. Angin berhembus pelan. Seperti bisikan dari rumah.
Pagi itu, Arunika berdiri di dermaga, koper kecil di tangan. Ayah, ibu, dan Raka mengantarnya.
Bus antarkota datang. Ia menatap keluarganya. Tidak ada kata-kata besar. Hanya pelukan, doa, dan air mata yang ditahan.
“Hati-hati di jalan,” kata Pak Darmo. “Kalau kamu rindu laut, lihat langit. Kita lihat langit yang sama.”
Arunika mengangguk. Ia naik bus. Duduk di jendela. Melihat Tirtamulya perlahan menghilang di kejauhan.
Ia menatap laut terakhir kali.
Lalu menutup mata.
Kota yang Asing
Jogja ternyata tidak seperti yang ia bayangkan.
Tidak ada gedung tinggi, tapi ada riuhnya pasar, deru sepeda motor, dan aroma kopi dari warung pinggir jalan. Udara terasa lebih kering. Angin tidak membawa garam, tapi debu dan asap.
Dengan alamat yang telah Raka beritahu, ia berjalan ke gang kecil di dekat Pasar Beringharjo. Di ujung gang, ada rumah tua dengan papan kayu:
“Baca Bersama – Perpustakaan & Ruang Belajar Anak”
Pintunya terbuka. Di dalam, seorang pemuda menyambutnya dengan senyum hangat.
“Kamu Arunika? Aku Langit, koordinator relawan di sini. Selamat datang.”
Arunika tersenyum, tapi hatinya berdebar.
Ia merasa seperti ikan yang tiba-tiba dilempar ke darat.
Komunitas “Baca Bersama” bukan tempat mewah. Lantainya dari semen, rak bukunya dari kayu bekas, dan AC-nya hanya kipas angin tua. Tapi di sana, ada sesuatu yang langka: semangat.
Anak-anak datang dari keluarga buruh, pedagang kaki lima, bahkan tunawisma. Mereka tidak punya banyak, tapi punya rasa ingin tahu yang besar.
Langit memperkenalkan Arunika:
“Ini Kak Arunika. Ia dari desa pesisir. Ia akan bantu kita ngajar membaca dan menulis.”
Seorang anak kecil, Dina, langsung bertanya:
“Kak, lautnya besar nggak?”
Arunika tertawa. “Sangat besar. Dan sangat indah.”
“Nanti kamu cerita, ya?” ujar Dina, penuh antusias.
“Iya, janji.”
Untuk pertama kalinya, Arunika merasa dibutuhkan bukan karena prestasinya, tapi karena dirinya.
Mengajar ternyata tidak mudah.
Arunika tidak tahu cara menjelaskan huruf “A” agar menyenangkan. Ia salah mengucapkan kata. Ia kaku saat bercerita. Anak-anak tertawa — bukan karena menghina, tapi karena lucu.
Tapi ia tidak marah. Ia ikut tertawa.
“Kak Arun lucu kalau salah baca,” kata Dina.
“Ya, karena aku masih belajar,” jawab Arunika. “Kita semua sedang belajar.”
Malam itu, ia menulis di jurnal:
“Aku pikir, mengajar itu tentang tahu segalanya. Tapi ternyata, mengajar itu tentang mau belajar bersama.”
Laut dalam Cerita
Suatu hari, Arunika membawa cerita dari rumah. Ia menceritakan tentang Tirtamulya — tentang ombak, tentang nelayan, tentang ikan teri yang muncul saat bulan purnama.
Anak-anak terpukau.
“Kak, lautnya biru banget ya?”
“Ada hiu nggak?”
“Kamu pernah lihat lumba-lumba?”
Arunika tersenyum. Ia mulai menggambar laut di papan tulis. Ia menyanyikan lagu nelayan. Ia membuat drama kecil tentang perahu yang melawan ombak.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lautnya tidak jauh.
Lautnya ada di sini — dalam suara anak-anak yang tertawa.
Di sore hari, Dina datang dengan buku kecil.
“Kak, aku sudah bisa baca satu paragraf sendiri!”
Arunika membacanya. Itu tentang laut. Tentang perempuan yang melaut. Tentang harapan.
Air mata Arunika mengalir.
“Kamu hebat, Dina,” bisiknya. “Kamu hebat sekali.”
Malam itu, ia menulis:
“Aku datang ke sini karena ingin menemukan diriku. Tapi ternyata, aku menemukan sesuatu yang lebih besar: arti dari memberi.”
Mimpi Baru yang Perlahan Tumbuh
Lama-kelamaan, Arunika mulai menikmati hari-harinya. Ia membuat metode belajar dengan lagu, gambar, dan permainan. Ia mulai menulis blog kecil: “Catatan dari Gang Kecil”.
Salah satu tulisannya viral:
“Belajar dari Anak-Anak: Mereka Tidak Pernah Menyerah, Kenapa Aku Harus?”
Komentar masuk berbondong-bondong.
“Kamu inspiratif.”
“Aku dulu juga merasa gagal, tapi baca tulisanmu bikin aku semangat lagi.”
Arunika menangis. Bukan karena sedih.
Tapi karena ia merasa berguna.
Di malam hari, pada hari yang sama— Arunika duduk di atap rumah komunitas. Ia menatap langit. Bintang-bintang bersinar.
Ia membayangkan laut Tirtamulya. Ombak yang memecah. Angin yang menyapa. Suara ayah yang memanggil dari dermaga.
Ia membuka jurnal:
“Aku merindukan laut. Tapi aku sadar: laut bukan hanya tempat. Laut adalah perasaan. Laut adalah keberanian. Laut adalah terus bergerak meski tidak tahu arah. Aku tidak perlu kembali ke pantai untuk merasa dekat dengan laut. Karena laut sekarang ada di dalam hatiku.”
Ia menutup jurnal. Angin berhembus pelan. Seperti bisikan dari rumah.
Other Stories
Mother & Son
Zyan tak sengaja merusak gitar Dana. Rasa bersalah membawanya pulang dalam diam, hingga na ...
Makna Dibalik Kalimat (never Ending)
Rangkaian huruf yang menjadi kata. Rangkaian kata yang menjadi kalimat. Kalimat yang mungk ...
Mr. Boros Vs Mrs. Perhitungan
Rani berjuang demi adiknya yang depresi hingga akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Radit ...
Dari Luka Menjadi Cahaya
Azzam adalah seorang pemuda sederhana dengan mimpi besar. Ia percaya bahwa cinta dan kerja ...
Jika Nanti
Adalah sebuah Novel yang dibuat untuk sebuah konten ...
Katamu Aku Cantik
Ratna adalah korban pelecehan seksual di masa kecil dan memilih untuk merahasiakannya samb ...