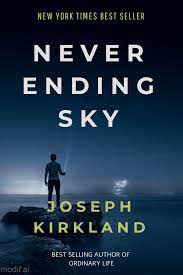BAB 10: RIAK YANG TAK TERUCAP
Pagi berikutnya, dermaga kembali ramai. Anak-anak kecil yang kemarin menertawakan Maheisa sudah nongol lagi, kali ini sambil membawa batok kelapa dan daun kering. Mereka duduk bergerombol, menunggu entah apa.
“Mas, coba main piano dari daun ini,” seru salah satu bocah sambil menata daun kering seperti tuts. Mereka tertawa terbahak-bahak.
Maheisa hanya tersenyum, mencoba tidak canggung. “Kalau nadanya fals, jangan salahkan aku, ya,” balasnya sambil menepuk-nepuk daun. Tawa bocah makin pecah.
Dari jauh, Selia menggelengkan kepala, separuh kesal separuh geli. “Mereka kalau sudah kepo begitu, susah dihentikan,” katanya pada Dara, yang sibuk menyiapkan logbook latihan.
“Dan kamu nggak keberatan, kan?” Dara balik menatapnya. “Lihat saja, Sel. Anak-anak itu bahkan lebih akrab dengannya daripada denganmu.”
Selia mendengus. “Itu karena mereka belum pernah aku ajak latihan bareng. Kalau sudah, mereka kabur sendiri.”
Dara tertawa keras, lalu menepuk bahu Selia. “Atau mungkin kamu saja yang terlalu kaku.”
Hari itu, latihan tidak dilakukan terlalu dalam. Arman ingin fokus pada teknik pernapasan. Mereka duduk melingkar di atas papan pelampung, mengambang di laut tenang.
“Dengarkan tubuhmu,” ucap Arman. “Tarik napas, tahan, lalu keluarkan perlahan. Fokus. Jangan buru-buru. Kita di laut, bukan di lomba lari.” Nasehatnya yang selalu bertafsirkan sama, seperti mantra rutin yang harus dirapalkan tiap kali Maheisa hendak menyelam.
Maheisa mencoba mengikuti. Ia menarik udara panjang, menahannya, lalu melepaskan sedikit demi sedikit. Selia yang duduk di sebelahnya sesekali melirik, memperhatikan ekspresi wajahnya yang serius tapi masih kaku.
“Kamu terlalu tegang,” gumam Selia.
“Aku sudah santai,” balas Maheisa, mata terpejam.
“Kamu bilang begitu sambil mengerutkan dahi,” potong Selia.
Arman menyela sambil tertawa. “Sudah, kalian jangan berdebat. Laut sudah menunggu.”
—
Setelah sesi berakhir, mereka kembali ke pondok. Dara menaruh gelas es kelapa di meja. “Minum dulu, biar segar. Panas sekali hari ini.”
Maheisa menyesap perlahan. “Terima kasih.”
Dara duduk di sebelah Selia, lalu berbisik cukup keras untuk terdengar, “Kamu sadar nggak, Sel? Dia beda. Biasanya, orang baru yang ikut kamu latihan entah kabur, entah menyerah. Tapi dia bertahan.”
Selia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Maheisa yang sedang berbicara dengan salah satu anggota komunitas lain. Ada sesuatu di cara pria itu menyimak, matanya penuh perhatian meski ia sendiri sering melewatkan banyak bunyi.
“Aku nggak tahu kenapa dia bertahan,” gumam Selia akhirnya.
“Karena laut,” timpal Dara cepat. “Laut selalu punya cara menahan orang. Termasuk kamu dulu.”
—
Menjelang sore, ketika semua orang sudah pulang, hanya Selia dan Maheisa yang masih duduk di dermaga. Laut tenang, memantulkan cahaya jingga dari matahari yang perlahan tenggelam.
“Selia Maris,” suara Maheisa pelan, nyaris kalah oleh angin.
“Hm?” Selia menoleh, sedikit terkejut dipanggil begitu serius.
“Kamu pernah merasa hidupmu seperti ditarik ke dalam air? Sampai-sampai kamu lupa caranya bernapas?”
Selia terdiam. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia menatap horizon, mencoba meramu jawaban.
“Aku sering,” lanjut Maheisa, suaranya berat. “Sejak kecil. Rumahku selalu penuh suara tapi bukan suara yang ingin kudengar. Bentakan, piring pecah, pintu dibanting. Kadang aku berharap bisa menutup telinga sepenuhnya. Dan sekarang, sebagian doaku terkabul.” Ia tertawa hambar.
Selia memeluk lututnya, membiarkan kalimat itu meresap. “Laut juga pernah jadi seperti itu buatku,” akhirnya ia bicara. “Awalnya aku menyelam untuk kabur. Dari tuntutan, dari pandangan orang, dari diriku sendiri. Tapi lama-lama aku sadar, laut tidak menenggelamkan. Ia justru mengajarkan caranya bernapas lagi. Dengan ritme berbeda.”
Maheisa menoleh. Tatapan itu tajam, tapi rapuh. “Kamu masih bisa memilih bernapas. Aku takut aku tidak bisa lagi.”
“Kamu bisa,” jawab Selia mantap, meski suaranya bergetar. “Kamu hanya perlu menemukan cara baru. Entah itu lewat piano, atau… lewat kedalaman laut.”
Mereka terdiam. Hanya suara ombak kecil yang mengisi jeda.
Selia menambahkan pelan, “Kamu tahu, laut tidak pernah menolak siapa pun. Bahkan orang yang datang dengan luka terdalam sekalipun. Dia akan menampungmu. Selama kamu berani masuk.”
Maheisa menunduk, jemarinya mengetuk kayu dermaga seperti sedang memainkan tuts tak kasatmata. Ia tidak menjawab, tapi Selia tahu—kalimat itu menancap.
Matahari akhirnya hilang di balik cakrawala. Ombak terus berulang, seperti napas panjang yang tak pernah habis.
“Mas, coba main piano dari daun ini,” seru salah satu bocah sambil menata daun kering seperti tuts. Mereka tertawa terbahak-bahak.
Maheisa hanya tersenyum, mencoba tidak canggung. “Kalau nadanya fals, jangan salahkan aku, ya,” balasnya sambil menepuk-nepuk daun. Tawa bocah makin pecah.
Dari jauh, Selia menggelengkan kepala, separuh kesal separuh geli. “Mereka kalau sudah kepo begitu, susah dihentikan,” katanya pada Dara, yang sibuk menyiapkan logbook latihan.
“Dan kamu nggak keberatan, kan?” Dara balik menatapnya. “Lihat saja, Sel. Anak-anak itu bahkan lebih akrab dengannya daripada denganmu.”
Selia mendengus. “Itu karena mereka belum pernah aku ajak latihan bareng. Kalau sudah, mereka kabur sendiri.”
Dara tertawa keras, lalu menepuk bahu Selia. “Atau mungkin kamu saja yang terlalu kaku.”
Hari itu, latihan tidak dilakukan terlalu dalam. Arman ingin fokus pada teknik pernapasan. Mereka duduk melingkar di atas papan pelampung, mengambang di laut tenang.
“Dengarkan tubuhmu,” ucap Arman. “Tarik napas, tahan, lalu keluarkan perlahan. Fokus. Jangan buru-buru. Kita di laut, bukan di lomba lari.” Nasehatnya yang selalu bertafsirkan sama, seperti mantra rutin yang harus dirapalkan tiap kali Maheisa hendak menyelam.
Maheisa mencoba mengikuti. Ia menarik udara panjang, menahannya, lalu melepaskan sedikit demi sedikit. Selia yang duduk di sebelahnya sesekali melirik, memperhatikan ekspresi wajahnya yang serius tapi masih kaku.
“Kamu terlalu tegang,” gumam Selia.
“Aku sudah santai,” balas Maheisa, mata terpejam.
“Kamu bilang begitu sambil mengerutkan dahi,” potong Selia.
Arman menyela sambil tertawa. “Sudah, kalian jangan berdebat. Laut sudah menunggu.”
—
Setelah sesi berakhir, mereka kembali ke pondok. Dara menaruh gelas es kelapa di meja. “Minum dulu, biar segar. Panas sekali hari ini.”
Maheisa menyesap perlahan. “Terima kasih.”
Dara duduk di sebelah Selia, lalu berbisik cukup keras untuk terdengar, “Kamu sadar nggak, Sel? Dia beda. Biasanya, orang baru yang ikut kamu latihan entah kabur, entah menyerah. Tapi dia bertahan.”
Selia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Maheisa yang sedang berbicara dengan salah satu anggota komunitas lain. Ada sesuatu di cara pria itu menyimak, matanya penuh perhatian meski ia sendiri sering melewatkan banyak bunyi.
“Aku nggak tahu kenapa dia bertahan,” gumam Selia akhirnya.
“Karena laut,” timpal Dara cepat. “Laut selalu punya cara menahan orang. Termasuk kamu dulu.”
—
Menjelang sore, ketika semua orang sudah pulang, hanya Selia dan Maheisa yang masih duduk di dermaga. Laut tenang, memantulkan cahaya jingga dari matahari yang perlahan tenggelam.
“Selia Maris,” suara Maheisa pelan, nyaris kalah oleh angin.
“Hm?” Selia menoleh, sedikit terkejut dipanggil begitu serius.
“Kamu pernah merasa hidupmu seperti ditarik ke dalam air? Sampai-sampai kamu lupa caranya bernapas?”
Selia terdiam. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia menatap horizon, mencoba meramu jawaban.
“Aku sering,” lanjut Maheisa, suaranya berat. “Sejak kecil. Rumahku selalu penuh suara tapi bukan suara yang ingin kudengar. Bentakan, piring pecah, pintu dibanting. Kadang aku berharap bisa menutup telinga sepenuhnya. Dan sekarang, sebagian doaku terkabul.” Ia tertawa hambar.
Selia memeluk lututnya, membiarkan kalimat itu meresap. “Laut juga pernah jadi seperti itu buatku,” akhirnya ia bicara. “Awalnya aku menyelam untuk kabur. Dari tuntutan, dari pandangan orang, dari diriku sendiri. Tapi lama-lama aku sadar, laut tidak menenggelamkan. Ia justru mengajarkan caranya bernapas lagi. Dengan ritme berbeda.”
Maheisa menoleh. Tatapan itu tajam, tapi rapuh. “Kamu masih bisa memilih bernapas. Aku takut aku tidak bisa lagi.”
“Kamu bisa,” jawab Selia mantap, meski suaranya bergetar. “Kamu hanya perlu menemukan cara baru. Entah itu lewat piano, atau… lewat kedalaman laut.”
Mereka terdiam. Hanya suara ombak kecil yang mengisi jeda.
Selia menambahkan pelan, “Kamu tahu, laut tidak pernah menolak siapa pun. Bahkan orang yang datang dengan luka terdalam sekalipun. Dia akan menampungmu. Selama kamu berani masuk.”
Maheisa menunduk, jemarinya mengetuk kayu dermaga seperti sedang memainkan tuts tak kasatmata. Ia tidak menjawab, tapi Selia tahu—kalimat itu menancap.
Matahari akhirnya hilang di balik cakrawala. Ombak terus berulang, seperti napas panjang yang tak pernah habis.
Other Stories
Susan Ngesot Reborn
Renita yang galau setelah bertengkar dengan Abel kehilangan fokus saat berkendara, hingga ...
Jika Nanti
Adalah sebuah Novel yang dibuat untuk sebuah konten ...
Namaku May
Belajar tak mengenal usia, gender, maupun status sosial. Kisah ini menginspirasi untuk ter ...
Membabi Buta
Mariatin bekerja di rumah Sundari dan Sulasmi bersama anaknya, Asti. Awalnya nyaman, namun ...
Keikhlasan Cinta
6 tahun Hasrul pergi dari keluarganya, setelah dia kembali dia dipertemukan kembali dengan ...
Nyanyian Hati Seruni
Awalnya ragu dan kesal dengan aturan ketat sebagai istri prajurit TNI AD, ia justru belaja ...