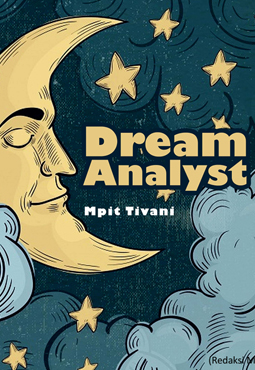Chapter 1
Bandung…
Akhirnya aku kembali ke tanah kelahiranku. Tempat di mana aku pernah terbang melayang bersama angan kekanakanku, berlari-lari di sepanjang kompleks rumah, berpetualang bersama kawan sekolah, dan membual tentang mimpi di masa depan. Meski kuakui kisahku tak sama dengan remaja seumuranku, namun aku masih bisa bahagia—setidaknya itu yang kurasakan.
Rindu ini menyeruak tidak karuan, mengisap habis semua daya ingatku dan memaksa mengenang semuanya kembali. Kisah suka, duka dan haru seolah mendorongku untuk tersenyum, lalu terdiam getir kemudian. Keluargaku sempat bahagia, utuh bersama Ayah dan Ibu yang mengapitku ketika tidur. Ya, meski Ayah hanya menemaniku hingga berumur 7 tahun. Setidaknya aku masih bisa mengingat wajah beliau yang tampan berseri—Ibu sering mengatakan aku mirip Ayah.
Namun di antara serpihan kenangan indah itu, ada satu yang masih terpatri di dalam hati. Ini tentang lelaki yang sempat kutelanjangi harga dirinya. Dan aku terlalu bodoh untuk jatuh cinta hingga nekat melakukannya. Entahlah apa yang pantas kukatakan. Bodoh? memalukan? Luar biasa? Atau mungkin berkesan? Yang pasti kenangan itu akan lekat selamanya. Dan aku tidak menyesal sama sekali.
Nael, How are you?
***
Lelah raga setelah berjibaku dengan waktu. Mulai dari perjalanan panjang di Bandara Changi hingga terjebak macet di jalanan Bandung. Tubuhku rasanya begitu pegal dan kaku. Ah seandainya saja aku berani pulang ke rumah Ibu, mungkin beliau masih mau menyiapkan air hangat lalu menyeduhkan segelas wedang jahe kesukaanku. Entahlah, kapan masa itu bisa kembali. Waktu menciptakan bentangan jarak di antara kami.
Lantunan lembut dari ponsel menyadarkanku dari lamunan panjang. Ada di mana aku sekarang? Kuintip jalanan dari kabin mobil. Luar biasa. Bandung dengan ciri khasnya masih menjadi tempat favorit untuk berakhir pekan. Kulihat kendaraan bernomor polisi B berjajar rapi di antara taksi yang kutumpangi.
“Ya. Halo?”
“Diaz! Kamu sudah tiba?”
Aku menghela napas panjang. Dari nada suaranya aku bisa menebak siapa pemilik suara riang ini. “Hm... iya, Bob. Ini aku di taksi, sedang on the way ke tempat tinggalku,” Aku baru ingat hari ini Geng Setan–kawan-kawan PLU[1] yang sempat akrab sejak tiga tahun terakhir—mengadakan pesta untuk menyambut kepulanganku. Tapi sungguh, ini bukan waktu yang tepat untuk bersenang-senang. Waktuku terbatas hanya untuk istirahat dan terbangun di pagi hari untuk memulai aktivitas di kantor baru.
“Hm… rasanya aku ti…”
“Sudahlah, jangan menghindar dari kami. Aku sudah jauh hari menyiapkan pesta ini,” sungut Bobby.
“Baiklah,” aku menyerah.
“See ya one hour later! At Metropolis. Still remember that place?”
“Sure.”
Bibirku tersungging. Selalu Metropolis. Kali pertama kami berempat bertemu di klub gay terkenal di Bandung itu. Sebelumnya kami hanya bertegur sapa saat berkenalan di Grindr—situs jejaring sosial khusus kalangan homoseksual. Tidak apa-apa, memiliki beberapa teman PLU kupikir tidak terlalu berlebihan. Ada kalanya aku membutuhkan kawan yang bisa kuajak bicara seputar masalah orientasi sex-ku—tentunya aku tak bisa bicara sembarangan pada orang-orang di sekitarku. Bobby, Dimas dan Chandra cukup kupercaya untuk memegang teguh rahasia kami masing-masing.
Di luar Geng Setan, aku masih memiliki seorang kawan gay. Dia adalah sahabat gay pertamaku. Sepuluh tahun kami berteman sejak duduk di bangku SMA. Kelak aku akan ceritakan lebih dalam tentang Eka, dan bagaimana akhirnya kami bisa berkawan akrab hingga sekarang.
Langkahku perlahan menjauhi lift, menelusuri koridor apartemen di lantai sepuluh menuju pintu bernomor 107. Damn, aku lelah sekali! Rasanya ingin segera berbaring di ranjang berukuran king size dan melupakan janjiku bertemu Geng Setan.
Baru saja aku meraih gagang pintu, panggilan nyaring yang berasal dari saku kananku berbunyi lagi. Oh God! Siapa lagi sekarang? Kuraih gadget, tertulis nama sahabatku di layar ponsel. Eka. Sial! Aku lupa mengabari kepulanganku kepadanya.
“Halo? Hei Eka. Maaf aku tidak sempat menghubungimu,” ujarku seraya memijit nomor kombinasi di pintu apartemen. “Yup aku baru tiba sejam yang lalu. Ini aku sudah tiba di apartemen,” masih tergopoh-gopoh dengan satu tangan mendorong travel bag menuju bagian dalam ruanganku. “Apa? Tidak perlu, lagi pula aku akan pergi ke luar. Aku ada janji dengan kawan-kawan di Metropolis. Atau kita janjian bertemu di sana?” aku menghela napas panjang lalu menutup pintu. “Kenapa sih, Ka? Kamu sepertinya tidak suka pada mereka?” sepanjang ocehan Eka aku hanya bisa menggaruk-garuk kepala. “Oke. Besok kita bertemu, ya?”
Satu tanda tanya yang masih menjadi misteri hingga kini. Kenapa Eka tak pernah menyukai Bobby, Dimas dan Chandra? Setahuku mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Whatever… kupikir tak seorangpun yang bisa melarangku berteman dengan Geng Setan.
Kurebahkan tubuhku seketika saat kutemui sofa di depan mata. Dalam sekejap tubuh ini terasa nyaman. Hal yang kutunggu sejak berjam-jam yang lalu, berbaring beralaskan kain sofa yang lembut dan harum. Tidak peduli travel bag-ku terlantar di depan mulut pintu apartemen, aku hanya ingin tidur sebentar.
Tentu saja, belum sepuluh menit aku menenangkan diri, ponsel sialan itu kembali berbunyi nyaring. Kusempatkan waktu untuk menggeliat sejenak.
“Hm…” aku perbaiki suara serakku. “Halo?” ucapku mantap.
“Diaz! Kamu di mana?”
“Aku… aku sedang on the way. Macet total di sini.”
“Cepatlah sedikit! Aku kesal menunggu kamu,” keluh Bobby.
“Sip. Aku akan telat sedikit,” mereka pasti tahu aku berbohong. Ah, biarlah… Bergegas aku menuju Bath room.
***
Ucapan adalah doa. Benar juga, kenyataannya taksiku kini terjebak di jalanan protokol Kota Bandung. Sebenarnya hanya butuh waktu lima belas menit untuk tiba di Metropolis bila jalanan dalam keadaan lengang. Syukurlah, dengan tingkat kesabaran yang luar biasa, lima belas menit perjalanan berubah menjadi satu jam menuju tepat di halaman parkir gedung klub Metropolis.
Aku menengadah menatap takjub gedung mewah itu. Dua tahun waktu yang cukup untuk menjaring member yang aku yakin sudah mencapai ribuan. Terbukti dengan fasilitas lux yang terlihat saat memasuki lobby gedung itu. Furnitur, lukisan, lampu, dan pernak-pernik lainnya. Semua begitu eksklusif. Baiklah, mau tidak mau aku harus berpesta juga malam ini, tenggelam di antara musik hingar-bingar, minuman beralkohol, dan para lelaki seksi. Kalau saja Peter tahu aku ada di sini, habislah sudah—bibirku tersungging memikirkan kekasihku.
Hentakan lagu kencang milik Lady Gaga seolah mengguncang lantai dansa. Aku yang masih kebingungan tak henti-hentinya mengedarkan pandanganku ke segala arah. Cahaya remang dan bias lampu disko membuatku kesulitan mencari mereka di tengah lautan pengunjung yang haus pesta. Di mana setan-setan itu? batinku jengkel.
Tak jauh dari tempatku berdiri akhirnya kulihat seseorang melambaikan tangannya padaku. Yup. Ini jelas sekali mirip Bobby. Tubuh tinggi besar dengan rambut berjambul tinggi ala Elvis Presley. Dari kejauhan aku hanya bisa menyeringai lalu beranjak mendekat. Di sana dua lelaki lain nampak gembira menyambutku.
“Diaz Aditya Kayana... akhirnya bintang kita datang juga,” tidak sabar Bobby mendekapku. Sepertinya di lingkungan seperti ini dia lebih bebas berekspresi. Tanpa malu-malu dia mencium pipi kananku, yang membuatku terpaksa melakukan hal yang sama dengan kedua teman lainnya.
“Maaf aku datang terlambat,” suara bising memaksaku berbicara setengah berteriak.
“Bagaimana kabarmu, Brother?” Dimas, lelaki yang paling kalem di antara kami. Perangainya yang tenang sangat cocok dengan profesinya sebagai seorang dokter.
“Betah ya di Singapura? Dua tahun kamu tidak pulang,” celoteh Chandra seraya menawarkan segelas Johnnie Walker Black Label padaku.
“Sungguh, Brother… aku sibuk sekali,” ujarku, lalu menenggak sedikit minuman itu. “Lalu bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan bisnis florist kebanggaanmu?” tanyaku pada Bobby.
“Siip! Bisnisku berkembang pesat, sudah ada puluhan pelanggan tetap yang hampir setiap minggu memesan bunga hiasku,” terang Bobby bangga.
“Lalu kamu, Chan? Kamu belum pindah kerja dari bank itu?”
Chandra mengangkat bahu. “Tidak ada jalan lain. Aku tidak bisa merawat bunga, apalagi merawat orang,” lelaki itu tertawa diikuti oleh pukulan kecil dari Bobby dan Dimas.
Senyumku terkulum. “Sedikit menyesal. Aku telah menyia-nyiakan banyak waktu berharga bersama kalian.”
“That’s fine. Yang penting sekarang kamu tinggal di satu kota dengan kami. Kita bisa bertemu setiap saat, right?”
“Sure…” aku mengiyakan.
Kami bersulang lalu tertawa kemudian. Ah, entah kenapa lelah ini tiba-tiba hilang setelah disambut meriah oleh para sahabatku.
“Ok. Let get out of here…” Bobby merangkulku, membuat aroma tajam Hugo Boss yang ia pakai menyeruak di hidungku. Aku hanya bisa memicingkan mata, pertanda curiga. Memangnya mau ke mana? Bukannya kami sudah berada di Metropolis? Bobby rupanya bisa melihat isyarat wajahku. “Private room,” bisiknya, diikuti dengan suara cekikikan yang terdengar sangat aneh.
Cepat-cepat aku menggeleng. “Oh, No! ini pasti rencanamu!” elakku.
Rupanya Bobby belum cukup puas mempermainkanku. Dua tahun lalu kami sempat berada di ruang yang sama. Dan tentu saja, Geng Setan membuatku mabuk dan hampir menelanjangiku bersama dengan seorang kucing[2].
“Don’t worry, Honey… aku tidak akan memberi tahu Peter. Rahasiamu aman bersama kami,” Bobby mengedipkan matanya, diikuti gelak tawa membahana kawanku yang lain.
Aku tak berdaya digiring paksa menuju lorong kamar bernuansa remang. Gila! Ini benar-benar kelewatan. Malam ini aku harus bisa menjaga tubuhku dari minuman beralkohol. Kalau tidak, kejadian dua tahun silam pasti terulang lagi.
Lorong demi lorong kami telusuri. Ternyata, kesan elegan dan mewah itu hanya terlihat di permukaaannya saja. Semakin lama aku malah tak bisa membedakan apakah ini klub hebat yang sering digaungkan namanya itu, atau sebuah hotel murahan tempat orang berbagi dosa.
Langkah kami terhenti tepat di satu ruangan berpintu dengan tanda Private Room. Dan akhirnya di ruangan inilah kami akan tinggal selama beberapa jam ke depan. Kami mulai merebahkan diri pada sofa besar yang tersedia di sana. Mereka nampak terbiasa sekali berada di ruangan ini.
Menahan sedikit kesal, aku hanya bisa menatap satu per satu kawanku. Mereka memperlihatkan satu mimik yang sama. “Apa yang sedang kalian rencanakan?” sekedar melepas gelisah, kuraih sebotol air mineral lalu meneguknya.
Chandra tersenyum nakal. “Kami telah menyewa empat kucing untuk ikut bersenang-senang di sini.”
“Uhuk! Uhuk!” sontak aku tersedak. “Hei! Kalian ambil tiga saja. Aku tidak mau ikut!” segera aku beranjak.
“Ow... ow... sabar, Brother…” Dimas menenangkanku. “Take it easy, oke? Tenang, kejadian waktu itu aku jamin tidak akan terulang lagi, I promise!” lelaki itu mengangkat jemarinya.
Aku hanya bisa terkulai dan kembali menjatuhkan diri ke sofa. Kalau Dimas sudah bicara, rasanya aku tak sanggup untuk menyanggahnya lagi.
“Awas kalau sampai kejadian itu terulang lagi, aku takkan memaafkan kalian!” kataku berultimatum. Bukannya ditanggapi serius, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Lagi-lagi aku hanya bisa duduk pasrah. Sumpah, aku tidak setuju dengan ini. Seorang lelaki asing duduk merayuku? Bukan tidak mungkin mereka bertelanjang. Gila! ini benar-benar gila!
Pintu ruangan berderit pertanda seseorang membuka pintu dari luar. Damn! Inilah puncak kegelisahanku saat nampak empat lelaki ganteng beruntun memasuki Private Room. Aku hanya bisa menahan napas sejenak.
Empat orang lelaki tampan itu berkemeja hitam dengan kancing yang terbuka hingga dada. Not bad, pikirku. Mereka berjejer seperti peserta kontes kecantikan di malam final dan kami adalah juri yang akan menilai makhluk-makhluk tampan itu. Lelaki pertama berambut cepak dengan alis tebal yang menambah indah bola matanya. Lelaki kedua memiliki postur tubuh yang tinggi dan badan yang tidak begitu kekar, namun tetap terlihat seksi—apalagi saat tersenyum memamerkan lesung di pipi kanannya. Lelaki ketiga berkulit gelap, kesan maskulin nampak dari tato bergambar singa di lengan kanannya. Namun yang membuatku tertarik tentu lelaki terakhir. Dia berparas oriental dengan kulit bersih dan tatanan rambut Korean style, sangat manis. Tubuhnya yang tinggi mengingatkanku akan seseorang di masa lampau, seperti… Nathanael Prayudha!
Aku membelalakkan mata saat nama itu melintas di kepalaku. Tidak mungkin! Bagaimana bisa Nael terdampar di tempat ini? Aku tahu dia straight[3]. Salah satu dari sekian banyak homophobia di Indonesia. Tapi itu, jelas sekali sepasang bola mata cokelat yang khas persis seperti milik Nael.
Teman-temanku menunjuk pada satu lelaki pilihannya. Aku pun melakukan hal yang sama. Kuberanikan diri telunjukku mengarah padanya. Lelaki yang mirip Nael itu menyunggingkan bibir saat sadar aku memilihnya. Tak lama dia menghampiri. Sungguh, aku semakin gelisah dibuatnya. Sekali lagi kuperhatikan dia lebih seksama.
“Nael…” lirihku.
Lelaki itu mengernyitkan dahi. “Apa? Kamu bilang apa barusan?” wajahnya mendekatiku.
“Nael! Kamu Nael!” kataku setengah berteriak. Membuat para sahabatku menoleh ke arah kami.
Dia mendongak. Sempat terdiam sesaat lalu tersenyum kemudian. “Nael? Siapa dia? Kawanmu?”
“Bukan! Kamu Nael!” tuduhku.
Lelaki itu tertawa. “Kamu salah, Sayang. Aku Heaven,” ujarnya seraya menjabat tanganku.
Yang kuingat Nael memiliki tanda lahir di jemari tangannya. Saat itu pula aku menarik lengan kanannya, memaksa untuk mencari tahu kebenarannya. Lelaki bernama Heaven itu sempat mengelak, namun aku tak peduli. Benar, tanda itu kudapati di sana! Aku menatap nanar wajah itu. Ini benar-benar Nael! Sahabatku!
Kulihat dia memahami tatapan gelisahku. Wajahnya mengisyaratkanku untuk tenang. Baiklah aku mengerti. Akan kucari waktu yang tepat untuk bicara dengannya. Saat ini kuanggap saja dia orang lain.
Namun rupanya itu sama sekali tak bisa meredakan kegundahanku. Rasanya ingin sekali berteriak dan memaksanya mengaku kalau dia adalah Nael.
“Heaven, bisa kita bicara di luar?” aku berbisik ke telinganya.
“Tentu,” jawabnya ragu.
Ketiga sahabatku menatap heran saat kami beranjak keluar dari ruangan. Aku tersenyum memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja lewat kedua tanganku. “Aku ingin menghirup udara segar,” alasanku.
Sepanjang perjalanan aku berusaha tenang, meski kehadiran lelaki itu di sampingku membuat sesak di dada.
Baiklah, kami berada di taman sekarang. Udara segar Kota Bandung di malam hari cukup membuat gelisahku sedikit mereda. Sekali lagi kutatap dalam lelaki di hadapanku ini. Mencoba menampik bahwa dia bukan seseorang yang kukenal, meski kerap tak pernah berhasil.
Dia menyalakan Marlboro lalu mengisapnya. “Apa kabar, Az?”
Dhuar!
Serasa petir menghantam kepalaku. Jadi benar firasatku? Dia benar-benar Nael! “Nael… ini benar kamu?” meski sejak awal yakin bahwa dia kawanku, tetap saja aku mempertanyakan kebenaran itu.
Lelaki itu tersenyum getir. “Tidak sangka aku jadi kucing dan melayani teman sendiri. Parah,” gumamnya mengasihani diri sendiri.
Aku tak mampu berkata-kata. Kucoba mencari kalimat yang tepat, berharap tidak menyinggung perasaannya. Yang ada aku malah terjebak dalam kebisuan!
“Bisa kita kembali ke dalam?” Nael malah menjatuhkan puntung rokok yang masih panjang itu lalu menginjaknya. “Dingin sekali di sini.”
Tubuhku masih mematung. Sial! Dia bersikap dingin, seolah tak mengenalku sama sekali.
Dalam perjalanan kembali ke Private Room. Nael bergumam, “Anggap kita tidak kenal, ya. Aku tidak mau merusak reputasimu,” lagi-lagi aku tak bereaksi, hanya membuntutinya dari belakang.
Nael dengan jiwa yang lain merasuk ke dalam tubuh itu. Entah apa yang terjadi selama sepuluh tahun berlalu. Sungguh! Sesaat raga ini kaku tak mampu melangkah. Sementara bayangan tubuhnya semakin jauh dari pandangan mata, seiring ribuan tanya berkelebat di dalam hati, serta berusaha meyakinkan diri bahwa aku sedang bermimpi.
[1] People Like Us adalah julukan bagi mereka yang menyembunyikan identitasnya sebagai Homoseksual. Dan berlaku seperti seorang Heteroseksual di kehidupan sehari-hari.
[2] Pelacur Gay
[3] Normal/ heteroseksual
Other Stories
Menantimu
Sejak dikhianati Beno, ia memilih jalan kelam menjajakan tubuh demi pelarian. Hingga Raka ...
Melodi Nada
Dua gadis kakak beradik dari sebuah desa yang memiliki mimpi tampil dipanggung impian. Mer ...
Dream Analyst
Dream Analyst. Begitu teman-temannya menyebut dirinya. Frisky dapat menganalisa mimpi sese ...
Penulis Misterius
Risma, 24 tahun, masih sulit move on dari mantan kekasihnya, Bastian, yang kini dijodohkan ...
Kau Bisa Bahagia
Airin Septiana terlahir sebagai wanita penyandang disabilitas. Meski keadaannya demikian, ...
Rahasia Ikal
Ikal, bocah yang lahir dari sebuah keluarga nelayan miskin di pesisir Pulau Bangka. Ia tin ...