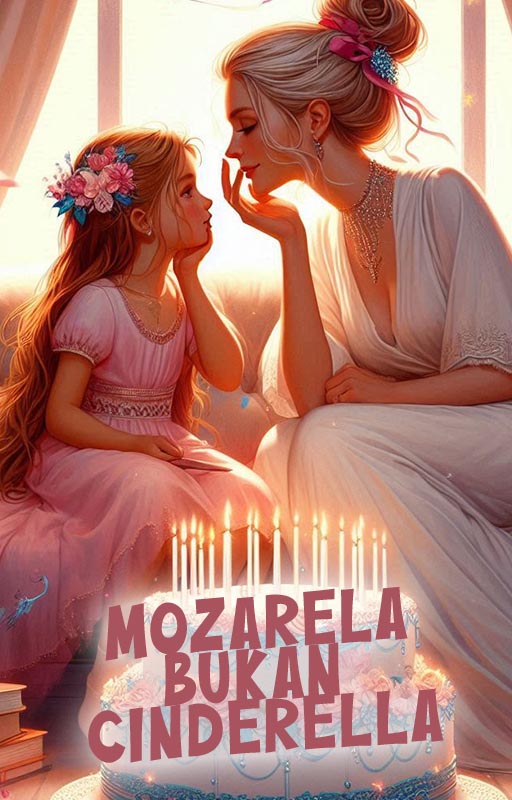Warung Kopi Haji Darsa
Pernahkah kamu masuk ke sebuah warung kopi yang kelihatannya kecil biasa saja tapi anehnya selalu ramai dan bikin betah orang berlama-lama di dalamnya. Kalau belum, mari saya ajak ke satu tempat di Garut tahun 1998, tepat di alun-alun kota. Di sanalah berdiri sebuah bangunan sederhana dari papan kayu agak usang, catnya sudah terkelupas di beberapa bagian, tapi jangan salah, papan itu penuh sejarah. Di depan warung ada tulisan tangan seadanya Warung Kopi Haji Darsa, hurufnya miring-miring, kadang tak terbaca jelas, tapi orang-orang tidak peduli, mereka sudah tahu kalau hanya di sini kopi bisa jadi obrolan, obrolan bisa jadi tawa, tawa bisa berubah jadi pertengkaran, dan pertengkaran pun kadang berakhir dengan persaudaraan.
Warung ini adalah jantung kecil di Garut, denyutnya terasa dari pagi sampai malam. Kursinya terbuat dari kayu panjang yang sudah miring ke sana-sini, meja bolong di ujungnya, tapi entah kenapa makanan dan minuman terasa lebih nikmat kalau disantap di sini. Mungkin karena suasana. Mungkin karena cerita. Atau mungkin karena ada satu gadis muda bernama Rahayu, anak pemilik warung yang lincah, cekatan, dan selalu menyajikan senyuman lebih manis daripada gula pasir. Saya yakin kamu nanti juga akan jatuh hati padanya, tapi sabar dulu, jangan buru-buru.
Pagi itu seperti biasa warung mulai ramai. Para nelayan baru pulang dari sungai dan danau, wajah mereka hitam terbakar matahari tapi mulut tidak berhenti berceloteh. Seorang pedagang pasar menaruh karung bawang di pojok warung, lalu ikut nimbrung. Ustaz Karna duduk di kursi kayu, membuka kitab kecilnya tapi bukannya membaca, ia malah ikut menimpali lelucon tentang harga cabe yang semakin melonjak.
“Kalau cabe naik segini terus, nanti orang Garut bukan makan sambel tapi makan doa,” celetuk seorang nelayan, lalu tawa meledak.
Rahayu hanya geleng-geleng kepala, sambil menuangkan kopi hitam ke gelas kaca tipis. Uap panasnya naik perlahan, membuat aroma kopi robusta Garut menyeruak. Ia tahu obrolan itu akan terus panjang. Dan benar saja, tak lama kemudian perdebatan berubah arah. Dari cabe ke beras, dari beras ke bensin, dari bensin ke krisis yang katanya sedang melanda seluruh negeri.
“Ini semua gara-gara pemerintah,” ujar seorang mahasiswa perantau yang baru duduk. Wajahnya masih muda, rambut agak gondrong, kacamatanya tebal. Ia menepuk meja pelan, mencoba menahan emosi.
Suasana seketika berubah. Dari tawa menjadi hening beberapa detik, sebelum pedagang pasar menimpali dengan suara keras, “Eh, jangan ngomong begitu, nanti bisa bahaya. Di sini banyak telinga aparat.”
Nah, kamu lihat kan. Warung ini bukan cuma soal kopi. Ini juga soal nyawa. Di tahun itu, orang bicara politik bisa berarti membuka pintu ke masalah besar. Tapi begitulah, justru di warung kopi orang jadi berani. Mungkin karena rasa pahit kopi memberi keberanian yang manis.
Rahayu mengamati semua itu sambil tersenyum tipis. Ia tidak terlalu paham dunia politik, tapi ia paham kalau orang-orang di sini butuh tempat untuk berbicara. Dan warung bapaknya, Haji Darsa, sudah jadi rumah bagi semua suara, entah itu suara tawa, suara doa, atau suara marah.
Haji Darsa sendiri pagi itu duduk di bangku paling pojok, wajahnya serius seperti biasa. Kumis tebal, peci hitam, mata tajam. Ia jarang bicara, tapi sekali bicara semua orang diam. Ia percaya warungnya harus tetap aman, tidak boleh ada keributan terlalu besar, tapi ia juga tahu kalau anak muda zaman sekarang susah dibendung semangatnya.
Kamu mungkin bertanya, lalu di mana romance-nya. Jangan khawatir, sebentar lagi kau akan lihat. Sebab hari itu bukan hari biasa. Hari itu akan datang seorang tamu tak terduga yang akan mengubah segalanya.
Angin siang berhembus, debu jalan beterbangan, dan dari kejauhan terlihat seorang pemuda berjalan tergesa. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keringat, matanya liar seperti sedang dikejar sesuatu. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang mengikutinya, lalu masuk begitu saja ke warung Haji Darsa.
“Assalamualaikum,” katanya cepat, hampir terengah.
Semua mata menoleh. Rahayu yang sedang menuang teh manis hampir menjatuhkan gelas. Pemuda itu berbeda dengan pelanggan biasa. Caranya duduk, caranya menatap, ada sesuatu yang membuat jantung Rahayu berdegup lebih kencang. Kamu juga pasti bisa merasakannya, bukan.
“Waalaikum salam,” jawab Haji Darsa dengan suara berat. “Dari mana, Nak.”
Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu memesan kopi hitam. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba terlihat tenang.
“Dari Bandung, Pak,” ujarnya singkat.
Nah, sekarang kau tahu. Bandung di tahun 1998 bukan kota biasa. Itu pusat gelombang mahasiswa yang menuntut reformasi. Jadi jelas, pemuda ini bukan sekadar perantau biasa. Ia membawa cerita, membawa bahaya, dan juga membawa cinta, meski ia sendiri belum sadar.
Rahayu meletakkan kopi di mejanya, mata mereka bertemu sepersekian detik. Ada yang bergetar, ada yang sulit dijelaskan. Apakah itu cinta pada pandangan pertama. Mungkin. Atau mungkin hanya rasa penasaran seorang gadis desa pada sosok asing yang penuh misteri.
Lalu kamu mungkin tertawa, kenapa semua ini terdengar seperti drama sinetron. Ya biarkan saja, toh hidup di tahun 98 memang lebih dramatis daripada sinetron mana pun. Orang bisa tertawa karena ayam kampung tiba-tiba masuk warung, tapi juga bisa menangis karena mendengar kabar mahasiswa ditembak di Jakarta. Semua bercampur.
Dan di warung kopi Haji Darsa, semua cerita itu menemukan tempatnya.
Hari itu tawa masih ada, meski lebih hati-hati. Obrolan tetap berlanjut, meski ada bayang-bayang ketakutan. Tapi di sudut warung, seorang gadis penjual kopi dan seorang mahasiswa perantau mulai menenun benang halus yang kelak akan berubah menjadi kisah besar.
Kamu yang membaca ini, mungkin ikut tersenyum, mungkin juga ikut tegang. Jangan khawatir, perjalanan masih panjang. Kopimu belum habis, ceritanya pun baru dimulai.
Warung ini adalah jantung kecil di Garut, denyutnya terasa dari pagi sampai malam. Kursinya terbuat dari kayu panjang yang sudah miring ke sana-sini, meja bolong di ujungnya, tapi entah kenapa makanan dan minuman terasa lebih nikmat kalau disantap di sini. Mungkin karena suasana. Mungkin karena cerita. Atau mungkin karena ada satu gadis muda bernama Rahayu, anak pemilik warung yang lincah, cekatan, dan selalu menyajikan senyuman lebih manis daripada gula pasir. Saya yakin kamu nanti juga akan jatuh hati padanya, tapi sabar dulu, jangan buru-buru.
Pagi itu seperti biasa warung mulai ramai. Para nelayan baru pulang dari sungai dan danau, wajah mereka hitam terbakar matahari tapi mulut tidak berhenti berceloteh. Seorang pedagang pasar menaruh karung bawang di pojok warung, lalu ikut nimbrung. Ustaz Karna duduk di kursi kayu, membuka kitab kecilnya tapi bukannya membaca, ia malah ikut menimpali lelucon tentang harga cabe yang semakin melonjak.
“Kalau cabe naik segini terus, nanti orang Garut bukan makan sambel tapi makan doa,” celetuk seorang nelayan, lalu tawa meledak.
Rahayu hanya geleng-geleng kepala, sambil menuangkan kopi hitam ke gelas kaca tipis. Uap panasnya naik perlahan, membuat aroma kopi robusta Garut menyeruak. Ia tahu obrolan itu akan terus panjang. Dan benar saja, tak lama kemudian perdebatan berubah arah. Dari cabe ke beras, dari beras ke bensin, dari bensin ke krisis yang katanya sedang melanda seluruh negeri.
“Ini semua gara-gara pemerintah,” ujar seorang mahasiswa perantau yang baru duduk. Wajahnya masih muda, rambut agak gondrong, kacamatanya tebal. Ia menepuk meja pelan, mencoba menahan emosi.
Suasana seketika berubah. Dari tawa menjadi hening beberapa detik, sebelum pedagang pasar menimpali dengan suara keras, “Eh, jangan ngomong begitu, nanti bisa bahaya. Di sini banyak telinga aparat.”
Nah, kamu lihat kan. Warung ini bukan cuma soal kopi. Ini juga soal nyawa. Di tahun itu, orang bicara politik bisa berarti membuka pintu ke masalah besar. Tapi begitulah, justru di warung kopi orang jadi berani. Mungkin karena rasa pahit kopi memberi keberanian yang manis.
Rahayu mengamati semua itu sambil tersenyum tipis. Ia tidak terlalu paham dunia politik, tapi ia paham kalau orang-orang di sini butuh tempat untuk berbicara. Dan warung bapaknya, Haji Darsa, sudah jadi rumah bagi semua suara, entah itu suara tawa, suara doa, atau suara marah.
Haji Darsa sendiri pagi itu duduk di bangku paling pojok, wajahnya serius seperti biasa. Kumis tebal, peci hitam, mata tajam. Ia jarang bicara, tapi sekali bicara semua orang diam. Ia percaya warungnya harus tetap aman, tidak boleh ada keributan terlalu besar, tapi ia juga tahu kalau anak muda zaman sekarang susah dibendung semangatnya.
Kamu mungkin bertanya, lalu di mana romance-nya. Jangan khawatir, sebentar lagi kau akan lihat. Sebab hari itu bukan hari biasa. Hari itu akan datang seorang tamu tak terduga yang akan mengubah segalanya.
Angin siang berhembus, debu jalan beterbangan, dan dari kejauhan terlihat seorang pemuda berjalan tergesa. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keringat, matanya liar seperti sedang dikejar sesuatu. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang mengikutinya, lalu masuk begitu saja ke warung Haji Darsa.
“Assalamualaikum,” katanya cepat, hampir terengah.
Semua mata menoleh. Rahayu yang sedang menuang teh manis hampir menjatuhkan gelas. Pemuda itu berbeda dengan pelanggan biasa. Caranya duduk, caranya menatap, ada sesuatu yang membuat jantung Rahayu berdegup lebih kencang. Kamu juga pasti bisa merasakannya, bukan.
“Waalaikum salam,” jawab Haji Darsa dengan suara berat. “Dari mana, Nak.”
Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu memesan kopi hitam. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba terlihat tenang.
“Dari Bandung, Pak,” ujarnya singkat.
Nah, sekarang kau tahu. Bandung di tahun 1998 bukan kota biasa. Itu pusat gelombang mahasiswa yang menuntut reformasi. Jadi jelas, pemuda ini bukan sekadar perantau biasa. Ia membawa cerita, membawa bahaya, dan juga membawa cinta, meski ia sendiri belum sadar.
Rahayu meletakkan kopi di mejanya, mata mereka bertemu sepersekian detik. Ada yang bergetar, ada yang sulit dijelaskan. Apakah itu cinta pada pandangan pertama. Mungkin. Atau mungkin hanya rasa penasaran seorang gadis desa pada sosok asing yang penuh misteri.
Lalu kamu mungkin tertawa, kenapa semua ini terdengar seperti drama sinetron. Ya biarkan saja, toh hidup di tahun 98 memang lebih dramatis daripada sinetron mana pun. Orang bisa tertawa karena ayam kampung tiba-tiba masuk warung, tapi juga bisa menangis karena mendengar kabar mahasiswa ditembak di Jakarta. Semua bercampur.
Dan di warung kopi Haji Darsa, semua cerita itu menemukan tempatnya.
Hari itu tawa masih ada, meski lebih hati-hati. Obrolan tetap berlanjut, meski ada bayang-bayang ketakutan. Tapi di sudut warung, seorang gadis penjual kopi dan seorang mahasiswa perantau mulai menenun benang halus yang kelak akan berubah menjadi kisah besar.
Kamu yang membaca ini, mungkin ikut tersenyum, mungkin juga ikut tegang. Jangan khawatir, perjalanan masih panjang. Kopimu belum habis, ceritanya pun baru dimulai.
Other Stories
Sinopsis
hdhjjfdseetyyygfd ...
Mozarella Bukan Cinderella
Moza tinggal di Panti Asuhan Muara Kasih Ibu sejak ia pertama kali melihat dunia. Seseo ...
Kacamata Kematian
Arsyil Langit Ramadhan lagi naksir berat sama cewek bernama Arshita Bintang Oktarina. Ia b ...
Cahaya Menembus Semesta
Manusia tidak akan mampu hidup sendiri, mereka membutuhkan teman. Sebab dengan pertemanan, ...
Aparar Keparat
aparat memang keparat ...
Dante Fairy Tale
“Dante! Ayo bangun, Sayang. Kamu bisa terlambat ke sekolah!” kata seorang wanita gemu ...