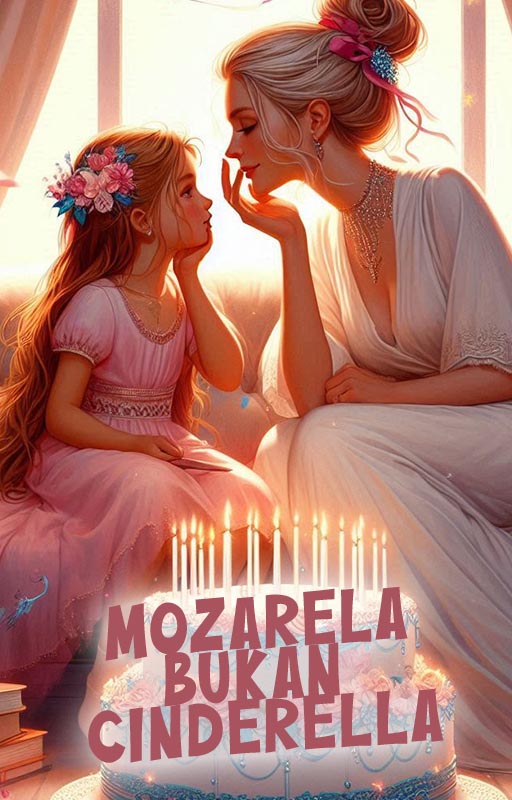Mahasiswa Dari Bandung
Kalau kamu pikir hidup di warung kopi hanya berputar soal harga cabe yang naik turun dan senyum Rahayu yang bikin semua orang betah nongkrong, maka bersiaplah, karena cerita kita akan sedikit lebih panas. Jangan salahkan saya kalau setelah ini degup jantungmu ikut berlari, sebab seorang tokoh baru akan masuk ke dalam panggung dan mengubah segalanya. Namanya Arman, mahasiswa dari Bandung yang tidak sedang jalan jalan santai melainkan kabur dari kejaran aparat. Ya kamu tidak salah dengar, kabur.
Hari itu sore langit Garut agak muram, awan menggantung seperti wajah orang yang sedang menahan amarah. Jalanan alun alun masih ramai dengan pedagang asongan, tukang becak, dan anak anak kecil yang main bola di tanah lapang. Dari kejauhan tampak seorang pemuda berjalan cepat dengan ransel lusuh di punggung, wajahnya berkeringat, matanya waspada seperti sedang mencari tempat aman. Itulah Arman. Kalau kamu sempat lihat lebih dekat, bajunya masih penuh debu, sepatunya sudah aus, dan nafasnya memburu seakan baru saja berlari jauh.
Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, khawatir ada yang mengikuti. Dan benar saja, dua orang berseragam tampak berpatroli di ujung jalan. Bukan kebetulan. Arman memang sedang diburu, karena ia baru saja ikut demo besar di Bandung, meneriakkan tuntutan reformasi bersama ribuan mahasiswa lain. Ada gas air mata, ada pentungan, ada teriakan massa yang tumpah ke jalan. Entah bagaimana ia berhasil lolos, naik angkot ke terminal, lalu menumpang truk sayur hingga akhirnya sampai ke Garut.
Kamu mungkin bertanya kenapa Garut, kenapa tidak ke tempat lain yang lebih jauh. Jawabannya sederhana, karena Arman pernah mendengar cerita tentang warung kopi kecil di dekat alun alun yang ramah pada siapa saja. Warung itu katanya selalu buka untuk orang lapar, untuk orang yang butuh tempat singgah. Dan di situlah kaki Arman berhenti.
Begitu tirai bambu warung tersibak, semua mata sejenak menoleh. Bayangkan suasananya, nelayan sedang menepuk meja karena kalah debat soal harga garam, pedagang pasar sedang tertawa karena cerita receh, Ustaz Karna sedang menyeruput kopi sambil geleng kepala melihat kelakuan jamaahnya, dan Rahayu sibuk membersihkan meja. Tiba tiba masuk seorang pemuda asing dengan wajah tegang. Kamu pasti bisa membayangkan hening singkat yang tercipta.
Arman menunduk sebentar, mencoba menyembunyikan kegugupannya, lalu duduk di pojok dekat jendela. Dari ranselnya ia mengeluarkan buku catatan yang sudah kusut, pura pura menulis padahal hatinya berdebar takut. Rahayu menghampiri dengan tatapan ingin tahu, suaranya lembut seperti biasanya.
“Mau pesan apa Kang”
Pertanyaan sederhana, tapi bagi Arman itu terdengar seperti pelarian yang menemukan pelabuhan. Ia tersenyum tipis, “Kopi hitam aja Neng”
Ah lihatlah, sudah mulai ada percikan. Kamu tahu kan bagaimana biasanya dalam cerita begini, satu cangkir kopi bisa jadi awal dari seribu cerita lain. Dan benar saja, ketika Rahayu meletakkan gelas kopi panas di mejanya, jari mereka hampir bersentuhan. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuat wajah Rahayu memerah, dan Arman lupa sejenak kalau ia sedang diburu.
Sementara itu pelanggan lain mulai bertanya tanya siapa pemuda itu. Nelayan berbisik bisik, pedagang pasar mencoba menebak. “Pasti anak kuliahan, lihat saja gaya rambutnya,” kata seorang bapak. “Atau jangan jangan intel,” timpal yang lain. Kamu pasti tertawa kalau mendengar gosip warung yang secepat itu beredar, padahal orangnya baru duduk lima menit.
Tapi Arman tidak peduli, ia hanya butuh tempat aman untuk berpikir. Dari jendela ia melihat aparat masih berkeliling. Dalam hati ia berdoa jangan sampai mereka masuk.
Sekarang biarkan saya ceritakan sedikit tentang Arman supaya kamu lebih paham. Ia lahir dari keluarga sederhana di Bandung, ayahnya sopir angkot, ibunya pedagang sayur di pasar. Ia kuliah di Fakultas Hukum, dan sejak awal sudah aktif di organisasi mahasiswa. Ia percaya bahwa negeri ini harus berubah, bahwa suara rakyat kecil tidak boleh terus dibungkam. Karena itu ia ikut turun ke jalan, berorasi, menulis pamflet, dan sekarang hasilnya, ia jadi buronan.
Lucu bukan, orang yang berteriak untuk keadilan malah dikejar, sementara orang yang merampas hak rakyat duduk tenang di kursi empuk. Tapi begitulah realita tahun itu, dan kamu tahu pasti betapa panasnya suasana 1998.
Kembali ke warung. Ketika suasana mulai kembali ramai, tiba tiba pintu warung terbuka keras. Dua aparat berseragam masuk, wajah mereka kaku, langkah mereka berat. Semua orang langsung diam. Kamu pasti bisa merasakan hawa tegang itu, seperti ada pisau yang menggantung di udara.
Aparat itu menatap sekeliling, lalu bertanya keras, “Ada yang lihat mahasiswa dari Bandung masuk ke sini”
Jantung Arman hampir melompat keluar. Ia menunduk makin dalam, tangannya menggenggam erat gelas kopi. Rahayu melirik sekilas, dan kamu tahu apa yang ia lakukan. Dengan cepat ia melangkah ke dapur, mengambil piring berisi gorengan, lalu berjalan ke meja Arman sambil pura pura menaruhnya.
“Ini Kang, tambahan gorengan biar kopinya tidak kesepian,” katanya dengan senyum seolah tidak terjadi apa apa.
Kamu lihat kepintaran gadis ini. Dengan begitu perhatian orang teralihkan, aparat tidak langsung curiga. Haji Darsa pun muncul dari balik dapur, wajahnya datar tapi suaranya tegas, “Di sini cuma ada orang kampung yang mau ngopi Pak, kalau cari mahasiswa mungkin lebih baik ke kampus.”
Aparat saling pandang, lalu akhirnya pergi, meski tatapan curiga masih tersisa. Begitu mereka keluar, semua orang menghela nafas lega. Ada yang menepuk meja, ada yang tertawa canggung, ada yang langsung meminum kopi yang tadi dibiarkan dingin.
Arman menatap Rahayu penuh terima kasih. “Neng, kalau bukan karena kamu mungkin saya sudah ditangkap,” bisiknya pelan.
Rahayu hanya tersenyum, “Di warung ini semua orang tamu, Kang. Selama kamu niatnya baik, kamu aman di sini.”
Dan kamu pasti tahu, kalimat sederhana itu terdengar seperti janji yang lebih dari sekadar kata kata. Ada sesuatu yang tumbuh di udara, sesuatu yang kita sebut harapan.
Malam itu warung masih ramai, tapi di pojok meja ada dua hati yang mulai bergetar. Arman dengan idealismenya, Rahayu dengan kelembutannya. Kamu mungkin ingin berteriak hati hati, dunia di luar sana keras, aparat bisa datang kapan saja, cinta di masa genting bisa melukai. Tapi siapa yang bisa mengatur perasaan.
Begitulah, di sebuah warung kopi kecil di Garut, seorang mahasiswa dari Bandung menemukan tempat singgah, dan seorang gadis desa menemukan alasan baru untuk menulis puisi.
Dan kamu yang membaca ini mungkin diam diam berharap semoga mereka selamat, semoga mereka kuat. Karena cerita ini baru saja mulai memanas, dan kita semua tahu badai besar sedang menunggu di depan.
Hari itu sore langit Garut agak muram, awan menggantung seperti wajah orang yang sedang menahan amarah. Jalanan alun alun masih ramai dengan pedagang asongan, tukang becak, dan anak anak kecil yang main bola di tanah lapang. Dari kejauhan tampak seorang pemuda berjalan cepat dengan ransel lusuh di punggung, wajahnya berkeringat, matanya waspada seperti sedang mencari tempat aman. Itulah Arman. Kalau kamu sempat lihat lebih dekat, bajunya masih penuh debu, sepatunya sudah aus, dan nafasnya memburu seakan baru saja berlari jauh.
Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, khawatir ada yang mengikuti. Dan benar saja, dua orang berseragam tampak berpatroli di ujung jalan. Bukan kebetulan. Arman memang sedang diburu, karena ia baru saja ikut demo besar di Bandung, meneriakkan tuntutan reformasi bersama ribuan mahasiswa lain. Ada gas air mata, ada pentungan, ada teriakan massa yang tumpah ke jalan. Entah bagaimana ia berhasil lolos, naik angkot ke terminal, lalu menumpang truk sayur hingga akhirnya sampai ke Garut.
Kamu mungkin bertanya kenapa Garut, kenapa tidak ke tempat lain yang lebih jauh. Jawabannya sederhana, karena Arman pernah mendengar cerita tentang warung kopi kecil di dekat alun alun yang ramah pada siapa saja. Warung itu katanya selalu buka untuk orang lapar, untuk orang yang butuh tempat singgah. Dan di situlah kaki Arman berhenti.
Begitu tirai bambu warung tersibak, semua mata sejenak menoleh. Bayangkan suasananya, nelayan sedang menepuk meja karena kalah debat soal harga garam, pedagang pasar sedang tertawa karena cerita receh, Ustaz Karna sedang menyeruput kopi sambil geleng kepala melihat kelakuan jamaahnya, dan Rahayu sibuk membersihkan meja. Tiba tiba masuk seorang pemuda asing dengan wajah tegang. Kamu pasti bisa membayangkan hening singkat yang tercipta.
Arman menunduk sebentar, mencoba menyembunyikan kegugupannya, lalu duduk di pojok dekat jendela. Dari ranselnya ia mengeluarkan buku catatan yang sudah kusut, pura pura menulis padahal hatinya berdebar takut. Rahayu menghampiri dengan tatapan ingin tahu, suaranya lembut seperti biasanya.
“Mau pesan apa Kang”
Pertanyaan sederhana, tapi bagi Arman itu terdengar seperti pelarian yang menemukan pelabuhan. Ia tersenyum tipis, “Kopi hitam aja Neng”
Ah lihatlah, sudah mulai ada percikan. Kamu tahu kan bagaimana biasanya dalam cerita begini, satu cangkir kopi bisa jadi awal dari seribu cerita lain. Dan benar saja, ketika Rahayu meletakkan gelas kopi panas di mejanya, jari mereka hampir bersentuhan. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuat wajah Rahayu memerah, dan Arman lupa sejenak kalau ia sedang diburu.
Sementara itu pelanggan lain mulai bertanya tanya siapa pemuda itu. Nelayan berbisik bisik, pedagang pasar mencoba menebak. “Pasti anak kuliahan, lihat saja gaya rambutnya,” kata seorang bapak. “Atau jangan jangan intel,” timpal yang lain. Kamu pasti tertawa kalau mendengar gosip warung yang secepat itu beredar, padahal orangnya baru duduk lima menit.
Tapi Arman tidak peduli, ia hanya butuh tempat aman untuk berpikir. Dari jendela ia melihat aparat masih berkeliling. Dalam hati ia berdoa jangan sampai mereka masuk.
Sekarang biarkan saya ceritakan sedikit tentang Arman supaya kamu lebih paham. Ia lahir dari keluarga sederhana di Bandung, ayahnya sopir angkot, ibunya pedagang sayur di pasar. Ia kuliah di Fakultas Hukum, dan sejak awal sudah aktif di organisasi mahasiswa. Ia percaya bahwa negeri ini harus berubah, bahwa suara rakyat kecil tidak boleh terus dibungkam. Karena itu ia ikut turun ke jalan, berorasi, menulis pamflet, dan sekarang hasilnya, ia jadi buronan.
Lucu bukan, orang yang berteriak untuk keadilan malah dikejar, sementara orang yang merampas hak rakyat duduk tenang di kursi empuk. Tapi begitulah realita tahun itu, dan kamu tahu pasti betapa panasnya suasana 1998.
Kembali ke warung. Ketika suasana mulai kembali ramai, tiba tiba pintu warung terbuka keras. Dua aparat berseragam masuk, wajah mereka kaku, langkah mereka berat. Semua orang langsung diam. Kamu pasti bisa merasakan hawa tegang itu, seperti ada pisau yang menggantung di udara.
Aparat itu menatap sekeliling, lalu bertanya keras, “Ada yang lihat mahasiswa dari Bandung masuk ke sini”
Jantung Arman hampir melompat keluar. Ia menunduk makin dalam, tangannya menggenggam erat gelas kopi. Rahayu melirik sekilas, dan kamu tahu apa yang ia lakukan. Dengan cepat ia melangkah ke dapur, mengambil piring berisi gorengan, lalu berjalan ke meja Arman sambil pura pura menaruhnya.
“Ini Kang, tambahan gorengan biar kopinya tidak kesepian,” katanya dengan senyum seolah tidak terjadi apa apa.
Kamu lihat kepintaran gadis ini. Dengan begitu perhatian orang teralihkan, aparat tidak langsung curiga. Haji Darsa pun muncul dari balik dapur, wajahnya datar tapi suaranya tegas, “Di sini cuma ada orang kampung yang mau ngopi Pak, kalau cari mahasiswa mungkin lebih baik ke kampus.”
Aparat saling pandang, lalu akhirnya pergi, meski tatapan curiga masih tersisa. Begitu mereka keluar, semua orang menghela nafas lega. Ada yang menepuk meja, ada yang tertawa canggung, ada yang langsung meminum kopi yang tadi dibiarkan dingin.
Arman menatap Rahayu penuh terima kasih. “Neng, kalau bukan karena kamu mungkin saya sudah ditangkap,” bisiknya pelan.
Rahayu hanya tersenyum, “Di warung ini semua orang tamu, Kang. Selama kamu niatnya baik, kamu aman di sini.”
Dan kamu pasti tahu, kalimat sederhana itu terdengar seperti janji yang lebih dari sekadar kata kata. Ada sesuatu yang tumbuh di udara, sesuatu yang kita sebut harapan.
Malam itu warung masih ramai, tapi di pojok meja ada dua hati yang mulai bergetar. Arman dengan idealismenya, Rahayu dengan kelembutannya. Kamu mungkin ingin berteriak hati hati, dunia di luar sana keras, aparat bisa datang kapan saja, cinta di masa genting bisa melukai. Tapi siapa yang bisa mengatur perasaan.
Begitulah, di sebuah warung kopi kecil di Garut, seorang mahasiswa dari Bandung menemukan tempat singgah, dan seorang gadis desa menemukan alasan baru untuk menulis puisi.
Dan kamu yang membaca ini mungkin diam diam berharap semoga mereka selamat, semoga mereka kuat. Karena cerita ini baru saja mulai memanas, dan kita semua tahu badai besar sedang menunggu di depan.
Other Stories
Mozarella Bukan Cinderella
Moza tinggal di Panti Asuhan Muara Kasih Ibu sejak ia pertama kali melihat dunia. Seseo ...
Kepentok Kacung Kampret
Renata bagai langit yang sulit digapai karena kekayaan dan kehormatan yang melingkupi diri ...
Keikhlasan Cinta
6 tahun Hasrul pergi dari keluarganya, setelah dia kembali dia dipertemukan kembali dengan ...
Sonata Laut
Di antara riak ombak dan bisikan angin, musik lahir dari kedalaman laut. Piano yang terdam ...
Luka
LUKA Tiga sahabat. Tiga jalan hidup. Tiga luka yang tak kasatmata. Moana, pejuang garis ...
Teka-teki Surat Merah
Seorang gadis pekerja klub malam ditemukan tewas dalam kantong plastik di taman kota, meng ...