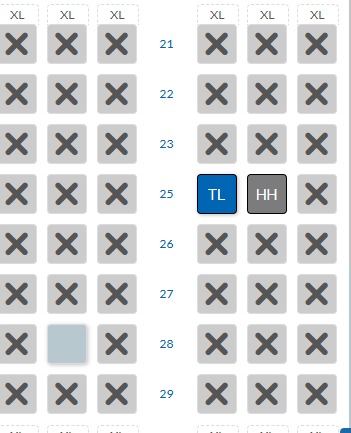Bab 1 Pulang Atau Dipulangkan?
Bab 1
Pulang atau Dipulangkan?
1985.
Namaku Handoyo. Umur? 35 tahun. Status? Masih single, tapi bukan karena kurang usaha—lebih karena dunia belum siap.
Beberapa hari lalu aku lagi santai di sebuah flat sempit di Hamburg, Jerman. Hidupku damai, penuh kebebasan. Aku bisa makan sosis bratwurst jam 3 pagi sambil nonton film Donal bebe . dan mencopet di jalan, stasiun dan pasar.
Tapi semua berubah ketika surat bersegel emas nyasar ke depan pintu. Surat dari Indonesia, tepatnya Surabaya. Surat yang dikirim oleh Dedy pelayan kakekku.
Surat singkat yang isinya "Segera kembali ke Indonesia. Sukarno telah meninggal. Semua warisan untukmu." dengan coretan gambar mirip anak tk. Gambar manusia vesi lidi dengan kepala terpenggal pedang yang dibawahnya bertuliskan. "AWAS KALAU NGGAK PULANG" ada gambar stickman kepotong kepalanya.
Aku langsung pegang leher ku.
Aku bengong. Sukarno? Kakekku?
Aku kira beliau sudah jadi legenda urban, karena terakhir ketemu aku masih SMA, itu pun cuma sebentar. saat aku disuruh pulang dan dikasih kepingan emas untuk diusir lagi ke luar negeri. Sambil bilang, "Kalau ingin hidup jangan balik ke Indonesia"
Kini aku disuruh balik ke Indonesia. Nggak hanya itu, aku di warisi Rumah gaya kolonial di Surabaya (katanya sih luasnya segede stadion sepakbola). Harta benda antik yang kalau dijual bisa bikin negara Swiss minder. Perusahaan-perusahaan di luar negeri, dari pabrik keju di Belanda sampai kilang minyak oles di Texas (memang ada ya di texas miyak oles?). Yang aku sendiri nggak bakalan bisa mengurusnya. Dan yang paling aneh, dokumen super rahasia dari Jerman. Sebanyak satu kamar penuh. Nah lho!!! Apa nggak puyeng.
Semua kekayaan itu ditujukan buatku. Bukan buat dua anaknya yang masih hidup alias dua pamanku yang, katanya, sudah berlatih jurus "warisan cepat cair" sejak dulu. Yang kini baru aku tahu sangan terobsesi ngirim keluarganya ke akhirat.
Om Mursid dan om Gunawan. kedua adik ayahku yang entah kenapa kalau ketemu aku matanya seolah ngomong "Ini anak pantesnya di tanam di mana ya". Yup! Bagi mereka aku layaknya tanaman kedondong. Buah yang bijinya nggak bisa di telan (semua biji nggak bisa di telan. Coba telan biji mu!!)
Kalau dipikir. Lucunya, aku nggak pernah benar-benar dekat sama kakek. Sejak umur 5 tahun aku diajak keliling dunia sama orangtuaku. Lari-larian di taman Shinjuku, makan roti di depan Menara Eiffel, sampai main petak umpet di Colosseum (dilarang petugas, tentu saja). Sampai akhirnya umur 15... kedua orangtuaku hilang saat berlayar ke Antartika. Katanya mau riset soal penguin. Entah beneran riset atau sekadar pengin liburan jauh biar nggak ketemu saudara yang nanya, "Udah punya cucu belum?". Padahal aku masih remaja. Nggak ada kepikiran suka sama perempuan.
Setelah itu, aku dititipkan ke kakek sebentar. Lalu, begitu cukup umur dan punya paspor, aku kabur keliling Eropa. Jadi pelukis jalanan, pengamen, kadang nyambi jadi penerjemah turis yang nyasar. Plus copet keliling.
Hidupku di Jerman aku jalani dengan santai. Nggak ada beban warisan. Nggak ada omelan tetangga. Nggak ada tagihan listrik (karena nebeng listrik apartemen sebelah). Nggak ada paman yang mau nanem aku di kebon belakang.
Tapi sekarang? Aku harus balik ke Indonesia. Surabaya. Dan menjadi orang yang nggak pernah aku bayangkan dan nggak mau aku bayangkan.
Bayangkan, dari dinginnya Hamburg yang bau roti gandum, tiba-tiba harus kembali ke Surabaya yang panasnya bisa bikin semangka meledak. Menjadi orang kaya yang aku sendiri nggak mau jadi orang kaya. Orang harus mengikuti pola hidup bangsawan yang banyak aturan. Ya, hal yang kubenci adalah ATURAN.
Aku lebih suka jadi orang biasa yang ditekan tagihan ini itu. berjuang ini itu untuk menutup tagihan itu. Di kejar tukang kredit karena nunggak 2 bulan. Dikejar polisi Jerman karena mencopet. Dan dikejar mertua karena anaknya hamil. Wait yang ini nggak!!!! TENANG. AKU MASIH PERJAKA!!!! Aib yang harus aku ungkapkan di usia 35.
Kata Fredy, anak dari Dedy, temanku kalau aku ke surabaya. Lewat suratnya, di rumah itu juga tersimpan satu pedang kuno bangsa elf (iya, elf kayak di dongeng itu). Dan sebuah dokumen Jerman yang isinya "jangan dibuka kecuali keadaan genting".
Entah kenapa, kalimat "keadaan genting" di keluargaku kayak "makan siang"—bisa kejadian tiap hari. Banyak insiden yang hampir membuat kakekku meninggal. Mulai rem mobil blong. Kebakaran rumah karena konslet listrik dan banyak lagi.
Dua pamanku?
Mereka jelas nggak akan tinggal diam. Kata Fredy, mereka udah mulai sebar rumor aneh. Konon mereka bikin grup arisan yang isinya rencana pembunuhan. Yang kalau di kopyok tertulis nama orang yang bakalan berlibur ke akhirat. Mereka mulai berkualisi, Entah dengan saudara lain atau mafia lokal (entah di Surabaya ada mafia atau nggak?). Yang pasti, komplotan yang menjadikan mereka mewarisi harta kakek.
Kini. Fredy sendiri yang nekat terbang ke Hamburg buat jemput aku. Setelah mendengar ada isu kalau pamanku kirim pembunuh bayaran ke jerman.
"Mas, kita harus pulang sekarang. Mereka mau habisin Mas sebelum Mas tanda tangan surat warisan," kata Fredy sambil masukin bajuku ke koper.
"Yah, aku belum pamit sama tukang kebab langganan, padahal aku punya utang kebab makan malam selama seminggu" jawabku sambil pegang saus sambal.
"Sudah, nanti tinggal di urus sama perusahaan pak Sukarno cabang Hamburg"
Lho baru tahu, Kakek punya perusahaan di Hamburg. Tahu gitu aku nggak repot jadi copet.
Begitulah.
35 tahun hidup santai.
Lalu tiba-tiba harus pulang ke Surabaya buat warisan yang mungkin akan bikin aku kaya raya... atau malah bikin aku jadi arwah gentayangan.
Begitu pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, hawa panas langsung nyambut kayak hair dryer mode turbo. Orang orang ngeliat aku kayak gembel yang ngemis bertahun tahun hanya untuk beli tiket pesawat.
Aku menatap Fredy. Dia masih kelihatan santai, kayak habis jogging sore di taman kota. Sementara aku? Keringet udah ngalahin guyuran ujan bulan Desember. Gila, tanah air begini amat.
Di pintu kedatangan, seorang pria tua berdiri dengan gagah. Kemeja putih, rambut sedikit memutih, wajah keras tapi berwibawa. Itu Dedy — ayah Fredy. Pelayan setia kakekku.
"Selamat datang, Mas Handoyo," katanya sambil menatapku dalam.
Aku baru mau jawab "terima kasih", tapi dia langsung lanjut.
"Di sini nyawa Anda terancam."
Lha, kalau nyawa terancam, ngapain disuruh pulang? Sinting ini orang, batinku. Bukannya kalau terancam harusnya disuruh liburan ke Bali, bukan malah balik ke Surabaya yang panasnya bikin otak meleleh.
Sebelum aku sempat protes, Dedy melanjutkan dengan nada lebih serius, "Tapi ada yang lebih penting dari nyawa Anda."
Aku mendelik. "Lebih penting dari nyawa? Apalagi?, cicilan rumah? Nikah? Apa, ada anak perempuan hamil yang belum aku nikah. WOY AKU MASIH SUCI. MASIH PERJAKA!!!"
Aku mengaku dengan hinanya. Dan mereka tidak perduli. Aku nangis dalam hati.
Dedy nggak senyum sama sekali. Dengan gerakan pelan tapi mantap, dia mengeluarkan sebuah buku catatan tebal, kulitnya udah agak sobek, warnanya cokelat kehitaman. Di tangan satunya, amplop kuning kecokelatan, seperti surat cinta zaman dulu.
"Ini buku catatan peninggalan Kakek Sukarno. Ini suratnya," katanya sambil menyerahkan dua benda itu ke tanganku.
Aku buka surat dulu. Tulisan tangan kakekku. Tulisan itu khas banget, huruf miring-miring mirip anak SD baru belajar sambung, tapi ada aura "jangan main-main sama saya" di setiap huruf.
Aku mulai membaca.
"Handoyo, cucuku.
Pada tahun 1990 akan terbuka portal yang menghubungkan bumi dengan dunia lain. Apapun yang keluar, harus kamu bunuh atau kamu tahan. Jangan biarkan mereka bebas berkeliaran di bumi.
Semua detail ada di buku catatan ini. Gunakan apa pun yang sudah kakek siapkan. Ingat, ini tanggung jawabmu, bukan hanya soal warisan.
— Sukarno"
Aku langsung melongo. Portal? Dunia lain? Ini apa, franchise film superhero yang belum rilis? Atau ramalan nostradamus yang lagi mabok tempe.
Aku balik ke Dedy.
"Pak... ini serius? Maksudnya... kayak portal di film film gitu?" tanyaku, setengah bercanda, setengah berharap jawaban "Ah, bercanda kok!"
Dedy cuma menghela napas panjang, kayak bapak-bapak habis bayar SPP anaknya yang dobel.
"Serius, Mas. Ini bukan lelucon. Kakek Anda sudah mempersiapkan ini sejak lama. Bahkan saat Anda masih kecil, beliau sudah mendalami berbagai riset. Dari buku kuno, naskah Jerman, sampai artefak bangsa elf. Semua tertulis di buku itu."
Aku membuka halaman pertama buku catatan. Ada gambar lingkaran aneh, tulisan kode, catatan kecil "Jangan makan bakso dekat portal" (oke, yang ini aku nggak ngerti maksudnya apa).
Fredy mendekat sambil bawa botol air mineral. "Mas, minum dulu. Kayaknya Mas butuh cairan sebelum pingsan," katanya.
Aku cuma bisa duduk lemas di kursi mobil jemputan.
Di satu sisi, baru saja dapat warisan segede gaban. Rumah kolonial di Surabaya, harta, perusahaan di luar negeri. Di sisi lain... harus siap-siap bunuh monster dari dunia lain yang entah bentuknya kayak apa. Naga? Kingkong? Atau raksasa kepala 10.
Aku menatap Fredy dan Dedy bergantian.
"Jadi, kita pulang ke rumah dulu atau langsung ke toko senjata terdekat? Kayaknya aku butuh beli golok, panah, dan mental baja," kataku.
Dedy akhirnya tersenyum tipis.
"Kita pulang dulu, Mas. Semua jawaban ada di rumah. Warisan Kakek sudah menunggu. Termasuk pedang bangsa elf yang diwariskan khusus untuk Anda."
Aku menghela napas panjang.
Oke, Surabaya... panasmu ternyata nggak seberapa dibanding panas masalah yang bakal aku hadapi. Masalah yang nggak ada saat aku di Jerman.
Mobil akhirnya berhenti di depan rumah kolonial peninggalan kakekku.
Rumahnya gede banget. Kalau dihitung, kayaknya cukup buat 30 keluarga gelar arisan sekaligus, sambil main futsal di halaman samping. Rumah yang dikelilingi halaman yang luas. Atau lebih pantas disebut hutan. Dan hutan itu dikelilingi tembok setinggi tiga meter dengan kaca yang di tanam di bagian atas pagar.
Begitu turun, aku langsung disambut hawa lembab khas Surabaya. Dedy menggiringku masuk. Fredy bawa koper, mukanya tegang kayak lagi nunggu hasil undian berhadiah.
Di dalam rumah, sudah ada beberapa orang berdiri. Pengacara yang mengurus warisanku dan stafnya. lalu cewek muda berambut pendek, postur tegak, tatapan tajam kayak detektor kebohongan manusia.
"Mas Handoyo, ini Dina. Anak angkat kakek Anda," kata Dedy sambil memperkenalkannya.
Dina hanya mengangguk singkat, lalu menatapku dari ujung kaki sampai ujung uban khayalan di kepalaku. Umurnya jauh dibawahku tapi dia anak angkat kakek. jadi aku memanggilnya bibi.
"Selamat datang, Mas. Kita nggak punya banyak waktu," katanya dingin, suaranya lebih galak daripada guru matematika pas bagi rapor.
Aku belum sempat jawab, Dedy langsung menyodorkan setumpuk dokumen di meja kayu besar.
"Ini surat warisan. Segera tanda tangan, sebelum mereka datang," katanya.
Aku pun duduk. Tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena penasaran: ini surat warisan atau kontrak jual ginjal? Saat lihat pengajara aku ngerasa dihadapkan sama penghulu yang siap nikahkan aku.
Begitu pena menyentuh kertas terakhir, suara pintu depan tiba-tiba dibanting keras.
DUAAMMM!
Dua pamanku—Om Mursid dan Om Gunawan—masuk dengan gaya sok cool, diikuti beberapa pria berbadan besar. Kalau dilihat sekilas, mirip rombongan orkes dangdut yang nyasar sambil di ikuti preman pasar..
"Handoyooooo!!!" teriak Om Mursid.
"Keluar kau! Harta itu harusnya untuk kami!" Om Gunawan menimpali.
Lha dianya sudah masuk ruangan. Kok aku disuruh keluar? Sakit ini orang.
Aku hanya menoleh pelan. "Bentar, Om. Saya baru tanda tangan, ini masih nyari tempat buat nulis tanggal," jawabku sambil setengah berdiri.
Mereka langsung maju sambil melotot. Para pria berbadan besar di belakang mereka juga ikut melangkah, udah kayak gladi resik demo bela warisan.
Tapi Fredy dan Dedy langsung maju. Dina juga ikut berdiri, membuka jaketnya, memperlihatkan beberapa senjata kecil yang terselip di pinggang.
Aku pun reflek mundur satu langkah. "Eh, kalian serius? Ini bukan karnaval perjuangan kan? Dan aku nggak mau ada yang tertusuk dadanya dengan belati atau jidatnya bolong karena peluru" kataku menengahi.
Fredy memegang sebuah tonfa (pentungan ala polisi Jepang), Dedy mengeluarkan pisau tempur, Dina malah sudah memegang dua belati yang entah sejak kapan nongkrong di pinggangnya.
Aura di ruang tamu mendadak tegang. Seperti suasana saat nasi tumpeng tinggal satu potong ayam, dan semua orang naksir potongan yang sama dan mengabaikan sayurannya. Bodo amat dengan urap-urap.
Dua pamanku jelas terkejut. Mereka saling pandang. Salah satu pria berbadan besar yang ikut rombongan sempat bisik ke Om Gunawan. "Bos, mereka ini mantan militer semua. Yang cewek itu juga latihan sama tentara khusus. Gawat."
Om Mursid mendengus. "Kali ini kami mundur. Tapi ingat, ini belum selesai, Handoyo!" katanya sambil melangkah mundur.
Aku ngibrit balik ke kursi, pura-pura sibuk merapikan kertas warisan. "Oke, Om. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai seatbelt," kataku sambil cengengesan.
Rombongan pun keluar rumah sambil mengomel, mirip penonton bioskop yang nggak puas ending film yang nggak ada adegan dewasanya.
Setelah pintu ditutup, suasana hening. Aku menatap Dina, Fredy, dan Dedy.
"Jadi... kita ini tim apa? team komik marvel atau alumni Kopassus?" tanyaku sambil tepuk dada, masih ngos-ngosan, mikir bakal terjadi baku tembak ala mafia.
Dina mendesah. "Mulai sekarang, Mas Handoyo harus siap. Portal itu bukan lelucon. Dan pamannya pasti akan terus mencoba segala cara."
Aku duduk, menatap buku catatan kakek yang masih terbuka di meja.
"Portal, monster, pamannya drama, warisan, dan ..." aku bergumam sambil garuk kepala.
"Ini hidupku atau spin-off telenovela Jerman?!"
Fredy menepuk bahuku."Selamat datang kembali di Surabaya, Mas."
Dan di situlah, untuk pertama kalinya, aku sadar
Warisan kakek ini bukan cuma harta... tapi juga tiket VIP ke masalah-masalah absurd.
Pulang atau Dipulangkan?
1985.
Namaku Handoyo. Umur? 35 tahun. Status? Masih single, tapi bukan karena kurang usaha—lebih karena dunia belum siap.
Beberapa hari lalu aku lagi santai di sebuah flat sempit di Hamburg, Jerman. Hidupku damai, penuh kebebasan. Aku bisa makan sosis bratwurst jam 3 pagi sambil nonton film Donal bebe . dan mencopet di jalan, stasiun dan pasar.
Tapi semua berubah ketika surat bersegel emas nyasar ke depan pintu. Surat dari Indonesia, tepatnya Surabaya. Surat yang dikirim oleh Dedy pelayan kakekku.
Surat singkat yang isinya "Segera kembali ke Indonesia. Sukarno telah meninggal. Semua warisan untukmu." dengan coretan gambar mirip anak tk. Gambar manusia vesi lidi dengan kepala terpenggal pedang yang dibawahnya bertuliskan. "AWAS KALAU NGGAK PULANG" ada gambar stickman kepotong kepalanya.
Aku langsung pegang leher ku.
Aku bengong. Sukarno? Kakekku?
Aku kira beliau sudah jadi legenda urban, karena terakhir ketemu aku masih SMA, itu pun cuma sebentar. saat aku disuruh pulang dan dikasih kepingan emas untuk diusir lagi ke luar negeri. Sambil bilang, "Kalau ingin hidup jangan balik ke Indonesia"
Kini aku disuruh balik ke Indonesia. Nggak hanya itu, aku di warisi Rumah gaya kolonial di Surabaya (katanya sih luasnya segede stadion sepakbola). Harta benda antik yang kalau dijual bisa bikin negara Swiss minder. Perusahaan-perusahaan di luar negeri, dari pabrik keju di Belanda sampai kilang minyak oles di Texas (memang ada ya di texas miyak oles?). Yang aku sendiri nggak bakalan bisa mengurusnya. Dan yang paling aneh, dokumen super rahasia dari Jerman. Sebanyak satu kamar penuh. Nah lho!!! Apa nggak puyeng.
Semua kekayaan itu ditujukan buatku. Bukan buat dua anaknya yang masih hidup alias dua pamanku yang, katanya, sudah berlatih jurus "warisan cepat cair" sejak dulu. Yang kini baru aku tahu sangan terobsesi ngirim keluarganya ke akhirat.
Om Mursid dan om Gunawan. kedua adik ayahku yang entah kenapa kalau ketemu aku matanya seolah ngomong "Ini anak pantesnya di tanam di mana ya". Yup! Bagi mereka aku layaknya tanaman kedondong. Buah yang bijinya nggak bisa di telan (semua biji nggak bisa di telan. Coba telan biji mu!!)
Kalau dipikir. Lucunya, aku nggak pernah benar-benar dekat sama kakek. Sejak umur 5 tahun aku diajak keliling dunia sama orangtuaku. Lari-larian di taman Shinjuku, makan roti di depan Menara Eiffel, sampai main petak umpet di Colosseum (dilarang petugas, tentu saja). Sampai akhirnya umur 15... kedua orangtuaku hilang saat berlayar ke Antartika. Katanya mau riset soal penguin. Entah beneran riset atau sekadar pengin liburan jauh biar nggak ketemu saudara yang nanya, "Udah punya cucu belum?". Padahal aku masih remaja. Nggak ada kepikiran suka sama perempuan.
Setelah itu, aku dititipkan ke kakek sebentar. Lalu, begitu cukup umur dan punya paspor, aku kabur keliling Eropa. Jadi pelukis jalanan, pengamen, kadang nyambi jadi penerjemah turis yang nyasar. Plus copet keliling.
Hidupku di Jerman aku jalani dengan santai. Nggak ada beban warisan. Nggak ada omelan tetangga. Nggak ada tagihan listrik (karena nebeng listrik apartemen sebelah). Nggak ada paman yang mau nanem aku di kebon belakang.
Tapi sekarang? Aku harus balik ke Indonesia. Surabaya. Dan menjadi orang yang nggak pernah aku bayangkan dan nggak mau aku bayangkan.
Bayangkan, dari dinginnya Hamburg yang bau roti gandum, tiba-tiba harus kembali ke Surabaya yang panasnya bisa bikin semangka meledak. Menjadi orang kaya yang aku sendiri nggak mau jadi orang kaya. Orang harus mengikuti pola hidup bangsawan yang banyak aturan. Ya, hal yang kubenci adalah ATURAN.
Aku lebih suka jadi orang biasa yang ditekan tagihan ini itu. berjuang ini itu untuk menutup tagihan itu. Di kejar tukang kredit karena nunggak 2 bulan. Dikejar polisi Jerman karena mencopet. Dan dikejar mertua karena anaknya hamil. Wait yang ini nggak!!!! TENANG. AKU MASIH PERJAKA!!!! Aib yang harus aku ungkapkan di usia 35.
Kata Fredy, anak dari Dedy, temanku kalau aku ke surabaya. Lewat suratnya, di rumah itu juga tersimpan satu pedang kuno bangsa elf (iya, elf kayak di dongeng itu). Dan sebuah dokumen Jerman yang isinya "jangan dibuka kecuali keadaan genting".
Entah kenapa, kalimat "keadaan genting" di keluargaku kayak "makan siang"—bisa kejadian tiap hari. Banyak insiden yang hampir membuat kakekku meninggal. Mulai rem mobil blong. Kebakaran rumah karena konslet listrik dan banyak lagi.
Dua pamanku?
Mereka jelas nggak akan tinggal diam. Kata Fredy, mereka udah mulai sebar rumor aneh. Konon mereka bikin grup arisan yang isinya rencana pembunuhan. Yang kalau di kopyok tertulis nama orang yang bakalan berlibur ke akhirat. Mereka mulai berkualisi, Entah dengan saudara lain atau mafia lokal (entah di Surabaya ada mafia atau nggak?). Yang pasti, komplotan yang menjadikan mereka mewarisi harta kakek.
Kini. Fredy sendiri yang nekat terbang ke Hamburg buat jemput aku. Setelah mendengar ada isu kalau pamanku kirim pembunuh bayaran ke jerman.
"Mas, kita harus pulang sekarang. Mereka mau habisin Mas sebelum Mas tanda tangan surat warisan," kata Fredy sambil masukin bajuku ke koper.
"Yah, aku belum pamit sama tukang kebab langganan, padahal aku punya utang kebab makan malam selama seminggu" jawabku sambil pegang saus sambal.
"Sudah, nanti tinggal di urus sama perusahaan pak Sukarno cabang Hamburg"
Lho baru tahu, Kakek punya perusahaan di Hamburg. Tahu gitu aku nggak repot jadi copet.
Begitulah.
35 tahun hidup santai.
Lalu tiba-tiba harus pulang ke Surabaya buat warisan yang mungkin akan bikin aku kaya raya... atau malah bikin aku jadi arwah gentayangan.
Begitu pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, hawa panas langsung nyambut kayak hair dryer mode turbo. Orang orang ngeliat aku kayak gembel yang ngemis bertahun tahun hanya untuk beli tiket pesawat.
Aku menatap Fredy. Dia masih kelihatan santai, kayak habis jogging sore di taman kota. Sementara aku? Keringet udah ngalahin guyuran ujan bulan Desember. Gila, tanah air begini amat.
Di pintu kedatangan, seorang pria tua berdiri dengan gagah. Kemeja putih, rambut sedikit memutih, wajah keras tapi berwibawa. Itu Dedy — ayah Fredy. Pelayan setia kakekku.
"Selamat datang, Mas Handoyo," katanya sambil menatapku dalam.
Aku baru mau jawab "terima kasih", tapi dia langsung lanjut.
"Di sini nyawa Anda terancam."
Lha, kalau nyawa terancam, ngapain disuruh pulang? Sinting ini orang, batinku. Bukannya kalau terancam harusnya disuruh liburan ke Bali, bukan malah balik ke Surabaya yang panasnya bikin otak meleleh.
Sebelum aku sempat protes, Dedy melanjutkan dengan nada lebih serius, "Tapi ada yang lebih penting dari nyawa Anda."
Aku mendelik. "Lebih penting dari nyawa? Apalagi?, cicilan rumah? Nikah? Apa, ada anak perempuan hamil yang belum aku nikah. WOY AKU MASIH SUCI. MASIH PERJAKA!!!"
Aku mengaku dengan hinanya. Dan mereka tidak perduli. Aku nangis dalam hati.
Dedy nggak senyum sama sekali. Dengan gerakan pelan tapi mantap, dia mengeluarkan sebuah buku catatan tebal, kulitnya udah agak sobek, warnanya cokelat kehitaman. Di tangan satunya, amplop kuning kecokelatan, seperti surat cinta zaman dulu.
"Ini buku catatan peninggalan Kakek Sukarno. Ini suratnya," katanya sambil menyerahkan dua benda itu ke tanganku.
Aku buka surat dulu. Tulisan tangan kakekku. Tulisan itu khas banget, huruf miring-miring mirip anak SD baru belajar sambung, tapi ada aura "jangan main-main sama saya" di setiap huruf.
Aku mulai membaca.
"Handoyo, cucuku.
Pada tahun 1990 akan terbuka portal yang menghubungkan bumi dengan dunia lain. Apapun yang keluar, harus kamu bunuh atau kamu tahan. Jangan biarkan mereka bebas berkeliaran di bumi.
Semua detail ada di buku catatan ini. Gunakan apa pun yang sudah kakek siapkan. Ingat, ini tanggung jawabmu, bukan hanya soal warisan.
— Sukarno"
Aku langsung melongo. Portal? Dunia lain? Ini apa, franchise film superhero yang belum rilis? Atau ramalan nostradamus yang lagi mabok tempe.
Aku balik ke Dedy.
"Pak... ini serius? Maksudnya... kayak portal di film film gitu?" tanyaku, setengah bercanda, setengah berharap jawaban "Ah, bercanda kok!"
Dedy cuma menghela napas panjang, kayak bapak-bapak habis bayar SPP anaknya yang dobel.
"Serius, Mas. Ini bukan lelucon. Kakek Anda sudah mempersiapkan ini sejak lama. Bahkan saat Anda masih kecil, beliau sudah mendalami berbagai riset. Dari buku kuno, naskah Jerman, sampai artefak bangsa elf. Semua tertulis di buku itu."
Aku membuka halaman pertama buku catatan. Ada gambar lingkaran aneh, tulisan kode, catatan kecil "Jangan makan bakso dekat portal" (oke, yang ini aku nggak ngerti maksudnya apa).
Fredy mendekat sambil bawa botol air mineral. "Mas, minum dulu. Kayaknya Mas butuh cairan sebelum pingsan," katanya.
Aku cuma bisa duduk lemas di kursi mobil jemputan.
Di satu sisi, baru saja dapat warisan segede gaban. Rumah kolonial di Surabaya, harta, perusahaan di luar negeri. Di sisi lain... harus siap-siap bunuh monster dari dunia lain yang entah bentuknya kayak apa. Naga? Kingkong? Atau raksasa kepala 10.
Aku menatap Fredy dan Dedy bergantian.
"Jadi, kita pulang ke rumah dulu atau langsung ke toko senjata terdekat? Kayaknya aku butuh beli golok, panah, dan mental baja," kataku.
Dedy akhirnya tersenyum tipis.
"Kita pulang dulu, Mas. Semua jawaban ada di rumah. Warisan Kakek sudah menunggu. Termasuk pedang bangsa elf yang diwariskan khusus untuk Anda."
Aku menghela napas panjang.
Oke, Surabaya... panasmu ternyata nggak seberapa dibanding panas masalah yang bakal aku hadapi. Masalah yang nggak ada saat aku di Jerman.
Mobil akhirnya berhenti di depan rumah kolonial peninggalan kakekku.
Rumahnya gede banget. Kalau dihitung, kayaknya cukup buat 30 keluarga gelar arisan sekaligus, sambil main futsal di halaman samping. Rumah yang dikelilingi halaman yang luas. Atau lebih pantas disebut hutan. Dan hutan itu dikelilingi tembok setinggi tiga meter dengan kaca yang di tanam di bagian atas pagar.
Begitu turun, aku langsung disambut hawa lembab khas Surabaya. Dedy menggiringku masuk. Fredy bawa koper, mukanya tegang kayak lagi nunggu hasil undian berhadiah.
Di dalam rumah, sudah ada beberapa orang berdiri. Pengacara yang mengurus warisanku dan stafnya. lalu cewek muda berambut pendek, postur tegak, tatapan tajam kayak detektor kebohongan manusia.
"Mas Handoyo, ini Dina. Anak angkat kakek Anda," kata Dedy sambil memperkenalkannya.
Dina hanya mengangguk singkat, lalu menatapku dari ujung kaki sampai ujung uban khayalan di kepalaku. Umurnya jauh dibawahku tapi dia anak angkat kakek. jadi aku memanggilnya bibi.
"Selamat datang, Mas. Kita nggak punya banyak waktu," katanya dingin, suaranya lebih galak daripada guru matematika pas bagi rapor.
Aku belum sempat jawab, Dedy langsung menyodorkan setumpuk dokumen di meja kayu besar.
"Ini surat warisan. Segera tanda tangan, sebelum mereka datang," katanya.
Aku pun duduk. Tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena penasaran: ini surat warisan atau kontrak jual ginjal? Saat lihat pengajara aku ngerasa dihadapkan sama penghulu yang siap nikahkan aku.
Begitu pena menyentuh kertas terakhir, suara pintu depan tiba-tiba dibanting keras.
DUAAMMM!
Dua pamanku—Om Mursid dan Om Gunawan—masuk dengan gaya sok cool, diikuti beberapa pria berbadan besar. Kalau dilihat sekilas, mirip rombongan orkes dangdut yang nyasar sambil di ikuti preman pasar..
"Handoyooooo!!!" teriak Om Mursid.
"Keluar kau! Harta itu harusnya untuk kami!" Om Gunawan menimpali.
Lha dianya sudah masuk ruangan. Kok aku disuruh keluar? Sakit ini orang.
Aku hanya menoleh pelan. "Bentar, Om. Saya baru tanda tangan, ini masih nyari tempat buat nulis tanggal," jawabku sambil setengah berdiri.
Mereka langsung maju sambil melotot. Para pria berbadan besar di belakang mereka juga ikut melangkah, udah kayak gladi resik demo bela warisan.
Tapi Fredy dan Dedy langsung maju. Dina juga ikut berdiri, membuka jaketnya, memperlihatkan beberapa senjata kecil yang terselip di pinggang.
Aku pun reflek mundur satu langkah. "Eh, kalian serius? Ini bukan karnaval perjuangan kan? Dan aku nggak mau ada yang tertusuk dadanya dengan belati atau jidatnya bolong karena peluru" kataku menengahi.
Fredy memegang sebuah tonfa (pentungan ala polisi Jepang), Dedy mengeluarkan pisau tempur, Dina malah sudah memegang dua belati yang entah sejak kapan nongkrong di pinggangnya.
Aura di ruang tamu mendadak tegang. Seperti suasana saat nasi tumpeng tinggal satu potong ayam, dan semua orang naksir potongan yang sama dan mengabaikan sayurannya. Bodo amat dengan urap-urap.
Dua pamanku jelas terkejut. Mereka saling pandang. Salah satu pria berbadan besar yang ikut rombongan sempat bisik ke Om Gunawan. "Bos, mereka ini mantan militer semua. Yang cewek itu juga latihan sama tentara khusus. Gawat."
Om Mursid mendengus. "Kali ini kami mundur. Tapi ingat, ini belum selesai, Handoyo!" katanya sambil melangkah mundur.
Aku ngibrit balik ke kursi, pura-pura sibuk merapikan kertas warisan. "Oke, Om. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai seatbelt," kataku sambil cengengesan.
Rombongan pun keluar rumah sambil mengomel, mirip penonton bioskop yang nggak puas ending film yang nggak ada adegan dewasanya.
Setelah pintu ditutup, suasana hening. Aku menatap Dina, Fredy, dan Dedy.
"Jadi... kita ini tim apa? team komik marvel atau alumni Kopassus?" tanyaku sambil tepuk dada, masih ngos-ngosan, mikir bakal terjadi baku tembak ala mafia.
Dina mendesah. "Mulai sekarang, Mas Handoyo harus siap. Portal itu bukan lelucon. Dan pamannya pasti akan terus mencoba segala cara."
Aku duduk, menatap buku catatan kakek yang masih terbuka di meja.
"Portal, monster, pamannya drama, warisan, dan ..." aku bergumam sambil garuk kepala.
"Ini hidupku atau spin-off telenovela Jerman?!"
Fredy menepuk bahuku."Selamat datang kembali di Surabaya, Mas."
Dan di situlah, untuk pertama kalinya, aku sadar
Warisan kakek ini bukan cuma harta... tapi juga tiket VIP ke masalah-masalah absurd.
Other Stories
Dante Fair Tale
Dante, bocah kesepian berusia 9 tahun, membuat perjanjian dengan peri terkurung dalam bola ...
Pra Wedding Escape
Nastiti yakin menikah dengan Bram karena pekerjaan, finansial, dan restu keluarga sudah me ...
Tilawah Hati
Terinspirasi tilawah gurunya, Pak Ridwan, Wina bertekad menjadi guru Agama Islam. Meski be ...
Sang Maestro
Mari kita sambut seorang pelukis jenius kita. Seorang perempuan yang cantik, kaya dan berb ...
Jjjjjj
ghjjjj ...
Terlupakan
Pras, fotografer berbakat namun pemalu, jatuh hati pada Gadis, seorang reporter. Gadis mem ...