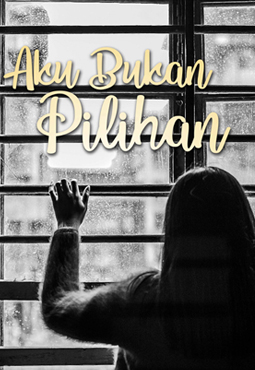Bab 24 Kabut Penyesalan Di Plains Of Vulkar
Bab 24
Kabut Penyesalan di Plains of Vulkar
Begitu kami mendarat di dataran tandus Plains of Vulkar, hawa dingin menyergap dari segala arah. Tanahnya kering, retak, dan dipenuhi kabut kelabu yang menggantung rendah. Tak ada suara burung. Tak ada hembusan angin. Hanya kesunyian yang berat... dan ribuan tatapan kosong dari tengkorak hidup yang menatap kami dari kejauhan di bawah kami.
Mereka berdiri dalam barisan rapi, senjata berkarat di tangan, baju zirah usang masih menempel di tubuh tulang belulang mereka. Sebagian duduk di atas kerangka kuda hitam besar yang sama seramnya. Dan ketika mereka melihat Chintya—seorang elf—suara gemeretak senjata dan desis amarah terdengar. Suasana mendadak tegang.
Aku cepat melangkah maju. Tanganku mencabut pedang perobek portal, dan—dengan satu gerakan—kutancapkan ke tanah.
Aku membungkuk. Dalam. Tunduk penuh hormat.
"Salam hormat dari Kota Stromcoast," kataku dengan suara lantang yang kutahan agar tak gemetar. "Saya Handoyo. Manusia dari dunia lain. Kami datang sebagai utusan perdamaian. Dan saya menghormati bangsa Undead, para kesatria yang dulu berani, kini abadi."
Sesaat tak ada suara.
Lalu, dari balik barisan para tengkorak, muncul satu sosok. Tengkorak tinggi mengenakan jubah baja hitam, duduk angkuh di atas kuda hitam raksasa. Matanya berkilat biru api jiwa yang tak padam.
Ia turun perlahan dari kudanya, lalu berdiri di hadapanku. Lalu... ia juga menancapkan pedangnya ke tanah.
"Kami adalah bangsa yang dikhianati dan diadu domba," katanya, suaranya berat dan menggema, seperti gaung dari liang kubur. "Kami menghormati pemegang pedang perobek portal."
Lalu kabut menggulung semakin tebal, menyelimuti kami semua. Dan tiba-tiba, pemandangan di hadapan kami berubah—seperti mimpi yang dihidupkan kembali.
Kami menyaksikan... masa lalu. Plains of Vulkar, berabad lalu. Para manusia dan naga hidup berdampingan. Mereka membangun desa, bertani bersama, membagi air sungai, bahkan saling menjaga anak-anak satu sama lain.
Tapi lalu datanglah para elf. Mereka menawarkan "keabadian" pada manusia. Mereka berbisik bahwa naga-naga diam-diam menyimpan kekuatan dan ingin menguasai dunia. Mereka menghasut... menebar ketakutan... memutarbalikkan kenyataan.
Dan manusia percaya.
Peperangan pun pecah. Para manusia, yang kini kami lihat adalah para Undead, menyerbu para naga yang dulu adalah sahabat mereka. Darah naga tumpah. Kristal mana pecah. Benua retak oleh sihir dan pengkhianatan.
Dan ketika semua usai... para elf meninggalkan medan perang, sedangkan manusia yang tersisa... dikutuk dalam keabadian.
"Apa yang mereka berikan bukanlah hidup abadi... tapi kutukan tak berakhir," kata tengkorak berjubah itu, suaranya penuh perih.
Chintya menunduk. Wajahnya pucat.
"Kami malu," lanjut sang pemimpin undead. "Malu karena membunuh saudara kami. Bangsa naga yang dulu memberi kami api di musim dingin. Air di musim kering. Dan kini, kami hanya ingin satu hal..."
Ia mendekat padaku.
"Tolong... sampaikan permintaan maaf kami pada para naga. Jika mereka sudi memaafkan... kami akan bisa tidur. Untuk pertama kalinya... dalam seribu tahun."
Aku menelan ludah. Lalu mengangguk.
"Dengan kehormatan yang tersisa... aku bersumpah akan menyampaikan permintaan maaf ini, pada Aslan, sang pemimpin naga" kataku.
Mereka semua—ribuan prajurit Undead—berlutut perlahan. Satu suara bergema dari seluruh daratan
"Kami siap berperang... di sisi kebenaran."
Dan kabut menyelimuti kami sekali lagi—kali ini bukan sebagai kutukan, tapi sebagai saksi sebuah ikrar.
Malam di Antara Tulang dan Rahasia
Malam ini, udara Plains of Vulkar terasa dingin... tapi bukan dingin yang menusuk kulit—ini dingin yang merayap pelan, menyelinap ke dalam dada, menggelitik pikiran, dan membuat hati tidak tenang.
Kami mendirikan tenda seadanya. Api unggun kecil menyala di tengah, dan para Undead berjalan mondar-mandir di sekitarnya. Ada yang menjaga, ada yang duduk diam menatap langit, dan ada pula yang hanya berdiri memandangi kabut... seolah masih mencari sisa-sisa masa lalu mereka di balik gelap malam.
Sebagian dari mereka sudah berangkat lebih dulu menuju Gunung Stromcoast. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bukan lagi alat, tapi sekutu sejati.
Tapi Aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh. Tentang manusia yang dijanjikan keabadian... lalu dihancurkan oleh janji itu sendiri. Tentang para naga yang dulunya hidup damai, tapi difitnah dan diburu. Tentang orang tua Chintya yang mungkin tahu semua ini... dan dibungkam sebelum kebenaran terungkap.
Dan bangsa elf... Bangsa yang dikenal menjunjung tinggi kehormatan, tapi tega mengadu domba, memanipulasi, dan memusnahkan. Bangsa pendatang yang malah mengacaukan bangsa yang sudah lama mendiami Drak'terra.
Kain tenda terbuka pelan. Chintya masuk. Ia duduk di sampingku, wajahnya diterangi nyala api unggun. Matanya teduh, tapi tampak lelah. Seperti ada pertarungan dalam dirinya yang belum usai.
"Kau belum tidur?" tanyanya pelan.
Aku menggeleng.
"Pikiranku penuh," jawabku. "Tentang bangsa Undead... tentang semua yang kita temui hari ini."
Chintya diam. Lalu menatap nyala api.
"Aku juga memikirkannya," katanya. "Aku... tidak menyangka sejarah bangsaku seperti ini. Kukira, kami adalah cahaya dunia ini. Kukira kehormatan bangsa elf adalah kebenaran.
Aku mengangguk perlahan.
"Chintya... bagaimana bisa bangsa yang katanya menjunjung kehormatan... bisa berbuat sehina itu?" tanyaku lirih. "Mereka janji memberi keabadian... lalu mengutuk. Mereka fitnah naga... lalu bunuh. Mereka bunuh orang tuamu, hanya karena mereka mungkin tahu kebenaran..."
Aku menoleh padanya. Wajah Chintya pucat, tapi tenang. Sebuah kenyataan pahit yang harus diketahui. Sebuah sejarah yang memilukan yang mengoyak hari nurani. Di satu sisi dia telah berdiri sebagai pemberontak bangsanya sendiri meski sekarang jadi buronan bangsa Elf.dan dia bangga.
"Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi aku tahu, bukan semua elf seperti itu. Seperti tidak semua manusia rakus. Tidak semua dwarf sombong. Tidak semua naga pendendam. Tapi... sejarah kami penuh darah. Dan sekarang, aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya monster dalam cerita ini?"
Hening sejenak. Hanya bunyi api yang berderak pelan.
"Aku bangga padamu," kataku akhirnya. "Kau tahu kebenaran dan kau tidak lari darinya."
Chintya menatapku, lembut.
"Kalau aku lari, aku tidak akan pernah bertemu kamu," katanya, tersenyum tipis. "Dan mungkin... aku tidak akan tahu apa itu cinta, di luar kehormatan dan tugas."
Dadaku hangat. Kata katanya memberiku harapan.
"Apakah ucapanmu adalah takdirmu atau takdirku, ya, Orang bodoh yang berjiwa Besar. " aku mengulangi kata kata Chintya. Tapi dalam hatiku. Apa benar aku sebodoh itu, hingga pedang ini memilihku?
Malam itu, kami duduk diam di antara barisan tengkorak yang bersiap untuk menebus dosa dan dua hati yang mulai menyatu, meski masa depan masih diliputi kabut perang. Kabut yang aku sendiri tidak tahu bakalan hidup atau mati, dan kami bisa bersatu meski beda ras.
Kabut Penyesalan di Plains of Vulkar
Begitu kami mendarat di dataran tandus Plains of Vulkar, hawa dingin menyergap dari segala arah. Tanahnya kering, retak, dan dipenuhi kabut kelabu yang menggantung rendah. Tak ada suara burung. Tak ada hembusan angin. Hanya kesunyian yang berat... dan ribuan tatapan kosong dari tengkorak hidup yang menatap kami dari kejauhan di bawah kami.
Mereka berdiri dalam barisan rapi, senjata berkarat di tangan, baju zirah usang masih menempel di tubuh tulang belulang mereka. Sebagian duduk di atas kerangka kuda hitam besar yang sama seramnya. Dan ketika mereka melihat Chintya—seorang elf—suara gemeretak senjata dan desis amarah terdengar. Suasana mendadak tegang.
Aku cepat melangkah maju. Tanganku mencabut pedang perobek portal, dan—dengan satu gerakan—kutancapkan ke tanah.
Aku membungkuk. Dalam. Tunduk penuh hormat.
"Salam hormat dari Kota Stromcoast," kataku dengan suara lantang yang kutahan agar tak gemetar. "Saya Handoyo. Manusia dari dunia lain. Kami datang sebagai utusan perdamaian. Dan saya menghormati bangsa Undead, para kesatria yang dulu berani, kini abadi."
Sesaat tak ada suara.
Lalu, dari balik barisan para tengkorak, muncul satu sosok. Tengkorak tinggi mengenakan jubah baja hitam, duduk angkuh di atas kuda hitam raksasa. Matanya berkilat biru api jiwa yang tak padam.
Ia turun perlahan dari kudanya, lalu berdiri di hadapanku. Lalu... ia juga menancapkan pedangnya ke tanah.
"Kami adalah bangsa yang dikhianati dan diadu domba," katanya, suaranya berat dan menggema, seperti gaung dari liang kubur. "Kami menghormati pemegang pedang perobek portal."
Lalu kabut menggulung semakin tebal, menyelimuti kami semua. Dan tiba-tiba, pemandangan di hadapan kami berubah—seperti mimpi yang dihidupkan kembali.
Kami menyaksikan... masa lalu. Plains of Vulkar, berabad lalu. Para manusia dan naga hidup berdampingan. Mereka membangun desa, bertani bersama, membagi air sungai, bahkan saling menjaga anak-anak satu sama lain.
Tapi lalu datanglah para elf. Mereka menawarkan "keabadian" pada manusia. Mereka berbisik bahwa naga-naga diam-diam menyimpan kekuatan dan ingin menguasai dunia. Mereka menghasut... menebar ketakutan... memutarbalikkan kenyataan.
Dan manusia percaya.
Peperangan pun pecah. Para manusia, yang kini kami lihat adalah para Undead, menyerbu para naga yang dulu adalah sahabat mereka. Darah naga tumpah. Kristal mana pecah. Benua retak oleh sihir dan pengkhianatan.
Dan ketika semua usai... para elf meninggalkan medan perang, sedangkan manusia yang tersisa... dikutuk dalam keabadian.
"Apa yang mereka berikan bukanlah hidup abadi... tapi kutukan tak berakhir," kata tengkorak berjubah itu, suaranya penuh perih.
Chintya menunduk. Wajahnya pucat.
"Kami malu," lanjut sang pemimpin undead. "Malu karena membunuh saudara kami. Bangsa naga yang dulu memberi kami api di musim dingin. Air di musim kering. Dan kini, kami hanya ingin satu hal..."
Ia mendekat padaku.
"Tolong... sampaikan permintaan maaf kami pada para naga. Jika mereka sudi memaafkan... kami akan bisa tidur. Untuk pertama kalinya... dalam seribu tahun."
Aku menelan ludah. Lalu mengangguk.
"Dengan kehormatan yang tersisa... aku bersumpah akan menyampaikan permintaan maaf ini, pada Aslan, sang pemimpin naga" kataku.
Mereka semua—ribuan prajurit Undead—berlutut perlahan. Satu suara bergema dari seluruh daratan
"Kami siap berperang... di sisi kebenaran."
Dan kabut menyelimuti kami sekali lagi—kali ini bukan sebagai kutukan, tapi sebagai saksi sebuah ikrar.
Malam di Antara Tulang dan Rahasia
Malam ini, udara Plains of Vulkar terasa dingin... tapi bukan dingin yang menusuk kulit—ini dingin yang merayap pelan, menyelinap ke dalam dada, menggelitik pikiran, dan membuat hati tidak tenang.
Kami mendirikan tenda seadanya. Api unggun kecil menyala di tengah, dan para Undead berjalan mondar-mandir di sekitarnya. Ada yang menjaga, ada yang duduk diam menatap langit, dan ada pula yang hanya berdiri memandangi kabut... seolah masih mencari sisa-sisa masa lalu mereka di balik gelap malam.
Sebagian dari mereka sudah berangkat lebih dulu menuju Gunung Stromcoast. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bukan lagi alat, tapi sekutu sejati.
Tapi Aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh. Tentang manusia yang dijanjikan keabadian... lalu dihancurkan oleh janji itu sendiri. Tentang para naga yang dulunya hidup damai, tapi difitnah dan diburu. Tentang orang tua Chintya yang mungkin tahu semua ini... dan dibungkam sebelum kebenaran terungkap.
Dan bangsa elf... Bangsa yang dikenal menjunjung tinggi kehormatan, tapi tega mengadu domba, memanipulasi, dan memusnahkan. Bangsa pendatang yang malah mengacaukan bangsa yang sudah lama mendiami Drak'terra.
Kain tenda terbuka pelan. Chintya masuk. Ia duduk di sampingku, wajahnya diterangi nyala api unggun. Matanya teduh, tapi tampak lelah. Seperti ada pertarungan dalam dirinya yang belum usai.
"Kau belum tidur?" tanyanya pelan.
Aku menggeleng.
"Pikiranku penuh," jawabku. "Tentang bangsa Undead... tentang semua yang kita temui hari ini."
Chintya diam. Lalu menatap nyala api.
"Aku juga memikirkannya," katanya. "Aku... tidak menyangka sejarah bangsaku seperti ini. Kukira, kami adalah cahaya dunia ini. Kukira kehormatan bangsa elf adalah kebenaran.
Aku mengangguk perlahan.
"Chintya... bagaimana bisa bangsa yang katanya menjunjung kehormatan... bisa berbuat sehina itu?" tanyaku lirih. "Mereka janji memberi keabadian... lalu mengutuk. Mereka fitnah naga... lalu bunuh. Mereka bunuh orang tuamu, hanya karena mereka mungkin tahu kebenaran..."
Aku menoleh padanya. Wajah Chintya pucat, tapi tenang. Sebuah kenyataan pahit yang harus diketahui. Sebuah sejarah yang memilukan yang mengoyak hari nurani. Di satu sisi dia telah berdiri sebagai pemberontak bangsanya sendiri meski sekarang jadi buronan bangsa Elf.dan dia bangga.
"Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi aku tahu, bukan semua elf seperti itu. Seperti tidak semua manusia rakus. Tidak semua dwarf sombong. Tidak semua naga pendendam. Tapi... sejarah kami penuh darah. Dan sekarang, aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya monster dalam cerita ini?"
Hening sejenak. Hanya bunyi api yang berderak pelan.
"Aku bangga padamu," kataku akhirnya. "Kau tahu kebenaran dan kau tidak lari darinya."
Chintya menatapku, lembut.
"Kalau aku lari, aku tidak akan pernah bertemu kamu," katanya, tersenyum tipis. "Dan mungkin... aku tidak akan tahu apa itu cinta, di luar kehormatan dan tugas."
Dadaku hangat. Kata katanya memberiku harapan.
"Apakah ucapanmu adalah takdirmu atau takdirku, ya, Orang bodoh yang berjiwa Besar. " aku mengulangi kata kata Chintya. Tapi dalam hatiku. Apa benar aku sebodoh itu, hingga pedang ini memilihku?
Malam itu, kami duduk diam di antara barisan tengkorak yang bersiap untuk menebus dosa dan dua hati yang mulai menyatu, meski masa depan masih diliputi kabut perang. Kabut yang aku sendiri tidak tahu bakalan hidup atau mati, dan kami bisa bersatu meski beda ras.
Other Stories
Pasti Ada Jalan
Sebagai ibu tunggal di usia muda, Sari, perempuan cerdas yang bernasib malang itu, selalu ...
Aku Bukan Pilihan
Cukup lama Rama menyendiri selepas hubungannya dengan Santi kandas, kini rasa cinta itu da ...
Kala Menjadi Cahaya Menjemput Harapan Di Tengah Gelap
Hidup Arka runtuh dalam sekejap. Pekerjaan yang ia banggakan hilang, ayahnya jatuh sakit p ...
Hujan Yang Tak Dirindukan
Perjalanan menuju kebun karet harus melalui jalan bertanah merah. Nyawa tak jarang banyak ...
Just, Open Your Heart
Muthia terjebak antara cinta lama yang menyakitkan dan cinta baru dari bosnya yang penuh k ...
Mewarnai
ini adalah contoh uplot buku ...