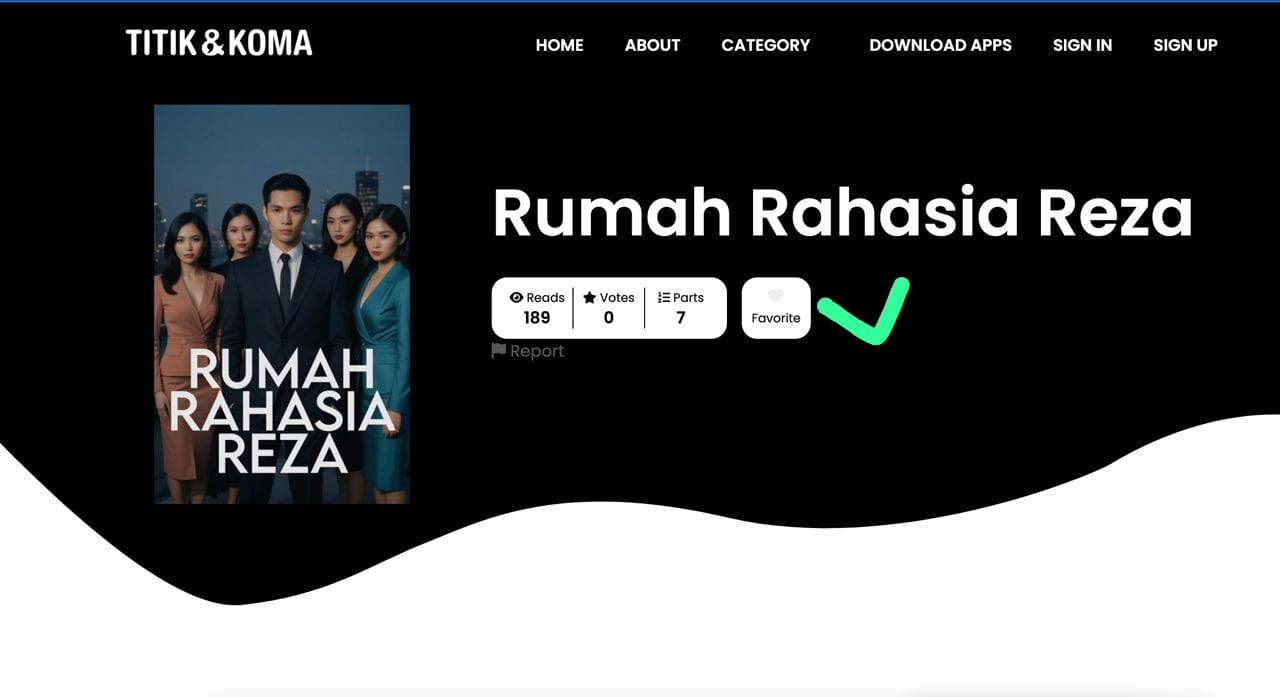Bagian 2
Beberapa bulan sebelumnya ....
Ikal terus melajukan langkahnya membelah jalanan setapak basah yang sisi kanan kirinya ditumbuhi sekumpulan semak keramunting[1] liar. Hujan yang turun lebat subuh tadi, menyisakan sekumpulan partikel air yang gagal terjerap oleh proses infiltrasi, di atas permukaan tanah. Tak hanya diselingi kilatan petir dahsyat, hujan dini hari tadi juga disertai angin yang mampu menggoyang bubungan atap-atap daun nipah kering. Membuat satu-satunya jalanan akses yang menghubungkan antara rumah Ikal dengan sekolah, menjadi becek dan sedikit licin. Ketimbang mendapati sepatunya kotor berlumpur, bocah dua belas tahun tersebut lebih memilih berjalan tanpa alas kaki. Menurutnya, sepasang kaki yang kotor masih bisa dicuci dengan air kolong[2] yang berada di belakang sekolah. Tapi, tidak dengan sepatu sekolahnya. Apalagi ketika memasuki musim penghujan seperti saat ini. Alas kakinya itu tentu tak akan mudah kering. Maka, memikirkan hal tersebut, Ikal memutuskan untuk mengikat ujung tali sepatu tadi ke belakang tas usang yang setia menggantung di punggungnya.
Meski waktu masih menunjukkan pukul enam lebih lima menit dan matahari belum sepenuhnya menyingsing melebihi tinggi manggar kelapa yang baru saja mekar di ufuk timur, namun Ikal—bocah dua belas tahun berseragam putih merah tadi—harus sudah mulai menempuh jalanan yang bisa dibilang panjang untuk ukuran kakinya yang tergolong mungil. Sudah dua tahun belakangan ini siswa kelas enam sekolah dasar itu harus rela berjalan kaki ke sekolah. Pasalnya, ibunya yang seorang janda melarat dan hanya menggantungkan penghidupan dari upah memilah ikan di pelelangan yang tak seberapa, belum mampu membelikan Ikal sebuah sepeda baru. Semenjak meninggalnya sang bapak dalam sebuah pelayaran yang diterjang ganas badai, perekonomian ibunya menjadi sedemikian carut-marut. Apalagi ketika Ikal baru saja duduk di bangku kelas empat, sepeda butut yang merupakan hibah dari seorang anak tauke ikan, mendadak rusak. Barangkali usia karat yang sudah menjalari batang sepedanya akibat korosi air laut itu, tak mampu lagi menahan bobot tubuh Ikal yang kian bertumbuh.
Alhasil, dalam perjalanan menuju ke sekolah di suatu pagi yang agak berangin, salah satu sambungan badan sepeda tersebut patah. Ikal yang melaju dengan kecepatan sedang, jatuh tersungkur dan berguling-guling di tanah. Lutut dan sikunya seketika lecet dan berdarah. Tapi, kala itu, Ikal sama sekali tidak menangis. Ia segera bangkit dan hanya menyapih debu yang menempel di seragam dengan ala kadarnya. Sambil meringis menahan perih, Ikal memilih meninggalkan begitu saja sepeda tua yang telah menjelma rongsokan, dan kembali melanjutkan langkah menuju sekolah. Bocah itu enggan untuk pulang ke rumah, mengingat jarak dari lokasi kejadian cenderung lebih dekat rentangnya ke sekolah ketimbang tempat tinggalnya yang berada jauh di pinggiran pantai.
Setiba di sekolah, teman-teman Ikal yang memang biasa menunggu di depan pintu kelas sebelum bel yang terbuat dari pelek mobil bekas dipukul bertalu-talu, dibuat terkaget-kaget ketika melihat kondisi rekannya yang cukup memprihatinkan. Belum lagi seragam Ikal yang memang sudah kusam sejak awal, robek di bagian bahu sebelah kanan.
“Ngape ikak, Kal?[3]” tanya salah seorang rekannya yang penasaran dengan keadaan Ikal yang berantakan dan penuh luka.
Ikal yang merasa lukanya semakin pedih lantaran digarami peluh, memilih tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya bisa meringis sembari melemparkan senyuman pada rekan-rekannya. Seolah tak ada yang perlu mereka khawatirkan mengenai keadaan dirinya. Sejenak, bocah berambut ikal itu merogoh saku celananya dengan gaya cengengesan seperti biasa. Ia lantas mengeluarkan segenggam sesuatu yang berbentuk bulat serta berwarna merah kecokelatan dari dalam sana dan menyodorkannya kepada para rekannya.
“Ambiklah. Pagi ini ku dapet banyak. Agik musim keramunting[4],” ujar bocah polos itu kemudian.
Saban pagi, Ikal memang telah terbiasa singgah sejenak di antara rimbun semak keramunting liar untuk memanen buah yang telah matang sempurna. Ia tahu, teman-temannya pasti gemar sekali mengonsumsi buah yang rasanya manis dengan kombinasi sedikit masam dan kelat tersebut. Bagi Ikal, melihat senyum rekan-rekannya ketika menerima ‘oleh-oleh’ sederhana dari tangan mungilnya tersebut, sudah cukup menjadi kebahagiaan tersendiri.
Dan semenjak sepedanya rusak dua tahun silam, setiap kali musim keramunting tiba, Ikal bisa membawa sekantong penuh buah liar tadi. Pasalnya, dengan berjalan kaki, Ikal jadi lebih mudah mengintai buah-buah yang masak ketimbang ketika ia melaju dengan mengendarai sepedanya. Sejak dua tahun itu pula, Ikal jadi terbiasa menempuh jarak belasan kilometer untuk menuju sekolah saban hari. Tentu saja selain hari Minggu. Sebab, di masa liburan itu, Ikal lebih memilih membantu Liana—ibunya—untuk membuat rusip[5]. Sebagai seorang janda melarat dengan satu orang anak usia sekolah, sehari-hari Liana hanya bisa menggantungkan nasibnya menjadi buruh pemilah ikan hasil tangkapan nelayan dengan bayaran yang tak seberapa. Jika beruntung, sang tauke akan berbaik hati menambahkan upahnya dengan sekantong ikan teri yang kelak bisa Liana jadikan sebagai bahan baku pembuatan rusip. Selain itu, menjelang lebaran, beberapa pengusaha mikro di kampung pesisir sebelah selatan yang membuat getas[6] atau kericu[7], tak akan sungkan untuk meminta bantuan jasanya. Namun demikian, dari segala peluang yang ada itu sudah cukup disyukuri oleh Liana.
Dulu, ketika ayah Ikal masih hidup, kehidupan mereka masihlah terbilang berkecukupan ketimbang kondisi sekarang. Sebagai seorang nelayan, hampir setiap kali pulang melaut, ayah Ikal bisa menjual hasil tangkapannya kepada tauke besar di dekat pelabuhan. Pundi-pundi rupiah yang ia terima masih mampu untuk menutupi sejumlah utang di toko Ko Ahen yang berdiri tepat di sudut pasar, tempat di mana Liana kerap meminjam segala jenis barang kebutuhan pokok: beras, telur, bawang, dan gula. Namun, di hari nahas belasan tahun lalu, pada akhirnya kabar duka itu bertandang pula ke telinga Liana. Di satu pagi yang mendung dan sangat berangin, seorang rekan nelayan sang suami datang ke kediaman mereka yang terbilang sempit.
“Suamimu tenggelam di laut. Ombak besar telah menerjang perahunya.” Begitu ucapan tadi terdengar, seolah menjelma petir di indra pendengaran Liana yang seakan langsung berdenging. Sepasang tungkai perempuan itu pun lunglai. Jika saja rekan sang suami tak segera menangkap tubuh perempuan hamil itu, tentu saja Liana akan langsung limbung di atas tanah pasir yang menjadi alas rumahnya. Yang lantas melintas dan berkelindan di kepala Liana kala itu adalah bagaimana nasib serta masa depan anak yang masih ada dalam kandungannya? Akankah ia mampu mengurus dan membesarkannya seorang diri hingga dewasa?
Benar saja, akibat petaka bertahun-tahun lalu itu, segalanya lantas berubah. Selain kelak harus berjuang menjadi orangtua tunggal, Liana juga harus siap menjadi tulang punggung keluarga. Berbagai pekerjaan serabutan ia lakoni meski dalam keadaan hamil tua, demi agar bisa membayar biaya persalinan yang dapat terjadi kapan saja. Beruntung, masih ada rekan-rekan almarhum suaminya yang berkenan membantu sejumlah materi, meski Liana tahu kalau kehidupan perekonomian mereka pun tak kalah sengsara dibanding dirinya.
Semenjak Ikal lahir, Liana pernah kepikiran untuk ikut membuka usaha pembuatan getas kecil-kecilan seperti kebanyakan istri nelayan yang lain. Namun, perempuan itu sama sekali tidak memiliki cukup modal. Sempat ingin meminjam sekarung sagu sebagai bahan baku kepada Ko Ahen, namun segera Liana urungkan. Ia hanya ragu akan dapat membayarnya kelak. Mengingat utang barang-barang kebutuhan sehari-hari ia dan Ikal saja masih menumpuk di sana. Dengan penghasilan yang kini sudah tak menentu, beruntung Ko Ahen masih berbaik hati untuk mau menambah daftar panjang catatan milik Liana di buku bon pelanggan miliknya.
“Sekolah yang bener, Jang. Biar dak melarat macem mamak ka ni[8],” petuah Liana pada Ikal di suatu waktu. Biar bagaimanapun, ia ingin Ikal bisa mengangkat derajat masa depannya sendiri melalui bangku pendidikan. Perempuan itu percaya kalau pendidikan bisa menyelamatkan anaknya kelak dari jerat lingkaran kemiskinan. Sebagai seorang ibu, ia tentu ingin anaknya suatu hari nanti bisa hidup jauh lebih layak dari dirinya. Kalau bisa, Liana ingin Ikal kelak menjadi seorang pegawai negeri seperti apa yang juga mendiang suaminya semogakan dulu.
“Semoga nanti bayi di dalam kandunganmu bise sukses macem mereka, Na,” ujar sang suami kala beberapa pegawai negeri berseragam kuning khaki dari Dinas Perikanan kabupaten datang mengunjungi kampung mereka untuk melakukan penyuluhan kepada para nelayan mengenai cara menjaga agar kualitas hasil tangkapan ikan mereka dapat bertahan lebih lama. Dengan begitu, nelayan-nelayan kecil seperti mereka akan mampu menjaga harga ikan tetap stabil meski harus dibawa dan dipasarkan sendiri ke Kota Pangkalpinang, ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Iya, Pak. Cuma sekolah yang bise bikin anak kita jadi pegawai negeri macem mereka. Jangan macem kite ni yang SD bai dak sampai tamat[9].”
Berbekal cita-cita yang ia gantungkan tinggi-tinggi di pundak Ikal sejak dalam kandungan itulah, Liana berusaha mati-matian untuk bisa terus menyekolahkan sang putra hingga ke jenjang mana pun yang bocah itu inginkan. Perempuan itu percaya bahwa setiap orang berhak bermimpi. Meski ia pun paham benar bahwa untuk mewujudkan mimpi tadi tidaklah mudah. Terkesan mustahil. Apalagi dengan statusnya yang hanya seorang janda miskin berpenghasilan seadanya dari upah bekerja sebagai buruh serabutan. Namun, Liana merasa tak boleh begitu saja mengeluh, apalagi sampai menyerah. Semua akan ia lakukan demi masa depan Ikal dan harapannya untuk bisa menjadikan bocah itu seorang pegawai negeri berseragam rapi. Bukan seperti almarhum bapaknya atau dirinya yang cukup mengenakan pakaian seadanya untuk melaut ataupun bekerja menjadi buruh pilah ikan di pelelangan.
Di tengah segala angan yang melambung kian tinggi seperti sekawanan camar yang melayang di puncak cakrawala saban senja, Liana juga mesti memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tahun depan, Ikal sudah akan lulus SD dan hendak melanjutkan pendidikan ke bangku SMP di kabupaten. Mulai sekarang, Liana juga harus bisa memutar otak dan semakin mengeratkan pengeluaran serta ikat pinggang. Bagaimana tidak, selain harus memikirkan bagaimana ia akan melunasi uang pembangunan sekolah menengah di awal tahun ajaran baru, Liana juga tak tahu lagi dari mana ia akan bisa mendapatkan uang untuk membeli seragam SMP Ikal.
Untuk seragam putih biru, Ikal tidak akan bisa memakai seragam lamanya yang putih merah. Selama enam tahun duduk di bangku sekolah dasar, jika diingat-ingat, Ikal hanya dua kali merasakan bagaimana memiliki seragam baru. Pertama, ketika bocah itu baru mendaftar di kelas satu. Kedua, sekaligus yang terakhir, saat Ikal akan naik ke kelas lima. Itu pun lantaran seragam lamanya tak lagi muat di badan Ikal yang mulai tumbuh. Padahal sebelumnya Liana telah berjaga-jaga akan hal tersebut. Setiap kali membelikan seragam baru untuk putra semata wayangnya itu, ia akan memilih ukuran yang dua hingga tiga kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Semua terpaksa Liana lakukan supaya seragam tersebut bisa Ikal pakai selama bertahun-tahun tanpa perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membeli seragam baru di setiap kenaikan kelas seperti bocah-bocah kebanyakan.
Jika seragam Ikal mulai tampak pudar, Liana selalu punya trik jitu untuk membuatnya terlihat jadi setingkat lebih baru. Untuk baju putih yang mulai kusam, sebelum dicuci, Liana akan membubuhkan sejumput monosodium glutamat[10] ke dalam air rendaman. Sedangkan untuk celana merah Ikal yang lama, akan perempuan itu masukan beberapa saat ke dalam ember berisi rendaman daun ketapang yang ia percaya akan membuat celana sekolah lama Ikal tersebut menjadi terlihat sedikit lebih merah dari sebelumnya. Beruntungnya, sebagai anak yang tak banyak tingkah, Ikal tidak pernah sekali pun mengeluh atau menuntut seragam baru pada sang ibu. Meski hal tersebut justru kerap membuat sepasang mata Liana berkabut. Perempuan berambut gelombang itu terkadang juga menganggap Tuhan sedemikian tak adil pada Ikal. Andai saja bocah penurut dan berhati baik itu tidak terlahir dari rahimnya, barangkali ia akan memiliki kehidupan yang jauh lebih layak dari saat ini.
***
[1] tumbuhan semak dengan bunga berwarna merah hijau, buahnya bulat berwarna merah kecokelat-cokelatan dan enak dimakan, daunnya dapat digunakan sebagai obat luka. Sering pula disebut kemunting (Rhodomyrtus tomentosa)
[2] Kubangan bekas tambang timah
[3] "Kamu kenapa, Kal?"
[4] "Ambillah. Pagi ini aku dapat banyak. Sedang musim keramunting."
[5] Makanan tradisional masyarakat Bangka yang terbuat dari ikan teri segar yang telah difermentasikan. Biasanya dimakan sebagai pendamping lalapan daun singkong.
[6] Camilan yang berbahan dasar ikan tenggiri. Masyarakat Bangka juga dengan kerap menyebutnya dengan nama lain, yaitu keretek.
[7] Camilan berbentuk bulat lonjong yang berbahan dasar telur cumi dan sagu.
[8] "Sekolah yang baik, Nak. Biar tidak miskin seperti ibumu ini."
[9] "Jangan seperti kita ini yang SD saja tidak sampai lulus."
[10] Bahan penyedap rasa
Other Stories
Bekasi Dulu, Bali Nanti
Tersesat dari Bali ke Bekasi, seorang chef-vlogger berdarah campuran mengubah aturan no-ca ...
Percobaan
percobaan ...
Baca Tanpa Dieja
itulah cara jpload yang bener da baik ...
Hold Me Closer
Pertanyaan yang paling kuhindari di dunia ini bukanlah pertanyaan polos dari anak-anak y ...
Melodi Nada
Dua gadis kakak beradik dari sebuah desa yang memiliki mimpi tampil dipanggung impian. Mer ...
Ada Apa Dengan Rasi
Saking seringnya melihat dan mendengar kedua orang tuanya bertengkar, membuat Rasi, gadis ...