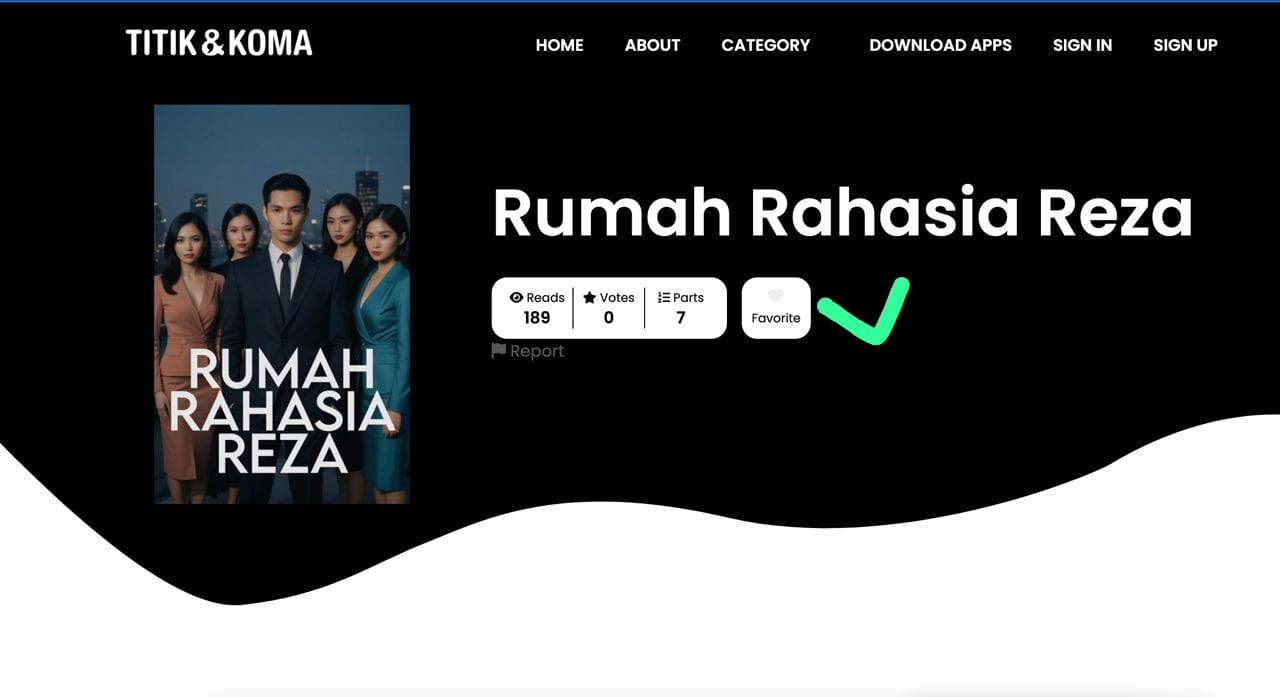Menerima Yang Mampu Menyongkong Harapan
Wanita itu menggaruk lengannya. Musonif mengalihkan pandangannya pada katalog, “Jadi, kau mau pasang di area mana?”
“Scaffold. Aku yakin dengan pilihanku. Aku sudah membayangkan dua tindikan dihubungkan dengan satu barbel panjang dan akan membuatku terlihat menawan.”
“Kau yakin?”
“Tentu!” katanya tersinggung.
“Aku hanya khawatir wawancaramu tidak berjalan dengan baik nantinya.”
Tiba-tiba, Akasia tertawa. “Ya Tuhan… Apa yang sedang kau lakukan? Tolong lakukan saja. Sikapmu mengingatkanku pada seseorang. Aku jadi lupa tujuan awalku datang ke kios tindik ini; aku ingin membuat seseorang terpukau dengan penamipalanku.”
“Jadi kau tenang saja, ini bukan untuk wawancara kerja minggu depan.” Akasia bersikap santai, “Aku akan membuat direktur rumah sakit yang memecatku tidak mengedipkan matanya begitu dia melihatku. Aku masih heran dia memecatku hanya karena seorang ibu sinting yang membuang anaknya setiap pukul enam pagi di daycare dan memungutnya kembali pukul delapan malam. Bahkan pada hari libur pun dia akan tetap membuangannya pada gim. Bodohnya, dia masih mengeluh dan bertanya mengapa sikap putranya semena-mena padanya. Bukankah putranya itu menirunya?” Akasia menarik napas tertawa lebih geli.
“Dia tidak terima saat aku mengatakan fakta sampai dia ingin mendorongku, tapi aku lebih dulu mendorongnya. Kenyataannya mereka telah kehilangan putra mereka. Dan konyolnya, direktur rumah sakit tidak terima aku memperlakukan istrinya seperti itu. Saat aku dipanggil ke ruangannya, Aku mengatakan, \'bukankah kita hanya harus menerima jika sesuatu hilang dari kita. Tapi, direktur itu justru malah tambah mengamuk.” Akasia menyesap liurnya yang hampir keluar.
Musonif mengangkat bahu kecil, dia tidak tahu mengapa wanita itu berbicara kasar seperti itu. “Kau tidak bisa meninta seseorang untuk menerima sesuatu yang terjadi diluar kehendak mereka. Itu tidak sama seperti kau meraut pensilmu yang patah, tapi seberapa tajam pisau itu membuat pensilmu menjadi runcing.” Katanya sedikit sinis.
Akasia menghela napas dingin. “Bisakah kamu menerima jika sesuatu itu… bukan hlang, melainkan pergi? Atau katakanlah, kekuatanmu tidak mampu memilikinya? Aku terlalu pengar mendengar, aku tahu seperti apa anakku, aku mencintai anakku, aku berhak atasnya.”
Musonif terdiam, menatapnya dalam. “Kau terdengar seperti orang yang sedang bersembunyi.” Munosif menarik napas pelan. “Tapi bagaimana kalau kepergian itu adalah pelajaran yang tidak pernah kau sukai.”
Akasia membuang wajahnya, lalu tertawa keras. “Aku tidak suka caramu memasak. Memangnya siapa yang menyukai belajar? Orang hanya ingin tahu. Mereka membutuhkan jawaban atas pertanyaan mereka. Padahal pertanyaan itu lah yang menambah masalah mereka. Duduk berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hanya untuk membuka buku dari halaman ke halaman. Alih-alih untuk mendapatkan sebuah jawaban mereka hanya perlu pindah… Pergi.”
Musonif menghela napas, “Kalau begitu, jangan membicarakan tentang menerima jika kau tidak benar-benar mengerti artinya.”
Kali ini Akasia tertawa lebih keras. “Justru menerimalah agar kau mengerti. Tidak ada satu pun yang dapat menyongkong harapanmu kecuali menerima.” Akasia menghela napas. “Kalau begitu tidak jadi. Aku sudah tidak berselera.” Akasia bangun dari kursi, lalu pergi begitu saja.
Sejak awal Musonif mengetahuinya, wanita itu bukanlah Tanika. Namun, kemiripan wajah Akasia dengan putrinya membuat Musonif menunggunya setiap hari lewat di depan kiosnya. Ia sadar kehadiran wanita itu tidak pernah bisa menyentuh kekosongan dalam dirinya.
Pertemuannya dengan Akasia bukan pada hari ini saja, melainkan sejak tujuh tahun lalu, tepat pada hari saat Eda meninggalkannya. Saat itu, Akasia baru saja turun dari ojek lalu berjalan kaki melewati kiosnya. Lalu, pada hari-hari berikutnya, Akasia kembali melewati kiosnya. Kadang ia berlari seperti sedang dikejar waktu, kadang berjalan santai sambil menari kecil, atau sambil menendang-nendang batu kerikil jalan. Ia selalu mengalungkan tiket kereta di lehernya. Rambutnya berubah-ubah: kadang lurus dengan warna hitam panjang sebahu, terkadang sedikit kecokelatan, pernah juga dengan beberapa helai rambut keabu-abuan, atau bahkan ombre keunguan, dicatok keriting, ataupun ikal. Penampilannya selalu kasual dengan sepatu kets, rambut diikat, dan kadang memakai topi.
Musonif bahkan hafal kapan Akasia akan melewati kiosnya. Namun, ia tidak pernah menceritakan hal ini pada Wayan, ia takut jika dirinya dianggap tidak tumbuh sama sekali. Ia tahu bagaimana cara Wayan memandangnya selama lima belas tahun; mengapa Wayan meminta saham kepemilikan enam puluh lima persen, mengapa Wayan memutuskan untuk masuk terlambat dan pulang lebih awal, mengapa Wayan berhenti memutar musik, dan mengapa ia tidak lagi bicara dengannya. Semuanya, dilakukan Wayan demi kewarasannya. Namun, simpati Wayan itu justru yang membuat Musonif semakin tak berdaya. Apa yang dilakukan Wayan padanya, menyadarkan Musonif pada kegagalannya terhadap dirinya sendiri.
Sementara itu, tidak ada upaya pencarian atas kepergian Eda. Dengan berat hati, Musonif menerima keputusan itu demi kesehatan Eda yang kian hari kian menurun. Musonif sepenuhnya menyadari, nalurinya yang tak bisa berhenti menyalahkan Eda membuatnya tak lagi mampu bicara pada istrinya itu. Ketidakmampuannya telah menyakiti seorang yang dicintainya. Bagi Musonif, semua kegagalan sudah cukup memakan seluruh waktu dan hidupnya.
Dan, ia menerima penuh pandangan itu. Lima belas tahun, putus asa dan harapan carut-marut. Gelisah, resah, bersalah, dan ketidakpastian menghantuinya setiap waktu. Waktunya habis untuk berduka yang tertunda.
Selama waktu berjalan, Musonif hanya tidak tahu harus berkata apa. Apa yang harus dikatakan pada Eda, pada Wayan, pada dirinya sendiri. Berhari-hari ia mencoba mengendalikan emosinya, bertahan untuk tidak gila. Yang terlintas jika dirinya gila, lalu bagaimana dengan Eda, Wayan, kios tindik, dan Tanika? Bagaimana jika suatu hari Tanika pulang dan menemuinya dalam keadaan yang bahkan membuatnya takut? Semua itu seperti penyakit. Tiap kali memikirkannya, membuat dada Musonif sesak.
Yang tidak diketahui siapa pun, Musonif telah lama menunggu wanita itu datang. Menunggu untuk dapat mengenal Akasia. Seandainya Eda masih mau bicara dengannya, ia pasti akan mengenalkan Akasia padanya.
Tanpa sadar, percakapannya dengan Akasia menyadarinya bahwa sesuatu yang hilang, mungkin saja bukan hilang, melainkan pergi. Sebab bisa jadi kekuatanmu tidak mampu untuk memilikinya. Dan, hanya menerima yang dapat menyongkong harapan. Musonif memutuskan untuk meninggalkan kios, menyerahkkan seluruhnya pada Wayan sebagai ganti rugi atas waktu yang telah ia buang. Dan berhenti menatap jalan, berhenti menunggu Tanika datang.
Other Stories
Don't Touch Me
Malam pukul 19.30 di Jakarta. Setelah melaksanakan salat isya dan tadarusan. Ken, Inaya, ...
Kepingan Hati Alisa
Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita paruh baya berkerudung hitam, berbincang agak ...
Dia Bukan Dia
Sebuah pengkhianatan yang jauh lebih gelap dari perselingkuhan biasa. Malam itu, di tengah ...
Percobaan
percobaan ...
After Honeymoon
Sama-sama tengah menyembuhkan rasa sakit hati, bertemu dengan nuansa Pulau Dewata yang sel ...
Pucuk Rhu Di Pusaka Sahara
Mahasiswa Indonesia di Yaman diibaratkan seperti pucuk rhu di Padang Sahara: selalu diuji ...