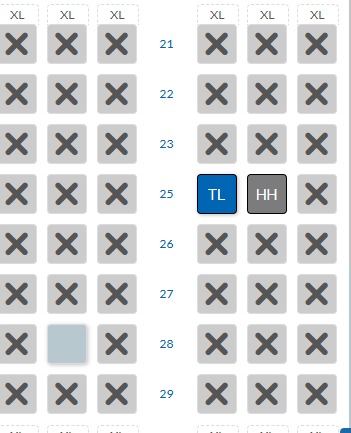BABAK I ILUSI YANG DISEBUT RINDU
Ketika Kesepian Menyamar Sebagai Cinta
Irna pertama kali menyadari ada yang keliru dengan caranya mencintai bukan ketika ditinggalkan, melainkan ketika ia tetap merasa sepi meski sedang ditemani. Sepi itu tidak gaduh, tidak menangis, tidak menuntut. Ia hadir seperti kabut tipis yang merayap pelan, membuat segala sesuatu tampak ada, tetapi tidak pernah benar-benar terasa.
Ia hidup sebagaimana orang-orang pada umumnya hidup: bekerja, tertawa secukupnya, menyimpan lelah di tempat yang tidak terlihat. Dari luar, hidup Irna tampak rapi. Ia tidak kekurangan apa pun yang secara sosial dianggap penting. Namun di dalam dirinya, selalu ada ruang kosong yang tak pernah terisi, meski berkali-kali ia coba penuhi dengan kehadiran orang lain.
Irna menyebut ruang itu rindu.
Bukan rindu kepada seseorang tertentu. Bukan rindu pada masa lalu. Rindu itu seperti rasa haus yang tidak tahu air mana yang dapat memuaskannya. Maka setiap kali seseorang datang—membawa perhatian, janji, atau sekadar kesediaan untuk tinggal—Irna mengira itulah jawabannya. Ia menyambut dengan harap yang terlalu cepat tumbuh.
Dalam relasi-relasi sebelumnya, Irna dikenal sebagai sosok yang “mudah memahami.” Ia tidak banyak menuntut, jarang bertanya, selalu berusaha mengerti. Ia percaya, cinta adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Maka ia menyesuaikan: jadwal, selera, bahkan cara berpikir. Sedikit demi sedikit, ia mengecil, agar muat dalam kehidupan orang lain.
Tak ada yang memaksanya. Dan justru di situlah masalahnya.
Irna tidak pernah merasa dipaksa untuk mengalah. Ia melakukannya dengan sukarela, dengan senyum yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah bentuk kedewasaan. Ia tidak menyadari bahwa di balik sikap “mengerti” itu, ada ketakutan purba yang bekerja diam-diam: takut ditinggalkan, takut tidak dipilih, takut tidak cukup.
Di kota tempat ia tinggal, cinta diperlakukan seperti pencapaian. Menikah tepat waktu, memiliki pasangan stabil, membangun hidup bersama—semua itu dianggap bukti bahwa seseorang telah berhasil mengelola hidupnya. Irna tumbuh dengan narasi itu. Ia tidak pernah benar-benar mempertanyakannya, hanya menjalani.
Namun setiap kali relasi berakhir—selalu dengan alasan yang terdengar masuk akal—Irna merasakan kehampaan yang sama. Seolah bukan orang lain yang pergi, melainkan bagian dari dirinya yang selama ini ia titipkan pada orang tersebut.
Ia mulai bertanya-tanya, dalam sunyi yang panjang:
Apakah yang ia cari selama ini benar-benar cinta, atau sekadar rasa aman?
Pertanyaan itu tidak segera ia jawab. Irna terbiasa menunda kejujuran yang menyakitkan. Ia lebih suka menyebut lukanya sebagai nasib, bukan pilihan. Lebih mudah merasa menjadi korban daripada mengakui bahwa ia turut berperan dalam pola yang sama.
Setiap malam, setelah hari melelahkan, Irna duduk di kamarnya yang sederhana. Ia menatap ponsel, berharap ada pesan masuk, bukan dari siapa pun secara spesifik—hanya tanda bahwa ia diingat. Ketika layar tetap gelap, rindu itu kembali menguat. Ia menyebutnya rindu, karena kata itu terdengar lebih indah daripada kesepian.
Padahal, yang ia rasakan bukan rindu pada seseorang, melainkan rindu pada versi dirinya yang merasa utuh saat dicintai.
Irna mulai menyadari bahwa ia sering jatuh cinta bukan pada manusia yang utuh, melainkan pada kemungkinan: kemungkinan dimengerti, kemungkinan diterima, kemungkinan diselamatkan dari kesendirian. Ia mencintai harapan lebih dari kenyataan. Dan ketika kenyataan tidak mampu memenuhi harapan itu, ia kecewa—pada orang lain, bukan pada ekspektasinya sendiri.
Dalam dirinya terjadi dialog batin yang tidak pernah selesai. Satu suara berkata bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Suara lain bertanya, berapa banyak diri yang harus dikorbankan agar cinta tetap layak disebut cinta?
Ia belum menemukan jawabannya.
Pada suatu sore, Irna berjalan sendirian melewati taman kecil dekat tempat tinggalnya. Ia melihat pasangan-pasangan duduk berdampingan, sebagian berbincang, sebagian diam. Ia memperhatikan bagaimana diam itu berbeda-beda: ada diam yang nyaman, ada diam yang penuh jarak. Irna bertanya dalam hati, berapa banyak orang yang bertahan dalam relasi bukan karena cinta, melainkan karena takut sendirian.
Pertanyaan itu menakutkannya, sebab ia merasa termasuk di dalamnya.
Irna mulai mengingat kembali semua relasi yang pernah ia jalani. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kelelahan yang jujur. Ia melihat pola yang berulang: ia datang dengan harapan besar, bertahan dengan pengorbanan, lalu pergi dengan rasa bersalah. Ia selalu merasa kurang—kurang sabar, kurang dewasa, kurang mencintai dengan benar.
Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa mungkin masalahnya bukan pada kurangnya cinta, melainkan pada arah cinta itu sendiri.
Malam itu, Irna menulis di buku catatan kecilnya, sesuatu yang belum pernah ia tulis sebelumnya:
“Aku tidak tahu apakah aku benar-benar mencintai mereka, atau hanya mencintai diriku sendiri saat merasa dibutuhkan.”
Tulisan itu membuatnya terdiam lama. Ada rasa bersalah yang menyelinap, seolah ia baru saja mengakui dosa yang tak pernah ia sadari. Namun bersamaan dengan itu, ada kelegaan kecil—kelegaan karena akhirnya ia berani jujur, meski hanya kepada dirinya sendiri.
Irna mulai memahami bahwa rindunya selama ini bukanlah panggilan cinta sejati, melainkan sinyal dari kekosongan yang belum ia kenali. Ia terlalu sibuk mencari orang yang bisa mengisi ruang itu, tanpa pernah bertanya mengapa ruang itu kosong sejak awal.
Ia belum siap menerima sepenuhnya kesadaran itu. Terlalu banyak hal yang harus ia bongkar: keyakinan lama, pola pikir yang diwariskan, luka yang ia anggap tak penting. Namun untuk pertama kalinya, Irna tidak lari dari pertanyaan-pertanyaan itu.
Babak ini dalam hidupnya bukan tentang menemukan seseorang. Melainkan tentang kehilangan ilusi—ilusi bahwa cinta selalu datang dari luar, bahwa keutuhan bisa dipinjam dari orang lain, bahwa rindu selalu berarti kurangnya kehadiran seseorang.
Irna belum tahu ke mana pencarian ini akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal: rindu yang selama ini ia rawat ternyata bukan peta menuju cinta, melainkan pintu menuju dirinya sendiri.
Dan pintu itu, meski menakutkan, akhirnya mulai ia buka.
Other Stories
Cahaya Menembus Semesta
Manusia tidak akan mampu hidup sendiri, mereka membutuhkan teman. Sebab dengan pertemanan, ...
Jjjjjj
ghjjjj ...
Tukar Pasangan
Ratna, wanita dengan hiperseksualitas ekstrem, menyadari suaminya Ardi berselingkuh dengan ...
Pitstop: Rewrite The Stars. Menepi Dari Dunia, Menulis Ulang Takdir
Bagaimana jika hidup Anda yang tampak sempurna runtuh hanya dalam sekejap? Dari ruang rapa ...
Ayudiah Dan Kantini
Waktu terasa lambat karena pahitnya hidup, namun rasa syukur atas persahabatan Ayudyah dan ...
Kastil Piano
Kastil Piano. Sebuah benda transparan mirip bangunan kastil kuno yang di dalamnya terdapat ...