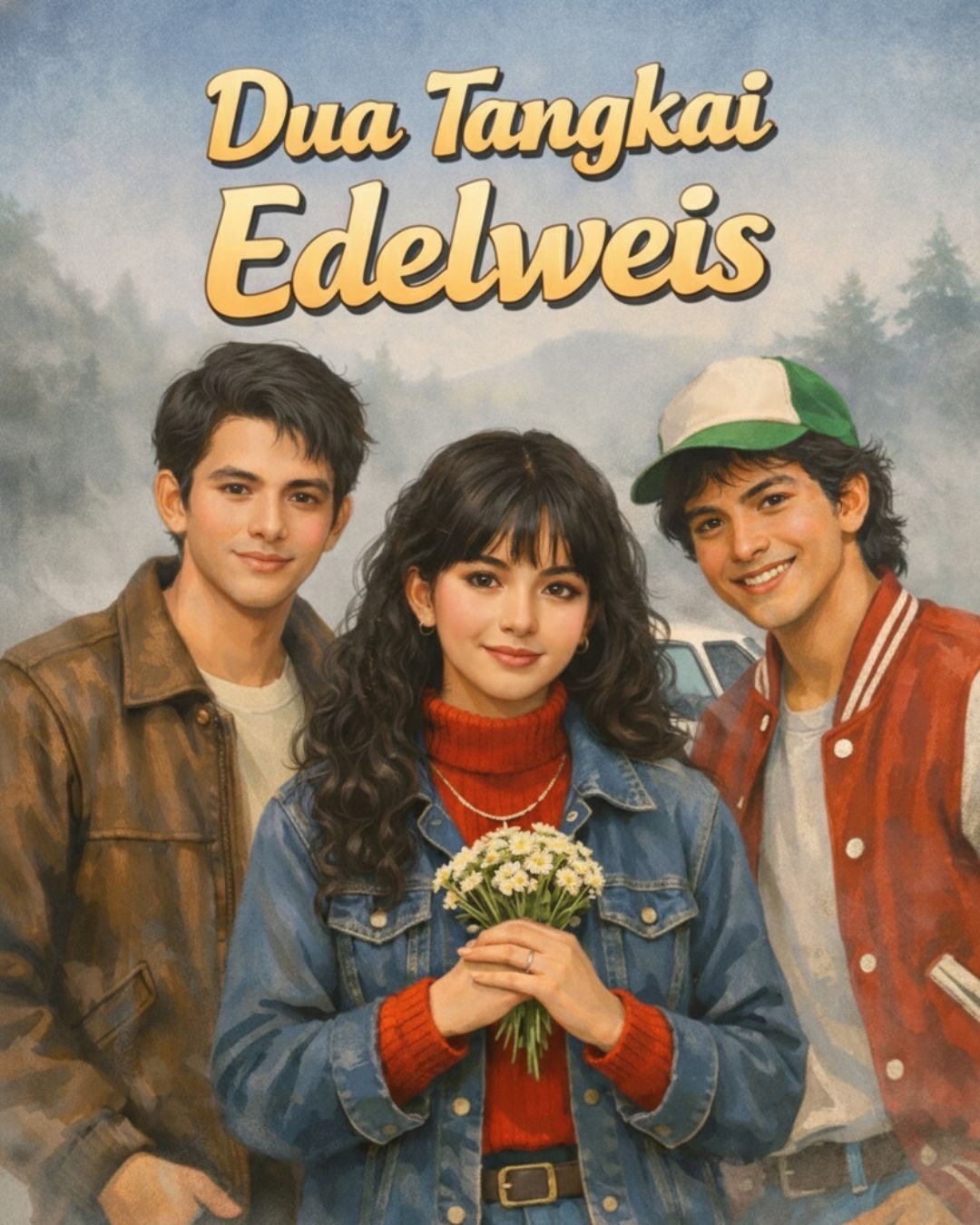TELEPON DARI CIANJUR
Beberapa bulan setelah Bagas dan keluarganya pulang ke Cianjur, hidup Rani kembali dipenuhi rutinitas.
Hari-harinya kembali padat: sekolah, latihan, rapat, lomba, tugas, dan ekskul yang membuat waktunya terasa selalu kurang.
Ia jarang memikirkan Cianjur.
Bukan karena lupa—
tapi karena hidupnya terlalu ramai untuk memberi ruang pada satu kota kecil yang pernah begitu sunyi di hatinya.
Sore itu, hujan turun tipis di Cirebon.
Rani sedang mengerjakan tugas di kamar ketika telepon rumah berdering.
“Ibu!” panggil Ayah dari ruang tengah.
Ibu mengangkat.
Rani mendengar suara lirih Ibu dari balik pintu.
“Iya, Neng…”
“Iya…”
“Ya Allah…”
Ada jeda panjang.
Lalu langkah kaki Ibu mendekat ke kamar Rani.
“Ran…”
Nada itu membuat Rani berdiri.
“Ada apa, Bu?”
Ibu menatapnya. Matanya basah.
“Itu Bi Nadin.”
Rani menelan ludah.
“Kinkin… meninggal.”
Rani seperti tak mengerti arti kata itu.
“Meninggal?”
Ibu mengangguk pelan.
“Kata Bi Nadin, Kinkin kena demam berdarah. Telat dibawa ke rumah sakit… karena nggak punya cukup biaya.”
Kalimat itu seperti palu.
Dada Rani sesak.
Ia mundur selangkah, lalu duduk di tepi ranjang.
Dunia terasa terlalu sunyi.
Tanpa suara, Rani masuk ke lemari.
Menarik jaketnya.
Dan menemukan edelweis itu.
Ia memeluknya.
Dan tangisnya pecah.
Tangis yang selama ini ia simpan—tentang Cianjur, tentang Kinkin, tentang pagi berkabut dan janji kecil.
Dalam pelukan bunga kering itu, Rani belajar satu hal yang paling berat:
ikhlas.
Bukan karena ia siap,
tapi karena hidup memaksanya.
Hari-harinya kembali padat: sekolah, latihan, rapat, lomba, tugas, dan ekskul yang membuat waktunya terasa selalu kurang.
Ia jarang memikirkan Cianjur.
Bukan karena lupa—
tapi karena hidupnya terlalu ramai untuk memberi ruang pada satu kota kecil yang pernah begitu sunyi di hatinya.
Sore itu, hujan turun tipis di Cirebon.
Rani sedang mengerjakan tugas di kamar ketika telepon rumah berdering.
“Ibu!” panggil Ayah dari ruang tengah.
Ibu mengangkat.
Rani mendengar suara lirih Ibu dari balik pintu.
“Iya, Neng…”
“Iya…”
“Ya Allah…”
Ada jeda panjang.
Lalu langkah kaki Ibu mendekat ke kamar Rani.
“Ran…”
Nada itu membuat Rani berdiri.
“Ada apa, Bu?”
Ibu menatapnya. Matanya basah.
“Itu Bi Nadin.”
Rani menelan ludah.
“Kinkin… meninggal.”
Rani seperti tak mengerti arti kata itu.
“Meninggal?”
Ibu mengangguk pelan.
“Kata Bi Nadin, Kinkin kena demam berdarah. Telat dibawa ke rumah sakit… karena nggak punya cukup biaya.”
Kalimat itu seperti palu.
Dada Rani sesak.
Ia mundur selangkah, lalu duduk di tepi ranjang.
Dunia terasa terlalu sunyi.
Tanpa suara, Rani masuk ke lemari.
Menarik jaketnya.
Dan menemukan edelweis itu.
Ia memeluknya.
Dan tangisnya pecah.
Tangis yang selama ini ia simpan—tentang Cianjur, tentang Kinkin, tentang pagi berkabut dan janji kecil.
Dalam pelukan bunga kering itu, Rani belajar satu hal yang paling berat:
ikhlas.
Bukan karena ia siap,
tapi karena hidup memaksanya.
Other Stories
Kado Dari Dunia Lain
"Jika Kebahagiaan itu bisa dibeli, maka aku akan membelinya." Di tengah kondisi hidup Yur ...
Breast Beneath The Spotlight
Di tengah mimpi menjadi idol K-Pop yang semakin langka dan brutal, delapan gadis muda dari ...
Melinda Dan Dunianya Yang Hilang
Melinda seorang gadis biasa menjalani hari-hari seperti biasa, hingga pada suatu saat ia b ...
Kucing Emas
Kara Swandara, siswi cerdas, mendadak terjebak di panggung istana Kerajaan Kucing, terikat ...
Bisikan Lada
Kejadian pagi tadi membuat heboh warga sekitar. Penemuan tiga mayat pemuda yang diketahui ...
Blind
Ketika dunia gelap, seorang hampir kehilangan harapan. Tapi di tengah kegelapan, cinta dar ...