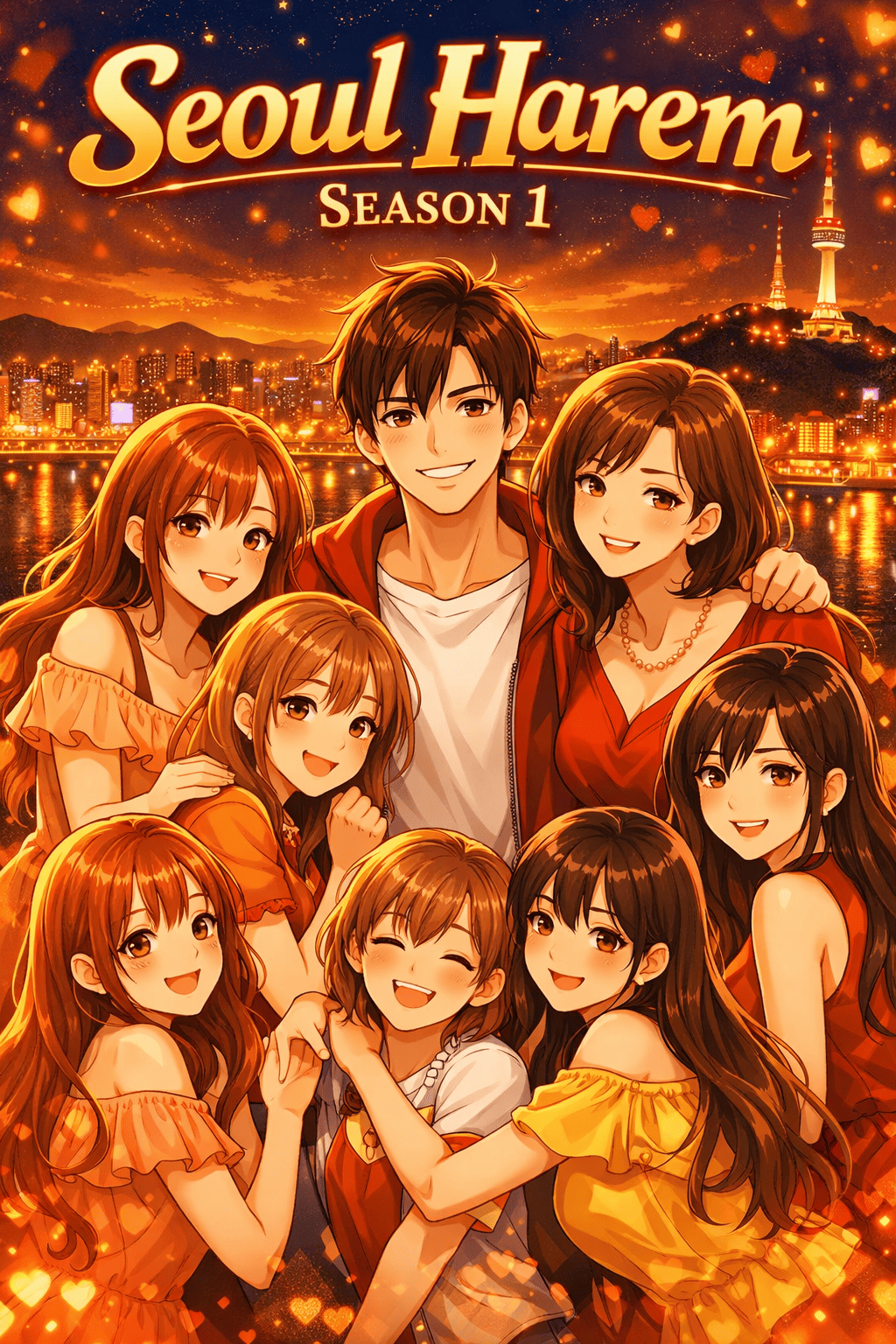Bab 1
Kopi yang Terlalu Dekat
Antika menghapus paragraf yang sama untuk keempat kalinya.
Kursor berkedip di ujung kalimat seperti ejekan kecil yang konsisten. Ia tidak melanjutkan. Ia juga tidak menyerah. Ia hanya menatap layar terlalu lama, berharap sesuatu berubah dengan sendirinya.
Jam di pojok kanan atas menunjukkan 21.37.
Deadline tinggal dua jam dua puluh tiga menit.
Di luar jendela kafe, kota bergerak dengan ritme orang-orang yang sudah memutuskan hari ini cukup. Di dalam, hampir semua meja dipenuhi laptop. Tidak ada tawa keras. Tidak ada obrolan santai. Tempat itu tidak terasa seperti kafe—ia terasa seperti ruang tunggu kolektif bagi orang-orang yang percaya produktivitas bisa diperas dari kopi dan Wi-Fi.
Antika duduk di meja nomor empat sejak sore.
Bukan karena nyaman.
Bukan karena strategis.
Karena hanya meja itu yang colokannya masih hidup.
Latte di depannya sudah dingin. Busanya mengempis. Sama seperti keyakinannya pada bab yang sedang ia tulis.
“Fokus,” gumamnya, tapi jarinya sudah bergerak lebih cepat dari pikirannya.
Ia mengetik.
Ia menatap matanya dan tahu, cintanya telah pulang.
Antika berhenti.
Membaca ulang.
Keningnya mengerut.
“Apaan sih,” desisnya, lalu menekan delete tanpa ragu.
Sudah tiga hari ia terjebak di bab ini. Sudah seminggu ia memaksa emosi lama bekerja kembali. Menulis romansa selalu seperti itu: orang-orang mengira ini soal perasaan, padahal sebagian besar waktu hanyalah negosiasi dengan kelelahan.
Ponselnya bergetar.
Notifikasi saldo.
Rp 312.000.
Antika tidak membuka detailnya. Angka itu sudah cukup bicara. Ia mengunci layar, menarik napas pendek, lalu kembali ke laptop—
tepat ketika bayangan seseorang menutup sebagian cahaya layar.
“Mbak.”
Suaranya rendah. Tenang. Terlalu tenang untuk jarak sedekat itu.
“Ini colokan saya.”
Antika tidak langsung mendongak. Jemarinya masih bergerak, seolah dengan berpura-pura sibuk, dunia bisa menunggu sedikit lebih lama.
“Siapa cepat, dia dapat, Mas,” jawabnya datar. “Saya sudah di sini dari sore.”
“Saya reservasi meja nomor empat lewat aplikasi.”
Sekarang Antika mendongak.
Pria itu berdiri dengan satu tangan di saku hoodie hitam, satu tangan lagi memegang Americano. Esnya hampir habis. Wajahnya datar, tapi matanya tajam—mata orang yang terbiasa menghitung risiko sebelum bicara.
Antika melirik jam.
21.41.
“Oke,” katanya cepat. “Kita bagi dua. Tapi jangan protes kalau saya sering menghela napas berat. Saya lagi nulis adegan putus cinta yang sangat tragis.”
Pria itu menarik kursi tanpa banyak komentar. Duduk. Menyambungkan charger ke colokan yang sama.
“Terserah,” katanya tanpa menoleh. “Asal jangan nangis beneran. Saya lagi mikirin cara membuang mayat.”
Antika berhenti mengetik.
Menoleh perlahan.
“Maaf?”
“Tokoh saya,” jawabnya singkat, seperti menutup pintu. “Bukan orang sungguhan.”
“Oh.” Antika mengangguk cepat. “Bagus.”
“Kenapa?”
“Soalnya kalau orang sungguhan, saya pindah meja.”
Sudut bibir pria itu bergerak tipis. Hampir tidak bisa disebut senyum.
“Komaruzaman.”
“Antika.”
Tidak ada basa-basi lanjutan.
Mereka kembali ke layar masing-masing.
Keheningan jatuh—bukan yang nyaman, tapi yang tegang. Keheningan dua orang yang sama-sama lelah dan tidak punya energi untuk berpura-pura ramah.
Antika melirik layar Komaruzaman tanpa sadar. Paragrafnya pendek. Kalimatnya dingin. Tidak ada metafora berlebihan. Semuanya terasa terukur, seperti seseorang yang menulis sambil memegang jarak dari emosinya sendiri.
Thriller banget, pikirnya.
Komaruzaman, di sisi lain, melirik laptop Antika. Stiker bunga di sudut layar. Kutipan pastel: Write with feelings. Judul file panjang dan terlalu optimistis.
Romance banget.
Antika menulis seperti sedang berusaha menyelamatkan sesuatu.
Komaruzaman menulis seperti sedang memastikan sesuatu tidak bocor.
Dua jam berlalu tanpa kata.
Jam berubah menjadi 23.02.
Antika mulai gelisah. Bukan karena Komaruzaman. Karena waktu.
Ia baru sadar baterai laptopnya turun lebih cepat dari biasanya. Angkanya bergerak, lalu berhenti seolah ragu.
Di meja lain, seseorang mengeluh soal Wi-Fi yang tiba-tiba putus, lalu tersambung lagi.
Antika meneguk kopi dingin tanpa rasa. Untuk pertama kalinya malam itu, ia berhenti merasa punya waktu.
Ia menutup dokumen, membuka folder, memastikan file final masih ada. Nama file itu memberinya rasa aman palsu:
DRAFT_FINAL_FIX_BANGET.docx
“Fix banget,” gumamnya—terlalu cepat untuk terdengar yakin.
Di luar, hujan turun pelan lalu deras. Musik kafe berubah. Beberapa pengunjung mengeluh. Pegawai mondar-mandir dengan wajah tegang.
Lalu—
Pet.
Lampu berkedip.
Pet.
Gelap.
“Eh—!”
“Lho?”
Suara panik muncul dari berbagai arah. Seseorang mengumpat. Pegawai berteriak minta maaf. Generator belum menyala.
Antika menatap indikator baterai laptopnya.
5%.
Angka itu terasa seperti vonis, bukan informasi.
“Anjir,” bisiknya.
Di meja yang sama, Komaruzaman menatap layar sendiri.
4%.
Mereka saling pandang satu detik—cukup lama untuk saling mengenali kepanikan, terlalu singkat untuk bertindak rasional.
Tidak ada diskusi.
Tidak ada kesepakatan.
Hanya refleks.
Antika menyambar laptop di depannya dan memasukkannya ke tas. Komaruzaman melakukan hal yang sama. Mereka berdiri hampir bersamaan, menerobos kerumunan yang mulai gaduh.
Hujan turun deras saat mereka keluar kafe. Jalanan mengilap. Motor melintas sembarangan. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang mengecek ulang.
Dua laptop perak.
Model sama.
Berat sama.
Dan satu kesalahan kecil yang belum tahu seberapa mahal harganya.
Di kamar kos yang sempit, Antika menyalakan laptop.
Jam menunjukkan 23.47.
Tidak ada waktu untuk membaca ulang. Tidak ada ruang untuk ragu.
Ia membuka dashboard lomba. Klik Create Story.
Judul diisi.
Genre: Romance.
Tag: #Romance #Metropop #Sayembara.
Upload.
Publish.
Selesai.
Antika bersandar di kursi. Napasnya tidak langsung tenang. Bahunya masih tegang. Tangannya belum sepenuhnya berhenti gemetar.
“Aman,” katanya pelan.
Di layar laptop yang sama—yang bukan miliknya—sebuah cerita lain baru saja terbit.
Cerita tentang darah.
Tentang koper.
Tentang seseorang yang tidak percaya pada bahagia.
Dan di tempat lain di kota yang sama, Komaruzaman menutup laptopnya dengan keyakinan serupa.
“Sempurna.”
Other Stories
Testing
testing ...
Seoul Harem
Raka Aditya, pemuda tangguh dari Indonesia, memimpin keluarganya memulai hidup baru di gem ...
Hanya Ibu
Perjuangan bunga, pengamen kecil yang ditinggal ayahnya meninggal karena sakit jantung sej ...
Bangkit Dari Luka
Almira Brata Qeenza punya segalanya. Kecuali satu hal, yaitu kasih sayang. Sejak kecil, ia ...
Perpustakaan Berdarah
Sita terbayang ketika Papa marah padanya karena memutuskan masuk Fakultas Desain Komunikas ...
Breast Beneath The Spotlight
Di tengah mimpi menjadi idol K-Pop yang semakin langka dan brutal, delapan gadis muda dari ...