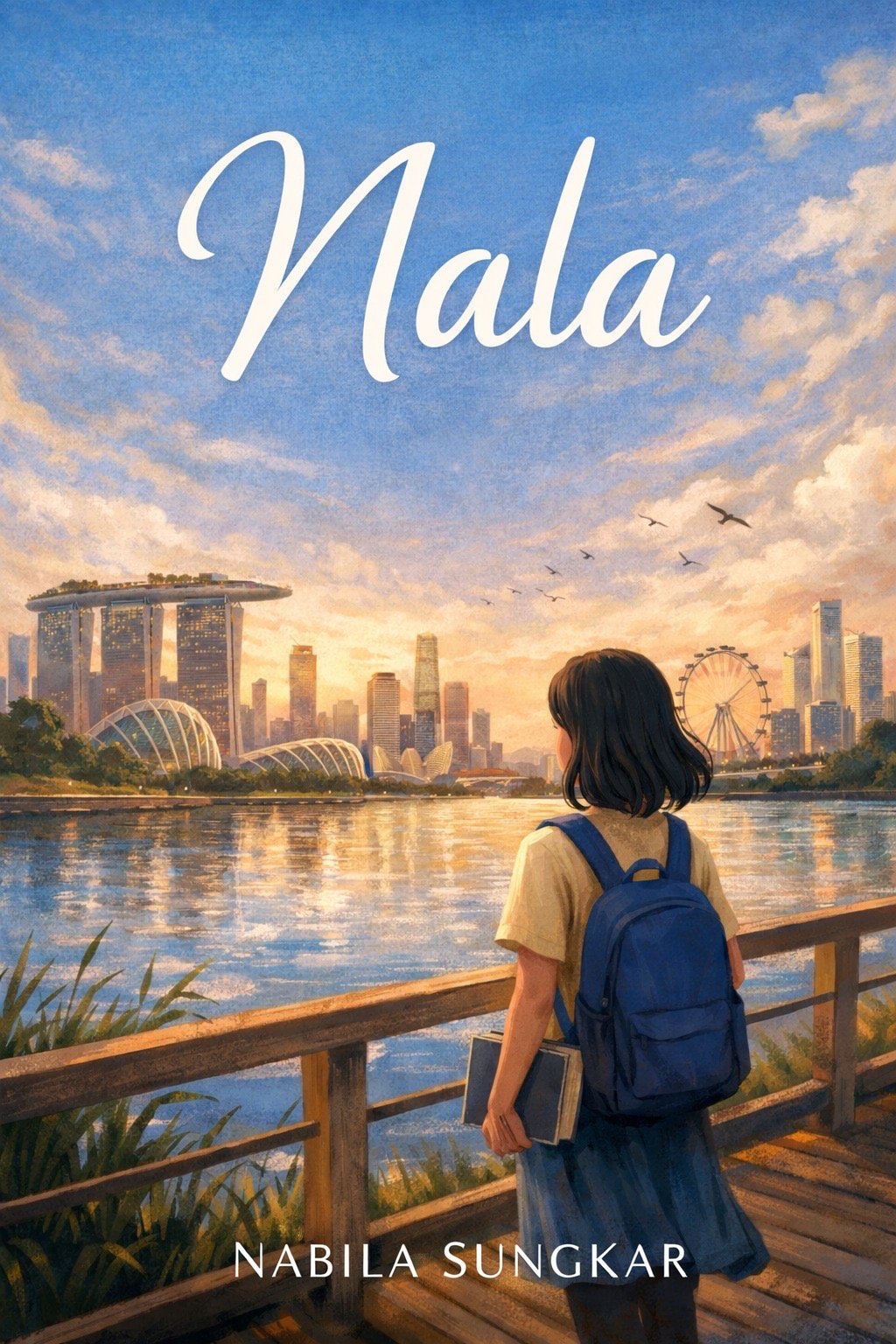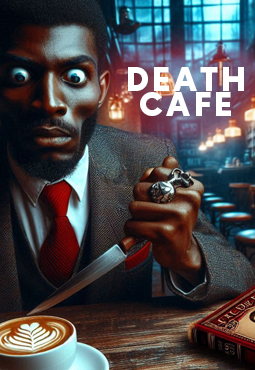Pulang
Nala melirik jam dinding di kelas. 13.58.
“Dua menit lagi,” gumamnya pelan.
Dadanya terasa sesak. Kepalanya pusing, napasnya tak kunjung teratur. Ia menghela napas berkali-kali, seolah mencoba menenangkan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya.
Kriiinggg…
Bel berbunyi.
Seluruh kelas langsung riuh. Teriakan gembira memenuhi ruangan.
Berbeda dengan Nala.
Ia justru berdoa agar bunyi itu tidak pernah ia dengar. Bel pulang hari itu adalah penanda berakhirnya tahun ajaran. Dan itu berarti satu hal: libur sekolah.
Waktu di mana Nala tidak punya pilihan selain berada di rumah.
Di rumah, ia memang lebih sering mengurung diri di kamar dan belajar. Tapi di kamar itu pula, kenangan Ayah selalu hadir. Ayah yang dulu mengetuk pintu setiap pagi, membangunkannya untuk salat Subuh. Ayah yang kadang duduk di tepi tempat tidurnya, memberi nasihat saat Nala bertengkar dengan Mama.
Ayah.
Ayah.
Ayah.
Tak pernah sedetik pun Nala melupakan Ayah.
Pernah terlintas di benaknya, “Apa aku susul Ayah saja, ya?”
Tapi pikiran itu segera ia tepis. Ia teringat pelajaran agama di sekolah. Ia teringat Mama. Mila. Gala.
Meski begitu, pikiran itu tetap datang sesekali, tanpa permisi.
Hari itu, Nala pulang berjalan kaki. Tiga kilometer ia tempuh sendirian. Ia memikirkan satu hal: sebentar lagi ia akan naik ke kelas 6 SD. Dulu, itu sesuatu yang terasa besar, sesuatu yang pantas dirayakan. Tapi sekarang, Nala memilih untuk tidak berekspektasi apa-apa.
Saat sampai di depan rumah, suasananya ramai.
Mama membuka usaha ayam goreng krispi dan nasi dengan gerobak kaca di depan rumah. Pilihan pekerjaan paling masuk akal saat ini—Mama bisa tetap menjaga ketiga anaknya sambil mengurus rumah.
Mila dan Gala membantu. Mila sibuk memasukkan ayam ke dalam boks, sementara Gala memberikan plastik ke pelanggan. Nala meletakkan tasnya, mencuci tangan, lalu ikut membantu mencetak nasi ke dalam mangkuk.
Inilah libur sekolah versi baru Nala.
Berjualan ayam.
.
.
.
Suatu hari, Nala meminta izin kepada Mama untuk pergi ke rumah Anita, kakak kelasnya yang dulu pernah mewakili sekolah dalam lomba sains tingkat nasional. Ia ingin meminjam buku soal-soal lomba sains.
“Nanti diantar Pak Rohim kok, Mah,” kata Nala.
Sejak Ayah tiada, Pak Rohim adalah pahlawan kecil keluarga mereka, orang yang biasa mengantar ketiga bersaudara ke mana pun saat Mama sibuk. Kalau Pak Rohim tidak bisa, izin dari Mama hampir mustahil didapat.
Namun hari itu jawabannya berbeda.
“Gak bisa, neng, Nala. Gunung Putri itu jauh banget,” kata Pak Rohim. “Nanti Bapak dimarahi warga kalau berjam-jam gak jaga pos.”
“Emangnya Pak Samsul gak ada?” tanya Nala.
“Gak ada. Pak Samsul lagi sakit. Saya sendirian jaga pos.”
Pak Rohim tak bisa meninggalkan pos. Nala juga tak mungkin kembali ke rumah untuk membatalkan rencananya. Akhirnya, ia nekat naik angkutan umum.
Angkot pertama ditempuh empat puluh menit. Lalu berganti angkot lain hampir lima puluh menit. Setelah itu, ia masih harus berjalan kaki sekitar dua puluh menit.
“Hampir sampai…” gumamnya.
Hampir dua jam kemudian, Nala tiba di rumah Anita. Namun rumah itu sepi. Di bangku depan terletak setumpuk buku dan secarik catatan:
Aku dan orang tua ke mal. Ini bukunya. Sukses lombanya ya.
Nala menghela napas.
Tak apa. Tidak boleh berekspektasi. Ia sempat berharap setidaknya diberi air minum, tapi yang penting bukunya bisa dipinjam.
Saat berjalan menuju tempat angkot, hujan turun tiba-tiba. Byur.
Nala melipir ke sebuah musala kecil.
Di dalam musala, pikirannya melayang.
Andai ada Ayah, ia tak mungkin kehujanan.
Tak mungkin berteduh sendirian di musala kecil ini.
Pasti sedang duduk di mobil bersama Ayah, pulang membawa buku.
Ada jajan. Ada air minum.
Sekarang, air putih pun tak ada.
Berandai-andai. Andaikan…
Tanpa sadar, air mata menetes. Nala segera menghapusnya dan keluar. Hujan sudah reda.
Ia menunduk. Menoleh ke kanan dan ke kiri.
Sepatunya tidak ada.
Nala berdiri diam.
Lima menit.
Sepuluh menit.
Lima belas menit.
Tak ada siapa-siapa. Daerah itu sepi. Sandal musala pun tidak terlihat.
Sepatunya benar-benar hilang.
Nala menangis.
“Ayah dimana?” tangisnya pecah.
Ia tak tahu bagaimana caranya pulang tanpa sepatu. Dengan ragu, ia melangkahkan kaki kanannya ke atas aspal yang masih basah.
Setiap langkah terasa berat, meski sudah sepuluh menit berjalan. Di kepalanya muncul pikiran-pikiran buruk: ini bekas ludah orang, ini bekas kotoran kucing, ini jorok banget.
Ia melewati sebuah warung kecil yang memajang sandal jepit bertuliskan paling murah lima ribu rupiah.
Uangnya hanya tujuh ribu— hanya cukup untuk dua kali naik angkot.
Ia menangis sejadi-jadinya, lalu berjalan lagi. Tidak ada pilihan lain.
Akhirnya, ia sampai di tempat angkot dan naik.
Di dalam angkot, seorang ibu memperhatikannya.
“Kamu kenapa, Dek?”
Nala tak bisa berhenti menangis. Sambil tersedu-sedu, ia menceritakan semuanya.
Ibu itu terdiam sebentar, lalu membuka tasnya.
“Ibu punya sandal,” katanya. “Hak-nya agak tinggi. Tadinya mau Ibu betulkan.”
“Mau… mau aku pakai. Nanti aku balikin ke rumah Ibu. Aku janji,” jawab Nala sambil mengusap air di wajahnya, dimana air mata dan air hujan telah melebur jadi satu.
“Nggak usah,” jawabnya lembut. “Pakai aja.”
Nala pulang memakai sandal hak tinggi lima sentimeter. Sandal kanan bagian depannya menganga, seperti mulut buaya yang siap menerkam. Tapi Nala lega, kakinya tidak perlu lagi menyentuh aspal.
Ia sampai rumah dalam keadaan kuyup dan lelah. Jualan Mama sudah tutup, ayamnya pasti habis hari itu.
Nala masuk kamar, membersihkan diri, lalu diam.
Ia tidak menceritakan apa pun—kepada Mama, Mila, maupun Gala.
Malam itu, Nala memeluk bantal erat-erat.
Ia tidak marah.
Ia juga tidak menyalahkan siapa pun.
Ia hanya rindu.
Rindu pada seseorang yang dulu selalu ada, dan kini hanya datang dalam ingatan.
“Dua menit lagi,” gumamnya pelan.
Dadanya terasa sesak. Kepalanya pusing, napasnya tak kunjung teratur. Ia menghela napas berkali-kali, seolah mencoba menenangkan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya.
Kriiinggg…
Bel berbunyi.
Seluruh kelas langsung riuh. Teriakan gembira memenuhi ruangan.
Berbeda dengan Nala.
Ia justru berdoa agar bunyi itu tidak pernah ia dengar. Bel pulang hari itu adalah penanda berakhirnya tahun ajaran. Dan itu berarti satu hal: libur sekolah.
Waktu di mana Nala tidak punya pilihan selain berada di rumah.
Di rumah, ia memang lebih sering mengurung diri di kamar dan belajar. Tapi di kamar itu pula, kenangan Ayah selalu hadir. Ayah yang dulu mengetuk pintu setiap pagi, membangunkannya untuk salat Subuh. Ayah yang kadang duduk di tepi tempat tidurnya, memberi nasihat saat Nala bertengkar dengan Mama.
Ayah.
Ayah.
Ayah.
Tak pernah sedetik pun Nala melupakan Ayah.
Pernah terlintas di benaknya, “Apa aku susul Ayah saja, ya?”
Tapi pikiran itu segera ia tepis. Ia teringat pelajaran agama di sekolah. Ia teringat Mama. Mila. Gala.
Meski begitu, pikiran itu tetap datang sesekali, tanpa permisi.
Hari itu, Nala pulang berjalan kaki. Tiga kilometer ia tempuh sendirian. Ia memikirkan satu hal: sebentar lagi ia akan naik ke kelas 6 SD. Dulu, itu sesuatu yang terasa besar, sesuatu yang pantas dirayakan. Tapi sekarang, Nala memilih untuk tidak berekspektasi apa-apa.
Saat sampai di depan rumah, suasananya ramai.
Mama membuka usaha ayam goreng krispi dan nasi dengan gerobak kaca di depan rumah. Pilihan pekerjaan paling masuk akal saat ini—Mama bisa tetap menjaga ketiga anaknya sambil mengurus rumah.
Mila dan Gala membantu. Mila sibuk memasukkan ayam ke dalam boks, sementara Gala memberikan plastik ke pelanggan. Nala meletakkan tasnya, mencuci tangan, lalu ikut membantu mencetak nasi ke dalam mangkuk.
Inilah libur sekolah versi baru Nala.
Berjualan ayam.
.
.
.
Suatu hari, Nala meminta izin kepada Mama untuk pergi ke rumah Anita, kakak kelasnya yang dulu pernah mewakili sekolah dalam lomba sains tingkat nasional. Ia ingin meminjam buku soal-soal lomba sains.
“Nanti diantar Pak Rohim kok, Mah,” kata Nala.
Sejak Ayah tiada, Pak Rohim adalah pahlawan kecil keluarga mereka, orang yang biasa mengantar ketiga bersaudara ke mana pun saat Mama sibuk. Kalau Pak Rohim tidak bisa, izin dari Mama hampir mustahil didapat.
Namun hari itu jawabannya berbeda.
“Gak bisa, neng, Nala. Gunung Putri itu jauh banget,” kata Pak Rohim. “Nanti Bapak dimarahi warga kalau berjam-jam gak jaga pos.”
“Emangnya Pak Samsul gak ada?” tanya Nala.
“Gak ada. Pak Samsul lagi sakit. Saya sendirian jaga pos.”
Pak Rohim tak bisa meninggalkan pos. Nala juga tak mungkin kembali ke rumah untuk membatalkan rencananya. Akhirnya, ia nekat naik angkutan umum.
Angkot pertama ditempuh empat puluh menit. Lalu berganti angkot lain hampir lima puluh menit. Setelah itu, ia masih harus berjalan kaki sekitar dua puluh menit.
“Hampir sampai…” gumamnya.
Hampir dua jam kemudian, Nala tiba di rumah Anita. Namun rumah itu sepi. Di bangku depan terletak setumpuk buku dan secarik catatan:
Aku dan orang tua ke mal. Ini bukunya. Sukses lombanya ya.
Nala menghela napas.
Tak apa. Tidak boleh berekspektasi. Ia sempat berharap setidaknya diberi air minum, tapi yang penting bukunya bisa dipinjam.
Saat berjalan menuju tempat angkot, hujan turun tiba-tiba. Byur.
Nala melipir ke sebuah musala kecil.
Di dalam musala, pikirannya melayang.
Andai ada Ayah, ia tak mungkin kehujanan.
Tak mungkin berteduh sendirian di musala kecil ini.
Pasti sedang duduk di mobil bersama Ayah, pulang membawa buku.
Ada jajan. Ada air minum.
Sekarang, air putih pun tak ada.
Berandai-andai. Andaikan…
Tanpa sadar, air mata menetes. Nala segera menghapusnya dan keluar. Hujan sudah reda.
Ia menunduk. Menoleh ke kanan dan ke kiri.
Sepatunya tidak ada.
Nala berdiri diam.
Lima menit.
Sepuluh menit.
Lima belas menit.
Tak ada siapa-siapa. Daerah itu sepi. Sandal musala pun tidak terlihat.
Sepatunya benar-benar hilang.
Nala menangis.
“Ayah dimana?” tangisnya pecah.
Ia tak tahu bagaimana caranya pulang tanpa sepatu. Dengan ragu, ia melangkahkan kaki kanannya ke atas aspal yang masih basah.
Setiap langkah terasa berat, meski sudah sepuluh menit berjalan. Di kepalanya muncul pikiran-pikiran buruk: ini bekas ludah orang, ini bekas kotoran kucing, ini jorok banget.
Ia melewati sebuah warung kecil yang memajang sandal jepit bertuliskan paling murah lima ribu rupiah.
Uangnya hanya tujuh ribu— hanya cukup untuk dua kali naik angkot.
Ia menangis sejadi-jadinya, lalu berjalan lagi. Tidak ada pilihan lain.
Akhirnya, ia sampai di tempat angkot dan naik.
Di dalam angkot, seorang ibu memperhatikannya.
“Kamu kenapa, Dek?”
Nala tak bisa berhenti menangis. Sambil tersedu-sedu, ia menceritakan semuanya.
Ibu itu terdiam sebentar, lalu membuka tasnya.
“Ibu punya sandal,” katanya. “Hak-nya agak tinggi. Tadinya mau Ibu betulkan.”
“Mau… mau aku pakai. Nanti aku balikin ke rumah Ibu. Aku janji,” jawab Nala sambil mengusap air di wajahnya, dimana air mata dan air hujan telah melebur jadi satu.
“Nggak usah,” jawabnya lembut. “Pakai aja.”
Nala pulang memakai sandal hak tinggi lima sentimeter. Sandal kanan bagian depannya menganga, seperti mulut buaya yang siap menerkam. Tapi Nala lega, kakinya tidak perlu lagi menyentuh aspal.
Ia sampai rumah dalam keadaan kuyup dan lelah. Jualan Mama sudah tutup, ayamnya pasti habis hari itu.
Nala masuk kamar, membersihkan diri, lalu diam.
Ia tidak menceritakan apa pun—kepada Mama, Mila, maupun Gala.
Malam itu, Nala memeluk bantal erat-erat.
Ia tidak marah.
Ia juga tidak menyalahkan siapa pun.
Ia hanya rindu.
Rindu pada seseorang yang dulu selalu ada, dan kini hanya datang dalam ingatan.
Other Stories
Hopeless Cries
Merasa kesepian, tetapi sama sekali tidak menginginkan kehadiran seseorang untuk menemanin ...
Bisikan Lada
Kejadian pagi tadi membuat heboh warga sekitar. Penemuan tiga mayat pemuda yang diketahui ...
Hantu Dan Hati
Di tengah duka dan rutinitasnya berjualan bunga, seorang pemuda menyadari bahwa ia tidak s ...
Namaku May
Belajar tak mengenal usia, gender, maupun status sosial. Kisah ini menginspirasi untuk ter ...
Bisikan Lada
Kejadian pagi tadi membuat heboh warga sekitar. Penemuan tiga mayat pemuda yang diketah ...
Death Cafe
Sakti tidak dapat menahan diri lagi, ia penasaran dengan death cafe yang selama ini orang- ...