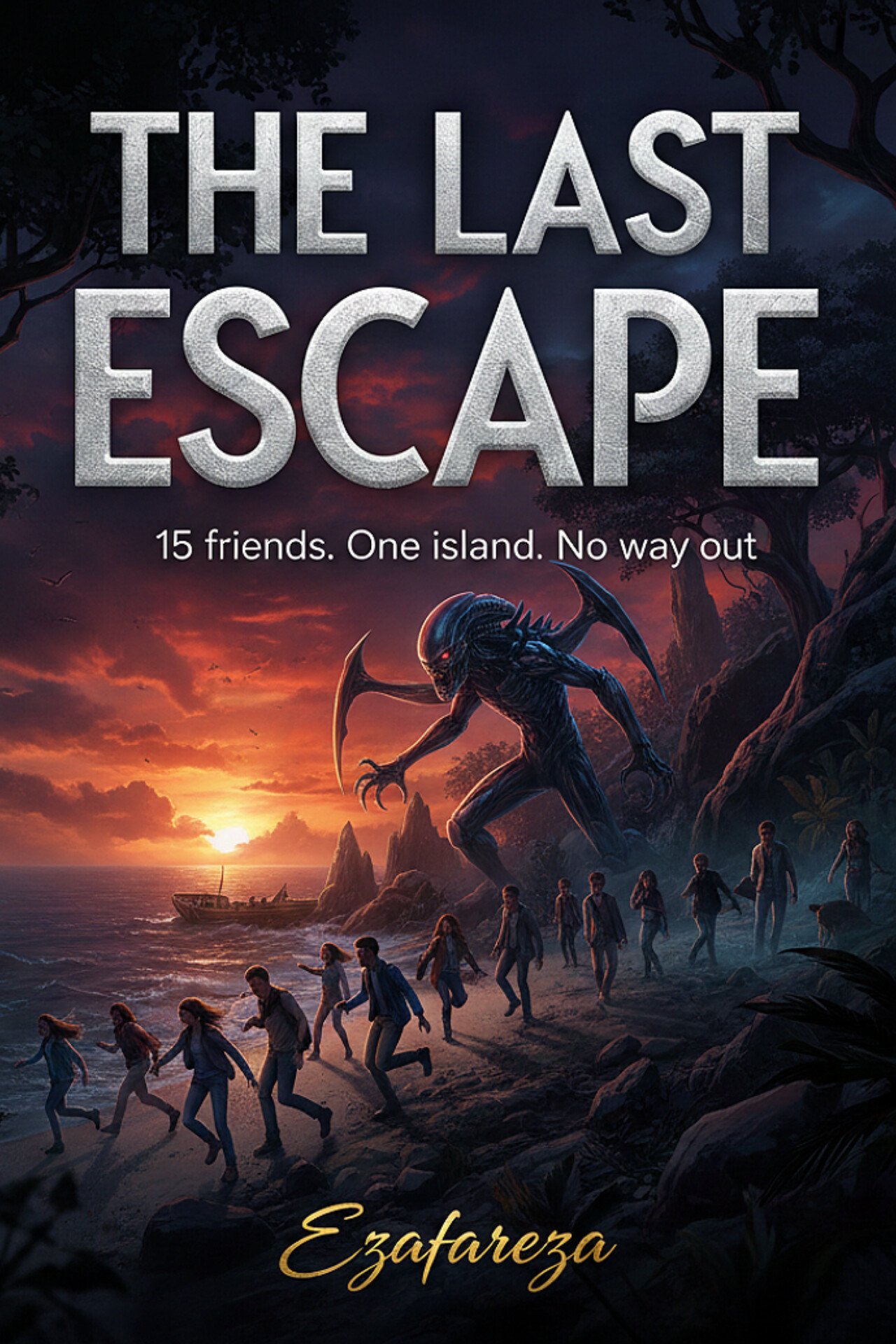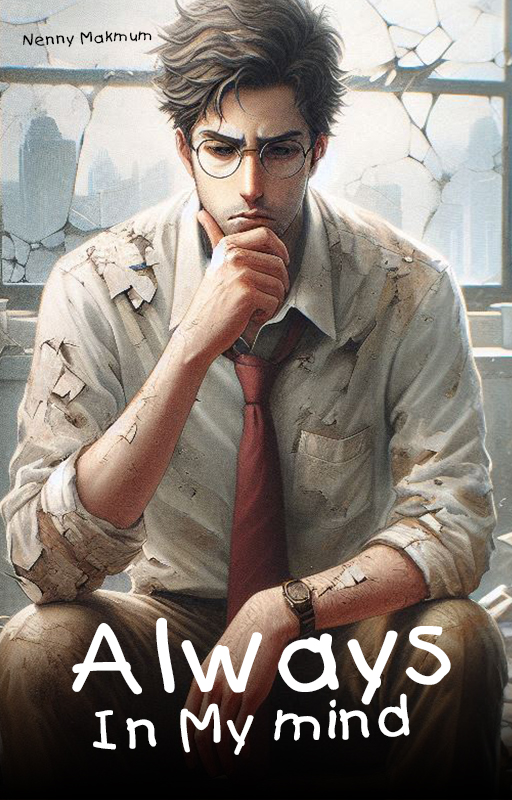BAB 10 | "Ujian Kesetiaan Labirin Bawah Tanah"
Gua batu itu terasa semakin sempit, seolah dinding-dinding granitnya adalah rahang raksasa yang perlahan mengunyah keberanian mereka. Langkah kaki empat belas orang itu menimbulkan gema yang aneh, seolah ada langkah kaki tambahan yang mengikuti dari kejauhan, berhenti saat mereka berhenti, dan melangkah saat mereka melangkah. Udara di dalam sini berbau tanah basah yang purba, bercampur dengan aroma keringat dingin yang mengucur dari tubuh-tubuh yang ketakutan.
Bab 10: Ujian Kesetiaan Labirin Bawah Tanah
"Pelan-pelan, jangan sampai ada yang kepentok," bisik Adit. Ia memimpin di depan, tangannya sesekali meraba dinding gua yang licin karena lumut. Di belakangnya, Aris terus mengarahkan senter ke arah bawah, memastikan tidak ada celah atau lubang yang bisa membuat teman-temannya terperosok.
"Dit, lu yakin kita masih di jalur yang bener?" tanya Rio. Suaranya terdengar hampa, bergema di sepanjang lorong sempit. Rio sejak tadi tidak melepaskan genggamannya pada sebilah pisau lipat. Matanya liar menatap ke setiap celah kegelapan, mencari sosok Jaka atau mungkin, sosok yang telah membawa Jaka pergi.
"Gue nggak yakin, Yo. Tapi kalau kita diem di depan barikade tadi, kita cuma nunggu pintu itu didobrak," jawab Adit tanpa menoleh. "Seenggaknya di sini kita masih napas."
Nadia berjalan di tengah, memegangi pundak Dina yang masih berjalan terpincang-pincang. Nadia bisa merasakan betapa kencangnya detak jantung Dina melalui sentuhan tangannya. Di belakang mereka, Bram dan Bimo menjadi benteng terakhir. Bimo, meski tangannya dibalut perban putih yang mulai kotor, tetap memegang potongan kayu besar dengan sisa kekuatannya.
"Gila ya, padahal baru kemarin kita ketawa-ketiwi di pantai," gumam Lala pelan. Ia mencoba mencari secercah humor untuk menutupi rasa takutnya yang membuncah. "Gue pikir penderitaan terbesar liburan ini cuma kalau lipstik gue ilang atau sinyal HP doang yang susah. Ternyata ada yang lebih parah lagi. Ini insane!"
"Yah, seenggaknya sekarang kita nggak perlu mikirin tugas akhir buat sementara," sahut Tora dari belakang. "Cuma ya... Diganti sama tugas bertahan hidup. Dosennya pun lebih galak dari Bu Mirna kan."
Beberapa orang sempat terkekeh tipis, sebuah tawa kering yang langsung hilang ditelan kegelapan gua. Humor itu seperti lilin kecil di tengah badai, mudah padam, tapi setidaknya memberi sedikit kehangatan sebelum benar-benar lenyap.
Namun, suasana santai yang dipaksakan itu tidak bertahan lama. Lorong gua tiba-tiba bercabang menjadi tiga. Aris menghentikan langkahnya, membuat seluruh rombongan ikut berhenti.
"Kenapa berhenti, Ris?" tanya Santi cemas. Ia mengeratkan pelukannya pada lengan Rico.
"Ada tiga jalan," jawab Aris sambil mengarahkan senternya ke masing-masing lubang. "Kanan, tengah, kiri. Yang tengah paling lebar, tapi tanahnya becek banget. Yang kanan sempit, tapi udaranya terasa lebih segar. Yang kiri... baunya nggak enak."
"Bau apa?" tanya Eka, ia memegang buku gambarnya seolah itu adalah perisai.
Aris melangkah sedikit ke arah lorong kiri, lalu mundur dengan cepat. "Bau daging busuk. Kayak... kayak tempat pembuangan. Ugh... Busuk banget."
Mendengar itu, Dina hampir muntah. Bayangan tentang apa yang ada di dalam lorong kiri itu langsung memenuhi kepala mereka. Jika itu adalah tempat pembuangan, artinya sang predator membawa hasil buruannya ke sana.
"Kita ambil yang kanan," putus Adit cepat. "Udaranya seger, berarti mungkin ada akses ke luar."
Mereka mulai masuk ke lorong kanan. Jalannya sangat sempit, memaksa mereka berjalan satu per satu. Di sinilah konflik pertama yang sesungguhnya mulai muncul. Rico, yang biasanya tampak tenang dan protektif pada Santi, mulai menunjukkan kegelisahan yang berbeda. Ia terus-terusan mendorong orang di depannya agar berjalan lebih cepat.
"Woy, Ric! Jangan dorong-dorong dong! Ini sempit, kalau gue jatuh gimana?" protes Maya yang berada tepat di depan Rico.
"Ya lu jalannya jangan kayak siput, May! Kita ini dikejar maut, bukan lagi catwalk!" bentak Rico. Suaranya kasar, sangat berbeda dengan Rico yang biasanya lembut.
"Rico, tenang sayang. Maya juga lagi usaha kok itu," kata Santi mencoba menenangkan pacarnya.
"Tenang gimana? Kita semua bisa mati di sini gara-gara kalian jalannya kelamaan!" teriak Rico lagi. Egoismenya mulai muncul ke permukaan. Di bawah tekanan maut, topeng kesopanan yang selama ini ia pakai mulai retak. Rico adalah tipe orang yang sangat menghargai hidupnya sendiri di atas segalanya. Liburan "mahal" ini ia ikuti sebenarnya hanya untuk pamer di media sosial, dan sekarang ketika kenyataan berbalik, ia menjadi orang pertama yang kehilangan kendali diri.
"Udah! Jangan berantem!" bentak Bram dari belakang. "Suara kalian bisa manggil makhluk itu!"
Seketika semuanya diam. Namun, benih perpecahan sudah tertanam. Mereka mulai saling curiga, saling menyalahkan dalam hati tentang siapa yang paling lambat dan siapa yang paling membebani kelompok.
Sambil merangkak di lorong yang semakin rendah, mereka mulai bercerita tentang hal-hal mendalam untuk mengalihkan pikiran. Bimo mulai bercerita tentang masa lalunya.
"Kalian tahu nggak kenapa gue obses banget sama basket?" tanya Bimo sambil terengah-engah. "Gue lahir di lingkungan yang kalau lu nggak kuat, lu diinjek. Bokap gue kabur pas gue umur lima tahun. Nyokap gue kerja jadi buruh cuci. Basket itu tiket gue buat keluar dari sana. Gue pikir kalau gue jadi pemain hebat, gue bisa jagain nyokap. Gue bisa punya kuasa. Tapi sekarang... di depan makhluk itu, tinggi badan sama otot gue nggak ada gunanya sama sekali."
Bimo berhenti sejenak, mengusap keringat di matanya dengan tangan yang tidak terluka. "Gue ngerasa gagal lagi. Gue nggak bisa jagain Jaka."
"Jangan ngomong gitu, Bim," sahut Nadia dari depan. "Lu udah berjuang di pantai tadi. Lu itu pahlawan kita."
"Pahlawan nggak bakal biarin temennya ilang, Nad," balas Bimo lirih.
Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara gemeretak tulang. Bukan dari lorong tempat mereka datang, tapi dari dinding batu di samping mereka.
Krak... krak... krak...
Dinding batu itu tidak sepadat yang mereka kira. Ada celah-celah kecil yang tertutup tanah dan akar pohon. Dan dari salah satu celah itu, sebuah tangan panjang dengan kulit hitam legam dan kuku melengkung keluar, menyambar tas milik Gilang.
"KAMERA GUE!" teriak Gilang saat tasnya ditarik paksa masuk ke dalam celah dinding.
"Lepasin, Lang! Lepasin!" teriak Adit.
Gilang mencoba mempertahankan tasnya. Di dalam tas itu ada semua rekaman mereka, semua bukti tentang apa yang terjadi di pulau ini. Namun, kekuatan dari balik dinding itu terlalu besar. Tiba-tiba, makhluk itu mengubah targetnya. Ia melepaskan tas Gilang dan justru mencengkeram lengan Gilang.
"TOLONG! TANGAN GUE!" jerit Gilang. Tubuhnya mulai ditarik ke arah celah dinding yang sempit.
Bimo dan Bram segera bereaksi. Bimo menghantamkan sisa kayu pemukulnya ke arah tangan makhluk itu melalui celah dinding, sementara Bram memegang pinggang Gilang dan menariknya sekuat tenaga.
"BANTU GUE, RIC! BIMO TANGANNYA LAGI SAKIT!" teriak Bram pada Rico yang berdiri paling dekat.
Namun, Rico justru mundur. Wajahnya pucat pasi, ia membeku karena ketakutan. "Enggak... gue nggak mau jadi ketarik juga! Mundur semuanya, mundur!" Rico justru mendorong Santi dan Maya agar menjauh dari Gilang, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri.
"RICO, LU BRENGSEK! BIADAP!" teriak Rio. Rio melompati Rico, ia menerjang ke arah celah dinding dan menghujamkan pisau lipatnya ke tangan hitam itu berkali-kali.
Makhluk itu mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia melepaskan lengan Gilang. Darah berwarna biru kehitaman yang kental menyemprot keluar dari luka tusukan Rio, mengenai wajah Gilang dan baju Rio.
"Lari! Terus gerak!" perintah Adit.
Mereka berlari secepat mungkin menyusuri lorong yang mulai menanjak. Gilang memegangi lengannya yang berdarah karena goresan kuku tajam tadi. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena melihat bagaimana teman-temannya bertaruh nyawa untuknya sementara Rico, orang yang selama ini ia anggap teman baik, justru membiarkannya hampir mati.
Setelah beberapa menit berlari, mereka sampai di sebuah ruangan gua yang lebih luas. Di sana terdapat sebuah lubang besar di bagian atas yang memperlihatkan langit malam yang bertabur bintang. Cahaya bulan masuk dengan indahnya, kontras dengan kengerian yang baru saja mereka alami.
"Kita berhenti di sini bentar," kata Adit sambil mengatur napas.
Rio langsung berbalik dan mencengkeram kerah baju Rico. BUG! Satu pukulan keras mendarat di pipi Rico, membuatnya tersungkur di lantai gua.
"LU APA-APAAN, RIC?! GILANG HAMPIR MATI TADI!" teriak Rio dengan mata menyala-nyala. "LU LEBIH MILIH KABUR DARIPADA BANTU TEMEN LU? OTAK LU KEMANA!"
Rico memegangi pipinya yang bengkak. "Gue... gue panik! Lu semua nggak ngerasa takut apa?! Kita semua mungkin bakal mati di sini! Gue cuma nggak mau mati! Gue cuma mau hidup dan keluar dari sini secepat mungkin!"
"Kita semua takut, Rico!" sahut Nadia dengan nada mature namun penuh kekecewaan. "Tapi rasa takut bukan alasan buat jadi pengecut. Lu liat Bimo? Tangannya patah tapi dia masih mau bantu kita semua. Lu? Lu punya tangan sehat tapi malah lu pake buat dorong cewek-cewek biar lu bisa lari duluan. Lu keterlaluan Ric."
Santi menatap Rico dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tidak membela pacarnya kali ini. Ia duduk menjauh, bergabung dengan Dina dan Lala. Kesetiaan yang selama ini mereka agung-agungkan mulai runtuh di bawah tekanan insting purba untuk bertahan hidup.
Di sudut ruangan, Aris tidak ikut campur dalam perdebatan itu. Ia justru sedang mengamati darah makhluk itu yang menempel di baju Rio. Darah itu tidak mengering seperti darah manusia, ia tetap basah dan mulai mengeluarkan uap tipis.
"Dit," panggil Aris.
Adit menghampiri Aris. "Kenapa, Ris?"
"Makhluk ini... dia bukan hewan biasa. Darahnya punya suhu yang sangat tinggi. Dan liat ini..." Aris menunjuk ke arah lantai tempat darah itu menetes. Lantai batu itu sedikit terkikis, seolah terkena cairan asam. "Mereka punya sistem tubuh yang sangat efisien buat menghancurkan apa pun yang masuk ke tubuh mereka. Dan mereka nggak sendirian."
Aris mengarahkan senternya ke arah lubang di atas langit-langit gua. Di sana, di tepian lubang yang mengarah ke permukaan pulau, terlihat tiga pasang mata merah yang sedang menatap ke bawah dengan tenang.
Mereka tidak menyerang. Mereka hanya menonton, seperti penonton yang sedang menikmati babak penentuan dalam sebuah drama panggung yang mahal.
"Mereka nunggu kita keluar lewat atas," bisik Maya. "Mereka tahu kita kejebak di sini."
"Tapi kita nggak punya jalan lain," kata Adit. Ia melihat ke arah teman-temannya yang hancur secara emosional. Ada yang terluka secara fisik, ada yang luka secara batin. "Kita harus keluar. Kita harus lawan mereka di atas sana, di tempat yang lebih luas."
"Pakai apa, Dit?" tanya Eka lirih. "Kita cuma punya kayu sama pisau lipat."
"Kita punya otak," balas Adit. "Dan kita punya satu sama lain. Kecuali kalau ada yang masih mau mikirin diri sendiri, silakan tetep di sini." Adit melirik tajam ke arah Rico.
Malam di Pulau Seribu Hening baru saja mencapai puncaknya. Di dalam gua batu itu, mereka belajar satu hal yang paling menyakitkan, bahwa predator yang paling menakutkan bukan hanya makhluk bermata merah di luar sana, tapi juga monster egoisme yang bisa muncul dari dalam diri mereka sendiri saat nyawa menjadi taruhannya.
•••
Bab 10: Ujian Kesetiaan Labirin Bawah Tanah
"Pelan-pelan, jangan sampai ada yang kepentok," bisik Adit. Ia memimpin di depan, tangannya sesekali meraba dinding gua yang licin karena lumut. Di belakangnya, Aris terus mengarahkan senter ke arah bawah, memastikan tidak ada celah atau lubang yang bisa membuat teman-temannya terperosok.
"Dit, lu yakin kita masih di jalur yang bener?" tanya Rio. Suaranya terdengar hampa, bergema di sepanjang lorong sempit. Rio sejak tadi tidak melepaskan genggamannya pada sebilah pisau lipat. Matanya liar menatap ke setiap celah kegelapan, mencari sosok Jaka atau mungkin, sosok yang telah membawa Jaka pergi.
"Gue nggak yakin, Yo. Tapi kalau kita diem di depan barikade tadi, kita cuma nunggu pintu itu didobrak," jawab Adit tanpa menoleh. "Seenggaknya di sini kita masih napas."
Nadia berjalan di tengah, memegangi pundak Dina yang masih berjalan terpincang-pincang. Nadia bisa merasakan betapa kencangnya detak jantung Dina melalui sentuhan tangannya. Di belakang mereka, Bram dan Bimo menjadi benteng terakhir. Bimo, meski tangannya dibalut perban putih yang mulai kotor, tetap memegang potongan kayu besar dengan sisa kekuatannya.
"Gila ya, padahal baru kemarin kita ketawa-ketiwi di pantai," gumam Lala pelan. Ia mencoba mencari secercah humor untuk menutupi rasa takutnya yang membuncah. "Gue pikir penderitaan terbesar liburan ini cuma kalau lipstik gue ilang atau sinyal HP doang yang susah. Ternyata ada yang lebih parah lagi. Ini insane!"
"Yah, seenggaknya sekarang kita nggak perlu mikirin tugas akhir buat sementara," sahut Tora dari belakang. "Cuma ya... Diganti sama tugas bertahan hidup. Dosennya pun lebih galak dari Bu Mirna kan."
Beberapa orang sempat terkekeh tipis, sebuah tawa kering yang langsung hilang ditelan kegelapan gua. Humor itu seperti lilin kecil di tengah badai, mudah padam, tapi setidaknya memberi sedikit kehangatan sebelum benar-benar lenyap.
Namun, suasana santai yang dipaksakan itu tidak bertahan lama. Lorong gua tiba-tiba bercabang menjadi tiga. Aris menghentikan langkahnya, membuat seluruh rombongan ikut berhenti.
"Kenapa berhenti, Ris?" tanya Santi cemas. Ia mengeratkan pelukannya pada lengan Rico.
"Ada tiga jalan," jawab Aris sambil mengarahkan senternya ke masing-masing lubang. "Kanan, tengah, kiri. Yang tengah paling lebar, tapi tanahnya becek banget. Yang kanan sempit, tapi udaranya terasa lebih segar. Yang kiri... baunya nggak enak."
"Bau apa?" tanya Eka, ia memegang buku gambarnya seolah itu adalah perisai.
Aris melangkah sedikit ke arah lorong kiri, lalu mundur dengan cepat. "Bau daging busuk. Kayak... kayak tempat pembuangan. Ugh... Busuk banget."
Mendengar itu, Dina hampir muntah. Bayangan tentang apa yang ada di dalam lorong kiri itu langsung memenuhi kepala mereka. Jika itu adalah tempat pembuangan, artinya sang predator membawa hasil buruannya ke sana.
"Kita ambil yang kanan," putus Adit cepat. "Udaranya seger, berarti mungkin ada akses ke luar."
Mereka mulai masuk ke lorong kanan. Jalannya sangat sempit, memaksa mereka berjalan satu per satu. Di sinilah konflik pertama yang sesungguhnya mulai muncul. Rico, yang biasanya tampak tenang dan protektif pada Santi, mulai menunjukkan kegelisahan yang berbeda. Ia terus-terusan mendorong orang di depannya agar berjalan lebih cepat.
"Woy, Ric! Jangan dorong-dorong dong! Ini sempit, kalau gue jatuh gimana?" protes Maya yang berada tepat di depan Rico.
"Ya lu jalannya jangan kayak siput, May! Kita ini dikejar maut, bukan lagi catwalk!" bentak Rico. Suaranya kasar, sangat berbeda dengan Rico yang biasanya lembut.
"Rico, tenang sayang. Maya juga lagi usaha kok itu," kata Santi mencoba menenangkan pacarnya.
"Tenang gimana? Kita semua bisa mati di sini gara-gara kalian jalannya kelamaan!" teriak Rico lagi. Egoismenya mulai muncul ke permukaan. Di bawah tekanan maut, topeng kesopanan yang selama ini ia pakai mulai retak. Rico adalah tipe orang yang sangat menghargai hidupnya sendiri di atas segalanya. Liburan "mahal" ini ia ikuti sebenarnya hanya untuk pamer di media sosial, dan sekarang ketika kenyataan berbalik, ia menjadi orang pertama yang kehilangan kendali diri.
"Udah! Jangan berantem!" bentak Bram dari belakang. "Suara kalian bisa manggil makhluk itu!"
Seketika semuanya diam. Namun, benih perpecahan sudah tertanam. Mereka mulai saling curiga, saling menyalahkan dalam hati tentang siapa yang paling lambat dan siapa yang paling membebani kelompok.
Sambil merangkak di lorong yang semakin rendah, mereka mulai bercerita tentang hal-hal mendalam untuk mengalihkan pikiran. Bimo mulai bercerita tentang masa lalunya.
"Kalian tahu nggak kenapa gue obses banget sama basket?" tanya Bimo sambil terengah-engah. "Gue lahir di lingkungan yang kalau lu nggak kuat, lu diinjek. Bokap gue kabur pas gue umur lima tahun. Nyokap gue kerja jadi buruh cuci. Basket itu tiket gue buat keluar dari sana. Gue pikir kalau gue jadi pemain hebat, gue bisa jagain nyokap. Gue bisa punya kuasa. Tapi sekarang... di depan makhluk itu, tinggi badan sama otot gue nggak ada gunanya sama sekali."
Bimo berhenti sejenak, mengusap keringat di matanya dengan tangan yang tidak terluka. "Gue ngerasa gagal lagi. Gue nggak bisa jagain Jaka."
"Jangan ngomong gitu, Bim," sahut Nadia dari depan. "Lu udah berjuang di pantai tadi. Lu itu pahlawan kita."
"Pahlawan nggak bakal biarin temennya ilang, Nad," balas Bimo lirih.
Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara gemeretak tulang. Bukan dari lorong tempat mereka datang, tapi dari dinding batu di samping mereka.
Krak... krak... krak...
Dinding batu itu tidak sepadat yang mereka kira. Ada celah-celah kecil yang tertutup tanah dan akar pohon. Dan dari salah satu celah itu, sebuah tangan panjang dengan kulit hitam legam dan kuku melengkung keluar, menyambar tas milik Gilang.
"KAMERA GUE!" teriak Gilang saat tasnya ditarik paksa masuk ke dalam celah dinding.
"Lepasin, Lang! Lepasin!" teriak Adit.
Gilang mencoba mempertahankan tasnya. Di dalam tas itu ada semua rekaman mereka, semua bukti tentang apa yang terjadi di pulau ini. Namun, kekuatan dari balik dinding itu terlalu besar. Tiba-tiba, makhluk itu mengubah targetnya. Ia melepaskan tas Gilang dan justru mencengkeram lengan Gilang.
"TOLONG! TANGAN GUE!" jerit Gilang. Tubuhnya mulai ditarik ke arah celah dinding yang sempit.
Bimo dan Bram segera bereaksi. Bimo menghantamkan sisa kayu pemukulnya ke arah tangan makhluk itu melalui celah dinding, sementara Bram memegang pinggang Gilang dan menariknya sekuat tenaga.
"BANTU GUE, RIC! BIMO TANGANNYA LAGI SAKIT!" teriak Bram pada Rico yang berdiri paling dekat.
Namun, Rico justru mundur. Wajahnya pucat pasi, ia membeku karena ketakutan. "Enggak... gue nggak mau jadi ketarik juga! Mundur semuanya, mundur!" Rico justru mendorong Santi dan Maya agar menjauh dari Gilang, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri.
"RICO, LU BRENGSEK! BIADAP!" teriak Rio. Rio melompati Rico, ia menerjang ke arah celah dinding dan menghujamkan pisau lipatnya ke tangan hitam itu berkali-kali.
Makhluk itu mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia melepaskan lengan Gilang. Darah berwarna biru kehitaman yang kental menyemprot keluar dari luka tusukan Rio, mengenai wajah Gilang dan baju Rio.
"Lari! Terus gerak!" perintah Adit.
Mereka berlari secepat mungkin menyusuri lorong yang mulai menanjak. Gilang memegangi lengannya yang berdarah karena goresan kuku tajam tadi. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena melihat bagaimana teman-temannya bertaruh nyawa untuknya sementara Rico, orang yang selama ini ia anggap teman baik, justru membiarkannya hampir mati.
Setelah beberapa menit berlari, mereka sampai di sebuah ruangan gua yang lebih luas. Di sana terdapat sebuah lubang besar di bagian atas yang memperlihatkan langit malam yang bertabur bintang. Cahaya bulan masuk dengan indahnya, kontras dengan kengerian yang baru saja mereka alami.
"Kita berhenti di sini bentar," kata Adit sambil mengatur napas.
Rio langsung berbalik dan mencengkeram kerah baju Rico. BUG! Satu pukulan keras mendarat di pipi Rico, membuatnya tersungkur di lantai gua.
"LU APA-APAAN, RIC?! GILANG HAMPIR MATI TADI!" teriak Rio dengan mata menyala-nyala. "LU LEBIH MILIH KABUR DARIPADA BANTU TEMEN LU? OTAK LU KEMANA!"
Rico memegangi pipinya yang bengkak. "Gue... gue panik! Lu semua nggak ngerasa takut apa?! Kita semua mungkin bakal mati di sini! Gue cuma nggak mau mati! Gue cuma mau hidup dan keluar dari sini secepat mungkin!"
"Kita semua takut, Rico!" sahut Nadia dengan nada mature namun penuh kekecewaan. "Tapi rasa takut bukan alasan buat jadi pengecut. Lu liat Bimo? Tangannya patah tapi dia masih mau bantu kita semua. Lu? Lu punya tangan sehat tapi malah lu pake buat dorong cewek-cewek biar lu bisa lari duluan. Lu keterlaluan Ric."
Santi menatap Rico dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tidak membela pacarnya kali ini. Ia duduk menjauh, bergabung dengan Dina dan Lala. Kesetiaan yang selama ini mereka agung-agungkan mulai runtuh di bawah tekanan insting purba untuk bertahan hidup.
Di sudut ruangan, Aris tidak ikut campur dalam perdebatan itu. Ia justru sedang mengamati darah makhluk itu yang menempel di baju Rio. Darah itu tidak mengering seperti darah manusia, ia tetap basah dan mulai mengeluarkan uap tipis.
"Dit," panggil Aris.
Adit menghampiri Aris. "Kenapa, Ris?"
"Makhluk ini... dia bukan hewan biasa. Darahnya punya suhu yang sangat tinggi. Dan liat ini..." Aris menunjuk ke arah lantai tempat darah itu menetes. Lantai batu itu sedikit terkikis, seolah terkena cairan asam. "Mereka punya sistem tubuh yang sangat efisien buat menghancurkan apa pun yang masuk ke tubuh mereka. Dan mereka nggak sendirian."
Aris mengarahkan senternya ke arah lubang di atas langit-langit gua. Di sana, di tepian lubang yang mengarah ke permukaan pulau, terlihat tiga pasang mata merah yang sedang menatap ke bawah dengan tenang.
Mereka tidak menyerang. Mereka hanya menonton, seperti penonton yang sedang menikmati babak penentuan dalam sebuah drama panggung yang mahal.
"Mereka nunggu kita keluar lewat atas," bisik Maya. "Mereka tahu kita kejebak di sini."
"Tapi kita nggak punya jalan lain," kata Adit. Ia melihat ke arah teman-temannya yang hancur secara emosional. Ada yang terluka secara fisik, ada yang luka secara batin. "Kita harus keluar. Kita harus lawan mereka di atas sana, di tempat yang lebih luas."
"Pakai apa, Dit?" tanya Eka lirih. "Kita cuma punya kayu sama pisau lipat."
"Kita punya otak," balas Adit. "Dan kita punya satu sama lain. Kecuali kalau ada yang masih mau mikirin diri sendiri, silakan tetep di sini." Adit melirik tajam ke arah Rico.
Malam di Pulau Seribu Hening baru saja mencapai puncaknya. Di dalam gua batu itu, mereka belajar satu hal yang paling menyakitkan, bahwa predator yang paling menakutkan bukan hanya makhluk bermata merah di luar sana, tapi juga monster egoisme yang bisa muncul dari dalam diri mereka sendiri saat nyawa menjadi taruhannya.
•••
Other Stories
Padang Kuyang
Warga desa yakin jika Mariam lah hantu kuyang yang selama ini mengganggu desa mereka. Bany ...
Keluarga Baru
Surya masih belum bisa memaafkan ayahnya karena telah meninggalkannya sejak kecil, disaat ...
Tilawah Hati
Terinspirasi tilawah gurunya, Pak Ridwan, Wina bertekad menjadi guru Agama Islam. Meski be ...
Katamu Aku Cantik
Ratna adalah korban pelecehan seksual di masa kecil dan memilih untuk merahasiakannya samb ...
Always In My Mind
Sempat kepikiran saya ingin rehat setelah setahun berpengalaman menjadi guru pendamping, t ...
Dante Fair Tale
Dante, bocah kesepian berusia 9 tahun, membuat perjanjian dengan peri terkurung dalam bola ...