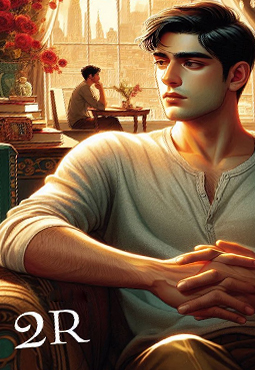Bab 2: Di Bawah Langit Uskudar
Suara azan Subuh berkumandang dari berbagai penjuru Istanbul, saling bersahutan dengan nada yang mendayu-dayu, khas gaya Makam Turki yang meliuk indah. Fatimah terbangun dengan sentakan kecil. Dinginnya udara musim gugur di distrik Uskudar menembus celah jendela asramanya, membuat ujung jemarinya terasa kaku.
Ini adalah minggu pertamanya sebagai mahasiswi pascasarjana. Ia bangkit, merapatkan selimut wolnya sejenak sebelum melangkah ke kamar mandi untuk berwudu. Air yang menyentuh kulitnya terasa seperti es, seketika melenyapkan sisa-sisa kantuk akibat jet lag yang masih membayangi.
Setelah menunaikan salat, Fatimah duduk di atas sajadahnya, menatap ke luar jendela. Dari kejauhan, permukaan Selat Bosphorus tampak keabu-abuan di bawah langit fajar. Ia teringat kejadian di Bukit Çamlıca kemarin sore. Wajah pria itu—pria dengan mata cokelat teduh dan suara berat yang sopan—terus terbayang di benaknya.
"Siapa dia?" bisiknya pelan. "Dan kenapa kata-katanya terdengar begitu dalam?"
Fatimah segera menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Istighfar, Fatimah. Kamu di sini untuk belajar, bukan untuk memikirkan orang asing, tegurnya pada diri sendiri.
Pagi itu, Fatimah harus menuju kampus Istanbul Technical University (ITU) di Maslak. Ia memilih menggunakan Marmaray, kereta bawah laut yang menghubungkan sisi Asia dan Eropa. Baginya, setiap sudut Istanbul adalah pelajaran arsitektur yang hidup. Ia mengamati bagaimana bangunan modern berdampingan dengan sisa-sisa kejayaan Bizantium dan Ottoman tanpa terlihat dipaksakan.
Sesampainya di fakultas arsitektur, suasana tampak riuh. Mahasiswa dari berbagai belahan dunia berkumpul di aula besar. Fatimah merasa sedikit minder dengan tinggi badan gadis-gadis Turki yang menjulang dan gaya berpakaian mereka yang modis meski tetap tertutup. Namun, ia memegang erat tas ranselnya, mengingatkan dirinya bahwa ia membawa harapan Ibu dan doa-doa dari Jakarta.
"Fatimah Azzahra?" sebuah suara memanggil namanya.
Seorang wanita paruh baya dengan kacamata berbingkai perak tersenyum padanya. "Saya Profesor Elif, pembimbing akademikmu. Mari ikut ke ruangan saya."
Di dalam ruangan yang penuh dengan maket bangunan dan gulungan cetak biru, Profesor Elif menjelaskan fokus riset Fatimah. "Kamu tertarik pada akustik masjid-masjid kuno di Istanbul, bukan? Itu topik yang berat namun sangat indah. Istanbul butuh sudut pandang dari arsitek muda seperti kamu."
Fatimah mengangguk antusias. "Iya, Prof. Saya ingin mempelajari bagaimana Mimar Sinan—arsitek agung Ottoman—bisa menciptakan harmoni suara yang sempurna tanpa teknologi modern."
"Bagus. Tapi untuk itu, kamu tidak bisa hanya di perpustakaan. Kamu harus turun ke lapangan. Saya punya seorang asisten riset, arsitek muda berbakat yang sedang mengerjakan proyek restorasi di Fatih. Dia akan membantumu mengenal lapangan."
Jantung Fatimah berdegup lebih kencang.
"Terima kasih, Prof. Siapa nama asisten itu?"
"Namanya Emir. Emir Arslan. Dia mungkin sedikit kaku, tapi dia yang terbaik di bidangnya."
Siang harinya, sesuai instruksi Profesor Elif, Fatimah harus menemui Emir di sebuah kafe kecil di dekat Masjid Suleymaniye. Kafe itu berada di atas bukit, memberikan pemandangan Golden Horn yang menakjubkan.
Fatimah duduk di sudut kafe, memesan segelas Çay (teh Turki) panas. Ia terus melihat ke pintu masuk. Setiap kali lonceng pintu berbunyi, ia mendongak dengan cemas. Ia menyiapkan beberapa kalimat perkenalan dalam bahasa Turki yang sudah ia latih di kereta tadi.
Hingga kemudian, seorang pria masuk. Pria itu memakai mantel panjang berwarna abu-abu gelap. Rambutnya yang sedikit berantakan tertiup angin musim gugur tetap tidak mengurangi kesan rapinya.
Fatimah terpaku. Gelas teh di tangannya hampir saja tumpah. Pria itu adalah pria yang sama dengan pria di Bukit Çamlıca kemarin sore.
Pria itu melangkah mendekat, matanya menyisir ruangan hingga berhenti pada sosok Fatimah yang mengenakan jilbab berwarna marun. Ia tampak terkejut sejenak, namun dengan cepat menguasai keadaan. Ia berjalan menuju meja Fatimah dengan langkah yang tenang.
"Merhaba," sapanya. Kali ini, ada sedikit binar pengenalan di matanya. "Kita bertemu lagi, Nona Arsitek."
Fatimah berdiri dengan canggung, menundukkan kepalanya sedikit. "Anda... Emir Bey?"
Emir menarik kursi di depan Fatimah dan duduk. "Dan kau adalah Fatimah, mahasiswi Indonesia yang dikirim Profesor Elif untuk 'merepotkan' jadwal saya?" Emir berucap dengan nada bercanda yang sangat tipis, hampir tidak terlihat jika Fatimah tidak memperhatikan sudut bibirnya yang sedikit terangkat.
"Maaf jika saya merepotkan, Emir Bey. Saya hanya ingin belajar," jawab Fatimah dalam bahasa Inggris yang kini lebih stabil.
Emir menatap Fatimah dengan lekat, seolah sedang menilai kesungguhan gadis di depannya.
"Arsitektur di Istanbul bukan soal menggambar garis di atas kertas, Fatimah. Ini soal memahami jiwa dari batu-batu yang tersusun. Jika kau hanya ingin nilai bagus, kau salah orang. Tapi jika kau ingin memahami 'suara' dari sejarah, kau berada di tangan yang tepat."
Sore itu juga, Emir mengajak Fatimah berjalan kaki menuju kompleks Masjid Suleymaniye. Fatimah harus setengah berlari untuk mengimbangi langkah kaki Emir yang panjang. Pria itu tidak banyak bicara, namun ia selalu memastikan Fatimah tidak tertinggal jauh di keramaian pasar rempah.
"Berdirilah di sini," ujar Emir saat mereka masuk ke dalam area salat utama masjid.
Masjid itu kosong karena bukan waktu salat. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela-jendela kecil di kubah raksasa, menciptakan berkas cahaya yang menari-nari di atas karpet tebal.
"Tutup matamu," perintah Emir pelan.
Fatimah ragu sejenak, namun ia mengikuti instruksi itu. Ia menutup matanya.
"Apa yang kau dengar?" bisik Emir di sampingnya.
"Hanya keheningan," jawab Fatimah jujur.
"Dengarkan lebih dalam. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati."
Fatimah mencoba fokus. Perlahan, ia mendengar deru angin yang tertahan di sela kubah, bisikan halus dari kejauhan, dan gema napasnya sendiri yang terpantul dengan begitu lembut. Ada sebuah harmoni frekuensi yang membuat jiwanya merasa sangat tenang, seolah-olah ruangan itu sedang memeluknya.
"Mimar Sinan meletakkan ratusan periuk kosong di dalam struktur kubah ini untuk mengatur akustik," Emir menjelaskan dengan suara rendah, hampir seperti berbisik agar tidak merusak kesucian suasana. "Dia ingin suara imam terdengar jelas hingga ke sudut terjauh, namun tetap lembut agar doa-doa jamaah bisa naik ke langit tanpa gangguan. Itulah arsitektur Islam: tidak menonjolkan diri, namun melayani."
Fatimah membuka matanya dan menoleh ke arah Emir. Pria itu sedang menatap ke arah mihrab dengan tatapan yang sangat melankolis. Ada kesedihan yang tersembunyi di balik ketegasannya.
"Kenapa Anda tahu begitu banyak tentang perasaan bangunan ini, Emir Bey?" tanya Fatimah spontan.
Emir terdiam cukup lama. Ia mengalihkan pandangannya dari mihrab ke arah Fatimah. "Karena bangunan tidak pernah berkhianat, Fatimah. Manusia bisa pergi, janji bisa diingkari, tapi batu-batu ini... mereka tetap di sini, menjaga rahasia selama ratusan tahun."
Kalimat itu membuat Fatimah tertegun. Ia menyadari bahwa di balik keahlian arsitekturnya, Emir adalah seorang pria yang menyimpan rahasia besar.
Hari mulai gelap ketika mereka keluar dari masjid. Emir mengantar Fatimah hingga ke dermaga Eminonu.
"Besok jam sembilan pagi, temui saya di lokasi restorasi di Fatih. Jangan terlambat. Orang Turki sangat menghargai waktu, apalagi jika itu waktu untuk sejarah," ujar Emir sebelum berbalik pergi.
Fatimah menaiki kapal feri menuju Uskudar. Sambil berdiri di dek kapal, ia menatap siluet kota Istanbul yang dihiasi lampu-lampu. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma garam dan kenangan tentang rumah.
Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada ibunya di Jakarta.
“Ibu, Fatimah sudah mulai belajar. Gurunya sangat hebat, meski sedikit misterius. Doakan Fatimah kuat di sini ya, Bu.”
Di bawah langit Uskudar yang bertabur bintang, Fatimah menyadari satu hal. Tantangannya di negeri ini bukan hanya tentang memahami struktur bangunan, tapi juga memahami struktur hati yang baru saja ia temui. Ia merasa, kehidupannya di Istanbul akan menjadi sebuah desain yang sangat rumit, yang hanya bisa diselesaikan dengan doa dan kesabaran.
Sambil menatap Menara Çamlıca di kejauhan yang bersinar seperti mercusuar harapan, Fatimah membisikkan satu janji: ia tidak akan membiarkan hatinya jatuh sebelum ia berhasil menyelesaikan amanah ilmunya. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir seringkali memiliki pena yang lebih cepat dari rencana manusia.
Ini adalah minggu pertamanya sebagai mahasiswi pascasarjana. Ia bangkit, merapatkan selimut wolnya sejenak sebelum melangkah ke kamar mandi untuk berwudu. Air yang menyentuh kulitnya terasa seperti es, seketika melenyapkan sisa-sisa kantuk akibat jet lag yang masih membayangi.
Setelah menunaikan salat, Fatimah duduk di atas sajadahnya, menatap ke luar jendela. Dari kejauhan, permukaan Selat Bosphorus tampak keabu-abuan di bawah langit fajar. Ia teringat kejadian di Bukit Çamlıca kemarin sore. Wajah pria itu—pria dengan mata cokelat teduh dan suara berat yang sopan—terus terbayang di benaknya.
"Siapa dia?" bisiknya pelan. "Dan kenapa kata-katanya terdengar begitu dalam?"
Fatimah segera menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Istighfar, Fatimah. Kamu di sini untuk belajar, bukan untuk memikirkan orang asing, tegurnya pada diri sendiri.
Pagi itu, Fatimah harus menuju kampus Istanbul Technical University (ITU) di Maslak. Ia memilih menggunakan Marmaray, kereta bawah laut yang menghubungkan sisi Asia dan Eropa. Baginya, setiap sudut Istanbul adalah pelajaran arsitektur yang hidup. Ia mengamati bagaimana bangunan modern berdampingan dengan sisa-sisa kejayaan Bizantium dan Ottoman tanpa terlihat dipaksakan.
Sesampainya di fakultas arsitektur, suasana tampak riuh. Mahasiswa dari berbagai belahan dunia berkumpul di aula besar. Fatimah merasa sedikit minder dengan tinggi badan gadis-gadis Turki yang menjulang dan gaya berpakaian mereka yang modis meski tetap tertutup. Namun, ia memegang erat tas ranselnya, mengingatkan dirinya bahwa ia membawa harapan Ibu dan doa-doa dari Jakarta.
"Fatimah Azzahra?" sebuah suara memanggil namanya.
Seorang wanita paruh baya dengan kacamata berbingkai perak tersenyum padanya. "Saya Profesor Elif, pembimbing akademikmu. Mari ikut ke ruangan saya."
Di dalam ruangan yang penuh dengan maket bangunan dan gulungan cetak biru, Profesor Elif menjelaskan fokus riset Fatimah. "Kamu tertarik pada akustik masjid-masjid kuno di Istanbul, bukan? Itu topik yang berat namun sangat indah. Istanbul butuh sudut pandang dari arsitek muda seperti kamu."
Fatimah mengangguk antusias. "Iya, Prof. Saya ingin mempelajari bagaimana Mimar Sinan—arsitek agung Ottoman—bisa menciptakan harmoni suara yang sempurna tanpa teknologi modern."
"Bagus. Tapi untuk itu, kamu tidak bisa hanya di perpustakaan. Kamu harus turun ke lapangan. Saya punya seorang asisten riset, arsitek muda berbakat yang sedang mengerjakan proyek restorasi di Fatih. Dia akan membantumu mengenal lapangan."
Jantung Fatimah berdegup lebih kencang.
"Terima kasih, Prof. Siapa nama asisten itu?"
"Namanya Emir. Emir Arslan. Dia mungkin sedikit kaku, tapi dia yang terbaik di bidangnya."
Siang harinya, sesuai instruksi Profesor Elif, Fatimah harus menemui Emir di sebuah kafe kecil di dekat Masjid Suleymaniye. Kafe itu berada di atas bukit, memberikan pemandangan Golden Horn yang menakjubkan.
Fatimah duduk di sudut kafe, memesan segelas Çay (teh Turki) panas. Ia terus melihat ke pintu masuk. Setiap kali lonceng pintu berbunyi, ia mendongak dengan cemas. Ia menyiapkan beberapa kalimat perkenalan dalam bahasa Turki yang sudah ia latih di kereta tadi.
Hingga kemudian, seorang pria masuk. Pria itu memakai mantel panjang berwarna abu-abu gelap. Rambutnya yang sedikit berantakan tertiup angin musim gugur tetap tidak mengurangi kesan rapinya.
Fatimah terpaku. Gelas teh di tangannya hampir saja tumpah. Pria itu adalah pria yang sama dengan pria di Bukit Çamlıca kemarin sore.
Pria itu melangkah mendekat, matanya menyisir ruangan hingga berhenti pada sosok Fatimah yang mengenakan jilbab berwarna marun. Ia tampak terkejut sejenak, namun dengan cepat menguasai keadaan. Ia berjalan menuju meja Fatimah dengan langkah yang tenang.
"Merhaba," sapanya. Kali ini, ada sedikit binar pengenalan di matanya. "Kita bertemu lagi, Nona Arsitek."
Fatimah berdiri dengan canggung, menundukkan kepalanya sedikit. "Anda... Emir Bey?"
Emir menarik kursi di depan Fatimah dan duduk. "Dan kau adalah Fatimah, mahasiswi Indonesia yang dikirim Profesor Elif untuk 'merepotkan' jadwal saya?" Emir berucap dengan nada bercanda yang sangat tipis, hampir tidak terlihat jika Fatimah tidak memperhatikan sudut bibirnya yang sedikit terangkat.
"Maaf jika saya merepotkan, Emir Bey. Saya hanya ingin belajar," jawab Fatimah dalam bahasa Inggris yang kini lebih stabil.
Emir menatap Fatimah dengan lekat, seolah sedang menilai kesungguhan gadis di depannya.
"Arsitektur di Istanbul bukan soal menggambar garis di atas kertas, Fatimah. Ini soal memahami jiwa dari batu-batu yang tersusun. Jika kau hanya ingin nilai bagus, kau salah orang. Tapi jika kau ingin memahami 'suara' dari sejarah, kau berada di tangan yang tepat."
Sore itu juga, Emir mengajak Fatimah berjalan kaki menuju kompleks Masjid Suleymaniye. Fatimah harus setengah berlari untuk mengimbangi langkah kaki Emir yang panjang. Pria itu tidak banyak bicara, namun ia selalu memastikan Fatimah tidak tertinggal jauh di keramaian pasar rempah.
"Berdirilah di sini," ujar Emir saat mereka masuk ke dalam area salat utama masjid.
Masjid itu kosong karena bukan waktu salat. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela-jendela kecil di kubah raksasa, menciptakan berkas cahaya yang menari-nari di atas karpet tebal.
"Tutup matamu," perintah Emir pelan.
Fatimah ragu sejenak, namun ia mengikuti instruksi itu. Ia menutup matanya.
"Apa yang kau dengar?" bisik Emir di sampingnya.
"Hanya keheningan," jawab Fatimah jujur.
"Dengarkan lebih dalam. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati."
Fatimah mencoba fokus. Perlahan, ia mendengar deru angin yang tertahan di sela kubah, bisikan halus dari kejauhan, dan gema napasnya sendiri yang terpantul dengan begitu lembut. Ada sebuah harmoni frekuensi yang membuat jiwanya merasa sangat tenang, seolah-olah ruangan itu sedang memeluknya.
"Mimar Sinan meletakkan ratusan periuk kosong di dalam struktur kubah ini untuk mengatur akustik," Emir menjelaskan dengan suara rendah, hampir seperti berbisik agar tidak merusak kesucian suasana. "Dia ingin suara imam terdengar jelas hingga ke sudut terjauh, namun tetap lembut agar doa-doa jamaah bisa naik ke langit tanpa gangguan. Itulah arsitektur Islam: tidak menonjolkan diri, namun melayani."
Fatimah membuka matanya dan menoleh ke arah Emir. Pria itu sedang menatap ke arah mihrab dengan tatapan yang sangat melankolis. Ada kesedihan yang tersembunyi di balik ketegasannya.
"Kenapa Anda tahu begitu banyak tentang perasaan bangunan ini, Emir Bey?" tanya Fatimah spontan.
Emir terdiam cukup lama. Ia mengalihkan pandangannya dari mihrab ke arah Fatimah. "Karena bangunan tidak pernah berkhianat, Fatimah. Manusia bisa pergi, janji bisa diingkari, tapi batu-batu ini... mereka tetap di sini, menjaga rahasia selama ratusan tahun."
Kalimat itu membuat Fatimah tertegun. Ia menyadari bahwa di balik keahlian arsitekturnya, Emir adalah seorang pria yang menyimpan rahasia besar.
Hari mulai gelap ketika mereka keluar dari masjid. Emir mengantar Fatimah hingga ke dermaga Eminonu.
"Besok jam sembilan pagi, temui saya di lokasi restorasi di Fatih. Jangan terlambat. Orang Turki sangat menghargai waktu, apalagi jika itu waktu untuk sejarah," ujar Emir sebelum berbalik pergi.
Fatimah menaiki kapal feri menuju Uskudar. Sambil berdiri di dek kapal, ia menatap siluet kota Istanbul yang dihiasi lampu-lampu. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma garam dan kenangan tentang rumah.
Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada ibunya di Jakarta.
“Ibu, Fatimah sudah mulai belajar. Gurunya sangat hebat, meski sedikit misterius. Doakan Fatimah kuat di sini ya, Bu.”
Di bawah langit Uskudar yang bertabur bintang, Fatimah menyadari satu hal. Tantangannya di negeri ini bukan hanya tentang memahami struktur bangunan, tapi juga memahami struktur hati yang baru saja ia temui. Ia merasa, kehidupannya di Istanbul akan menjadi sebuah desain yang sangat rumit, yang hanya bisa diselesaikan dengan doa dan kesabaran.
Sambil menatap Menara Çamlıca di kejauhan yang bersinar seperti mercusuar harapan, Fatimah membisikkan satu janji: ia tidak akan membiarkan hatinya jatuh sebelum ia berhasil menyelesaikan amanah ilmunya. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir seringkali memiliki pena yang lebih cepat dari rencana manusia.
Other Stories
2r
Fajri tak sengaja mendengar pembicaraan Ryan dan Rafi, ia terkejut ketika mengetahui kalau ...
Ibu, Kuizinkan Engkau Jadi Egois Malam Ini
Setiap akhir tahun, ia pulang dengan harapan ibunya ada di rumah. Yang berulang justru dap ...
Haruskah Bertemu?
Aku bertemu dengan wanita di gerbong yang sama dengan satu kursi juga. Dia sangat riang se ...
Relung
Edna kehilangan suaminya, Nugraha, secara tiba-tiba. Demi ketenangan hati, ia meninggalkan ...
My Love
Sandi dan Teresa menunda pernikahan karena Teresa harus mengajar di Timor Leste. Lama tak ...
The Unkindled Of The Broken Soil
Di dunia yang terpecah belah dan terkubur di bawah abu perang masa lalu, suara adalah keme ...