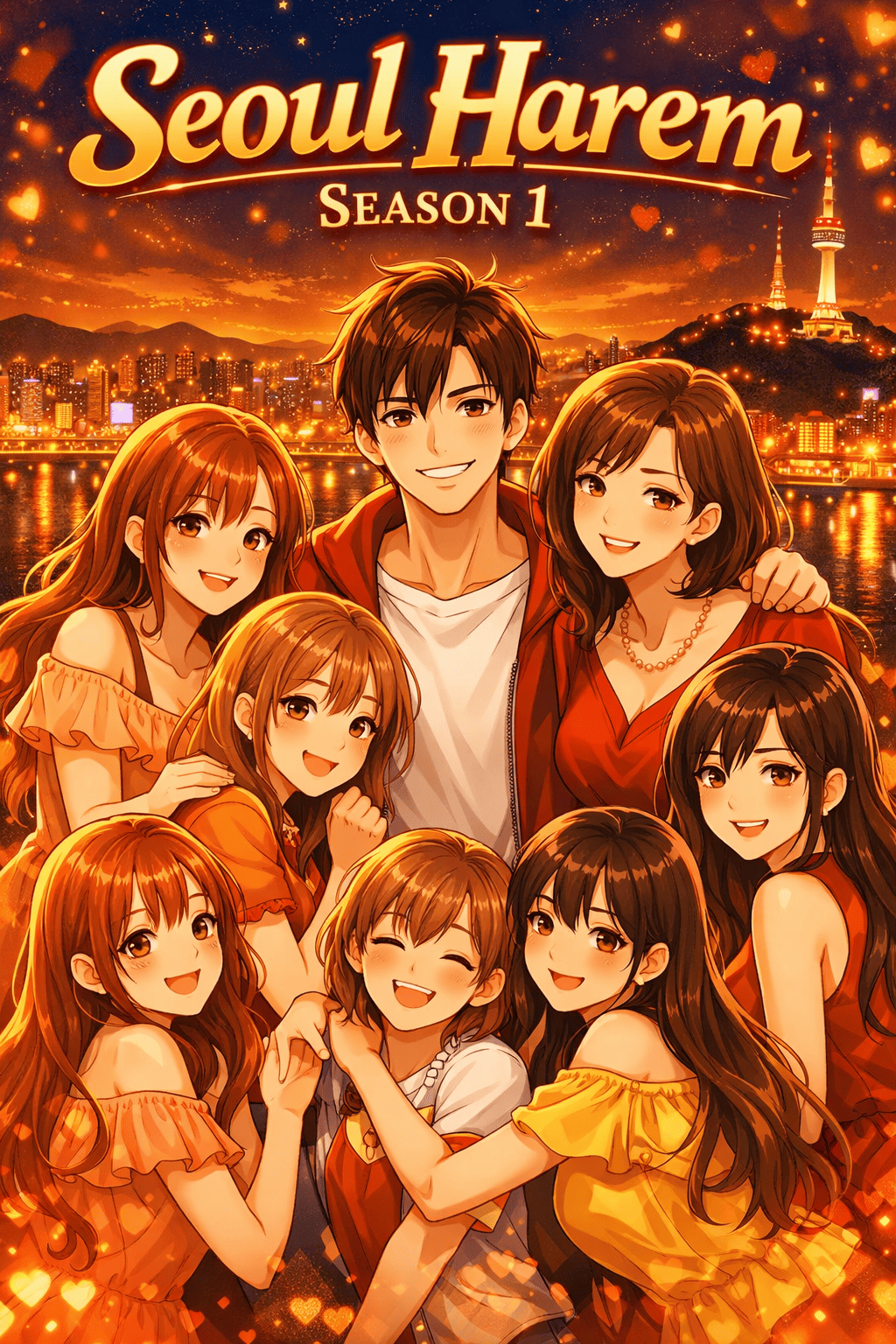Bab 8: Kesaksian Di Balik Bayang-bayang
Ruang sidang kode etik universitas terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Jika minggu lalu hanya ada Profesor Elif dan Dekan, kali ini hadir pula komite disiplin dan perwakilan dari yayasan pemberi beasiswa. Nasib pendidikan Fatimah dipertaruhkan di sini.
Fatimah duduk di kursi kayu yang keras, jemarinya bertaut di bawah meja. Ia mengenakan gamis hitam pekat dan jilbab abu-abu, sebuah pernyataan tanpa suara bahwa ia sedang berduka namun tetap tegar.
"Fatimah Azzahra," suara ketua komite disiplin, seorang pria tua dengan janggut putih yang rapi, memecah keheningan. "Kami telah meninjau bukti foto dan laporan yang masuk. Akses Anda ke manuskrip tertutup tanpa izin tertulis adalah pelanggaran serius. Apakah Anda memiliki pembelaan yang lebih kuat selain 'disuruh oleh Emir Arslan'?"
Fatimah menarik napas dalam. "Bismillah," bisiknya. Ia berdiri, lalu meletakkan sebuah map tebal di atas meja komite.
"Ini bukan sekadar pembelaan, Tuan," ujar Fatimah dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Ini adalah draf awal temuan saya mengenai restorasi akustik Masjid Suleymaniye. Di dalam sana, saya membuktikan bahwa ada kesalahan teknik pada restorasi tahun 1980 yang jika tidak segera diperbaiki, akan menyebabkan keretakan permanen pada kubah utama. Saya membutuhkan manuskrip itu bukan untuk pamer, tapi untuk menemukan formula mortar yang tepat untuk menyelamatkan bangunan tersebut."
Para penguji saling berpandangan. Mereka mulai membuka map tersebut. Suasana yang tadinya penuh penghakiman berubah menjadi diskusi teknis yang intens. Namun, sang ketua komite masih tampak ragu.
"Temuan ini luar biasa. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Anda melompati birokrasi. Siapa yang bisa menjamin bahwa data ini murni hasil kerja Anda dan bukan 'hadiah' dari Emir Arslan?"
Tepat saat itu, pintu ruang sidang terbuka. Bukan Emir yang masuk—karena ia memang dilarang hadir—melainkan Ali Ihsan.
Ali melangkah masuk dengan gaya tenang khasnya. Ia membawa sebuah laptop dan beberapa gulungan kertas kalkir.
"Maaf mengganggu jalannya persidangan, Dewan yang terhormat," Ali membungkuk hormat. "Saya Ali Ihsan, asisten peneliti doktoral. Saya hadir di sini sebagai saksi kunci."
Fatimah menatap Ali dengan bingung. Bukankah Ali sering berseberangan dengan Emir? Mengapa dia di sini?
"Saya telah memantau progres riset Fatimah sejak hari pertama di perpustakaan," Ali mulai menjelaskan sambil membuka slide presentasi di layar besar. "Banyak orang menuduh adanya favoritisme karena Emir Arslan adalah pembimbingnya. Namun, sebagai orang yang juga mengincar data yang sama, saya bersaksi bahwa Fatimah menemukan celah logika dalam teks Ottoman tersebut sendirian. Bahkan, sayalah yang mencoba 'menyuapnya' dengan bantuan bahasa agar dia memberikan data itu pada saya, tapi dia menolak."
Ali menoleh ke arah Fatimah dan mengedipkan mata tipis. "Dia sangat keras kepala dalam menjaga integritas datanya. Foto-foto yang tersebar itu diambil saat Emir sedang memarahi Fatimah karena Fatimah mempertanyakan metodologi Emir. Itu bukan kencan atau favoritisme; itu adalah perdebatan ilmiah yang sengit."
Melalui bantuan Ali, narasi yang dibangun Melisa perlahan runtuh. Ali menunjukkan bukti-bukti log yang mencatat bahwa Fatimah sering berada di perpustakaan hingga jam tutup, bekerja sendiri tanpa kehadiran Emir.
Setelah tiga jam yang melelahkan, keputusan akhirnya keluar. Beasiswa Fatimah tidak dicabut, namun ia diberikan teguran tertulis dan diwajibkan melakukan pengabdian masyarakat dengan membantu tim kearsipan universitas selama tiga bulan. Bagi Fatimah, itu adalah anugerah luar biasa.
Saat ia keluar dari gedung dekanat, ia mendapati Ali sedang menunggu di bawah pohon ek besar.
"Ali Bey... kenapa Anda membantu saya?" tanya Fatimah tulus. "Bukankah ini bisa merugikan posisi Anda di mata Profesor Elif jika ternyata saya benar-benar bersalah?"
Ali tertawa kecil, menyampirkan tasnya di bahu. "Fatimah, di Istanbul kita punya banyak arsitek, tapi sedikit sekali yang punya 'hati' untuk bangunan. Aku melihat hati itu padamu. Dan jujur saja, melihat Emir Arslan menderita karena tidak bisa membantumu adalah hiburan tersendiri bagiku."
Fatimah tersenyum tipis. "Terima kasih, Ali. Anda teman yang sangat baik."
"Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada pria yang berdiri di sana," Ali menunjuk ke arah gerbang fakultas.
Di sana, Emir Arslan berdiri di samping mobilnya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja memenangkan perang namun terlalu lelah untuk merayakannya. Ali melambaikan tangan pada Emir dengan gaya mengejek, lalu berjalan pergi meninggalkan Fatimah.
Fatimah berjalan mendekati Emir, namun berhenti dalam jarak tiga meter. Aturan skorsing masih berlaku; mereka tidak boleh terlihat "bekerja sama" secara resmi.
"Semuanya lancar?" tanya Emir. Suaranya terdengar parau, seperti orang yang kurang tidur selama berhari-hari.
"Alhamdulillah, Bey. Beasiswa saya aman. Terima kasih karena sudah... mempercayai saya."
Emir menatap Fatimah dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kerinduan yang tertahan, namun juga ada rasa bangga yang besar. "Ali memberitahuku apa yang kau katakan di dalam. Tentang kesalahan restorasi tahun 80-an itu. Kau berani sekali menantang sejarah, Fatimah."
"Saya hanya mengikuti apa yang batu-batu itu katakan pada saya, seperti yang Anda ajarkan," jawab Fatimah lembut.
Emir tersenyum, kali ini sebuah senyuman yang benar-benar lepas. "Kau sudah bukan lagi mahasiswi yang bingung di Bukit Çamlıca. Kau sudah menjadi bagian dari Istanbul sekarang."
Tiba-tiba, Emir merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil kayu. Ia meletakkannya di atas pembatas jalan dari batu, lalu mundur beberapa langkah, membiarkan Fatimah mengambilnya.
"Apa ini?" tanya Fatimah saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah tesbih (tasbih) dari batu amber berwarna madu yang sangat cantik.
"Itu milik ibuku," ucap Emir pelan. "Dia selalu membawanya saat merasa cemas. Aku ingin kau memegangnya. Sebagai pengingat bahwa di setiap butir doa yang kau ucapkan, ada seseorang di kota ini yang juga sedang menyebut namamu dalam doanya."
Fatimah merasakan matanya memanas. Pemberian ini jauh lebih berharga daripada perhiasan mahal mana pun. "Bey, ini terlalu berharga..."
"Simpanlah. Anggap itu sebagai 'fondasi' baru untuk persahabatan kita... atau apa pun sebutannya nanti," Emir berbalik menuju mobilnya. "Besok kau mulai bekerja di kearsipan. Itu tempat yang membosankan dan berdebu. Tapi aku tahu kau akan menemui harta karun di sana."
Sebelum masuk ke mobil, Emir menoleh sekali lagi. "Dan Fatimah? Melisa sudah dikirim ayahnya ke London untuk mengurus cabang di sana. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah menyelesaikan 'restorasi' pada hubungan keluarga kami."
Mobil Volvo itu perlahan meninggalkan area kampus. Fatimah berdiri diam, menggenggam tasbih amber itu erat-erat. Harum aroma kayu cendana masih tertinggal di udara.
Malam itu, Fatimah duduk di balkon asramanya. Ia memutar butir-butir tasbih amber milik ibu Emir sambil menatap Menara Çamlıca yang bercahaya di kejauhan.
Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia alami sejak menginjakkan kaki di Turki adalah cara Allah untuk memperkuat strukturnya. Seperti bangunan Ottoman yang harus tahan gempa, hatinya pun sedang diuji kelenturannya.
Ia teringat sebuah kutipan dari Jalaluddin Rumi yang pernah Emir ceritakan: "Luka adalah tempat di mana cahaya memasuki dirimu." Hari ini, luka fitnah itu telah sembuh, dan cahaya yang masuk terasa jauh lebih terang dari sebelumnya.
Fatimah tidak tahu apa yang menantinya di babak pengabdian masyarakat di kearsipan, atau bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Emir yang kini terasa semakin dalam. Namun satu hal yang pasti: di bawah langit Istanbul, ia telah menemukan rumah bagi jiwanya.
Ia membuka buku hariannya dan menulis singkat:
Saat batu-batu mulai bicara, hati pun belajar untuk mendengar. Terima kasih, Ya Allah, atas tasbih amber dan keberanian yang Kau titipkan lewat orang-orang baik.
Fatimah menutup matanya, menghirup udara malam yang segar. Di kejauhan, suara azan Isya mulai berkumandang, bersahutan di antara dua benua, membawa pesan damai bagi mereka yang bersabar.
Fatimah duduk di kursi kayu yang keras, jemarinya bertaut di bawah meja. Ia mengenakan gamis hitam pekat dan jilbab abu-abu, sebuah pernyataan tanpa suara bahwa ia sedang berduka namun tetap tegar.
"Fatimah Azzahra," suara ketua komite disiplin, seorang pria tua dengan janggut putih yang rapi, memecah keheningan. "Kami telah meninjau bukti foto dan laporan yang masuk. Akses Anda ke manuskrip tertutup tanpa izin tertulis adalah pelanggaran serius. Apakah Anda memiliki pembelaan yang lebih kuat selain 'disuruh oleh Emir Arslan'?"
Fatimah menarik napas dalam. "Bismillah," bisiknya. Ia berdiri, lalu meletakkan sebuah map tebal di atas meja komite.
"Ini bukan sekadar pembelaan, Tuan," ujar Fatimah dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Ini adalah draf awal temuan saya mengenai restorasi akustik Masjid Suleymaniye. Di dalam sana, saya membuktikan bahwa ada kesalahan teknik pada restorasi tahun 1980 yang jika tidak segera diperbaiki, akan menyebabkan keretakan permanen pada kubah utama. Saya membutuhkan manuskrip itu bukan untuk pamer, tapi untuk menemukan formula mortar yang tepat untuk menyelamatkan bangunan tersebut."
Para penguji saling berpandangan. Mereka mulai membuka map tersebut. Suasana yang tadinya penuh penghakiman berubah menjadi diskusi teknis yang intens. Namun, sang ketua komite masih tampak ragu.
"Temuan ini luar biasa. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Anda melompati birokrasi. Siapa yang bisa menjamin bahwa data ini murni hasil kerja Anda dan bukan 'hadiah' dari Emir Arslan?"
Tepat saat itu, pintu ruang sidang terbuka. Bukan Emir yang masuk—karena ia memang dilarang hadir—melainkan Ali Ihsan.
Ali melangkah masuk dengan gaya tenang khasnya. Ia membawa sebuah laptop dan beberapa gulungan kertas kalkir.
"Maaf mengganggu jalannya persidangan, Dewan yang terhormat," Ali membungkuk hormat. "Saya Ali Ihsan, asisten peneliti doktoral. Saya hadir di sini sebagai saksi kunci."
Fatimah menatap Ali dengan bingung. Bukankah Ali sering berseberangan dengan Emir? Mengapa dia di sini?
"Saya telah memantau progres riset Fatimah sejak hari pertama di perpustakaan," Ali mulai menjelaskan sambil membuka slide presentasi di layar besar. "Banyak orang menuduh adanya favoritisme karena Emir Arslan adalah pembimbingnya. Namun, sebagai orang yang juga mengincar data yang sama, saya bersaksi bahwa Fatimah menemukan celah logika dalam teks Ottoman tersebut sendirian. Bahkan, sayalah yang mencoba 'menyuapnya' dengan bantuan bahasa agar dia memberikan data itu pada saya, tapi dia menolak."
Ali menoleh ke arah Fatimah dan mengedipkan mata tipis. "Dia sangat keras kepala dalam menjaga integritas datanya. Foto-foto yang tersebar itu diambil saat Emir sedang memarahi Fatimah karena Fatimah mempertanyakan metodologi Emir. Itu bukan kencan atau favoritisme; itu adalah perdebatan ilmiah yang sengit."
Melalui bantuan Ali, narasi yang dibangun Melisa perlahan runtuh. Ali menunjukkan bukti-bukti log yang mencatat bahwa Fatimah sering berada di perpustakaan hingga jam tutup, bekerja sendiri tanpa kehadiran Emir.
Setelah tiga jam yang melelahkan, keputusan akhirnya keluar. Beasiswa Fatimah tidak dicabut, namun ia diberikan teguran tertulis dan diwajibkan melakukan pengabdian masyarakat dengan membantu tim kearsipan universitas selama tiga bulan. Bagi Fatimah, itu adalah anugerah luar biasa.
Saat ia keluar dari gedung dekanat, ia mendapati Ali sedang menunggu di bawah pohon ek besar.
"Ali Bey... kenapa Anda membantu saya?" tanya Fatimah tulus. "Bukankah ini bisa merugikan posisi Anda di mata Profesor Elif jika ternyata saya benar-benar bersalah?"
Ali tertawa kecil, menyampirkan tasnya di bahu. "Fatimah, di Istanbul kita punya banyak arsitek, tapi sedikit sekali yang punya 'hati' untuk bangunan. Aku melihat hati itu padamu. Dan jujur saja, melihat Emir Arslan menderita karena tidak bisa membantumu adalah hiburan tersendiri bagiku."
Fatimah tersenyum tipis. "Terima kasih, Ali. Anda teman yang sangat baik."
"Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada pria yang berdiri di sana," Ali menunjuk ke arah gerbang fakultas.
Di sana, Emir Arslan berdiri di samping mobilnya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja memenangkan perang namun terlalu lelah untuk merayakannya. Ali melambaikan tangan pada Emir dengan gaya mengejek, lalu berjalan pergi meninggalkan Fatimah.
Fatimah berjalan mendekati Emir, namun berhenti dalam jarak tiga meter. Aturan skorsing masih berlaku; mereka tidak boleh terlihat "bekerja sama" secara resmi.
"Semuanya lancar?" tanya Emir. Suaranya terdengar parau, seperti orang yang kurang tidur selama berhari-hari.
"Alhamdulillah, Bey. Beasiswa saya aman. Terima kasih karena sudah... mempercayai saya."
Emir menatap Fatimah dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kerinduan yang tertahan, namun juga ada rasa bangga yang besar. "Ali memberitahuku apa yang kau katakan di dalam. Tentang kesalahan restorasi tahun 80-an itu. Kau berani sekali menantang sejarah, Fatimah."
"Saya hanya mengikuti apa yang batu-batu itu katakan pada saya, seperti yang Anda ajarkan," jawab Fatimah lembut.
Emir tersenyum, kali ini sebuah senyuman yang benar-benar lepas. "Kau sudah bukan lagi mahasiswi yang bingung di Bukit Çamlıca. Kau sudah menjadi bagian dari Istanbul sekarang."
Tiba-tiba, Emir merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil kayu. Ia meletakkannya di atas pembatas jalan dari batu, lalu mundur beberapa langkah, membiarkan Fatimah mengambilnya.
"Apa ini?" tanya Fatimah saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah tesbih (tasbih) dari batu amber berwarna madu yang sangat cantik.
"Itu milik ibuku," ucap Emir pelan. "Dia selalu membawanya saat merasa cemas. Aku ingin kau memegangnya. Sebagai pengingat bahwa di setiap butir doa yang kau ucapkan, ada seseorang di kota ini yang juga sedang menyebut namamu dalam doanya."
Fatimah merasakan matanya memanas. Pemberian ini jauh lebih berharga daripada perhiasan mahal mana pun. "Bey, ini terlalu berharga..."
"Simpanlah. Anggap itu sebagai 'fondasi' baru untuk persahabatan kita... atau apa pun sebutannya nanti," Emir berbalik menuju mobilnya. "Besok kau mulai bekerja di kearsipan. Itu tempat yang membosankan dan berdebu. Tapi aku tahu kau akan menemui harta karun di sana."
Sebelum masuk ke mobil, Emir menoleh sekali lagi. "Dan Fatimah? Melisa sudah dikirim ayahnya ke London untuk mengurus cabang di sana. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah menyelesaikan 'restorasi' pada hubungan keluarga kami."
Mobil Volvo itu perlahan meninggalkan area kampus. Fatimah berdiri diam, menggenggam tasbih amber itu erat-erat. Harum aroma kayu cendana masih tertinggal di udara.
Malam itu, Fatimah duduk di balkon asramanya. Ia memutar butir-butir tasbih amber milik ibu Emir sambil menatap Menara Çamlıca yang bercahaya di kejauhan.
Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia alami sejak menginjakkan kaki di Turki adalah cara Allah untuk memperkuat strukturnya. Seperti bangunan Ottoman yang harus tahan gempa, hatinya pun sedang diuji kelenturannya.
Ia teringat sebuah kutipan dari Jalaluddin Rumi yang pernah Emir ceritakan: "Luka adalah tempat di mana cahaya memasuki dirimu." Hari ini, luka fitnah itu telah sembuh, dan cahaya yang masuk terasa jauh lebih terang dari sebelumnya.
Fatimah tidak tahu apa yang menantinya di babak pengabdian masyarakat di kearsipan, atau bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Emir yang kini terasa semakin dalam. Namun satu hal yang pasti: di bawah langit Istanbul, ia telah menemukan rumah bagi jiwanya.
Ia membuka buku hariannya dan menulis singkat:
Saat batu-batu mulai bicara, hati pun belajar untuk mendengar. Terima kasih, Ya Allah, atas tasbih amber dan keberanian yang Kau titipkan lewat orang-orang baik.
Fatimah menutup matanya, menghirup udara malam yang segar. Di kejauhan, suara azan Isya mulai berkumandang, bersahutan di antara dua benua, membawa pesan damai bagi mereka yang bersabar.
Other Stories
Kenangan Indah Bersama
tentang cinta masa smk,di buat dengan harapan tentang kenangan yang tidak bisa di ulang ...
Seoul Harem
Raka Aditya, pemuda tangguh dari Indonesia, memimpin keluarganya memulai hidup baru di gem ...
Dia Bukan Dia
Sebuah pengkhianatan yang jauh lebih gelap dari perselingkuhan biasa. Malam itu, di tengah ...
Ophelia
Claire selalu bilang, kematian Ophelia itu indah, tenang dan lembut seperti arus sungai. T ...
Egler
Anton, anak tunggal yang kesepian karena orang tuanya sibuk, melarikan diri ke dunia game ...
Pahlawan Revolusi
tes upload cerita jgn di publish ...