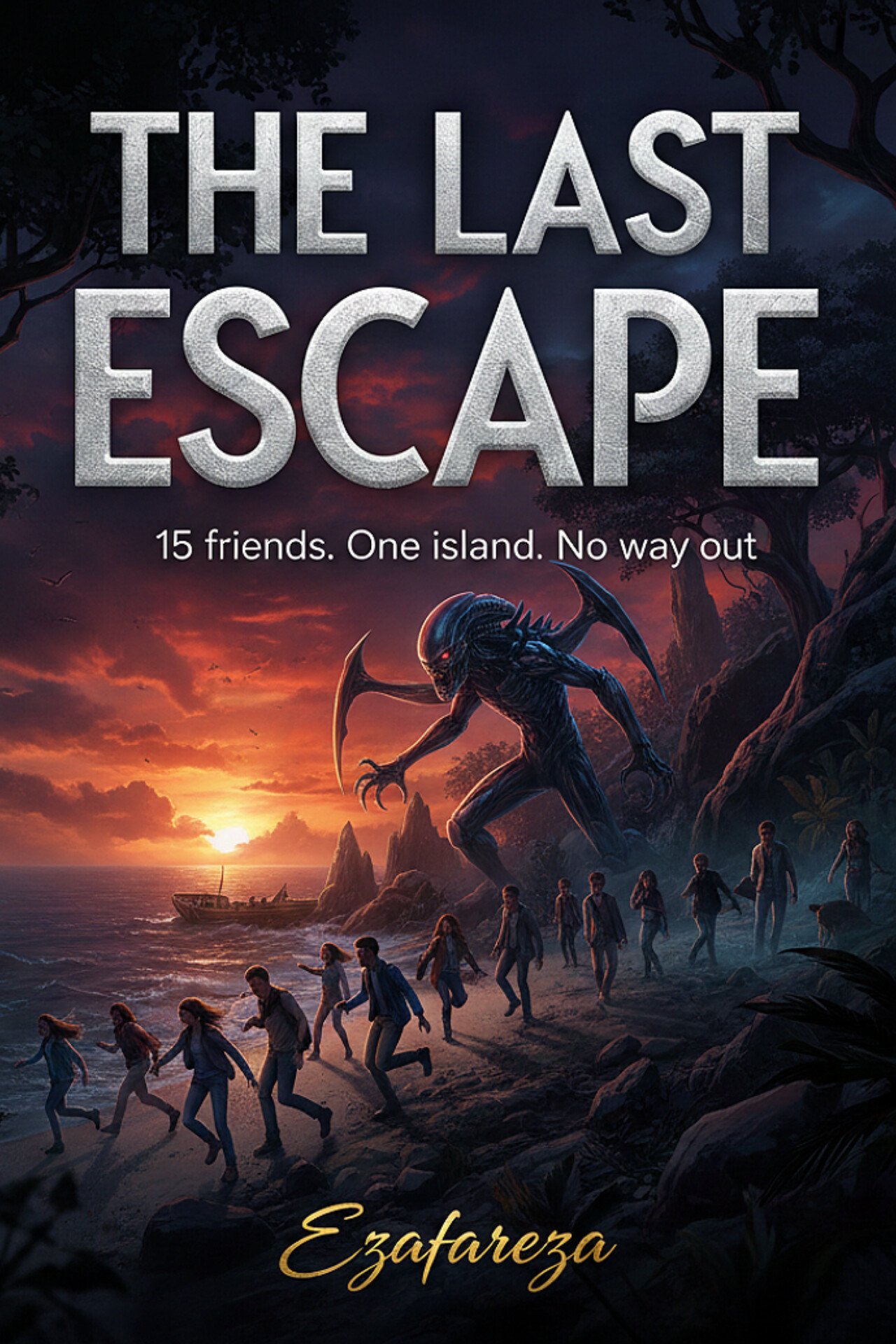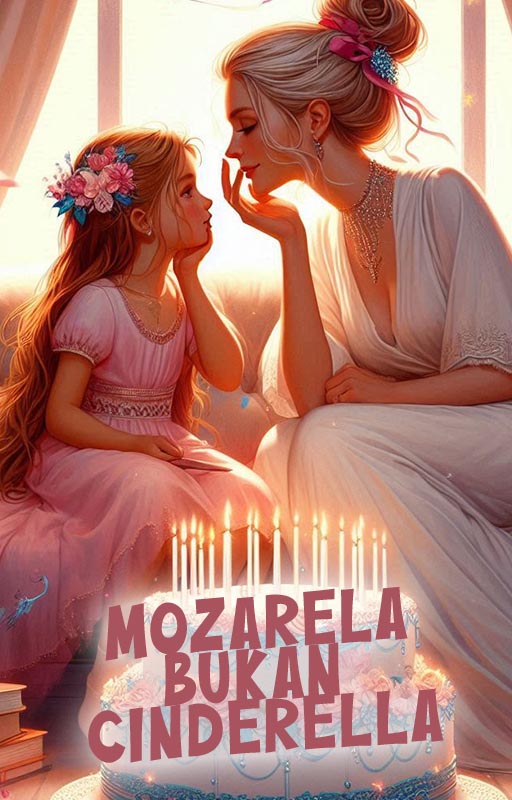Bab 11: Debu Jakarta Dan Muslihat Istanbul
Pagi hari di Bandara Istanbul (IST) terasa dingin dan sibuk. Emir Arslan berdiri di depan pintu keberangkatan internasional dengan koper kecil dan tas berisi dokumen proyek. Ia mengenakan setelan jas santai tanpa dasi, wajahnya menunjukkan ketegasan seorang pria yang sedang menjalankan misi hidup dan mati.
Fatimah mengantarnya bersama Ali Ihsan. Ini adalah momen yang aneh; seorang pria Turki yang paling berpengaruh dalam karier akademis Fatimah, kini terbang ke belahan dunia lain demi menyelamatkan sebuah toko kue kecil di Jakarta.
"Jangan terlalu khawatir," ucap Emir, menatap Fatimah yang tampak gelisah. "Aku sudah mempelajari struktur tanah dan hukum agraria di sana melalui kolega di KBRI. Aku tidak akan membiarkan sejarah kakek kita dihancurkan oleh mesin pengeruk tanah."
Fatimah mengangguk, namun jemarinya terus memutar butir tasbih amber di dalam saku.
"Hati-hati, Bey. Jakarta tidak sedingin Istanbul, tapi persaingan di sana bisa jauh lebih panas."
"Aku membawa Ali sebagai penerjemah dan asisten teknis," Emir melirik Ali yang sedang sibuk memotret paspornya sendiri untuk diunggah ke media sosial. "Setidaknya dia bisa berguna untuk mengajak bapak-bapak pejabat itu tertawa saat negosiasi mulai buntu."
Setelah pelukan singkat yang penuh rasa hormat dengan Pakde Anwar—yang juga kembali ke Jakarta—Emir melangkah menuju pemeriksaan paspor. Sebelum menghilang di balik gerbang, ia menoleh sekali lagi dan memberi isyarat tangan pada Fatimah agar tetap kuat.
Hanya beberapa jam setelah pesawat Emir lepas landas, badai di Istanbul mulai bekerja. Di sebuah restoran mewah di kawasan Nişantaşı, Melisa duduk berhadapan dengan ayahnya, Tuan Sahin. Di depan mereka tersedia berbagai macam meze (hidangan pembuka) yang mewah, namun selera makan Melisa telah hilang.
"Emir sudah berangkat ke Jakarta, Ayah," lapor Melisa dengan nada tajam. "Dia benar-benar gila. Dia mempertaruhkan reputasi firma kita untuk melindungi sebuah pasar kumuh di negara dunia ketiga hanya demi gadis itu."
Tuan Sahin menyesap kopinya perlahan.
Matanya yang licik menunjukkan bahwa ia sudah selangkah lebih maju. "Emir itu arsitek yang hebat, tapi dia terlalu emosional soal sejarah. Dia lupa bahwa fondasi bisnis tidak dibangun di atas kenangan, tapi di atas keuntungan. Jika dia ingin bermain pahlawan di Jakarta, biarkan saja. Tapi kita harus memastikan bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan panggung di sana."
Melisa tersenyum licik. "Apa rencana Ayah?"
"Aku sudah menghubungi mitra kita di pengembang Jakarta. Katakan pada mereka untuk mempercepat proses eksekusi lahan sebelum Emir sempat mempresentasikan proposal cagar budayanya. Dan satu lagi," Tuan Sahin menaruh cangkirnya dengan bunyi denting yang keras. "Buatlah masalah di kampus. Jika beasiswa gadis itu dicabut karena skandal moral yang baru, Emir tidak akan punya alasan lagi untuk membelanya."
Fatimah kembali ke rutinitasnya di gudang arsip dengan perasaan yang berat. Namun, saat ia masuk ke ruangan bawah tanah itu, ia menemukan kekacauan. Rak-rak yang kemarin sudah ia rapikan kini terguling. Map cokelat berisi dokumen Masjid Istiqlal dan foto kakeknya telah hilang.
"Tidak mungkin..." Fatimah mencari di setiap sudut dengan panik. "Semua data digitalnya juga terhapus?"
Ia segera menuju komputer pusat kearsipan, namun layarnya hanya menunjukkan pesan Error: Data Not Found. Seseorang telah masuk menggunakan akun administrator dan menghapus jejak kerja Fatimah selama berminggu-minggu. Tanpa dokumen itu, Emir tidak akan punya bukti otentik tentang hubungan sejarah antara ITU dan pembangunan di Jakarta untuk dibawa ke meja menteri.
Fatimah terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ini bukan lagi sekadar persaingan akademik. Ini adalah sabotase sistematis.
Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah panggilan video dari Jakarta. Itu adalah Ali Ihsan.
"Fat! Kau tidak akan percaya!" Ali berteriak di depan kamera, memperlihatkan latar belakang kemacetan Jakarta yang legendaris. "Emir sedang di dalam mobil, menggerutu karena panas dan macet. Tapi kau tahu apa? Kami baru saja bertemu dengan pengurus Masjid Istiqlal. Mereka menyambut kami seperti pahlawan yang pulang!"
Fatimah mencoba tersenyum meskipun matanya sembab. "Ali, dengarkan aku. Dokumen sejarah itu... dokumen yang membuktikan kerjasama kakek Emir dan kakekku... semuanya dicuri di sini. Datanya dihapus."
Suara tawa Ali terhenti. Di latar belakang, Fatimah bisa melihat Emir yang tadinya sedang membaca dokumen, langsung merampas ponsel dari tangan Ali.
"Fatimah?" Wajah Emir memenuhi layar. Matanya yang tajam langsung menangkap sisa air mata di wajah Fatimah. "Siapa yang melakukannya?"
"Aku tidak tahu, Bey. Tapi map aslinya hilang.
Aku tidak punya bukti untuk mendukung proposal Anda di sana."
Emir terdiam sejenak, rahangnya mengeras.
"Dengarkan aku baik-baik. Mereka bisa mencuri kertasnya, mereka bisa menghapus datanya, tapi mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa bangunan itu berdiri di depan mataku sekarang. Jangan panik. Aku ingin kau pergi ke rumah lamaku di Bursa. Ada kunci di bawah pot bunga zaitun di teras belakang. Cari di gudang bawah tanah, di sana ada salinan pribadi milik kakekku."
"Bursa? Itu jauh, Bey. Dan saya tidak punya izin keluar kampus."
"Persetan dengan izin!" Emir membentak, bukan pada Fatimah, tapi pada situasi itu. "Pakai mobilku, kuncinya ada di laci meja kantorku yang sudah kau ketahui. Pergilah sekarang sebelum mereka sadar bahwa ada salinan kedua. Aku akan menahan situasi di Jakarta selama mungkin."
Fatimah mengambil keputusan berani. Ia menyelinap ke kantor Emir, mengambil kunci mobil Volvo tua itu, dan berkendara menuju Bursa melalui jembatan Osmangazi yang membelah laut. Ini adalah pertama kalinya ia menyetir di Turki, namun ketakutannya pada kegagalan jauh lebih besar daripada ketakutannya pada jalan raya.
Bursa menyambutnya dengan udara yang lebih segar dan pemandangan Gunung Uludağ yang berselimut salju di puncaknya. Ia menemukan rumah tua keluarga Arslan—sebuah rumah kayu bergaya Ottoman yang tampak terawat namun sunyi.
Dengan tangan gemetar, ia menemukan kunci di bawah pot zaitun sesuai instruksi Emir. Saat pintu terbuka, aroma kayu tua dan kenangan menyergapnya. Ia menuju gudang bawah tanah yang dipenuhi dengan peti-peti kayu.
Setelah berjam-jam mencari, Fatimah menemukan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya, tidak hanya ada dokumen yang ia cari, tapi juga ada sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak: seikat surat-surat lama.
Surat-surat itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang kaku, dikirim dari Jakarta tahun 1965.
"Untuk Mustafa Arslan. Terima kasih telah menjaga rahasia pembangunan ini. Aku telah menyimpan bagian dari desainmu di bawah fondasi utama sebagai tanda persaudaraan. Jika suatu saat anak cucu kita bertemu, biarlah rahasia ini menjadi jembatan bagi mereka."
Fatimah menyadari sesuatu yang besar. Ada bagian dari desain Istiqlal yang sengaja disembunyikan untuk menjaga keamanan struktur saat gejolak politik di Indonesia masa itu. Dan rahasia itu adalah kunci untuk menyelamatkan pasar di sebelahnya.
Sementara itu, di Jakarta, Tuan Sahin dan mitranya sudah mulai mengerahkan buldoser ke area pasar. Mereka mengklaim bahwa izin cagar budaya yang diajukan Emir tidak sah karena kekurangan dokumen asli dari Turki.
"Maaf, Tuan Arslan," ujar sang kontraktor di Jakarta dengan nada meremehkan. "Tanpa bukti otentik bahwa lahan pasar ini adalah bagian dari zona penyangga sejarah yang dirancang kakek Anda, kami akan meratakannya sore ini."
Emir berdiri di depan buldoser, tangannya bersedekap. Ia menatap jam tangannya. "Tunggu sepuluh menit lagi."
"Sepuluh menit tidak akan mengubah sejarah, Tuan," ejek si kontraktor.
Tiba-tiba, ponsel Emir bergetar. Sebuah email masuk dari Fatimah yang sudah berhasil memindai dokumen dari Bursa. Emir tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang mematikan.
"Sebenarnya," Emir memutar layar tabletnya ke arah kontraktor dan pejabat yang hadir, "sepuluh menit adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan bahwa tepat di bawah pasar ini terdapat saluran drainase kuno yang terhubung langsung dengan fondasi Masjid Istiqlal. Jika kalian menghancurkan pasar ini, kalian akan merusak stabilitas fondasi masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Apakah kalian siap bertanggung jawab atas runtuhnya Istiqlal?"
Semua orang di sana mendadak pucat. Menghancurkan pasar adalah urusan bisnis, tapi merusak Istiqlal adalah urusan nasional yang bisa memicu amarah jutaan orang.
Di Istanbul, Fatimah yang sedang duduk di teras rumah tua di Bursa, menerima pesan singkat dari Ali:
"OPERASI BERHASIL! Buldoser mundur. Emir baru saja menjadi pahlawan nasional di sini. Dan kau... kau adalah malaikat pelindungnya, Fatimah."
Fatimah menangis bahagia di bawah pohon zaitun. Namun, di saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar rumah Bursa. Pintu terbuka, dan Melisa turun dengan wajah merah padam karena amarah.
"Kau pikir kau sudah menang, gadis desa?" Melisa berjalan mendekat dengan tatapan mengancam. "Kau mencuri dokumen keluarga Arslan. Aku sudah melaporkanmu pada polisi Turki atas tuduhan pencurian properti pribadi."
Fatimah berdiri, menggenggam tasbih ambernya kuat-kuat. Ia tidak lagi takut. "Ini bukan pencurian, Melisa Hanım. Ini adalah pemulihan sejarah. Dan rumah ini milik Emir Bey, dialah yang memberikan kuncinya padaku."
"Kita lihat saja siapa yang akan dipercaya polisi saat Emir sedang berada di belahan dunia lain," Melisa mengangkat ponselnya, siap melakukan panggilan.
Namun, sebelum Melisa sempat menekan tombol, suara sirine polisi justru terdengar mendekat. Tapi bukan menuju Fatimah. Dua petugas polisi turun dan menghampiri Melisa.
"Melisa Sahin? Anda ditahan atas tuduhan sabotase data universitas dan pencurian dokumen negara dari ruang kearsipan Taşkışla. Kami memiliki rekaman CCTV yang baru saja dipulihkan oleh tim IT universitas."
Fatimah tertegun. Di balik polisi itu, muncul Profesor Elif yang tampak sangat marah namun juga lega.
"Kau melakukan pekerjaan hebat, Fatimah," ujar Profesor Elif. "Ali Ihsan memberikan akses jarak jauh pada tim IT kami untuk melacak siapa yang menghapus datamu. Melisa lupa bahwa di universitas ini, jejak digital lebih sulit dihapus daripada debu."
Malam itu, Istanbul dan Jakarta terhubung oleh satu frekuensi kemenangan. Emir yang masih berada di Jakarta, menelepon Fatimah yang sudah kembali ke asrama Istanbul.
"Terima kasih, Fatimah," suara Emir terdengar lembut, jauh dari kesan tegas biasanya. "Kau tidak hanya menyelamatkan pasar itu, tapi kau menyelamatkan kehormatan keluargaku."
"Kita melakukannya bersama, Bey," jawab Fatimah.
"Bersiaplah," lanjut Emir. "Aku akan pulang lusa. Dan aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku sudah bicara dengan ibumu di Jakarta... dan ada sebuah 'restorasi' lain yang ingin aku ajukan secara resmi padanya."
Jantung Fatimah berdegup kencang. Ia tahu, babak pengabdiannya mungkin akan segera berakhir, namun babak baru dalam hidupnya sebagai "jembatan dua benua" baru saja akan dimulai.
Fatimah mengantarnya bersama Ali Ihsan. Ini adalah momen yang aneh; seorang pria Turki yang paling berpengaruh dalam karier akademis Fatimah, kini terbang ke belahan dunia lain demi menyelamatkan sebuah toko kue kecil di Jakarta.
"Jangan terlalu khawatir," ucap Emir, menatap Fatimah yang tampak gelisah. "Aku sudah mempelajari struktur tanah dan hukum agraria di sana melalui kolega di KBRI. Aku tidak akan membiarkan sejarah kakek kita dihancurkan oleh mesin pengeruk tanah."
Fatimah mengangguk, namun jemarinya terus memutar butir tasbih amber di dalam saku.
"Hati-hati, Bey. Jakarta tidak sedingin Istanbul, tapi persaingan di sana bisa jauh lebih panas."
"Aku membawa Ali sebagai penerjemah dan asisten teknis," Emir melirik Ali yang sedang sibuk memotret paspornya sendiri untuk diunggah ke media sosial. "Setidaknya dia bisa berguna untuk mengajak bapak-bapak pejabat itu tertawa saat negosiasi mulai buntu."
Setelah pelukan singkat yang penuh rasa hormat dengan Pakde Anwar—yang juga kembali ke Jakarta—Emir melangkah menuju pemeriksaan paspor. Sebelum menghilang di balik gerbang, ia menoleh sekali lagi dan memberi isyarat tangan pada Fatimah agar tetap kuat.
Hanya beberapa jam setelah pesawat Emir lepas landas, badai di Istanbul mulai bekerja. Di sebuah restoran mewah di kawasan Nişantaşı, Melisa duduk berhadapan dengan ayahnya, Tuan Sahin. Di depan mereka tersedia berbagai macam meze (hidangan pembuka) yang mewah, namun selera makan Melisa telah hilang.
"Emir sudah berangkat ke Jakarta, Ayah," lapor Melisa dengan nada tajam. "Dia benar-benar gila. Dia mempertaruhkan reputasi firma kita untuk melindungi sebuah pasar kumuh di negara dunia ketiga hanya demi gadis itu."
Tuan Sahin menyesap kopinya perlahan.
Matanya yang licik menunjukkan bahwa ia sudah selangkah lebih maju. "Emir itu arsitek yang hebat, tapi dia terlalu emosional soal sejarah. Dia lupa bahwa fondasi bisnis tidak dibangun di atas kenangan, tapi di atas keuntungan. Jika dia ingin bermain pahlawan di Jakarta, biarkan saja. Tapi kita harus memastikan bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan panggung di sana."
Melisa tersenyum licik. "Apa rencana Ayah?"
"Aku sudah menghubungi mitra kita di pengembang Jakarta. Katakan pada mereka untuk mempercepat proses eksekusi lahan sebelum Emir sempat mempresentasikan proposal cagar budayanya. Dan satu lagi," Tuan Sahin menaruh cangkirnya dengan bunyi denting yang keras. "Buatlah masalah di kampus. Jika beasiswa gadis itu dicabut karena skandal moral yang baru, Emir tidak akan punya alasan lagi untuk membelanya."
Fatimah kembali ke rutinitasnya di gudang arsip dengan perasaan yang berat. Namun, saat ia masuk ke ruangan bawah tanah itu, ia menemukan kekacauan. Rak-rak yang kemarin sudah ia rapikan kini terguling. Map cokelat berisi dokumen Masjid Istiqlal dan foto kakeknya telah hilang.
"Tidak mungkin..." Fatimah mencari di setiap sudut dengan panik. "Semua data digitalnya juga terhapus?"
Ia segera menuju komputer pusat kearsipan, namun layarnya hanya menunjukkan pesan Error: Data Not Found. Seseorang telah masuk menggunakan akun administrator dan menghapus jejak kerja Fatimah selama berminggu-minggu. Tanpa dokumen itu, Emir tidak akan punya bukti otentik tentang hubungan sejarah antara ITU dan pembangunan di Jakarta untuk dibawa ke meja menteri.
Fatimah terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ini bukan lagi sekadar persaingan akademik. Ini adalah sabotase sistematis.
Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah panggilan video dari Jakarta. Itu adalah Ali Ihsan.
"Fat! Kau tidak akan percaya!" Ali berteriak di depan kamera, memperlihatkan latar belakang kemacetan Jakarta yang legendaris. "Emir sedang di dalam mobil, menggerutu karena panas dan macet. Tapi kau tahu apa? Kami baru saja bertemu dengan pengurus Masjid Istiqlal. Mereka menyambut kami seperti pahlawan yang pulang!"
Fatimah mencoba tersenyum meskipun matanya sembab. "Ali, dengarkan aku. Dokumen sejarah itu... dokumen yang membuktikan kerjasama kakek Emir dan kakekku... semuanya dicuri di sini. Datanya dihapus."
Suara tawa Ali terhenti. Di latar belakang, Fatimah bisa melihat Emir yang tadinya sedang membaca dokumen, langsung merampas ponsel dari tangan Ali.
"Fatimah?" Wajah Emir memenuhi layar. Matanya yang tajam langsung menangkap sisa air mata di wajah Fatimah. "Siapa yang melakukannya?"
"Aku tidak tahu, Bey. Tapi map aslinya hilang.
Aku tidak punya bukti untuk mendukung proposal Anda di sana."
Emir terdiam sejenak, rahangnya mengeras.
"Dengarkan aku baik-baik. Mereka bisa mencuri kertasnya, mereka bisa menghapus datanya, tapi mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa bangunan itu berdiri di depan mataku sekarang. Jangan panik. Aku ingin kau pergi ke rumah lamaku di Bursa. Ada kunci di bawah pot bunga zaitun di teras belakang. Cari di gudang bawah tanah, di sana ada salinan pribadi milik kakekku."
"Bursa? Itu jauh, Bey. Dan saya tidak punya izin keluar kampus."
"Persetan dengan izin!" Emir membentak, bukan pada Fatimah, tapi pada situasi itu. "Pakai mobilku, kuncinya ada di laci meja kantorku yang sudah kau ketahui. Pergilah sekarang sebelum mereka sadar bahwa ada salinan kedua. Aku akan menahan situasi di Jakarta selama mungkin."
Fatimah mengambil keputusan berani. Ia menyelinap ke kantor Emir, mengambil kunci mobil Volvo tua itu, dan berkendara menuju Bursa melalui jembatan Osmangazi yang membelah laut. Ini adalah pertama kalinya ia menyetir di Turki, namun ketakutannya pada kegagalan jauh lebih besar daripada ketakutannya pada jalan raya.
Bursa menyambutnya dengan udara yang lebih segar dan pemandangan Gunung Uludağ yang berselimut salju di puncaknya. Ia menemukan rumah tua keluarga Arslan—sebuah rumah kayu bergaya Ottoman yang tampak terawat namun sunyi.
Dengan tangan gemetar, ia menemukan kunci di bawah pot zaitun sesuai instruksi Emir. Saat pintu terbuka, aroma kayu tua dan kenangan menyergapnya. Ia menuju gudang bawah tanah yang dipenuhi dengan peti-peti kayu.
Setelah berjam-jam mencari, Fatimah menemukan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya, tidak hanya ada dokumen yang ia cari, tapi juga ada sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak: seikat surat-surat lama.
Surat-surat itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang kaku, dikirim dari Jakarta tahun 1965.
"Untuk Mustafa Arslan. Terima kasih telah menjaga rahasia pembangunan ini. Aku telah menyimpan bagian dari desainmu di bawah fondasi utama sebagai tanda persaudaraan. Jika suatu saat anak cucu kita bertemu, biarlah rahasia ini menjadi jembatan bagi mereka."
Fatimah menyadari sesuatu yang besar. Ada bagian dari desain Istiqlal yang sengaja disembunyikan untuk menjaga keamanan struktur saat gejolak politik di Indonesia masa itu. Dan rahasia itu adalah kunci untuk menyelamatkan pasar di sebelahnya.
Sementara itu, di Jakarta, Tuan Sahin dan mitranya sudah mulai mengerahkan buldoser ke area pasar. Mereka mengklaim bahwa izin cagar budaya yang diajukan Emir tidak sah karena kekurangan dokumen asli dari Turki.
"Maaf, Tuan Arslan," ujar sang kontraktor di Jakarta dengan nada meremehkan. "Tanpa bukti otentik bahwa lahan pasar ini adalah bagian dari zona penyangga sejarah yang dirancang kakek Anda, kami akan meratakannya sore ini."
Emir berdiri di depan buldoser, tangannya bersedekap. Ia menatap jam tangannya. "Tunggu sepuluh menit lagi."
"Sepuluh menit tidak akan mengubah sejarah, Tuan," ejek si kontraktor.
Tiba-tiba, ponsel Emir bergetar. Sebuah email masuk dari Fatimah yang sudah berhasil memindai dokumen dari Bursa. Emir tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang mematikan.
"Sebenarnya," Emir memutar layar tabletnya ke arah kontraktor dan pejabat yang hadir, "sepuluh menit adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan bahwa tepat di bawah pasar ini terdapat saluran drainase kuno yang terhubung langsung dengan fondasi Masjid Istiqlal. Jika kalian menghancurkan pasar ini, kalian akan merusak stabilitas fondasi masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Apakah kalian siap bertanggung jawab atas runtuhnya Istiqlal?"
Semua orang di sana mendadak pucat. Menghancurkan pasar adalah urusan bisnis, tapi merusak Istiqlal adalah urusan nasional yang bisa memicu amarah jutaan orang.
Di Istanbul, Fatimah yang sedang duduk di teras rumah tua di Bursa, menerima pesan singkat dari Ali:
"OPERASI BERHASIL! Buldoser mundur. Emir baru saja menjadi pahlawan nasional di sini. Dan kau... kau adalah malaikat pelindungnya, Fatimah."
Fatimah menangis bahagia di bawah pohon zaitun. Namun, di saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar rumah Bursa. Pintu terbuka, dan Melisa turun dengan wajah merah padam karena amarah.
"Kau pikir kau sudah menang, gadis desa?" Melisa berjalan mendekat dengan tatapan mengancam. "Kau mencuri dokumen keluarga Arslan. Aku sudah melaporkanmu pada polisi Turki atas tuduhan pencurian properti pribadi."
Fatimah berdiri, menggenggam tasbih ambernya kuat-kuat. Ia tidak lagi takut. "Ini bukan pencurian, Melisa Hanım. Ini adalah pemulihan sejarah. Dan rumah ini milik Emir Bey, dialah yang memberikan kuncinya padaku."
"Kita lihat saja siapa yang akan dipercaya polisi saat Emir sedang berada di belahan dunia lain," Melisa mengangkat ponselnya, siap melakukan panggilan.
Namun, sebelum Melisa sempat menekan tombol, suara sirine polisi justru terdengar mendekat. Tapi bukan menuju Fatimah. Dua petugas polisi turun dan menghampiri Melisa.
"Melisa Sahin? Anda ditahan atas tuduhan sabotase data universitas dan pencurian dokumen negara dari ruang kearsipan Taşkışla. Kami memiliki rekaman CCTV yang baru saja dipulihkan oleh tim IT universitas."
Fatimah tertegun. Di balik polisi itu, muncul Profesor Elif yang tampak sangat marah namun juga lega.
"Kau melakukan pekerjaan hebat, Fatimah," ujar Profesor Elif. "Ali Ihsan memberikan akses jarak jauh pada tim IT kami untuk melacak siapa yang menghapus datamu. Melisa lupa bahwa di universitas ini, jejak digital lebih sulit dihapus daripada debu."
Malam itu, Istanbul dan Jakarta terhubung oleh satu frekuensi kemenangan. Emir yang masih berada di Jakarta, menelepon Fatimah yang sudah kembali ke asrama Istanbul.
"Terima kasih, Fatimah," suara Emir terdengar lembut, jauh dari kesan tegas biasanya. "Kau tidak hanya menyelamatkan pasar itu, tapi kau menyelamatkan kehormatan keluargaku."
"Kita melakukannya bersama, Bey," jawab Fatimah.
"Bersiaplah," lanjut Emir. "Aku akan pulang lusa. Dan aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku sudah bicara dengan ibumu di Jakarta... dan ada sebuah 'restorasi' lain yang ingin aku ajukan secara resmi padanya."
Jantung Fatimah berdegup kencang. Ia tahu, babak pengabdiannya mungkin akan segera berakhir, namun babak baru dalam hidupnya sebagai "jembatan dua benua" baru saja akan dimulai.
Other Stories
Dante Fairy Tale
“Dante! Ayo bangun, Sayang. Kamu bisa terlambat ke sekolah!” kata seorang wanita ge ...
Dia Bukan Dia
Sebuah pengkhianatan yang jauh lebih gelap dari perselingkuhan biasa. Malam itu, di tengah ...
The Last Escape
The Last Escape, Berawal dari rencana liburan oleh 15 sekawan dari satu universitas, untuk ...
Kala Cinta Di Dermaga
Saat hatimu patah, di mana kamu akan berlabuh? Bagi Gisel, jawabannya adalah dermaga tua y ...
Mozarella Bukan Cinderella
Moza tinggal di Panti Asuhan Muara Kasih Ibu sejak ia pertama kali melihat dunia. Seseo ...
Mozarela Bukan Cinderella
Moza, sejak bayi dirawat di Panti Asuhan Muara Kasih Ibu oleh Bu Kezia, baru boleh diadops ...