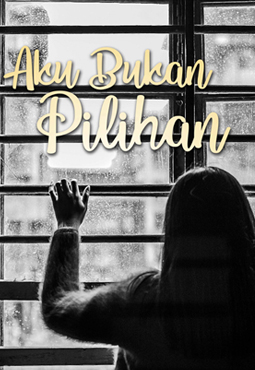Last Chapter : Polaroid
Dua minggu. Waktu yang sebenarnya terasa tak cukup. Tak ada pilihan lain. Setidaknya mereka bisa tinggal di rumah yang sama—kali ini di rumah Ibu, rumah masa kecil mereka. Bercengkrama adalah cara mereka saling menguatkan. Mereka tumbuh tanpa figur orang tua yang lengkap, dan yang paling sulit adalah merelakan keluarga kecil itu tak lagi utuh. Mungkin beginilah cara Tuhan membuat keduanya akur.
Di masa kecil, tak ada hari tanpa pertengkaran—berselisih, berebut, atau saling menggoda, hingga salah satunya merajuk. Sejak Ayah dan Ibu bertengkar semakin sering, Birru dan Bening justru lebih banyak bersama. Saling menatap dengan mata nanar. Anak berusia tujuh tahun itu belum memahami apa yang terjadi, hanya merasakan jejak sedih yang menggantung di rumah.
Hingga suatu malam, Ayah dan Bening pergi. Meninggalkan rumah. Meninggalkan kota itu. Kenangan itu masih terekam jelas di kepala Bening: ia dipaksa meninggalkan ibunya—dan Birru.
Melangkah keluar sambil terisak, tangisnya memuncak. Suara koper diseret keras di lantai. Tatapan Birru basah oleh air mata. Lalu suara Birru yang pecah, “Ayah dan Bening mau ke mana, Bu?”.
Ibunya menangis. Diam. Memeluk Birru erat. Ia tak mencegah Bening pergi. Wajahnya menunjukkan betapa berat momen itu bagi mereka semua. Rumah itu menjadi saksi: pernah ada kehangatan—dan juga perpisahan.
Sembilan foto berjajar – hasil karya Bening. Ia memang suka mengabadikan kisah dalam lensa. Kamera polaroid biru itu baru saja ia beli; warna yang mewakili Birru. Meski si kembar terpisah, setidaknya momen-momen itu bisa abadi.
Pagi ini mereka jogging bersama, melewati taman yang masih basah oleh embun. Udara sejuk. Jam menunjukkan setengan enam. Bening memandangi bunga-bunga, lalu menunjuk langit.
“Birru, sini dong. Liat awan itu. Bagus. Cerah” katanya. “Langit membiru”, gumamnya lirih.
Birru masih diam, memandangi awan yang ditunjuk Bening.
“Kamu sini dong. Pose disini”, perintah Bening sambil mengatur posisi tubuh Birru. “Mumpung masih liburan, biar punya banyak foto”.
“Satu… Dua… Tiga…”
Jepretan itu mengabadikan Birru dengan latar awan yang bersih. “Nanti aku tulis disini: Se-Birru Langit”, kata Bening, menunjuk bagian belakang foto.
“Puitis banget dah, adik gue”, goda Birru.
“Eh, ini aku mau difoto juga dong”, pinta Bening. Ia menunduk, mencium setangkai bunga yang masih basah. Latar taman itu terekam lembut.
“Waw, Estetik”, ucap Bening setelah melihat hasilnya.
Mereka melanjutkan langkah pulang. Santai. Penuh canda dan ejekan kecil.
“Birru, bagi duit dong. Adik lo mau koleksi banyak kamera nih. Tapi nggak ada duit”, kata Bening, menengadahkan tangan.
“Hah? Lo pikir gue udah punya duit?”, Birru menyentil jidat Bening.
“Nah itu. Lo kan udah punya bisnis”, Bening menunjuk depot pengisian air minum. “Punya lo, kan? Baca tuh: depot air isi ulang Banyu Biru”.
“Garing, ah, lo”, kata Birru sambil berlari mendahului.
“Abang, tungguin", teriak Bening.
Langkah Birru terhenti. Ia menoleh. Bening memegangi kepalanya.
“Kenapa?”
Birru mendekat. “Pusing", timpal Bening.
“Cuma jogging bentar kok udah capek", ejek Birru.
“Iya nih, gue payah kalau soal fisik", sahut Bening.
"Masih kuat jalan sampai rumah? Atau mau duduk bentar?” Birru memegang pundak Bening.
“Kuat sih, tapi ya harus istirahat dulu".
Bening menepi dan duduk di pinggir jalan. Jalanan masih sepi. Birru duduk di sampingnya, menarik napas lebih panjang.
“Kamu sering pusing?” suara Birru memecah hening.
“Iya. Mulai umur sepuluh, aku sering tiba-tiba pusing. Bahkan kalau upacara bisa pingsan”, jawab Bening.
“Udah cerita ke Ayah?” Sorot mata Birru mengeras.
“Cuma pusing doang. Nggak perlu bilang. Lagian Ayah sibuk. Meeting, lembur", kata Bening.
Birru terdiam.
Adiknya tampak pucat. Ada rasa khawatir yang sama — menempel, tapi belum bisa ia ucapkan.
Ingatannya melompat ke malam gaduh itu: Birru kecil terbangun; Bening kecil masih terlelap di sisinya. Suara Ayah meninggi, isak Ibu terdengar jelas.
“Kamu nggak pernah ada waktu untuk keluarga ini". Hanya kalimat itu yang Birru ingat.
Selebihnya, ia tak mau tahu. Ia menutup telinga, memeluk guling, menarik selimut. Tubuh kecil itu hilang di balik kain tebal — dan untuk sesaat terasa lebih baik.
Malam itu tumbuh nyeri. Membekas hingga sekarang — kali ini, denyutnya lebih kencang.
"Gue mau tidur dulu bentar", kata Bening sesampainya di rumah.
Kamar masa kecil mereka kini jadi kamar Birru.
Kalau liburan di rumah Ibu, Bening tidur dengan Ibu — kompensasi atas waktu yang terpotong sejak perpisahan.
Hal yang sama Birru lakukan saat menginap di rumah Ayah.
“Oke". Birru mengacungkan jempol lalu ke dapur.
Ia mengambil sepotong pisang. Mengunyahnya pelan — dan kenangan datang tanpa permisi.
Rumah ini tak pernah netral baginya.
Bittersweet.
Ada masa ketika mereka tumbuh bersama, ada masa ketika rumah yang hangat itu mendadak sepi dan dingin. Bahkan meja makan ini, bertahun-tahun, tak pernah terisi penuh.
Birru sudah berdamai—setidaknya ia bilang begitu pada dirinya sendiri. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Komunikasi masih terjaga. Ayah masih mengirim uang, menanyakan kabar, kadang mengirim hadiah. Bagi Birru, itu cukup.
Ia teringat keluarga Adilla—yang tampak utuh, tapi retaknya terdengar. Bedanya, pertengkaran di rumah Adilla selalu punya cerita pilu yang bisa dibagi dengannya. Birru memilih menyimpannya sendiri.
*****
Senja tiba.
Bening belum juga terbangun.
“Itu adik kamu tidurnya nyenyak banget", kata Ibu, menatap putrinya yang masih terlelap. Ia tak tega membangunkan. Padahal, seharusnya suara hairdryer di meja rias sudut kamar cukup mengganggu.
“Dari pagi lho, Bu", sahut Birru.
“Hah? Lama amat? Bangunin coba".
Birru bergegas ke kamar Ibu. Namun pintu keburu terbuka. Sosok Bening melangkah keluar.
“Lama amat tidurnya", kata Birru.
Bening melirik jam dinding.
“Iya ya… padahal aku tidur jam tujuh pagi", ujarnya, heran.
Ia mengingat kalender — tanggal periodnya memang sudah dekat.
“Kamu kecapekan, Dek?” tanya Ibu.
“Nggak, Bu. Cuma harusnya minggu-minggu ini aku datang bulan”. Bening menuang air ke gelas.
“Yaudah, mandi dulu. Ibu siapin makan malam".
Bening tak menjawab. Langkahnya menuju belakang. Sebuah handuk ia sandarkan di pundak.
“Cepetan. Yuk, main game bareng", kata Birru sambil mengangkat stik console.
Bening duduk di samping Birru. “Bang, bawa sini”.
Birru menyerahkan stik itu. Mereka bermain PlayStation. Liburan mereka sering habis dengan cara ini.
“Bang, besok pergi yuk. Bosen main PS terus”, ajak Bening.
“Kemana?” tanya Birru, masih fokus ke game bola favoritnya.
“Ke Dufan. Seru".
“Oke. Lo nanti kecapekan lagi, nggak?” goda Birru.
“Nggak kok. Hari ini kan udah istirahat lama”.
“Abis ini nonton film horor aja”, lanjut Bening.
“Bentar lagi”, jawab Birru.
Setengah jam berlalu.
“Cukup. Gue bosen”. Birru mematikan PlayStation, melempar remot ke arah Bening, lalu menekan aplikasi streaming.
“Nonton apa ya?”
“Terserah. Gue ngikut”, katanya sambil mengambil toples camilan.
Bening memilih film teratas. “Ini aja. Yang direkomendasi".
“Jangan tidur malam-malam", kata Ibu tanpa mengalihkan pandang dari layar laptop.
“Bening, sini". Beberapa lembar uang berpindah ke tangan Bening.
“Buat main besok. Ke Dufan", ujar Ibu, lalu kembali bekerja.
Bening mengangguk. Birru melihat adiknya —sekilas lebih lama — sebelum kembali menatap layar.
Di masa kecil, tak ada hari tanpa pertengkaran—berselisih, berebut, atau saling menggoda, hingga salah satunya merajuk. Sejak Ayah dan Ibu bertengkar semakin sering, Birru dan Bening justru lebih banyak bersama. Saling menatap dengan mata nanar. Anak berusia tujuh tahun itu belum memahami apa yang terjadi, hanya merasakan jejak sedih yang menggantung di rumah.
Hingga suatu malam, Ayah dan Bening pergi. Meninggalkan rumah. Meninggalkan kota itu. Kenangan itu masih terekam jelas di kepala Bening: ia dipaksa meninggalkan ibunya—dan Birru.
Melangkah keluar sambil terisak, tangisnya memuncak. Suara koper diseret keras di lantai. Tatapan Birru basah oleh air mata. Lalu suara Birru yang pecah, “Ayah dan Bening mau ke mana, Bu?”.
Ibunya menangis. Diam. Memeluk Birru erat. Ia tak mencegah Bening pergi. Wajahnya menunjukkan betapa berat momen itu bagi mereka semua. Rumah itu menjadi saksi: pernah ada kehangatan—dan juga perpisahan.
Sembilan foto berjajar – hasil karya Bening. Ia memang suka mengabadikan kisah dalam lensa. Kamera polaroid biru itu baru saja ia beli; warna yang mewakili Birru. Meski si kembar terpisah, setidaknya momen-momen itu bisa abadi.
Pagi ini mereka jogging bersama, melewati taman yang masih basah oleh embun. Udara sejuk. Jam menunjukkan setengan enam. Bening memandangi bunga-bunga, lalu menunjuk langit.
“Birru, sini dong. Liat awan itu. Bagus. Cerah” katanya. “Langit membiru”, gumamnya lirih.
Birru masih diam, memandangi awan yang ditunjuk Bening.
“Kamu sini dong. Pose disini”, perintah Bening sambil mengatur posisi tubuh Birru. “Mumpung masih liburan, biar punya banyak foto”.
“Satu… Dua… Tiga…”
Jepretan itu mengabadikan Birru dengan latar awan yang bersih. “Nanti aku tulis disini: Se-Birru Langit”, kata Bening, menunjuk bagian belakang foto.
“Puitis banget dah, adik gue”, goda Birru.
“Eh, ini aku mau difoto juga dong”, pinta Bening. Ia menunduk, mencium setangkai bunga yang masih basah. Latar taman itu terekam lembut.
“Waw, Estetik”, ucap Bening setelah melihat hasilnya.
Mereka melanjutkan langkah pulang. Santai. Penuh canda dan ejekan kecil.
“Birru, bagi duit dong. Adik lo mau koleksi banyak kamera nih. Tapi nggak ada duit”, kata Bening, menengadahkan tangan.
“Hah? Lo pikir gue udah punya duit?”, Birru menyentil jidat Bening.
“Nah itu. Lo kan udah punya bisnis”, Bening menunjuk depot pengisian air minum. “Punya lo, kan? Baca tuh: depot air isi ulang Banyu Biru”.
“Garing, ah, lo”, kata Birru sambil berlari mendahului.
“Abang, tungguin", teriak Bening.
Langkah Birru terhenti. Ia menoleh. Bening memegangi kepalanya.
“Kenapa?”
Birru mendekat. “Pusing", timpal Bening.
“Cuma jogging bentar kok udah capek", ejek Birru.
“Iya nih, gue payah kalau soal fisik", sahut Bening.
"Masih kuat jalan sampai rumah? Atau mau duduk bentar?” Birru memegang pundak Bening.
“Kuat sih, tapi ya harus istirahat dulu".
Bening menepi dan duduk di pinggir jalan. Jalanan masih sepi. Birru duduk di sampingnya, menarik napas lebih panjang.
“Kamu sering pusing?” suara Birru memecah hening.
“Iya. Mulai umur sepuluh, aku sering tiba-tiba pusing. Bahkan kalau upacara bisa pingsan”, jawab Bening.
“Udah cerita ke Ayah?” Sorot mata Birru mengeras.
“Cuma pusing doang. Nggak perlu bilang. Lagian Ayah sibuk. Meeting, lembur", kata Bening.
Birru terdiam.
Adiknya tampak pucat. Ada rasa khawatir yang sama — menempel, tapi belum bisa ia ucapkan.
Ingatannya melompat ke malam gaduh itu: Birru kecil terbangun; Bening kecil masih terlelap di sisinya. Suara Ayah meninggi, isak Ibu terdengar jelas.
“Kamu nggak pernah ada waktu untuk keluarga ini". Hanya kalimat itu yang Birru ingat.
Selebihnya, ia tak mau tahu. Ia menutup telinga, memeluk guling, menarik selimut. Tubuh kecil itu hilang di balik kain tebal — dan untuk sesaat terasa lebih baik.
Malam itu tumbuh nyeri. Membekas hingga sekarang — kali ini, denyutnya lebih kencang.
"Gue mau tidur dulu bentar", kata Bening sesampainya di rumah.
Kamar masa kecil mereka kini jadi kamar Birru.
Kalau liburan di rumah Ibu, Bening tidur dengan Ibu — kompensasi atas waktu yang terpotong sejak perpisahan.
Hal yang sama Birru lakukan saat menginap di rumah Ayah.
“Oke". Birru mengacungkan jempol lalu ke dapur.
Ia mengambil sepotong pisang. Mengunyahnya pelan — dan kenangan datang tanpa permisi.
Rumah ini tak pernah netral baginya.
Bittersweet.
Ada masa ketika mereka tumbuh bersama, ada masa ketika rumah yang hangat itu mendadak sepi dan dingin. Bahkan meja makan ini, bertahun-tahun, tak pernah terisi penuh.
Birru sudah berdamai—setidaknya ia bilang begitu pada dirinya sendiri. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Komunikasi masih terjaga. Ayah masih mengirim uang, menanyakan kabar, kadang mengirim hadiah. Bagi Birru, itu cukup.
Ia teringat keluarga Adilla—yang tampak utuh, tapi retaknya terdengar. Bedanya, pertengkaran di rumah Adilla selalu punya cerita pilu yang bisa dibagi dengannya. Birru memilih menyimpannya sendiri.
*****
Senja tiba.
Bening belum juga terbangun.
“Itu adik kamu tidurnya nyenyak banget", kata Ibu, menatap putrinya yang masih terlelap. Ia tak tega membangunkan. Padahal, seharusnya suara hairdryer di meja rias sudut kamar cukup mengganggu.
“Dari pagi lho, Bu", sahut Birru.
“Hah? Lama amat? Bangunin coba".
Birru bergegas ke kamar Ibu. Namun pintu keburu terbuka. Sosok Bening melangkah keluar.
“Lama amat tidurnya", kata Birru.
Bening melirik jam dinding.
“Iya ya… padahal aku tidur jam tujuh pagi", ujarnya, heran.
Ia mengingat kalender — tanggal periodnya memang sudah dekat.
“Kamu kecapekan, Dek?” tanya Ibu.
“Nggak, Bu. Cuma harusnya minggu-minggu ini aku datang bulan”. Bening menuang air ke gelas.
“Yaudah, mandi dulu. Ibu siapin makan malam".
Bening tak menjawab. Langkahnya menuju belakang. Sebuah handuk ia sandarkan di pundak.
“Cepetan. Yuk, main game bareng", kata Birru sambil mengangkat stik console.
Bening duduk di samping Birru. “Bang, bawa sini”.
Birru menyerahkan stik itu. Mereka bermain PlayStation. Liburan mereka sering habis dengan cara ini.
“Bang, besok pergi yuk. Bosen main PS terus”, ajak Bening.
“Kemana?” tanya Birru, masih fokus ke game bola favoritnya.
“Ke Dufan. Seru".
“Oke. Lo nanti kecapekan lagi, nggak?” goda Birru.
“Nggak kok. Hari ini kan udah istirahat lama”.
“Abis ini nonton film horor aja”, lanjut Bening.
“Bentar lagi”, jawab Birru.
Setengah jam berlalu.
“Cukup. Gue bosen”. Birru mematikan PlayStation, melempar remot ke arah Bening, lalu menekan aplikasi streaming.
“Nonton apa ya?”
“Terserah. Gue ngikut”, katanya sambil mengambil toples camilan.
Bening memilih film teratas. “Ini aja. Yang direkomendasi".
“Jangan tidur malam-malam", kata Ibu tanpa mengalihkan pandang dari layar laptop.
“Bening, sini". Beberapa lembar uang berpindah ke tangan Bening.
“Buat main besok. Ke Dufan", ujar Ibu, lalu kembali bekerja.
Bening mengangguk. Birru melihat adiknya —sekilas lebih lama — sebelum kembali menatap layar.
Other Stories
Cerella Flost
Aku pernah menjadi gadis yang terburuk.Tentu bukan karena parasku yang menjaminku menjadi ...
Separuh Dzarrah
Dzarrah berarti sesuatu yang kecil, namun kebaikan atau keburukan sekecil apapun jangan di ...
315 Kilometer
Yatra, seorang pegawai kantoran di Surabaya, yang merasa jenuh dengan kehidupan serba hedo ...
Kacamata Kematian
Arsyil Langit Ramadhan lagi naksir berat sama cewek bernama Arshita Bintang Oktarina. Ia b ...
November Kelabu
Veya hanya butuh pengakuan, sepercik perhatian, dan seulas senyum dari orang yang seharusn ...
Aku Bukan Pilihan
Cukup lama Rama menyendiri selepas hubungannya dengan Santi kandas, kini rasa cinta itu da ...