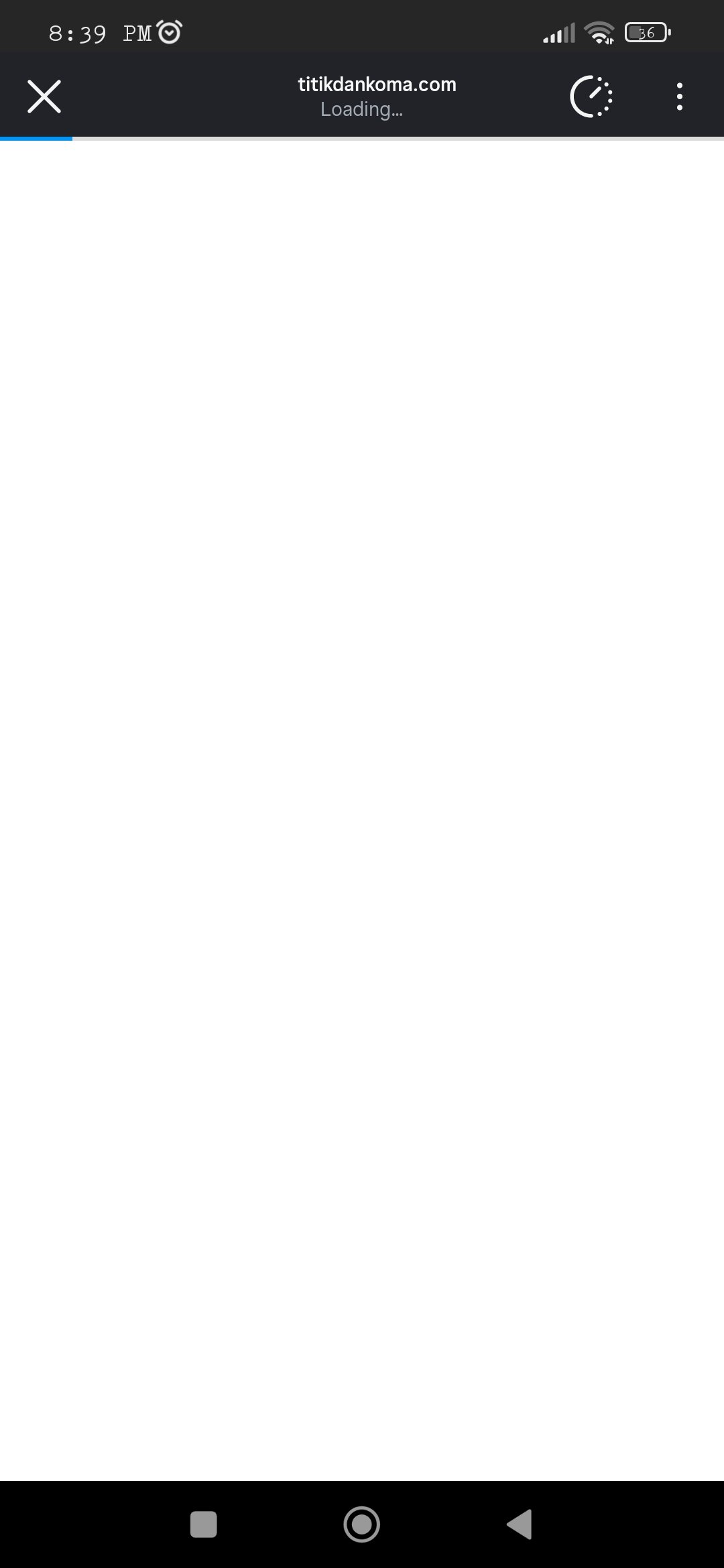10. Batas Desa Seribu Sesajen
Langkah kaki mereka terasa sangat berat saat memapah Nara keluar dari area sumur. Bobi memimpin di depan, matanya waspada menyisir setiap sudut jalan desa.
Pemandangan di sekitar mereka kini jauh lebih mengerikan; di depan setiap pintu rumah panggung dan di bawah akar pohon-pohon tua, terdapat ratusan sesajen. Bau anyir darah ayam hitam bercampur harum kemenyan yang menyengat memenuhi udara.
"Cepat! Jangan lihat sesajen itu!" bisik Arga tajam.
Ketegangan merayap di tengkuk mereka saat bayangan pohon di atas tanah perlahan-lahan memendek. Sinar matahari mulai menyengat tepat di atas kepala.
Warga desa yang tadinya berdiri linglung, kini mulai menggerakkan leher mereka dengan patah-patah. Mata mereka yang kosong mulai mengikuti gerak-gerik rombongan Arga.
Suasana yang tadinya sunyi berubah mencekam, warga perlahan mulai beranjak, melangkah mengepung dari kejauhan seiring matahari yang merangkak menuju titik tertinggi.
Di persimpangan jalan menuju hutan perbatasan, mereka mendadak terhenti. Wanita tua itu berdiri di sana, di bawah bayang-bayang pohon beringin besar. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya terlihat renta.
"Kalian hampir sampai," suara wanita itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan angin. Ia menatap Arga dengan tatapan yang sangat dalam.
"Dengarkan pesanku... jangan pernah menoleh ke belakang begitu kalian melewati gerbang beringin kembar itu. Sekali kalian menoleh, suara desa ini akan memanggil sukma kalian kembali selamanya."
Arga berhenti sejenak, menatap wanita yang telah menyelamatkan nyawa mereka itu dengan rasa haru yang luar biasa. Ia menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir yang paling tulus.
"Terima kasih... untuk segalanya."
Wanita tua itu hanya tersenyum tipis—sebuah senyuman lega yang menyedihkan. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, menyatu dengan asap kabut yang menguap ditelan panas matahari. Ia memilih tinggal, tetap menjadi bagian dari tanah keramat ini.
"Lari!" raung Arga saat melihat gerbang beringin kembar berkain putih sudah di depan mata.
Namun, beberapa meter sebelum gerbang tersebut, sosok Kepala Desa muncul secara tiba-tiba. Ia berdiri tegak di tengah jalan, menyeret parang panjangnya di atas tanah yang becek.
Suara gesekan logam itu—sreeet... sreeet...—terdengar memilukan. Ia tidak lagi menyerang dengan kekuatan gaib, melainkan dengan keputusasaan seorang penjaga yang tidak ingin kehilangan persembahan agungnya.
Suara burung gagak hitam pecah di atas dahan-dahan beringin. Ratusan burung itu berputar-putar, berteriak riuh rendah menciptakan suasana hiruk-pikuk yang memekakkan telinga.
"Bobi! Reno! Terobos!"
Dengan sigap, Bobi dan Reno menerjang dan menghalangi langkah Kepala Desa agar Selin dan Arga yang memapah Nara bisa lewat.
Tepat saat itu, detak jantung mereka seolah berpacu dengan waktu. Sinar matahari jatuh tegak lurus. Bayangan mereka menghilang sepenuhnya, tepat berada di bawah kaki.
"Cepaaat!"
Dengan kekuatan terakhir, mereka semua melewati dua pohon beringin kembar itu.
Tiba-tiba, Hening.
Seketika, suara riuh gagak, bau kemenyan, dan hawa pengap yang menekan dada hilang tak berbekas.
Mereka berlari terus berlari hingga benar-benar menjauhi pohon beringin tersebut.
Pada akhirnya udara berganti menjadi angin hutan yang segar dan normal. Mereka jatuh terjerembab ke atas tanah, terengah-engah dengan tubuh bersimbah darah dan noda tanah merah.
Nara tersentak, kesadarannya pulih sepenuhnya. Ia melihat teman-temannya yang hancur demi menyelamatkannya.
Nara menatap teman-temannya satu per satu dengan mata berkaca-kaca, menyadari sepenuhnya bahwa setiap embusan napas yang ia miliki sekarang adalah hutang nyawa pada mereka yang bertaruh nyawa di tanah terkutuk itu.
Di tengah deru napas mereka yang memburu, Reno perlahan bangkit dengan tubuh gemetar, hawa dingin yang mencekam itu sudah lenyap lalu menoleh ke arah jalan yang baru saja mereka lalui.
"Lihat..." bisik Reno dengan suara serak yang nyaris hilang.
"Desanya dan pohon beringin kembar itu... hilang."
Mendengar itu, Arga dan yang lainnya memberanikan diri untuk ikut melihat ke belakang. Napas mereka seolah terhenti.
Desa Seribu Sesajen sudah tidak ada. Di sana hanya ada kabut putih yang sangat tebal dan dinding pepohonan hutan yang rapat. Desa itu seolah telah ditelan bumi, kembali ke dimensi yang tak tersentuh manusia.
Mereka selamat. Mereka terduduk lemas di pinggir jalan raya yang jauh, di bawah sinar matahari yang kini terasa hangat, bukan lagi mengancam.
Namun, luka di tubuh dan ingatan tentang daging teman mereka di atas piring akan menjadi trauma yang tak akan pernah hilang.
TAMAT
Pemandangan di sekitar mereka kini jauh lebih mengerikan; di depan setiap pintu rumah panggung dan di bawah akar pohon-pohon tua, terdapat ratusan sesajen. Bau anyir darah ayam hitam bercampur harum kemenyan yang menyengat memenuhi udara.
"Cepat! Jangan lihat sesajen itu!" bisik Arga tajam.
Ketegangan merayap di tengkuk mereka saat bayangan pohon di atas tanah perlahan-lahan memendek. Sinar matahari mulai menyengat tepat di atas kepala.
Warga desa yang tadinya berdiri linglung, kini mulai menggerakkan leher mereka dengan patah-patah. Mata mereka yang kosong mulai mengikuti gerak-gerik rombongan Arga.
Suasana yang tadinya sunyi berubah mencekam, warga perlahan mulai beranjak, melangkah mengepung dari kejauhan seiring matahari yang merangkak menuju titik tertinggi.
Di persimpangan jalan menuju hutan perbatasan, mereka mendadak terhenti. Wanita tua itu berdiri di sana, di bawah bayang-bayang pohon beringin besar. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya terlihat renta.
"Kalian hampir sampai," suara wanita itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan angin. Ia menatap Arga dengan tatapan yang sangat dalam.
"Dengarkan pesanku... jangan pernah menoleh ke belakang begitu kalian melewati gerbang beringin kembar itu. Sekali kalian menoleh, suara desa ini akan memanggil sukma kalian kembali selamanya."
Arga berhenti sejenak, menatap wanita yang telah menyelamatkan nyawa mereka itu dengan rasa haru yang luar biasa. Ia menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir yang paling tulus.
"Terima kasih... untuk segalanya."
Wanita tua itu hanya tersenyum tipis—sebuah senyuman lega yang menyedihkan. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, menyatu dengan asap kabut yang menguap ditelan panas matahari. Ia memilih tinggal, tetap menjadi bagian dari tanah keramat ini.
"Lari!" raung Arga saat melihat gerbang beringin kembar berkain putih sudah di depan mata.
Namun, beberapa meter sebelum gerbang tersebut, sosok Kepala Desa muncul secara tiba-tiba. Ia berdiri tegak di tengah jalan, menyeret parang panjangnya di atas tanah yang becek.
Suara gesekan logam itu—sreeet... sreeet...—terdengar memilukan. Ia tidak lagi menyerang dengan kekuatan gaib, melainkan dengan keputusasaan seorang penjaga yang tidak ingin kehilangan persembahan agungnya.
Suara burung gagak hitam pecah di atas dahan-dahan beringin. Ratusan burung itu berputar-putar, berteriak riuh rendah menciptakan suasana hiruk-pikuk yang memekakkan telinga.
"Bobi! Reno! Terobos!"
Dengan sigap, Bobi dan Reno menerjang dan menghalangi langkah Kepala Desa agar Selin dan Arga yang memapah Nara bisa lewat.
Tepat saat itu, detak jantung mereka seolah berpacu dengan waktu. Sinar matahari jatuh tegak lurus. Bayangan mereka menghilang sepenuhnya, tepat berada di bawah kaki.
"Cepaaat!"
Dengan kekuatan terakhir, mereka semua melewati dua pohon beringin kembar itu.
Tiba-tiba, Hening.
Seketika, suara riuh gagak, bau kemenyan, dan hawa pengap yang menekan dada hilang tak berbekas.
Mereka berlari terus berlari hingga benar-benar menjauhi pohon beringin tersebut.
Pada akhirnya udara berganti menjadi angin hutan yang segar dan normal. Mereka jatuh terjerembab ke atas tanah, terengah-engah dengan tubuh bersimbah darah dan noda tanah merah.
Nara tersentak, kesadarannya pulih sepenuhnya. Ia melihat teman-temannya yang hancur demi menyelamatkannya.
Nara menatap teman-temannya satu per satu dengan mata berkaca-kaca, menyadari sepenuhnya bahwa setiap embusan napas yang ia miliki sekarang adalah hutang nyawa pada mereka yang bertaruh nyawa di tanah terkutuk itu.
Di tengah deru napas mereka yang memburu, Reno perlahan bangkit dengan tubuh gemetar, hawa dingin yang mencekam itu sudah lenyap lalu menoleh ke arah jalan yang baru saja mereka lalui.
"Lihat..." bisik Reno dengan suara serak yang nyaris hilang.
"Desanya dan pohon beringin kembar itu... hilang."
Mendengar itu, Arga dan yang lainnya memberanikan diri untuk ikut melihat ke belakang. Napas mereka seolah terhenti.
Desa Seribu Sesajen sudah tidak ada. Di sana hanya ada kabut putih yang sangat tebal dan dinding pepohonan hutan yang rapat. Desa itu seolah telah ditelan bumi, kembali ke dimensi yang tak tersentuh manusia.
Mereka selamat. Mereka terduduk lemas di pinggir jalan raya yang jauh, di bawah sinar matahari yang kini terasa hangat, bukan lagi mengancam.
Namun, luka di tubuh dan ingatan tentang daging teman mereka di atas piring akan menjadi trauma yang tak akan pernah hilang.
TAMAT
Other Stories
Pucuk Rhu Di Pusaka Sahara
Mahasiswa Indonesia di Yaman diibaratkan seperti pucuk rhu di Padang Sahara: selalu diuji ...
Erase
Devi, seorang majikan santun yang selalu menghargai orang lain, menenangkan diri di ruang ...
Cinta Buta
Marthy jatuh cinta pada Edo yang dikenalnya lewat media sosial dan rela berkorban meski be ...
Padang Kuyang
Warga desa yakin jika Mariam lah hantu kuyang yang selama ini mengganggu desa mereka. Bany ...
Haura
Apa aku hidup sendiri? Ke mana orang-orang? Apa mereka pergi, atau aku yang sudah berbe ...
Wtf???
INI BELUM DI PUBLISH KOK MUNCUL??? ...