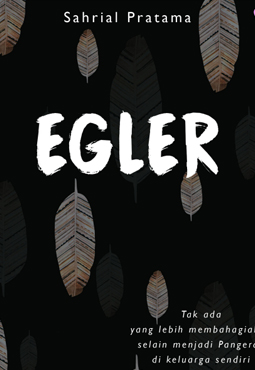BAB 3: TITIK TEMU DERMAGA
Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat jam menunjukkan tengah malam, lampu-lampu kota masih menyala benderang, suara kendaraan masih bersahutan. Tapi bagi Maheisa Mahatma, semua hiruk-pikuk itu hanya menjadi gema hambar.
Ia duduk sendirian di apartemen, di depan grand piano yang dulu selalu menjadi medan tempurnya. Tangannya sempat menyentuh tuts, lalu cepat-cepat ia tarik kembali. Tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin memainkan arpeggio Chopin atau cadenza Rachmaninoff, kalau ia bahkan tak yakin nadanya benar?
Seminggu penuh setelah diagnosis dokter, ia nyaris tidak tidur. Siang-malam diisi dengan upaya konyol menipu diri. Menekan tuts, berharap telinganya yang meradang bisa menangkap bunyi. Kadang ia menghantam piano dengan kasar, berharap dentumannya cukup keras untuk menusuk gendang telinga. Kadang ia hanya menunduk, membiarkan air mata jatuh ke permukaan piano, meninggalkan noda kecil yang segera mengering.
Lalu malam itu, kenangan lama datang tanpa diundang.
Suara pintu dibanting. Dentuman keras membuat gelas-gelas di meja bergetar. Maheisa kecil, usia delapan tahun, meringkuk di balik kursi ruang tamu.
“Apa-apaan ini?!” bentak sang ayah, suara beratnya menggelegar, seperti petir yang menyambar begitu dekat.
Ibunya hanya diam, berusaha menenangkan. Tapi bentakan berikutnya lebih keras, membelah udara. “Diam! Jangan banyak alasan!”
Barang pecah berserakan di lantai. Piring, vas bunga, entah apa lagi. Maheisa menutup kedua telinganya rapat-rapat. Ia ingin kabur, ingin berlari sejauh mungkin, tapi tubuh kecilnya membeku.
Suara itu menghantam gendang telinganya, berkali-kali, seperti palu besi. Bukan cuma keras, tapi juga menyakitkan. Dan di antara teriakan-teriakan itu, ia menemukan dirinya berbisik pelan: Andai saja telingaku tuli… mungkin aku tidak perlu mendengar semua ini.
Kalimat polos seorang anak kecil, yang entah bagaimana, menjadi doa gelap.
Maheisa terbangun dari lamunannya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, napasnya terengah. Ironis, pikirnya. Dulu ia ingin bisu telinga agar bebas dari bentakan. Kini, saat benar-benar kehilangan pendengaran, justru musik yang terenggut darinya.
Di malam yang sama, sang Ibu menelpon.
“Bagaimana kabar kamu, Nak?”
Suara lembut, tapi samar ada kegelisahan di baliknya.
“Aku baik-baik saja,” jawab Maheisa pendek.
Kebohongan yang bahkan dirinya pun tidak percaya.
hening sejenak, Maheisa tau sepandai apapun ia berbohong, kebenaran akan selalu diketahui cepat atau lambat oleh Ibu nya.
“Kakekmu dulu sering bilang… kalau sudah terlalu berat, kembalilah ke laut. Ingat? Di sana ada Nenekmu. Rumah itu masih ada, menunggu kamu.”
Laut. Kata itu bergema. Ia teringat masa kecil, hari-hari singkat bersama kakek-nenek di sebuah kota pesisir. Berlari di pasir, mencium bau asin angin, mendengar kakeknya bersenandung lagu daerah sambil menatap perahu-perahu berayun di dermaga.
-
Beberapa hari kemudian, ia benar-benar pergi. Menumpang kereta panjang menuju timur, melewati sawah-sawah, perbukitan, hingga akhirnya garis pantai menyambut dari kejauhan.
Begitu turun dari stasiun kecil, udara asin langsung menyergap paru-parunya. Angin laut bertiup lebih jujur dibanding kebisingan kota. Di wajahnya, ada nostalgia samar. Seakan tanah itu masih mengenalnya.
Senja pertama, langkahnya membawanya ke dermaga. Di ujung sana, terlihat beberapa orang berkumpul, menyambut sosok yang baru naik dari laut. Seorang perempuan, kulitnya kecokelatan karena matahari, rambut panjangnya basah menempel di punggung. Ia melepas fin dari kakinya dengan gerakan tenang, lalu mengibaskan kepala, menyingkirkan sisa air asin yang menetes.
Maheisa berhenti tanpa sadar. Ada sesuatu dari cara perempuan itu berdiri—diam, tapi mantap, seperti batu karang yang tidak tergoyahkan.
“Selia! Selia Maris!” seru beberapa anak muda sambil berlari kecil mendekat. Mereka membawa papan selam, minta tanda tangan, lalu mengeluarkan ponsel untuk berfoto bersama.
Nama itu, Maheisa pernah mendengarnya. Selia Maris, free diver muda yang kerap masuk headline olahraga ekstrem. Rekor napasnya bertahan lebih dari tujuh menit di kedalaman laut, tubuhnya mampu menari bebas di ruang hening yang bagi kebanyakan orang hanya berisi ketakutan. Ia bukan sekadar penyelam, tapi ikon.
Selia meladeni mereka dengan sabar, meski senyumnya sederhana, tidak berlebihan. Ada aura jarak di sana—ramah, tapi tetap tak terjangkau.
Seorang remaja lelaki memberanikan diri bertanya, “Kak Selia, gimana rasanya bisa nahan napas sedalam itu? Aku pasti panik kalau di bawah laut!”
Selia diam sejenak, menatap permukaan laut yang berkilau diterpa cahaya senja. Lalu ia menjawab dengan suara tenang, datar, tapi penuh bobot.
“Di kedalaman, semua sunyi. Tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri.”
Suara itu bukan ditujukan pada siapa pun secara khusus, tapi bagi Maheisa, kalimat itu seperti diarahkan tepat kepadanya. Dadanya bergetar aneh, seolah menemukan gema dari sesuatu yang lama ia cari.
Ia berdiri beberapa langkah di belakang kerumunan, hanya diam menatap. Angin sore membuat rambutnya sedikit berantakan.
Selia menunduk sejenak, menandatangani papan selam terakhir, lalu berjalan pergi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Orang-orang perlahan bubar, tapi Maheisa masih terpaku.
Bagi orang lain, itu mungkin hanya jawaban biasa. Tapi bagi dirinya, kalimat itu terasa seperti kunci.
Dan di situlah, tanpa mereka sadari, benang takdir mulai ditarik.
-
Senja mulai merayap, langit mewarnai air laut dengan oranye keemasan. Dermaga yang tadinya ramai kini menyisakan beberapa nelayan yang sedang membereskan jaring. Maheisa duduk di salah satu papan kayu, menggantungkan kakinya di tepi. Angin laut mengibaskan buku notasi kecil yang ia keluarkan dari tas.
Ia membuka halaman kosong, menuliskan beberapa garis paranada, lalu berhenti. Tangannya menggenggam pensil erat-erat. Kata-kata perempuan itu kembali terngiang dalam kepalanya: “Di kedalaman, semua sunyi. Tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri.”
Entah mengapa, kalimat itu terasa seperti jawaban dari sesuatu yang sudah lama ia tanyakan.
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maheisa tidak merasa sendirian dalam sunyi.
Ia duduk sendirian di apartemen, di depan grand piano yang dulu selalu menjadi medan tempurnya. Tangannya sempat menyentuh tuts, lalu cepat-cepat ia tarik kembali. Tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin memainkan arpeggio Chopin atau cadenza Rachmaninoff, kalau ia bahkan tak yakin nadanya benar?
Seminggu penuh setelah diagnosis dokter, ia nyaris tidak tidur. Siang-malam diisi dengan upaya konyol menipu diri. Menekan tuts, berharap telinganya yang meradang bisa menangkap bunyi. Kadang ia menghantam piano dengan kasar, berharap dentumannya cukup keras untuk menusuk gendang telinga. Kadang ia hanya menunduk, membiarkan air mata jatuh ke permukaan piano, meninggalkan noda kecil yang segera mengering.
Lalu malam itu, kenangan lama datang tanpa diundang.
Suara pintu dibanting. Dentuman keras membuat gelas-gelas di meja bergetar. Maheisa kecil, usia delapan tahun, meringkuk di balik kursi ruang tamu.
“Apa-apaan ini?!” bentak sang ayah, suara beratnya menggelegar, seperti petir yang menyambar begitu dekat.
Ibunya hanya diam, berusaha menenangkan. Tapi bentakan berikutnya lebih keras, membelah udara. “Diam! Jangan banyak alasan!”
Barang pecah berserakan di lantai. Piring, vas bunga, entah apa lagi. Maheisa menutup kedua telinganya rapat-rapat. Ia ingin kabur, ingin berlari sejauh mungkin, tapi tubuh kecilnya membeku.
Suara itu menghantam gendang telinganya, berkali-kali, seperti palu besi. Bukan cuma keras, tapi juga menyakitkan. Dan di antara teriakan-teriakan itu, ia menemukan dirinya berbisik pelan: Andai saja telingaku tuli… mungkin aku tidak perlu mendengar semua ini.
Kalimat polos seorang anak kecil, yang entah bagaimana, menjadi doa gelap.
Maheisa terbangun dari lamunannya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, napasnya terengah. Ironis, pikirnya. Dulu ia ingin bisu telinga agar bebas dari bentakan. Kini, saat benar-benar kehilangan pendengaran, justru musik yang terenggut darinya.
Di malam yang sama, sang Ibu menelpon.
“Bagaimana kabar kamu, Nak?”
Suara lembut, tapi samar ada kegelisahan di baliknya.
“Aku baik-baik saja,” jawab Maheisa pendek.
Kebohongan yang bahkan dirinya pun tidak percaya.
hening sejenak, Maheisa tau sepandai apapun ia berbohong, kebenaran akan selalu diketahui cepat atau lambat oleh Ibu nya.
“Kakekmu dulu sering bilang… kalau sudah terlalu berat, kembalilah ke laut. Ingat? Di sana ada Nenekmu. Rumah itu masih ada, menunggu kamu.”
Laut. Kata itu bergema. Ia teringat masa kecil, hari-hari singkat bersama kakek-nenek di sebuah kota pesisir. Berlari di pasir, mencium bau asin angin, mendengar kakeknya bersenandung lagu daerah sambil menatap perahu-perahu berayun di dermaga.
-
Beberapa hari kemudian, ia benar-benar pergi. Menumpang kereta panjang menuju timur, melewati sawah-sawah, perbukitan, hingga akhirnya garis pantai menyambut dari kejauhan.
Begitu turun dari stasiun kecil, udara asin langsung menyergap paru-parunya. Angin laut bertiup lebih jujur dibanding kebisingan kota. Di wajahnya, ada nostalgia samar. Seakan tanah itu masih mengenalnya.
Senja pertama, langkahnya membawanya ke dermaga. Di ujung sana, terlihat beberapa orang berkumpul, menyambut sosok yang baru naik dari laut. Seorang perempuan, kulitnya kecokelatan karena matahari, rambut panjangnya basah menempel di punggung. Ia melepas fin dari kakinya dengan gerakan tenang, lalu mengibaskan kepala, menyingkirkan sisa air asin yang menetes.
Maheisa berhenti tanpa sadar. Ada sesuatu dari cara perempuan itu berdiri—diam, tapi mantap, seperti batu karang yang tidak tergoyahkan.
“Selia! Selia Maris!” seru beberapa anak muda sambil berlari kecil mendekat. Mereka membawa papan selam, minta tanda tangan, lalu mengeluarkan ponsel untuk berfoto bersama.
Nama itu, Maheisa pernah mendengarnya. Selia Maris, free diver muda yang kerap masuk headline olahraga ekstrem. Rekor napasnya bertahan lebih dari tujuh menit di kedalaman laut, tubuhnya mampu menari bebas di ruang hening yang bagi kebanyakan orang hanya berisi ketakutan. Ia bukan sekadar penyelam, tapi ikon.
Selia meladeni mereka dengan sabar, meski senyumnya sederhana, tidak berlebihan. Ada aura jarak di sana—ramah, tapi tetap tak terjangkau.
Seorang remaja lelaki memberanikan diri bertanya, “Kak Selia, gimana rasanya bisa nahan napas sedalam itu? Aku pasti panik kalau di bawah laut!”
Selia diam sejenak, menatap permukaan laut yang berkilau diterpa cahaya senja. Lalu ia menjawab dengan suara tenang, datar, tapi penuh bobot.
“Di kedalaman, semua sunyi. Tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri.”
Suara itu bukan ditujukan pada siapa pun secara khusus, tapi bagi Maheisa, kalimat itu seperti diarahkan tepat kepadanya. Dadanya bergetar aneh, seolah menemukan gema dari sesuatu yang lama ia cari.
Ia berdiri beberapa langkah di belakang kerumunan, hanya diam menatap. Angin sore membuat rambutnya sedikit berantakan.
Selia menunduk sejenak, menandatangani papan selam terakhir, lalu berjalan pergi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Orang-orang perlahan bubar, tapi Maheisa masih terpaku.
Bagi orang lain, itu mungkin hanya jawaban biasa. Tapi bagi dirinya, kalimat itu terasa seperti kunci.
Dan di situlah, tanpa mereka sadari, benang takdir mulai ditarik.
-
Senja mulai merayap, langit mewarnai air laut dengan oranye keemasan. Dermaga yang tadinya ramai kini menyisakan beberapa nelayan yang sedang membereskan jaring. Maheisa duduk di salah satu papan kayu, menggantungkan kakinya di tepi. Angin laut mengibaskan buku notasi kecil yang ia keluarkan dari tas.
Ia membuka halaman kosong, menuliskan beberapa garis paranada, lalu berhenti. Tangannya menggenggam pensil erat-erat. Kata-kata perempuan itu kembali terngiang dalam kepalanya: “Di kedalaman, semua sunyi. Tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri.”
Entah mengapa, kalimat itu terasa seperti jawaban dari sesuatu yang sudah lama ia tanyakan.
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maheisa tidak merasa sendirian dalam sunyi.
Other Stories
Cinta Di 7 Keajaiban Dunia
Menjelang pernikahan, Devi dan Dimas ditugaskan meliput 7 keajaiban dunia. Pertemuan Devi ...
Keikhlasan Cinta
6 tahun Hasrul pergi dari keluarganya, setelah dia kembali dia dipertemukan kembali dengan ...
Kucing Emas
Kara Swandara, siswi cerdas, mendadak terjebak di panggung istana Kerajaan Kucing, terikat ...
Egler
Anton mengempaskan tas ke atas kasur. Ia melirik jarum pendek jam dinding yang berada di ...
32 Detik
Hanya 32 detik untuk menghancurkan cinta dan hidup Kirana. Saat video pribadinya bocor, du ...
Ada Apa Dengan Rasi
Saking seringnya melihat dan mendengar kedua orang tuanya bertengkar, membuat Rasi, gadis ...