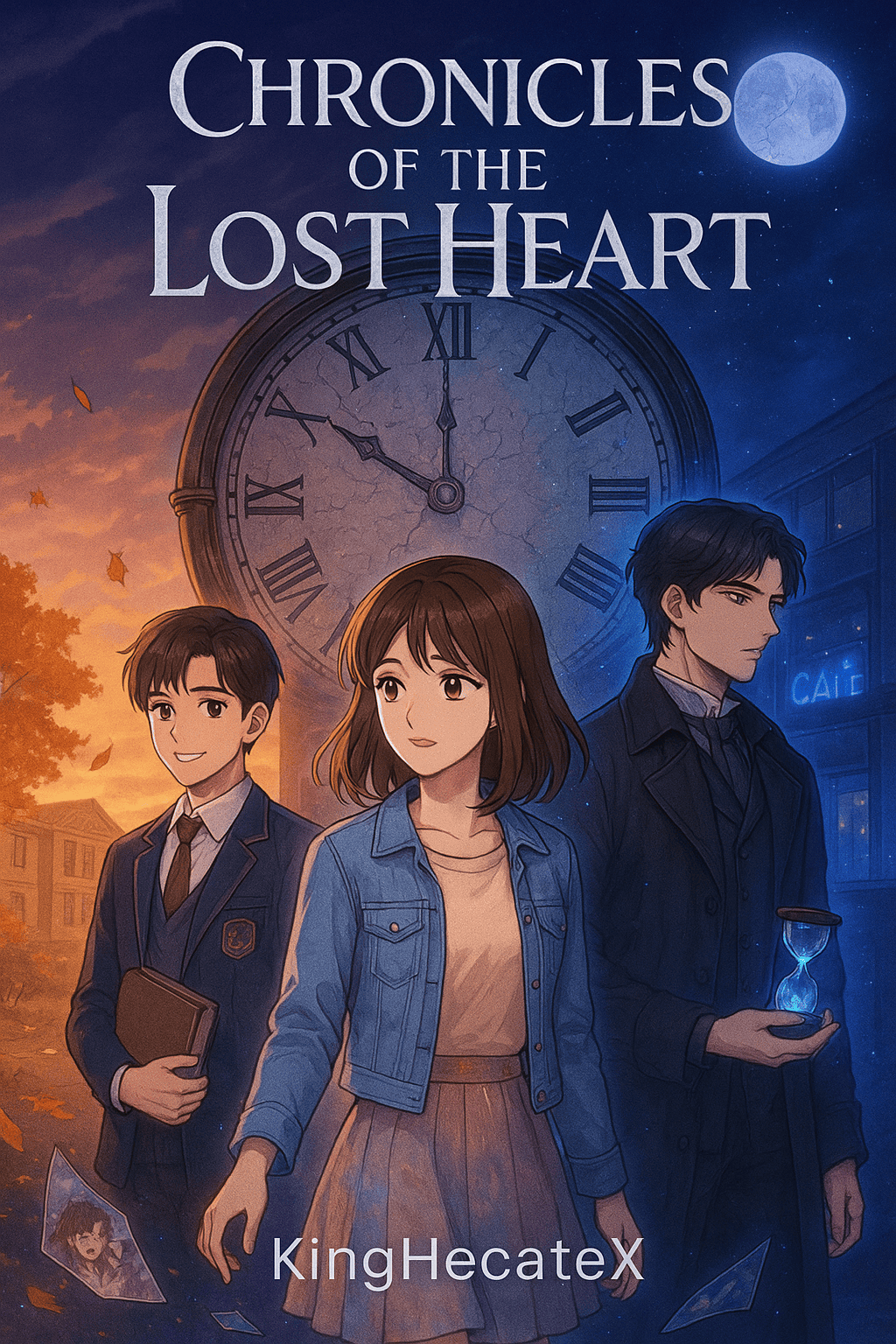BAB 13: NADA YANG MENYELAM
Hari itu laut tenang sekali. Tidak ada angin kencang, tidak ada gelombang yang menantang. Selia dan Maheisa baru saja selesai sesi latihan kedua mereka di kedalaman untuk hari ini. Kali ini lebih lancar daripada yang pertama—Selia memberi aba-aba lebih jelas, Maheisa sudah lebih berani menahan napas. Begitu mereka naik ke permukaan, wajahnya tidak lagi pucat seperti sebelumnya.
“Lihat? Kamu mulai terbiasa,” ujar Selia, menyeringai sambil melepas snorkel. Rambutnya basah, menempel di pipi.
Maheisa hanya mengangguk, setengah tersenyum, setengah kelelahan. “Masih jauh dari kata terbiasa.”
“Setidaknya kamu nggak langsung panik seperti kemarin,” balas Selia, mengangkat bahu.
Mereka berdua duduk di tepi perahu kayu yang membawa mereka kembali ke dermaga. Laut berkilau, matahari menuruni langit, membuat permukaan air seolah dihujani serpihan emas.
Suasana hening sesaat, hanya bunyi mesin perahu dan suara camar. Lalu Selia meliriknya, setengah iseng, setengah serius.
“Ngomong-ngomong, kamu selalu hadir dalam lautku. Tapi kapan aku boleh lihat lautmu sendiri?”
Maheisa menoleh, sedikit bingung. “Maksudmu?”
“Pianomu.”
Ucapan itu membuat Maheisa terdiam beberapa detik. Ada kilatan sesuatu di wajahnya, entah canggung, entah waspada. Ia memandang ke arah horizon, seolah mencari jawaban di balik garis laut.
Selia tidak memaksanya. Ia hanya tersenyum, menepuk-nepuk lutut. “Kalau belum siap, ya nggak apa-apa. Aku cuma penasaran.”
Perahu terus melaju. Sesampainya di dermaga, Selia membantu menurunkan peralatan, lalu pamit pada nelayan yang biasa menemani mereka. Maheisa berdiri agak jauh, memandangi jalan kecil yang menghubungkan dermaga ke desa.
Akhirnya, setelah menarik napas panjang, ia berucap lirih, “Kalau kamu benar-benar mau lihat ikut aku.”
Selia mengangkat alis. “Serius?”
“Serius.”
Maka sore itu juga, ia mengajak Selia ke rumah neneknya.
Rumah itu sederhana, berdiri di tepi jalan kecil yang dikelilingi pohon kelapa. Dari luar terlihat biasa saja, temboknya sedikit kusam, cat biru muda yang mulai pudar. Tapi begitu pintu terbuka, Selia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda: aroma kayu tua
bercampur wangi teh melati, dan di sudut ruang tengah, berdiri sebuah piano klasik.
Namun sebelum ia sempat mendekat, suara seorang perempuan tua terdengar dari dapur.
“Heisa? Kamu sudah pulang?”
Seorang nenek berusia sekitar tujuh puluhan keluar dengan langkah pelan, membawa nampan berisi dua cangkir teh. Wajahnya berkerut tapi teduh, matanya hangat meski sedikit berkaca-kaca saat melihat cucunya membawa tamu.
“Nenek, ini Selia,” ujar Maheisa, agak kaku.
“Teman yang ngajarin aku diving.”
Nenek menoleh pada Selia, lalu tersenyum lebar. “Oh, jadi ini selia yang sering kamu ceritakan belakangan ini.”
Maheisa mengerutkan kening, seolah tidak percaya neneknya bisa membocorkan hal itu. Selia hanya menahan tawa kecil. “Senang bertemu dengan Nenek.”
Mereka duduk sebentar di ruang tamu. Nenek menyodorkan teh melati dan kue pisang buatan tangan. Selia menerimanya dengan sopan, tapi dalam hati ia merasa hangat sekali—rumah ini jauh dari mewah, tapi penuh keintiman yang sulit dijelaskan.
“Kamu jangan sungkan ya, Nak Selia,” ucap nenek.
“Heisa jarang sekali bawa teman ke rumah. Piano itu biasanya cuma dia yang sentuh.”
Selia tersenyum, menoleh pada Maheisa yang pura-pura sibuk menyesap teh.
Beberapa menit kemudian, barulah Maheisa berdiri dan mengajaknya ke sudut ruangan. Piano tua itu berdiri, megah sekaligus rapuh. Selia menghentikan langkahnya, menatap benda itu. Tuts gadingnya sudah menguning, tapi tetap kokoh.
Maheisa membuka penutupnya, menekan satu nada. Suaranya bening, sederhana, tapi langsung mengisi ruangan. “Ini duniaku- laut yang ingin kau lihat.”
Selia melangkah mendekat, matanya berbinar. “Boleh aku duduk di sampingmu?”
“Kalau kamu siap untuk bosan,” jawab Maheisa, tapi ada senyum samar di ujung bibirnya.
Mereka pun duduk berdampingan. Selia memperhatikan jemari Maheisa membuka penutup tuts, menekan satu nada.
“Ini C,” ucapnya singkat.
Selia mencoba menirukan. Jemarinya kaku, tekanannya terlalu berat. Suara yang keluar jadi kasar. Ia meringis.
“Pelan,” kata Maheisa, kali ini suaranya tenang. Ia meraih tangan Selia, mengarahkan jemarinya ke tuts dengan tekanan lebih lembut. “Piano tidak butuh tenaga. Sama seperti laut. Kalau kau melawan, dia menolak. Kalau kau mengikuti, dia menerima.”
Selia mengangguk, lalu mencoba lagi. Suara kali ini lebih halus. Ia tersenyum puas.
Perlahan, Maheisa mengenalkan tangga nada sederhana. Selia mencoba, sering salah, tapi tidak pernah berhenti. Setiap salah, ia malah tertawa.
“Seperti kapal karam,” ujarnya setelah memainkan nada berantakan.
Mereka berdua tertawa. Suasana yang tadinya canggung berubah hangat.
Kemudian, Maheisa memainkan sebuah melodi ringan. Tidak panjang, tidak rumit. Hanya rangkaian nada yang berpadu sederhana, tapi mampu membuat ruangan itu terasa berbeda.
Selia terdiam, mendengarkan. Baginya, bunyi itu adalah sesuatu yang asing sekaligus akrab—tak sama dengan ombak atau desiran laut, tapi entah kenapa, memberi kedamaian yang serupa.
“Aku rasa laut dan piano itu mirip,” gumamnya.
“Mirip bagaimana?” tanya Maheisa, masih memainkan tuts.
“Dua-duanya butuh keberanian untuk tenggelam lebih dalam. Kalau hanya di permukaan, kau tidak akan pernah benar-benar mengerti. Laut punya kesunyian, piano punya keheningan yang bersuara.”
Maheisa menghentikan permainan, menatapnya lama. Ucapan itu, tanpa sadar, mengetuk bagian dalam dirinya yang sudah lama tertutup.
“Mungkin kamu benar,” bisiknya.
Dari dapur, suara nenek kembali terdengar. “Heisa, jangan biarkan tamumu pulang sebelum makan malam. Nenek sudah siapkan sup ikan.”
Selia tersenyum, merasa seolah bukan hanya masuk ke dunia piano Maheisa, tapi juga ke lingkaran kecil yang paling berarti dalam hidupnya.
Sore itu, dalam ruang sederhana dengan cahaya jingga yang jatuh indah, Selia akhirnya masuk ke dunia Maheisa. Bukan sekadar melihat dari luar, tapi ikut menyentuh, merasakan, belajar. Dan bagi Maheisa, itu pertama kalinya ia membuka pintu dunianya untuk orang lain, dengan cara yang tulus.
“Lihat? Kamu mulai terbiasa,” ujar Selia, menyeringai sambil melepas snorkel. Rambutnya basah, menempel di pipi.
Maheisa hanya mengangguk, setengah tersenyum, setengah kelelahan. “Masih jauh dari kata terbiasa.”
“Setidaknya kamu nggak langsung panik seperti kemarin,” balas Selia, mengangkat bahu.
Mereka berdua duduk di tepi perahu kayu yang membawa mereka kembali ke dermaga. Laut berkilau, matahari menuruni langit, membuat permukaan air seolah dihujani serpihan emas.
Suasana hening sesaat, hanya bunyi mesin perahu dan suara camar. Lalu Selia meliriknya, setengah iseng, setengah serius.
“Ngomong-ngomong, kamu selalu hadir dalam lautku. Tapi kapan aku boleh lihat lautmu sendiri?”
Maheisa menoleh, sedikit bingung. “Maksudmu?”
“Pianomu.”
Ucapan itu membuat Maheisa terdiam beberapa detik. Ada kilatan sesuatu di wajahnya, entah canggung, entah waspada. Ia memandang ke arah horizon, seolah mencari jawaban di balik garis laut.
Selia tidak memaksanya. Ia hanya tersenyum, menepuk-nepuk lutut. “Kalau belum siap, ya nggak apa-apa. Aku cuma penasaran.”
Perahu terus melaju. Sesampainya di dermaga, Selia membantu menurunkan peralatan, lalu pamit pada nelayan yang biasa menemani mereka. Maheisa berdiri agak jauh, memandangi jalan kecil yang menghubungkan dermaga ke desa.
Akhirnya, setelah menarik napas panjang, ia berucap lirih, “Kalau kamu benar-benar mau lihat ikut aku.”
Selia mengangkat alis. “Serius?”
“Serius.”
Maka sore itu juga, ia mengajak Selia ke rumah neneknya.
Rumah itu sederhana, berdiri di tepi jalan kecil yang dikelilingi pohon kelapa. Dari luar terlihat biasa saja, temboknya sedikit kusam, cat biru muda yang mulai pudar. Tapi begitu pintu terbuka, Selia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda: aroma kayu tua
bercampur wangi teh melati, dan di sudut ruang tengah, berdiri sebuah piano klasik.
Namun sebelum ia sempat mendekat, suara seorang perempuan tua terdengar dari dapur.
“Heisa? Kamu sudah pulang?”
Seorang nenek berusia sekitar tujuh puluhan keluar dengan langkah pelan, membawa nampan berisi dua cangkir teh. Wajahnya berkerut tapi teduh, matanya hangat meski sedikit berkaca-kaca saat melihat cucunya membawa tamu.
“Nenek, ini Selia,” ujar Maheisa, agak kaku.
“Teman yang ngajarin aku diving.”
Nenek menoleh pada Selia, lalu tersenyum lebar. “Oh, jadi ini selia yang sering kamu ceritakan belakangan ini.”
Maheisa mengerutkan kening, seolah tidak percaya neneknya bisa membocorkan hal itu. Selia hanya menahan tawa kecil. “Senang bertemu dengan Nenek.”
Mereka duduk sebentar di ruang tamu. Nenek menyodorkan teh melati dan kue pisang buatan tangan. Selia menerimanya dengan sopan, tapi dalam hati ia merasa hangat sekali—rumah ini jauh dari mewah, tapi penuh keintiman yang sulit dijelaskan.
“Kamu jangan sungkan ya, Nak Selia,” ucap nenek.
“Heisa jarang sekali bawa teman ke rumah. Piano itu biasanya cuma dia yang sentuh.”
Selia tersenyum, menoleh pada Maheisa yang pura-pura sibuk menyesap teh.
Beberapa menit kemudian, barulah Maheisa berdiri dan mengajaknya ke sudut ruangan. Piano tua itu berdiri, megah sekaligus rapuh. Selia menghentikan langkahnya, menatap benda itu. Tuts gadingnya sudah menguning, tapi tetap kokoh.
Maheisa membuka penutupnya, menekan satu nada. Suaranya bening, sederhana, tapi langsung mengisi ruangan. “Ini duniaku- laut yang ingin kau lihat.”
Selia melangkah mendekat, matanya berbinar. “Boleh aku duduk di sampingmu?”
“Kalau kamu siap untuk bosan,” jawab Maheisa, tapi ada senyum samar di ujung bibirnya.
Mereka pun duduk berdampingan. Selia memperhatikan jemari Maheisa membuka penutup tuts, menekan satu nada.
“Ini C,” ucapnya singkat.
Selia mencoba menirukan. Jemarinya kaku, tekanannya terlalu berat. Suara yang keluar jadi kasar. Ia meringis.
“Pelan,” kata Maheisa, kali ini suaranya tenang. Ia meraih tangan Selia, mengarahkan jemarinya ke tuts dengan tekanan lebih lembut. “Piano tidak butuh tenaga. Sama seperti laut. Kalau kau melawan, dia menolak. Kalau kau mengikuti, dia menerima.”
Selia mengangguk, lalu mencoba lagi. Suara kali ini lebih halus. Ia tersenyum puas.
Perlahan, Maheisa mengenalkan tangga nada sederhana. Selia mencoba, sering salah, tapi tidak pernah berhenti. Setiap salah, ia malah tertawa.
“Seperti kapal karam,” ujarnya setelah memainkan nada berantakan.
Mereka berdua tertawa. Suasana yang tadinya canggung berubah hangat.
Kemudian, Maheisa memainkan sebuah melodi ringan. Tidak panjang, tidak rumit. Hanya rangkaian nada yang berpadu sederhana, tapi mampu membuat ruangan itu terasa berbeda.
Selia terdiam, mendengarkan. Baginya, bunyi itu adalah sesuatu yang asing sekaligus akrab—tak sama dengan ombak atau desiran laut, tapi entah kenapa, memberi kedamaian yang serupa.
“Aku rasa laut dan piano itu mirip,” gumamnya.
“Mirip bagaimana?” tanya Maheisa, masih memainkan tuts.
“Dua-duanya butuh keberanian untuk tenggelam lebih dalam. Kalau hanya di permukaan, kau tidak akan pernah benar-benar mengerti. Laut punya kesunyian, piano punya keheningan yang bersuara.”
Maheisa menghentikan permainan, menatapnya lama. Ucapan itu, tanpa sadar, mengetuk bagian dalam dirinya yang sudah lama tertutup.
“Mungkin kamu benar,” bisiknya.
Dari dapur, suara nenek kembali terdengar. “Heisa, jangan biarkan tamumu pulang sebelum makan malam. Nenek sudah siapkan sup ikan.”
Selia tersenyum, merasa seolah bukan hanya masuk ke dunia piano Maheisa, tapi juga ke lingkaran kecil yang paling berarti dalam hidupnya.
Sore itu, dalam ruang sederhana dengan cahaya jingga yang jatuh indah, Selia akhirnya masuk ke dunia Maheisa. Bukan sekadar melihat dari luar, tapi ikut menyentuh, merasakan, belajar. Dan bagi Maheisa, itu pertama kalinya ia membuka pintu dunianya untuk orang lain, dengan cara yang tulus.
Other Stories
Nina Bobo ( Halusinada )
JAM DINDING menunjukkan pukul 12 lewat. Nina kini terlihat tidur sendiri. Suasana sunyi. S ...
Kita Pantas Kan?
Bukan soal berapa uangmu atau seberapa cantik dirimu tapi, bagaimana cara dirimu berdiri m ...
Youtube In Love
Wahyu yang berani kenalan lewat komentar YouTube berhasil mengajak Yunita bertemu. Asep pe ...
After Meet You
kacamata hitam milik pria itu berkilat tertimpa cahaya keemasan, sang mata dewa nyaris t ...
Chronicles Of The Lost Heart
Ketika seorang penulis novel gagal menemukan akhir bahagia dalam hidupnya sendiri, sebuah ...
Pesan Dari Hati
Riri hanya ingin kejujuran. Melihat Jo dan Sara masih mesra meski katanya sudah putus, ia ...