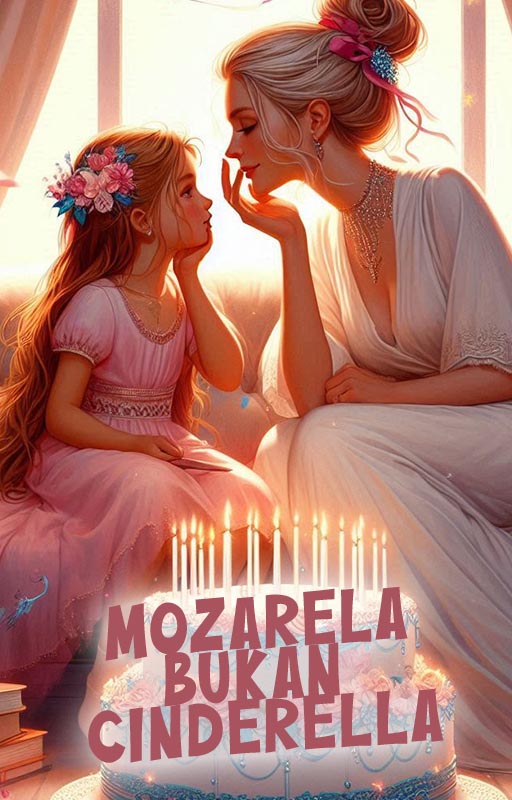16. Mencari Keadilan
Kepedihan kembali dirasakan Bayu suatu hari ketika Bayu dipanggil Pak Direja. Pun Barata.
“Ini Kakekmu, Pei.” ucap Bayu pada Pei.
Disaksikan seluruh keluarga, acara pun akhirnya kelar. Walau kecewa dan marah terlihat dari wajah Bayu.
“Ayah pilih kasih. Masa aku dikasih deposito yang sedikit dibanding Bara? Apakah aku bukan anak Ayah?” Bayu berkata lantang.
“Itu bukan warisan. Itu hanyalah uang dari Ayah untuk kalian. Pergunakanlah!”
“Tapi mengapa berbeda, Yah? Mengapa Ayah membuat pemisahan.”
“Bayu ingat! Kau sudah banyak mengeluarkan biaya. Hitunglah berapa puluh bahkan ratusan juta yang Ayah keluarkan dan membuat harta Ayah ludes. Berapa buah mobil yang rusak, berapa ratus juta untuk mengeluarkan kau dari penjara serta rehabilitasimu? Apa itu gratis? Semua itu dibayar, Bayu. Ayah masih mempunyai belas kasihan padamu. Terutama untuk cucuku, Pei. Kalau saja tak ingat, Ayah tak mau membaginya untukmu. Sudahlah gunakan untuk kehidupanmu. Ingat jangan saling mengungkit harta. Masing-masing sudah ada bagiannya. Dan kau Bara, gunakan uang itu sebaiknya. Jadikanlah cucuku, Alex orang yang bertanggung jawab sepertimu. Pintar dan membuat bangga kakeknya, walau nanti mungkin hanya melihat di alam lain,” suaranya lirih.
Bayu terdiam. Batinnya memendam bara. Tanpa pamit ia segera berlalu meninggalkan Pak Direja juga Barata.
“Tate (kakek)... Tate (kakek).” Pei menangis. Tangannya menunjuk pada Pak Direja yang ada di dalam rumah.
“Tidak, Pei. Cukuplah Ayah yang rasakan betapa hati ini begitu sakit dan terluka,” Bayu menghapus air mata yang jatuh lalu memangku Pei ke luar rumah. Tanpa memperhatikan Pei yang menangis memanggil kakeknya.
Hatinya dilanda kesedihan yang mendalam. Ternyata menjadi orang yang benar tetap saja disalahkan. Bukankah selama ini ia sudah berlaku baik? Menjauhkan perbuatan terlarang yang dulu menjadi sahabatnya? Kini ia lebih banyak mendekatkan diri pada keluarga. Pun pada yang Maha Pencipta, yang diharap adalah keadilan berada padanya. Tapi tetap saja semakin jauh. Ayahnya tak sedikit pun memberi jalan padanya. Memberi harapan hidup layak padanya pun Pei, Cucunya. Cucu yang mungkin tetap saja berbeda dengan cucunya yang lain, Alex.
Diniatkan dalam hatinya bahwa mulai detik itu takkan pernah lagi berhubungan dengan keluarga besarnya. Biarlah ia dianggap tiada. Toh, keberadaanya tak pernah dihiraukan. Selama ini, Bayu dianggap tiada oleh keluarganya. Dianggap sebagai suatu keuntungan. Hadirnya Bayu di rumah hanya menambah beban keluarga. Menambah malapetaka. Ketenangan keluarga besar terusik karena kehadirannya. Dan ia tak mau itu terjadi.
Beberapa tahun hidupnya dapat bertahan. Sisa deposito pemberian Pak Direja ia sisihkan dan berjualan di depan rumahnya. Sekali dua kali warungnya laris manis, tapi kemudian menyusut. Menyusut karena harga yang melambung tinggi. Keperluan ekonomi juga merangkak. Pun Pei yang mulai beranjak besar dan selalu merengek untuk minta sekolah. Sementara sekolah bukanlah hal yang gampang. Perlu pemikiran lebih mengingat ekonomi. Selalu ekonomi yang menjadi penghalang keluarganya untuk maju. Modal warung sedikit demi sedikit menyusut karena terpakai keperluan.
Belum lagi utang tetangga yang sampai kini tak dibayar, hingga modal semakin menipis. Sekali dua kali ditagih berperilaku baik dan biasa saja. Tapi ketika menagih kembali karena modal yang habis, apa yang kemudian diterimanya? Bentakan dan cacian dari para tetangga sang empunya utang. Apa sudah terbalik? Harusnya ia sebagai pemilik modal yang marah karena modalnya menyusut tanpa pernah dibayar. Hanya janji-janji yang menjadi pegangan tanpa bukti nyata.
“Hei, Bayu. Jangan mentang-mentang kamu punya warung dong. Nagih terus tiap hari. Apa nggak punya nurani? Kalau kami belum bayar berarti belum punya uang, kenapa sih?”
“Bukan begitu, Bu. Saya itu butuh duit. Modal sudah ludes. Nah, Ibulah yang diharap dapat membantu keberlangsungan dagangan kami. Utang Ibu paling besar.”
“Sudah, jangan ngomong utang-utang. Pokoknya nanti kalau punya uang, saya bayar,” Tetangganya melengos dengan muka ditekuk.
Duh. Kenapa jadi begini? Harusnya Bayu yang marah, ngomelin peminjam yang seenaknya meminjam tanpa pernah mau bayar. Tapi kini? Malah ia yang mendapat hardik dari tetangganya. Bayu pulang ke rumah dengan tangan hampa. Kesedihan begitu menggunung di hati. Keadilan yang diharap berpihak, tak bersimpati padanya.
“Bu, sudahlah. Tutup saja warungnya. Modal kita sudah habis.”
“Lantas nasib kita bagaimana, Pak? Itulah harapan kita satu-satunya.”
“Entahlah.”
***
Suasana masih sangat pagi ketika Bayu turun dari angkot, berdiri kaku di sebuah rumah megah. Sangat megah. Apakah Bara masih mengingatnya? Mau menerima kedatangannya. Lama tak bertemu, kini malah datang dalam keadaan susah. Apa itu takkan menambah beban? Hatinya bertanya. Tapi setidaknya ia sudah berusaha dan mencoba bahwa dirinya kali ini benar-benar membutuhkan pertolongan. Kalau pun rencana ini tidak berhasil. Sudahlah, mungkin bukan rezekinya.
“Ei, Bayu. Ayolah masuk. Syukurlah dipertemukan kembali,” Bara menyambutnya dengan ramah. Tak terlihat nada kesal atau marah atas kedatangannya. Malah ia begitu surprise menyambutnya.
“Begitulah Bara, maksud kedatanganku. Hanya engkaulah yang dapat menolongku. Pada siapa lagi aku meminta bantuan selain padamu. Sodaraku satu-satunya,” Bayu menunduk. Pandangannya tertuju pada permadani mewah yang diinjaknya. Harga permadani yang mungkin sangat tinggi, dibanding harga dirinya yang begitu lusuh dan kaku. Begitu miskin.
“Insya Allah aku akan membantumu. Tapi mudah-mudahan kau mau. Dan mudah-mudahan dapat membukakan jalanmu,” Bara berkata.
“Alhamdulillah, terima kasih bantuanmu. Bara.”
“Tak usah kau bilang seperti itu. Aku selalu teringat pesan Ayah menjelang meninggal. Bahwa sampai kapan pun, di mana pun, kau adalah tetap saudaraku. Itu selalu kuingat. Jadi wajarlah kalau aku membantumu. Kau tetap adikku, Bayu.”
“Bara, kau memang berhati mulia.”
“Kalau tak keberatan, tinggallah di sini. Kebetulan gudang di belakang rumah tidak dipakai. Mungkin itu bisa dipercantik sebagai tempat tinggalmu,” Barata menutup obrolan.
Semenjak itu Bayu menempati rumah baru. Gudang yang berada di belakang rumah diperbaiki dan dicat seperti baru. Pastilah modalnya dari Bara, kakaknya. Bukan hanya itu, ia pun dimasukkan bekerja, satu perusahaan dengan Bara. Bara sebagai pemilik perusahaan pasti dengan mudah memberi pekerjaan pada Bayu di perusahaannya. Praktis ke mana pun selalu berdua dan berbarengan karena bekerja satu atap pun satu rumah.
Istri Bayu begitu bahagia dapat melangsungkan hidupnya tanpa perlu mengemis pada orang. Di rumah Barata, ia tidak tinggal diam, dengan telaten dan dengan ikhlas membantu beragam pekerjaan rumah, walau istri Bara sudah berkali-kali melarang.
“Tak usahlah kau bekerja seperti itu. Sudah istirahatlah. Kan ini semua tugas Asih.”
“Ah, tak enak, Kak. Biarlah aku bekerja semampunya saja.”
“Ya, terserahmulah. Tapi aku tidak menyuruhmu.”
“Iyalah. Pokoknya adem-adem saja.”
Kini keluarga besar Bara yang biasanya sepi, menjadi ramai. Ramai karena Alex mempunyai teman. Alex dan Pei selalu bermain bersama. Ke mana pun selalu bersama. Maklumlah usianya hampir sama. Beda 1 tahun dengan Alex.
“Mama, Pei jahaat!”
“Kenapa?”
“Merebut mainanku. Ia menukarnya dengan mainan jelek, Ma.”
“Sudahlah. Berikan itu pada Pei, ya. Kasihan. Biar besok Alex beli yang baru.”
***
Other Stories
Sebelum Ya
Hidup adalah proses menuju pencapaian, seperti alif menuju ya. Kesalahan wajar terjadi, na ...
Kado Dari Dunia Lain
Kamu pasti pernah lelah akan kehidupan? Bahkan sampai di titik ingin mengakhirinya? Sepert ...
Cinta Di Ujung Asa
Alya mendapat beasiswa ke Leiden, namun dilema karena harus merawat bayi kembar peninggala ...
Mozarella Bukan Cinderella
Moza tinggal di Panti Asuhan Muara Kasih Ibu sejak ia pertama kali melihat dunia. Seseo ...
Cinta Harus Bahagia
Seorang kakak yang harus membesarkan adiknya karena kematian mendadak kedua orangtuanya, b ...
First Love Fall
Rena mengira dengan mendapat beasiswa akan menjadi petualangan yang menyenangkan. Tapi sia ...