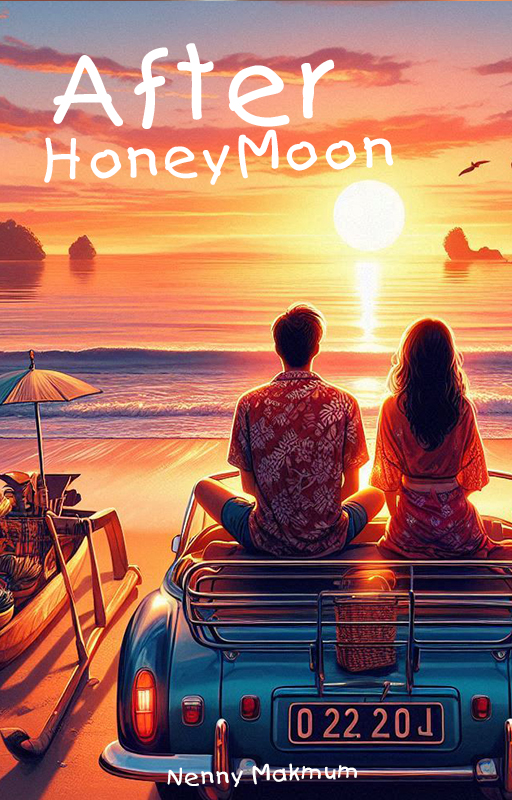Chapter 10
“Baiklah, sekarang kamu ceritakan, ada hubungan apa antara kamu dengan Heaven?” Dimas rupanya mulai kehabisan kesabaran. Lelaki itu melipat tangannya di dada menahan kesal.
Sementara aku malah duduk berpikir dengan tangan menyangga dagu di atas meja kerja Dimas. Memastikan bahwa langkahku tidak keliru, membagi cerita dengan lelaki yang ada di hadapanku.
“Kamu masih ingat kan soal sahabat masa aku SMA?” aku menengok ke arah Dimas.
“Tentang lelaki yang pernah kamu cium itu?”
Sial!
Kuanggukkan kepalaku tanpa berkata ‘iya’.
Perlahan Dimas mulai mengernyitkan dahinya. Mencoba menyangkutpautkan sahabat masa laluku dengan pria bernama Heaven. “Kamu jangan bilang kalau mereka adalah orang yang sama?”
Cerdas! Dia bisa menangkap maksudku.
“Memang itu kenyataannya,” aku sudah tidak bisa berpura-pura lagi.
“Astaga! Dunia memang selebar daun kelor,” sontak lelaki itu meraih satu kursi pasien dan duduk tepat di hadapanku. Dia mulai penasaran dengan ceritaku selanjutnya.
“Bukan dunia, Brother. Tapi Bandung memang kota kecil.”
“Terserah,” Dimas tertawa dengan leluconku. “Lalu? Bagaimana ceritanya dia bisa jadi seperti sekarang?” tanyanya antusias. “Sekarang aku paham kenapa kamu salah tingkah saat di Metropolis malam itu,” dia bergumam lagi. “Tapi, kamu bilang dia straight?” sepertinya ada banyak list pertanyaan di benak lelaki itu.
“Calm down, Dude. Aku akan mulai bercerita. Kamu ambil napas dulu, ya,” sindirku.
Dimas menggeserkan posisi kursinya lebih dekat lagi. “Ayo cerita. Jangan buat aku mati penasaran.”
Maka aku ceritakan semua kisah yang terjadi mulai dari malam itu hingga saat Nael menemaniku menemui Ibu.
Tak terasa kisahku melarutkan waktu di antara kami. Hampir satu jam aku bercerita dan membuat sahabatku itu tersenyum sendiri. Hingga pada satu saat kami termangu dalam keheningan. Tak ada kisah yang bisa kupaparkan lagi.
“Sekarang aku paham kenapa Nael mengambil jalan seperti ini,” Dimas mulai mengubah panggilan Heaven menjadi Nael. Lelaki itu melepas kacamata lalu beranjak dari kursinya. Sesaat dia meminta izin padaku untuk mengambil dokumen riwayat penyakit Tante Sofie di ruang arsip.
Hanya butuh beberapa menit hingga akhirnya dia kembali ke ruang kerjanya. “Hm... ini dokumen milik Bu Sofie. Kebetulan dokter yang merawat beliau adalah kawanku sendiri. Edgar.”
“Edgar?”
Dimas mendelik. “Kamu kenal Dokter Edgar?”
Kuanggukkan kepala dengan tampang polos. “Mana mungkin aku lupa begitu saja lelaki bertampang keren,” candaku.
“Damn! You know him!” serunya.
“Sudah! Sudah! Jangan membelokkan arah pembicaraan. Kamu harus terangkan dahulu soal kondisi Tante Sofie kepadaku,” aku mengibas jemariku menolak membahas soal dokter yang pernah memeriksaku tempo hari.
Aku menerima satu bundel dokumen yang berisi informasi kesehatan Tante Sofie. Perlahan aku mulai mengerti, Tante Sofie mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kerusakan otak yang sangat parah. Hingga kini tim dokter belum mampu mengobati. Meskipun bisa, itu hanya sebagian kecilnya saja. Kendala lain tentu saja masalah biaya. Bisa dibayangkan tiga tahun dirawat di rumah Sakit! Nael pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Saat ini adalah masa-masa kritis bagi Ibu Sofie,” ucapan Dimas membuyarkan lamunanku. “Beliau harus menjalani operasi, namun pihak keluarga harus menyelesaikan masalah administrasinya terlebih dahulu.”
Aku menghela napas panjang lalu menutup kembali dokumen kesehatan Tante Sofie. “Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan?” tanyaku seraya mengusap kening.
“Sekitar 200 jutaan.”
Miris hatiku saat Dimas mengucapkan angka nominal tersebut. Seorang Nael bagaimana bisa mendapatkan uang sebesar itu? Bahkan dia sendiri seperti diperas oleh mucikarinya, Si Madam itu.
Dimas mengusap bahuku. “Bantu dia, Az. Tak melulu materi, tapi buat dia bersemangat. Kamu kan sahabatnya,” nasihat Dimas.
Aku hanya menyunggingkan bibirku sedikit. Padahal jauh dalam hati aku gelisah. Dengan cara apa aku bisa meringankan beban yang ada di pundak Nael?
***
Untuk kedua kali kuputuskan untuk melihat lagi keadaan Tante Sofie di keesokan harinya. Langkahku pelan sekali menuju ruang rawat inap beliau. Bingung juga apa yang harus kukatakan nanti. Berharap saja Nael ada di sana hingga aku bisa sedikit bercakap-cakap soal penyakit ibunya.
Aku membuka pintu ruangan itu. Dugaanku salah. Nael tidak nampak di dalam ruangan tersebut. Hanya ada Angga dan seorang perempuan yang menjaga Tante Sofie.
“Bang?” Angga menyambutku.
“Bagaimana Tante Sofie?” aku membalas uluran tangannya.
“Lebih baik, Bang. Beliau tidur nyenyak sekali,” ujarnya. “Oh iya, kenalkan ini Nita, sepupu Bang Nael juga.”
Aku menyalami perempuan yang sebaya dengan Angga.
Canggung juga. Aku bingung bagaimana caranya memulai interaksi dengan Angga. Bahkan selama beberapa saat kami tak bicara sama sekali. Coba saja Tante Sofie terjaga, mungkin aku bisa sedikit berbincang dengan beliau.
“Ga, ngobrol yuk di luar?” ajakku spontan. Siapa tahu dari pemuda ini aku bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan Tante Sofie.
Angga menerima ajakanku. Sesaat ia berbicara dengan perempuan yang ia perkenalkan sebagai sepupunya itu. Mungkin menyampaikan pesan kalau ia akan keluar untuk sejenak bersamaku.
“Ayo, Bang,” ajaknya.
Tidak terlalu jauh kami meninggalkan rumah sakit. Tujuan kami hanya di sebuah minimarket yang menyediakan beberapa meja dan kursi di bagian terasnya. Kurasa itu cukup sambil menikmati semangkuk mie ayam yang kami pesan dari sebuah gerobak bakmie dekat dengan minimarket ini.
“Saya sudah belikan teh botol, Bang,” lelaki itu muncul dari dalam minimarket, seraya menjinjing kresek berisi minuman dingin untuk kami.
Senyumku berkembang. Melihat sosok Angga seperti melihat bayanganku sendiri di masa lalu. Santun dan sedikit malu-malu pada orang yang baru dikenalnya.
“Kamu tidak kerja, Ga?” tanyaku saat mulai meracik mie ayamku dengan sedikit saus dan sambal.
“Saya kerja shift siang, Bang. Jam dua.”
Spontan aku memeriksa arlojiku. Masih ada waktu tiga jam lagi untuk dia bekerja.
“Kerja shift, ya? Memangnya kerja di mana? Supermarket?”
Angga mengangguk seraya menyebutkan sebuah brand Hypermarket terkemuka di Indonesia. “Untung, tempat kerja saya masih di sekitar Sukajadi, dekat dengan lokasi rumah rumah sakit. Jadi tidak terburu-buru waktu,” ujarnya.
“Pasti menyenangkan ya bekerja di supermarket sebesar itu. Kamu bisa bertemu banyak orang di sana.”
Angga mengangguk setuju.
“Ngomong-ngomong, Bang Nael ke mana? Kok aku tidak melihatnya, ya?”
Angga menggeleng. “Mungkin lagi kerja, cari uang,” ujarnya setelah meneguk minumannya. “Bang,” ragu-ragu ia memanggilku tak lama kemudian.
Aku masih menunggu kalimatnya secara utuh. “Ada apa? Kok malah diam? Kamu mau bilang apa?” kataku setelah beberapa saat.
Angga masih diselimuti keraguan. Lelaki itu hanya memainkan sumpit di mangkuknya tanpa berani menatap langsung wajahku.
“Ga. Jujur kepadaku. Ada masalah apa? Soal Nael? Soal Ibu Nael?” desakku.
Angga menggelengkan kepalanya. “Saya hanya mau bilang terima kasih,” ujarnya gugup.
“Soal?” aku mengernyitkan dahi.
“Bang Diaz mau dekat dengan Bang Nael lagi.”
Kepalaku sedikit mendongak. Astaga! Bicara apa dia? Jujur saja, rasanya jantungku serasa berhenti untuk sesaat. Apa yang dia tahu tentang aku dan Nael?
“Maksud kamu?” aku masih menggali jawaban darinya.
“Saya tahu siapa Abang,” lirihnya tanpa berani menatapku. Dari nada suara yang kudengar, aku tahu dia gugup.
“Dan kamu siapanya Nael?” selidikku. Lama-lama aku curiga Angga bukan sekedar sepupu Nael.
“Saya... BF-nya Bang Nael,” lirih namun cukup terdengar jelas di telingaku.
Apa barusan dia bilang? Boyfriend? Pacar maksudnya? Demi Tuhan, aku terkejut, sampai-sampai sumpit yang kugenggam terlepas ke lantai.
“Maaf, saya tidak terus terang kepada Abang sebelumnya. Saya hanya ingin menjaga perasaan Bang Nael.”
Seraya mengelap sumpit yang terjatuh dengan tissue, aku mengulum senyum, seakan memaklumi perbuatannya yang membuatku merasa bodoh saat berkenalan kemarin. Rasanya aku tidak ingin mengeluarkan sepatah katapun. Hanya menunggu penjelasan apa lagi yang akan ia paparkan.
“Saya tahu siapa Bang Diaz. Bang Nael pernah menceritakan kisah kalian saat SMA. Dan saya tahu Bang Diaz adalah orang yang paling spesial di hati Bang Nael.”
Aku mengerutkan dahi. Masih tak mau berkata-kata.
“Terima kembali Bang Nael, Bang. Bang Nael sangat mencintai Abang,” bola mata Angga mulai mengembun.
Permohonan macam apa ini? Lelaki bau kencur ini seolah bermain drama memohon-mohon agar kekasihnya bisa bahagia, begitu? Sial!
“Kamu keliru, Ga!” seruku tegas. “Lalu apa arti kamu bagi Nael? Apalagi hanya kamu yang ada di sampingnya selama ini. Bahkan dengan tulusnya merawat Tante Sofie selama dia bekerja.”
Kembali Angga menundukkan kepalanya.
“Sudahlah. Kamu jangan banyak berprasangka. Kami hanya kawan. Tak lebih,” kuusap bahu lelaki itu.
“Saya melihat Bang Nael memeluk Bang Diaz malam itu. Di depan rumah kami.”
“Kalian tinggal serumah?” perbincangan ini semakin menarik. Aku memperbaiki posisi dudukku menjadi lebih dekat dengannya.
Angga mengangguk. “Bang Nael sudah menjual rumahnya demi perawatan Ibu di rumah sakit.”
“Tidak ada respons apapun dari Tante Sofie? Beliau tidak bertanya-tanya soal siapa kamu?”
Lelaki itu menghela napas panjang. “Tante Sofie tahu kami adalah pasangan,” terang Angga.
“Gila!” seruku spontan.
“Bukan tanpa perjuangan agar Tante Sofie mau menerima kami. Beliau pernah mengancam Bang Nael untuk tinggalkan saya. Namun sejak kecelakaan itu, saya memberanikan diri untuk menawarkan rumah saya untuk ditinggali bersama. Berangsur Tante Sofie menerima keadaan kami.”
“Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Memangnya bagaimana kamu menjelaskannya pada mereka?”
“Keluarga saya tinggal di Sumatra, Bang. Saya tinggal seorang diri.”
Kami terdiam, mendadak selera makanku menguap begitu saja. Kejutan yang Angga berikan hari ini sungguh di luar nalarku. Mereka tinggal bersama? Dengan Tante Sofie pula?
“Soal malam itu. Aku meminta maaf. Kami hanya terbawa emosi karena lama tidak bertemu. Tidak ada perasaan apapun. Kamu boleh pegang ucapanku,” tuturku.
Angga mengulum senyum. Seolah bersyukur semua perasaan gundah yang mengganggunya telah terselesaikan dengan baik. “Ternyata benar apa yang Bang Nael katakan. Bang Diaz adalah lelaki yang baik.”
Aku tak terlalu merespons pujiannya. “Sudah berapa lama kalian pacaran?” kualihkan arah pembicaraan.
“Lima tahun!”
Sial! Kejutan apa lagi yang diberikan pemuda itu? Untuk ukuran pasangan gay membina hubungan hingga lima tahun adalah sesuatu yang luar biasa.
Aku tersenyum takjub seraya berdecak kagum. Beruntung kisah cinta mereka berjalan tanpa ada hambatan dari siapapun. Seakan semuanya berjalan benar dan baik-baik saja.
“Kapan kalian bertemu,” ujarku sesaat setelah abang penjual mie ayam membereskan meja kami.
Angga melengkungkan bibirnya. Antara malu dan senang terlihat dari mimik wajahnya. “Saya bertemu Bang Nael saat masih di bangku kuliah,” terangnya.
Berarti Nael seorang sarjana, pikirku.
“Saat itu saya masih mahasiswa baru. Kami bertemu dalam kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa. Kebetulan Bang Nael adalah panitia kegiatan tersebut.”
Aku mendengarkan seraya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang terpancar di wajah Angga.
“Bang Nael waktu itu orangnya agak nakal dan suka bercanda. Tidak heran dia punya banyak teman di kampus.”
Aku mengangguk setuju dengan opininya. “Begitu pula saat kami masih SMA,” tambahku. “Terus bagaimana ceritanya sampai kalian bisa jadian?” desakku penasaran.
“Ya karena Bang Nael itu orangnya usil. Dia sering usilin saya. Seperti menyembunyikan sepatu saat sedang di Masjid kampus. Atau memarahi saya tanpa alasan hanya karena dia senior kami.”
Aku tertawa kecil.
“Ya, ternyata di balik semua itu. Ternyata Bang Nael menyimpan rasa sama saya.”
“Begitu saja? Kok kalian bisa menebak satu sama lain kalau kalian gay?”
“Gay radar, Bang. Orang seperti kita selalu bisa menebak siapa saja yang memiliki kesamaan dengan kita. Seolah memiliki antena panjang, dan bila menemukan ‘makhluk’ yang sama, gay radar kita spontan akan mendengung.”
Aku tergelak tawa mendengar penjelasan anak ingusan itu.
Perlahan tawa lelaki itu mereda. “Namun kebahagiaan Bang Nael sepertinya tidak bertahan lama. Semenjak kecelakaan yang menimpa Ibu tiga tahun silam.”
Aku menghela napas panjang merasa ikut prihatin.
“Ibu mengalami pendarahan di kepalanya yang membuat beliau tidak sadarkan diri beberapa hari. Entahlah sakit apa yang beliau derita, yang pasti hingga saat ini beliau masih berada di rumah sakit. Meski kami telah melakukan operasi dua kali tahun lalu.”
“Berarti ini adalah operasi yang ketiga kalinya?”
Angga sedikit mendongak ke arahku. “Kok Abang tahu Ibu harus dioperasi lagi?”
“Kebetulan aku ada teman dokter di rumah sakit ini. Dan dia menjelaskan keadaan Tante Sofie.”
“Dokter Edgard?” tebaknya.
Aku menggeleng. “Temannya Dokter Edgard. Dokter Dimas,” terangku.
Angga hanya mengangguk. Mungkin dia tidak mengenal Dimas.
“Kalau Bang Nael kuliah seharusnya dia sekarang sarjana dong,” analisaku. “Kenapa tidak kerja kantoran?”
“Bang Nael memutuskan kuliahnya saat semester 8. Karena dia tidak ada biaya. Terkuras habis untuk pengobatan Ibu.”
“...”
“Berkali-kali Bang Nael keluar masuk perusahaan. Dia berusaha mencari pekerjaan dengan gaji besar supaya bisa mencukupi biaya pengobatan Ibu.”
Aku masih mendengarkan.
“Hingga tak lama kemudian, muncul perempuan yang Bang Nael sebut Madam itu. Dia yang menawari pekerjaan ini, Bang,” lirihnya. “Pendapatannya memang lebih besar dibanding pekerjaan Bang Nael sebelumnya. Cukuplah untuk biaya kebutuhan pengobatan Ibu.”
“Lalu, kamu tidak kecewa dia bekerja sebagai kucing?”
“Saya bisa apa, Bang? Saat itu saya hanya mahasiswa yang tidak punya uang. Saya tidak berhak larang-larang Bang Nael,” terang Angga. “Tapi sebelumnya Bang Nael sempat bilang. Dia tidak akan terima tawaran itu kalau saya tidak ikhlas. Tapi tenyata situasi yang memaksa Bang Nael melakukan pekerjaan tersebut.”
Tak terasa uraian kisah Angga menyisakan embun di mataku. “Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian, Ga?” lirihku.
Angga menggeleng. “Saya menceritakan ini bukan bermaksud untuk minta belas kasihan dari Abang. Anggap saja hanya curhatan yang selama ini ada di hati saya,” tuturnya. “Abang pura-pura tidak tahu saja, ya? Saya takut Bang Nael marah.”
***
Untuk yang ketiga kali aku mengunjungi rumah sakit ini. Sungguh, pertemuan terakhir dengan Angga menyisakan banyak keresahan di hatiku. Bagaimana tidak? Ibu sahabatku tengah meregang nyawa di sana, dan secara tak langsung aku merasa harus ikut membantu, entah dengan cara apapun itu.
“Kamu yakin?” Dimas melepas kacamata lalu sedikit memijat pelipisnya. Sepertinya dia mengalami hari yang melelahkan seharian ini. “Setidaknya sampaikan dulu pada Nael maksud baikmu itu,” sarannya setelah menyeruput secangkir white coffee.
Aku hanya mengedikkan bahu seolah sarannya sulit untuk kupenuhi. Ya, kurasa Dimas tahu sendiri bagaimana perangai Nael dari cerita-ceritaku sebelumnya. Orang paling keras kepala yang pernah kukenal.
“Eh, bagaimana kabar Si Edgard?” alih-alih menuruti sarannya, aku sengaja memilih topik lain. Kurasa Dimas tak perlu ikut pusing dengan urusanku.
“Hah? Kenapa tiba-tiba kamu tanya kabar dia?” serunya diliputi tanda tanya.
“Sudahlah, sampai kapan sih kamu terus sembunyikan ini? Dari tampangmu aku tahu ada sesuatu yang terjadi di antara kalian.”
“Huss!” lirihnya seraya menutup bibir dengan telunjuk. “Kamu tidak boleh sembarangan bicara di tempat ini,” lanjut lelaki itu berultimatum.
“Tapi benar kan tebakanku?” aku kukuh menggodanya.
Lihat saja, rona merah nampak di wajahnya yang putih. Pertanda tebakanku tak keliru.
“Lalu bagaimana denganmu?” celoteh Dimas. “Semenjak dekat dengan si Nael, kamu jarang sekali membicarakan Peter.”
Aku mendongak, terkejut. Benarkah seperti itu? tanyaku dalam hati. Ragu-ragu aku mengembangkan senyuman. “Um... itu perasaanmu saja. Masalahnya kami memang belum bertemu lagi sejak keberangkatan dia ke Singapura dua minggu yang lalu.”
“Tapi kalian masih komunikasi, kan?”
“...”
“Tuh kan... ada yang salah dengan kalian. Bukan hanya aku yang merasa heran, bahkan Geng Setan lain pun melihat gelagat yang sama darimu.”
Sungguh, kali ini aku termangu, mencoba mencerna kalimat yang terucap Dimas barusan. Tak kupungkiri, aku pernah mencoba menghubungi Peter melalui pesan pendek, bahkan menelepon langsung, dan sialnya dia tak pernah membalas semua pesan dan teleponku. Tapi aku sama sekali tak begitu menghiraukannya. Dia sibuk, alibiku.
“Sorry, Brother. Sepertinya aku membuatmu cemas,” suara Dimas membuyarkan lamunanku.
“Saat seseorang tak pernah membalas pesan bahkan telepon dari pasangannya, menurutmu itu pertanda apa?”
“Hm... itu...”
“Forget it!” pertanyaan bodoh. Aku tertawa demi meredakan ketegangan di antara kami, diikuti derai tawa Dimas yang sama-sama terdengar aneh.
“Malam Minggu ini kita kumpul lagi di cafe biasa,” ujar Dimas sesaat setelah membaca pesan di gadget-nya.
“Hm…”
“Iya. Barusan ketua geng mengafirmasikan begitu di WhatsApps. Kamu jangan menghindar lagi, ya. Ada banyak cerita yang ingin kita bagi. Tentunya ceritamu soal Nael yang harus di-share kepada teman-teman”
“Oke,” balasku.
***
“Untuk yang kedua kali Bang Diaz gagal bertemu Bang Nael. Barusan dia pergi tidak tahu ke mana,” ujar Angga yang memanduku menuju sebuah taman di rumah sakit. “Tapi saya sudah sampaikan kok, kalau Bang Diaz jenguk Ibu kemarin.”
Aku mengulum senyum lalu mengajaknya duduk di kursi taman setibanya di sana.
“Lagian tujuan aku datang kemari bukan untuk bertemu Nael kok, Ga,” timpalku. “Justru aku mau bicara denganmu.”
“Sama saya?” Angga mengerutkan dahinya.
Kuhela napas panjang mencoba mencari cara menyampaikan maksud baikku dengan benar. “Iya, Ga. Ini soal rencana operasi Tante Sofie. Aku ingin membiayai operasi beliau.”
“Bang...” respons Angga. Seperti dugaanku, dia terkejut. “Jangan, Bang. Saya takut Bang Nael marah.”
“Sudahlah, jangan pedulikan orang itu. Nael biar urusanku. Aku hanya ingin melihat Tante Sofie segera sembuh dan sehat seperti sediakala. Tentunya itu juga kan yang kalian harapkan?”
Angga terdiam menunduk seraya memainkan ujung kemejanya. “Saya tidak tahu harus bicara apa sama Abang. Rasanya mengucapkan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan Abang kepada kami.”
“Tak perlu sentimentil seperti itu lah,” aku tertawa gemas. Lalu perlahan terdiam sejenak. Mengingat-ingat kenangan saat masih SMA. Tante Sofie kerap membuat kue tradisional untuk aku dan Nael. Bahkan beliau berteman akrab dengan ibuku. “Aku kenal banget Tante Sofie. Beliau orang baik. Tidak tega rasanya melihat beliau menderita seperti ini,” aku masih menerawang.
Tak lama aku menoleh dan mendapati raut gelisah Angga tak juga memudar. “Nanti aku bicara dengan Nael. Dia pasti akan mengerti. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah persiapkan semua kebutuhan menjelang operasi Tante Sofie. Hubungi Dokter Edgard dan minta arahan darinya, oke?”
Meski ragu, Angga menganggukkan kepala pada akhirnya.
Akhirnya aku paham kenapa Nael memutuskan untuk hidup seperti ini. Ya, meski pada awalnya kecewa, namun kucoba memosisikan diri sebagai seorang Nael. Anak lelaki yang berusaha menyelamatkan sang ibu. Apapun caranya... meski harus mengorbankan masa depannya.
Other Stories
Pasti Ada Jalan
Sebagai ibu tunggal di usia muda, Sari, perempuan cerdas yang bernasib malang itu, selalu ...
After Honeymoon
Sama-sama tengah menyembuhkan rasa sakit hati, bertemu dengan nuansa Pulau Dewata yang sel ...
Death Cafe
Sakti tidak dapat menahan diri lagi, ia penasaran dengan death cafe yang selama ini orang- ...
Melinda Dan Dunianya Yang Hilang
Melinda seorang gadis biasa menjalani hari-hari seperti biasa, hingga pada suatu saat ia b ...
Diary Superhero
lanjutan cerita kisah cinta superhero. dari sudut pandang Sefia. superhero berkekuatan tel ...
Menantimu
Sejak dikhianati Beno, ia memilih jalan kelam menjajakan tubuh demi pelarian. Hingga Raka ...