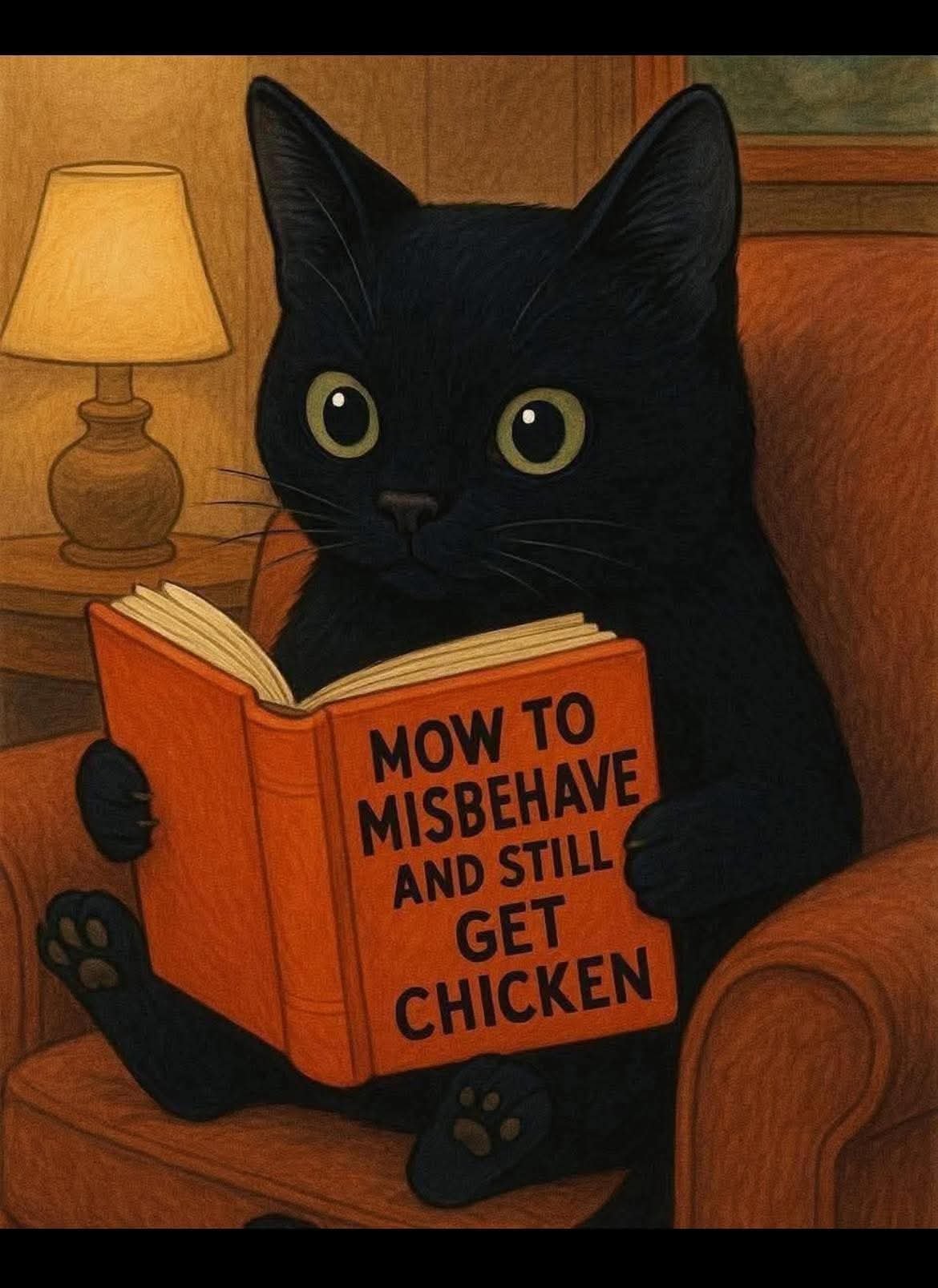Biola Dan Drum
“Latihan jam tujuh malam di studio, Stel! Jangan ngaret!” pesan dari Ria masuk di layar ponselnya, disusul stiker drum dan gitar.
Stella tersenyum tipis sambil mengetik, “Tenang. Aku cuma telat 10 menit.”
Studio itu tidak berubah: sempit, hangat, penuh kabel, dan bau kopi sachet yang menyatu dengan suara snare drum Roni yang baru diganti. Raka sudah memetik gitar pelan, Bayu membetulkan kabel bass, dan Reiza—masih dengan jaket hitam andalannya—membolak-balik lirik lagu baru.
“Eh, dokter gigi kesayangan akhirnya datang,” celetuk Roni sambil memainkan drum dengan irama pelan.
“Aku belum dokter, Beb,” jawab Stella, menaruh tas dan biola, lalu mencubit lengan Roni.
“Iya, tapi kan udah calon. Dan calonku juga,” bisik Roni lebih pelan, membuat Stella memutar bola matanya, pura-pura tidak terpengaruh, padahal pipinya memerah.
Malam itu mereka membawakan lagu-lagu lama dan mencoba satu lagu baru ciptaan Reiza—judul sementaranya “Yang Belum Selesai”. Stella memetik senar biolanya dengan lembut, mengisi bagian bridge lagu dengan melodi yang bikin Bayu sampai berhenti bermain bass sebentar.
“Gila, main biolamu makin jago, Stel,” puji Raka, mengacungkan jempol.
“Siapa dulu dong, Stella gitu,” jawab Stella, menatap satu-satu wajah mereka. Ria yang sok cuek tapi selalu siap menyambung vokal latar, Reiza yang kalau iseng nggak ada obat, Bayu yang kalem tapi tanggap, Raka yang cerewet di luar tapi peka dalam musik, dan tentu saja Roni.
Roni yang malam itu duduk di belakang drum, melirik Stella setiap kali ia tertawa. Yang diam-diam menulis lirik-lirik pendek untuk Stella di balik stik drumnya. Yang pulang latihan selalu mengantar ke rumah.
Sesi latihan selesai. Seperti biasa mereka duduk bersama di studio itu. Sekedar berbagi cerita kehidupan atau membahas rencana band mereka.
“Gimana kuliahnya, La? Seru?”, tanya Roni yang duduk di samping Stella.
“Seru sih. Walau udah mulai ngos-ngosan sama tugas plus praktikum”
“Udah dapet temen? Temen cowoknya gimana?”, goda Roni.
“Temen cowok ya? Hmm angkatanku emang lebih banyak cowoknya sih. Tumben kan? Tapi gak seekstrem Teknik ya. Kalau di tempatmu gimana Rei?”, Stella melirik Reiza yang sedang berdiri sibuk dengan ponselnya yang masih di-charge.
“Punyaku banyakan ceweknya lah”, jawabnya.
“Dan udah berapa yang pernah jadi pacarmu?”, Raka ikut menimpali. Disusul tawa teman-temannya.
“Sialan emang”, umpat Reiza.
Satu minggu kemudian, mereka tampil di kafe langganan di daerah Jalan Kaliurang. Panggung kecil, lampu kuning remang, tapi ramai oleh mahasiswa yang menyanyi bersama. Stella mengenakan blus putih dan celana jins hitam, sementara Roni memakai kaos band lokal yang udah mulai pudar.
Sebelum naik ke atas panggung, Roni memegang tangan Stella sebentar. “Kamu tahu nggak?”
“Apa?”
“Aku suka lihat kamu di atas panggung. Tapi aku lebih suka lihat kamu di deketku.”
Stella menunduk, senyum tak bisa disembunyikan.
Malam itu lagu terakhir mereka adalah lagu lama yang dulu mereka buat saat awal membentuk band. Stella memainkan intro dengan biolanya, lalu Ria dan Reiza menyanyikan bait pertama, dan Roni menyusul dengan irama drumnya yang khas.
Dan saat sorotan lampu menyapu panggung, Stella sempat berpikir—mungkin ini yang disebut rumah. Bukan bangunan, bukan tempat, tapi orang-orang yang membuatmu merasa hidup.
Suara tepuk tangan masih terasa di telinga Stella saat mereka keluar dari kafe. Udara Sleman malam itu dingin, sedikit berembus. Ria dan Reiza sibuk mengecek pesan-pesan dari teman-teman yang menonton, Raka dan Bayu saling ejek soal chord yang sempat salah, sementara Andre sibuk menggulung kabel.
“Kamu capek?” Roni berjalan di samping Stella, masih memegang stik drumnya yang tak pernah ia simpan jauh.
“Lumayan, tapi puas.” Stella menengadah sebentar menatap langit. “Aku kangen banget manggung.”
Roni menyeringai, lalu mengangguk ke arah motornya yang terparkir. “Ayo, aku anter. Rumah kamu kan nggak sejauh galaksi Andromeda.”
“Rumahku dekat, tapi hati kamu kan jauh,” cibir Stella, menggoda.
Roni tergelak. “Gitu, ya? Padahal aku udah setel Google Maps ke ‘hati Stella’ dari dulu.”
Mereka tertawa pelan. Tak ada suara lain selain langkah teman-teman yang mulai bubar. Stella akhirnya duduk di jok belakang motor Roni, tapi mereka belum menyalakan mesin.
“Kadang aku bingung, Ron,” ujar Stella pelan, “Kuliah kedokteran gigi itu serius banget. Tugasnya banyak, tekanannya besar. Tapi musik juga kayak bagian yang nggak bisa aku lepasin.”
“Kamu nggak harus milih salah satu, La.” Roni menatap ke depan, tak langsung menoleh. “Kamu bisa jadi dokter gigi yang jago, sekaligus musisi yang bikin hati orang hangat.”
“Kamu yakin?”
“Aku yakin sama kamu. Selalu.”
Kalimat itu mengendap di dada Stella lebih lama daripada seharusnya. Ia menatap punggung Roni yang lebar, yang selalu jadi tempat bersandar tanpa diminta.
Roni akhirnya menyalakan motor. Tapi sebelum berangkat, ia bertanya sambil menoleh sedikit.
---
Bengkel itu masih berdiri sama seperti dulu. Cat dindingnya memudar, bau oli dan kayu bercampur di udara, dan pintu rolling-nya berderit ketika dibuka. Tapi bagi mereka, tempat itu bukan sekadar ruang kosong di ujung gang. Itu tempat pulang.
Stella datang dengan setumpuk buku tebal dan laptop. Rambutnya dikuncir seadanya, mata sedikit bengkak karena kurang tidur. Di dalam, Roni sudah lebih dulu sampai, duduk di lantai sambil sibuk dengan maketnya.
“Wih, mau juga dong dibikinin rumah Kak” goda Stella, menjatuhkan diri di kursi panjang di belakang Roni.
“Mau rumah yang gimana kak?”, tanya Roni sambal tersenyum
“Yang ada tangganya dan ada kitanya”, Stella kembali menggoda Roni.
“Hahaha bisa aja kamu Beb. I’ll be your home”, ucap Roni sambil tersenyum dan menatap Stella dalam.
“Sibuk banget sih ya kuliah arsi tuh”
“Kuliahmu juga nggak kalah ribet, calon dokter gigi,” balas Roni, lalu menoleh sambil senyum, “Tapi tetap nyempetin ke sini ya?”
Stella mengangkat bahu. “Daripada meledak otak di rumah. Di sini adem... dan ada kamu.”
Roni mengedipkan sebelah mata. “Bonus dong itu.”
Tak lama, Bayu datang dengan dua bungkus gorengan dan es teh di plastik. Ria menyusul lima belas menit kemudian, membawa laptop dan headset, wajahnya ditekuk karena tugas belum selesai. Tak ada latihan hari itu, tak ada lagu yang direkam. Tapi studio bengkel tetap jadi tempat berteduh mereka dari riuhnya dunia luar.
“Pakai colokan sebelah sini ya, yang deket ampli,” kata Ria sambil menancapkan charger.
“Eh jangan ganggu setelan ampliku!” seru Bayu. “Nanti pas kita beneran mau latihan, setting-nya berubah.”
“Kayak kita sempat latihan aja,” celetuk Roni sambil tertawa.
“Kembaranmu yang rese itu kemana sih Beb, gak pernah kelihatan aja?”, tanya Stella.
“Reiza tuh emang lagi sibuk banget dia. Kadang sampe gak pulang. Gak tau ngapain”
“Huft. Emang yah semester atas kedokteran umum tuh”
Tawa di ruangan itu yang membuat semuanya terasa tetap utuh, meski hidup mereka sedang berlari ke arah masing-masing. Kadang mereka hanya duduk diam, sibuk dengan laptop masing-masing. Kadang saling curhat tentang dosen galak, deadline yang bikin stress.
Kadang Stella menatap biolanya di pojok ruangan—sudah lama tak disentuh. Tapi ia tahu, ketika ia siap, musik itu akan kembali. Roni sesekali memainkan ritme di lututnya, seperti tangannya tak bisa lepas dari irama. Mereka belum bubar. Mereka hanya tumbuh. Saat matahari tenggelam, Roni mengajak Stella keluar sebentar, duduk di kap mobil tua peninggalan ayah Bayu yang kini jadi ‘meja tamu’ mereka.
“Kamu takut kita bakal bener-bener bubar, Beb?” tanya Roni pelan.
Stella diam sebentar, lalu menggeleng. “Nggak sih. Kan masih ada tempat ini. Walau cuma buat nugas, atau tidur siang, atau ngopi sore. Tapi selama tempat ini ada, kita nggak akan jauh.”
Stella tersenyum tipis sambil mengetik, “Tenang. Aku cuma telat 10 menit.”
Studio itu tidak berubah: sempit, hangat, penuh kabel, dan bau kopi sachet yang menyatu dengan suara snare drum Roni yang baru diganti. Raka sudah memetik gitar pelan, Bayu membetulkan kabel bass, dan Reiza—masih dengan jaket hitam andalannya—membolak-balik lirik lagu baru.
“Eh, dokter gigi kesayangan akhirnya datang,” celetuk Roni sambil memainkan drum dengan irama pelan.
“Aku belum dokter, Beb,” jawab Stella, menaruh tas dan biola, lalu mencubit lengan Roni.
“Iya, tapi kan udah calon. Dan calonku juga,” bisik Roni lebih pelan, membuat Stella memutar bola matanya, pura-pura tidak terpengaruh, padahal pipinya memerah.
Malam itu mereka membawakan lagu-lagu lama dan mencoba satu lagu baru ciptaan Reiza—judul sementaranya “Yang Belum Selesai”. Stella memetik senar biolanya dengan lembut, mengisi bagian bridge lagu dengan melodi yang bikin Bayu sampai berhenti bermain bass sebentar.
“Gila, main biolamu makin jago, Stel,” puji Raka, mengacungkan jempol.
“Siapa dulu dong, Stella gitu,” jawab Stella, menatap satu-satu wajah mereka. Ria yang sok cuek tapi selalu siap menyambung vokal latar, Reiza yang kalau iseng nggak ada obat, Bayu yang kalem tapi tanggap, Raka yang cerewet di luar tapi peka dalam musik, dan tentu saja Roni.
Roni yang malam itu duduk di belakang drum, melirik Stella setiap kali ia tertawa. Yang diam-diam menulis lirik-lirik pendek untuk Stella di balik stik drumnya. Yang pulang latihan selalu mengantar ke rumah.
Sesi latihan selesai. Seperti biasa mereka duduk bersama di studio itu. Sekedar berbagi cerita kehidupan atau membahas rencana band mereka.
“Gimana kuliahnya, La? Seru?”, tanya Roni yang duduk di samping Stella.
“Seru sih. Walau udah mulai ngos-ngosan sama tugas plus praktikum”
“Udah dapet temen? Temen cowoknya gimana?”, goda Roni.
“Temen cowok ya? Hmm angkatanku emang lebih banyak cowoknya sih. Tumben kan? Tapi gak seekstrem Teknik ya. Kalau di tempatmu gimana Rei?”, Stella melirik Reiza yang sedang berdiri sibuk dengan ponselnya yang masih di-charge.
“Punyaku banyakan ceweknya lah”, jawabnya.
“Dan udah berapa yang pernah jadi pacarmu?”, Raka ikut menimpali. Disusul tawa teman-temannya.
“Sialan emang”, umpat Reiza.
Satu minggu kemudian, mereka tampil di kafe langganan di daerah Jalan Kaliurang. Panggung kecil, lampu kuning remang, tapi ramai oleh mahasiswa yang menyanyi bersama. Stella mengenakan blus putih dan celana jins hitam, sementara Roni memakai kaos band lokal yang udah mulai pudar.
Sebelum naik ke atas panggung, Roni memegang tangan Stella sebentar. “Kamu tahu nggak?”
“Apa?”
“Aku suka lihat kamu di atas panggung. Tapi aku lebih suka lihat kamu di deketku.”
Stella menunduk, senyum tak bisa disembunyikan.
Malam itu lagu terakhir mereka adalah lagu lama yang dulu mereka buat saat awal membentuk band. Stella memainkan intro dengan biolanya, lalu Ria dan Reiza menyanyikan bait pertama, dan Roni menyusul dengan irama drumnya yang khas.
Dan saat sorotan lampu menyapu panggung, Stella sempat berpikir—mungkin ini yang disebut rumah. Bukan bangunan, bukan tempat, tapi orang-orang yang membuatmu merasa hidup.
Suara tepuk tangan masih terasa di telinga Stella saat mereka keluar dari kafe. Udara Sleman malam itu dingin, sedikit berembus. Ria dan Reiza sibuk mengecek pesan-pesan dari teman-teman yang menonton, Raka dan Bayu saling ejek soal chord yang sempat salah, sementara Andre sibuk menggulung kabel.
“Kamu capek?” Roni berjalan di samping Stella, masih memegang stik drumnya yang tak pernah ia simpan jauh.
“Lumayan, tapi puas.” Stella menengadah sebentar menatap langit. “Aku kangen banget manggung.”
Roni menyeringai, lalu mengangguk ke arah motornya yang terparkir. “Ayo, aku anter. Rumah kamu kan nggak sejauh galaksi Andromeda.”
“Rumahku dekat, tapi hati kamu kan jauh,” cibir Stella, menggoda.
Roni tergelak. “Gitu, ya? Padahal aku udah setel Google Maps ke ‘hati Stella’ dari dulu.”
Mereka tertawa pelan. Tak ada suara lain selain langkah teman-teman yang mulai bubar. Stella akhirnya duduk di jok belakang motor Roni, tapi mereka belum menyalakan mesin.
“Kadang aku bingung, Ron,” ujar Stella pelan, “Kuliah kedokteran gigi itu serius banget. Tugasnya banyak, tekanannya besar. Tapi musik juga kayak bagian yang nggak bisa aku lepasin.”
“Kamu nggak harus milih salah satu, La.” Roni menatap ke depan, tak langsung menoleh. “Kamu bisa jadi dokter gigi yang jago, sekaligus musisi yang bikin hati orang hangat.”
“Kamu yakin?”
“Aku yakin sama kamu. Selalu.”
Kalimat itu mengendap di dada Stella lebih lama daripada seharusnya. Ia menatap punggung Roni yang lebar, yang selalu jadi tempat bersandar tanpa diminta.
Roni akhirnya menyalakan motor. Tapi sebelum berangkat, ia bertanya sambil menoleh sedikit.
---
Bengkel itu masih berdiri sama seperti dulu. Cat dindingnya memudar, bau oli dan kayu bercampur di udara, dan pintu rolling-nya berderit ketika dibuka. Tapi bagi mereka, tempat itu bukan sekadar ruang kosong di ujung gang. Itu tempat pulang.
Stella datang dengan setumpuk buku tebal dan laptop. Rambutnya dikuncir seadanya, mata sedikit bengkak karena kurang tidur. Di dalam, Roni sudah lebih dulu sampai, duduk di lantai sambil sibuk dengan maketnya.
“Wih, mau juga dong dibikinin rumah Kak” goda Stella, menjatuhkan diri di kursi panjang di belakang Roni.
“Mau rumah yang gimana kak?”, tanya Roni sambal tersenyum
“Yang ada tangganya dan ada kitanya”, Stella kembali menggoda Roni.
“Hahaha bisa aja kamu Beb. I’ll be your home”, ucap Roni sambil tersenyum dan menatap Stella dalam.
“Sibuk banget sih ya kuliah arsi tuh”
“Kuliahmu juga nggak kalah ribet, calon dokter gigi,” balas Roni, lalu menoleh sambil senyum, “Tapi tetap nyempetin ke sini ya?”
Stella mengangkat bahu. “Daripada meledak otak di rumah. Di sini adem... dan ada kamu.”
Roni mengedipkan sebelah mata. “Bonus dong itu.”
Tak lama, Bayu datang dengan dua bungkus gorengan dan es teh di plastik. Ria menyusul lima belas menit kemudian, membawa laptop dan headset, wajahnya ditekuk karena tugas belum selesai. Tak ada latihan hari itu, tak ada lagu yang direkam. Tapi studio bengkel tetap jadi tempat berteduh mereka dari riuhnya dunia luar.
“Pakai colokan sebelah sini ya, yang deket ampli,” kata Ria sambil menancapkan charger.
“Eh jangan ganggu setelan ampliku!” seru Bayu. “Nanti pas kita beneran mau latihan, setting-nya berubah.”
“Kayak kita sempat latihan aja,” celetuk Roni sambil tertawa.
“Kembaranmu yang rese itu kemana sih Beb, gak pernah kelihatan aja?”, tanya Stella.
“Reiza tuh emang lagi sibuk banget dia. Kadang sampe gak pulang. Gak tau ngapain”
“Huft. Emang yah semester atas kedokteran umum tuh”
Tawa di ruangan itu yang membuat semuanya terasa tetap utuh, meski hidup mereka sedang berlari ke arah masing-masing. Kadang mereka hanya duduk diam, sibuk dengan laptop masing-masing. Kadang saling curhat tentang dosen galak, deadline yang bikin stress.
Kadang Stella menatap biolanya di pojok ruangan—sudah lama tak disentuh. Tapi ia tahu, ketika ia siap, musik itu akan kembali. Roni sesekali memainkan ritme di lututnya, seperti tangannya tak bisa lepas dari irama. Mereka belum bubar. Mereka hanya tumbuh. Saat matahari tenggelam, Roni mengajak Stella keluar sebentar, duduk di kap mobil tua peninggalan ayah Bayu yang kini jadi ‘meja tamu’ mereka.
“Kamu takut kita bakal bener-bener bubar, Beb?” tanya Roni pelan.
Stella diam sebentar, lalu menggeleng. “Nggak sih. Kan masih ada tempat ini. Walau cuma buat nugas, atau tidur siang, atau ngopi sore. Tapi selama tempat ini ada, kita nggak akan jauh.”
Other Stories
Nyanyian Hati Seruni
Awalnya ragu dan kesal dengan aturan ketat sebagai istri prajurit TNI AD, ia justru belaja ...
Tersesat
Qiran yang suka hal baru nekat mengakses deep web dan menemukan sebuah lagu, lalu memamerk ...
Keikhlasan Cinta
6 tahun Hasrul pergi dari keluarganya, setelah dia kembali dia dipertemukan kembali dengan ...
After Meet You
kacamata hitam milik pria itu berkilat tertimpa cahaya keemasan, sang mata dewa nyaris t ...
Aku Pulang
Raina tumbuh di keluarga rapuh, dipaksa kuat tanpa pernah diterima. Kemudian, hadir sosok ...
O
o ...