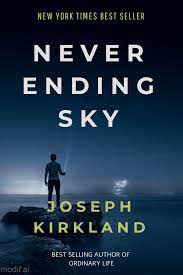Trio Tangguh
Belum sempat aku membalik badan, sebuah pelukan tiba-tiba melingkupiku dari samping. Lalu suara khas perempuan panik langsung memenuhi telinga.
“Kalau kencan tuh bilang-bilang napa, Ra!”
“Ya Allah, sumpah kita udah kepikiran mau lapor polisi, tahu nggak!”
Aku terbahak, meski sisa air mata masih terasa hangat di pipi. Dua sahabatku, Henny dan Moana, memandangku dengan wajah campur aduk antara lega dan kesal.
“Tadi ada kerjaan mendadak, maaf nggak sempat ngabarin,” jelasku cepat.
Moana mencubit lenganku gemas. “Ih, bilang aja kencan, Ra.”
“Enggak!” aku membela diri.
“Jawab iya aja napa, biar gampang,” Henny ikut menggoda sambil menggoyang-goyangkan tanganku.
Aku tertawa bersama mereka, rasa hangat kembali mengisi dada.
“Udah deh, buruan cerita, kalian dari mana aja?” desak Moana.
“Dih, kepo,” balasku sambil nyengir lalu merangkul keduanya masuk ke apartemen.
"Eh eh, tunggu anakku ketinggalan di ruang tunggu." Sontak Henny menghentikan langkah dan ngacir keruang tunggu.
Aku dan Moana saling pandang lalu tertawa. Dasar, Henny. Kami melangkah mengikuti Henny. Lalu membantu menggendong anak-anaknya yang sudah terlelap.
“Suami kalian bakalan nyariin nggak?” tanyaku begitu kami sampai di unitku. Alan dan Abel tidur lelap di kasur. Sementara kami di depan televisi. Aku langsung memesan beberapa makanan lewat lewat aplikasi.
“Aku udah ngabarin Mas Aditya,” jawab Moana santai sambil merebahkan diri di sofa. “Dia malah seneng aku keluar rumah, katanya biar nggak stres di rumah terus."
Kami terkekeh.
“Kalau Bang Sandi sih…” Henny menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya. “Kayaknya bodo amat ya sama aku.” Ia menoleh sebentar pada kami, senyum tipis di bibirnya tapi matanya nggak benar-benar tersenyum. “Eh, tapi ya, dia bakalan nyariin sih kalau lagi butuh bikin kopi.” Dia terdiam sepersekian detik, lalu melanjutkan, “Dan bikin…”
Moana langsung menyahut, “Anak.”
Sejenak hening, lalu tawa kami pecah bersamaan. Meledak, riuh, menutupi getir yang sempat menyelinap di ruangan.
Henny pun akhirnya ikut tertawa sampai menepuk pahanya. “Dasar kalian berdua, selalu aja bisa bikin aku ketawa padahal lagi pengen nangis, inget kalau Bang Sandy nggak perduli sama aku."
Aku meraih tangannya dan menggenggamnya sebentar. “Itu fungsi sahabat, Hen. Biar kamu nggak gila sendirian.”
Moana mengangguk setuju. “Tenang aja, kita bertiga udah kayak trio tangguh. Nggak bakal ada yang bisa bikin kita tumbang.”
“Eh eh, buruan cerita, siapa tadi yang nganter kamu? Cieee…,” seru Moana sambil menyenggol lenganku penuh goda, matanya menyipit nakal.
Aku berusaha tetap tenang. “Beliau atasan aku. Kami ada rapat mendadak di kantor.”
“Di kantor?” ulang Henny, keningnya terangkat tinggi seolah tak percaya.
Aku mengangguk mantap, mencoba meyakinkan. “Iya, beneran.”
Tapi Henny cepat sekali menangkap kejanggalan. “Kalau rapat di kantor, kenapa bisa pulangnya dianterin atasan? Bukannya kamu biasanya bawa mobil sendiri?” tanyanya penuh analisa, sambil melipat tangan di dada.
Aku membeku. Mata berkedip cepat, mencari celah jawaban. Iya juga ya… terus aku harus alasan apa sekarang?
Moana yang dari tadi memperhatikan ekspresi gugupku langsung bersorak. “Nah, kan ketahuan, cieee!” Ia menepuk-nepuk pundakku sambil ngakak, lalu refleks mengulurkan tangan ke Henny. Tanpa pikir panjang, Henny menepuknya balik. Toss mereka mendarat dengan bunyi keras, menandai keberhasilan mereka meledekku.
Aku hanya bisa menunduk sambil menghembuskan napas, pipi terasa panas terbakar malu.
** @ **
Pagi ini aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Baru saja jam kerja mulai, Roni datang dengan map di tangannya.
“Selamat pagi, Bu,” sapanya ramah. “Ini beberapa dokumen dari Pak Adrian. Hasil meeting kemarin. Beliau minta Ibu merapikannya jadi satu file.”
Aku tersenyum kecil, menerima map itu. “Baik, akan segera saya kerjakan.”
“Oh ya, satu lagi,” Roni menambahkan sambil menyesuaikan posisi kacamatanya. “Pak Adrian juga meminta Ibu menyiapkan bahan presentasi untuk pertemuan dengan klien dari Malaysia, dua hari lagi.”
Aku mengangguk lagi. “Baik.”
“Setelah jam istirahat, beliau minta Ibu datang ke ruangannya.”
“Baik, terima kasih.”
Begitu Roni pergi, aku langsung tenggelam dalam pekerjaan, berusaha menyelesaikan dengan rapi.
Siang hari, tepat setelah jam istirahat, aku berdiri di depan pintu ruang direktur. Nafasku kutahan sebentar, lalu ku ketuk pelan.
“Masuk,” suara berat itu terdengar jelas.
Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Rasanya seperti pertama kali masuk ke ruangan ini, seolah baru pertama kali berhadapan dengan Pak Adrian. Entah kenapa, grogi yang tak seharusnya ada malah menyerang.
“Silakan duduk,” ucapnya sopan namun tetap tegas.
Aku mengangguk, meletakkan tablet yang sudah penuh file di meja depannya, lalu duduk berhadapan.
“Semua sudah dikerjakan?” tanyanya sambil mulai membuka file dengan tangannya yang sigap.
“Sudah, Pak,” jawabku pelan.
“Baik. Saya periksa sebentar. Jika ada yang tidak tepat, revisi segera.” Suaranya tenang, tapi ada tekanan halus yang membuatku refleks menegakkan punggung.
Aku hanya bisa mengangguk lagi, sambil menunggu ia meneliti hasil kerjaku dengan jantung berdegup lebih kencang dari seharusnya.
“Semuanya rapi, tapi ada yang perlu diperbaiki,” katanya setelah selesai memeriksa file. Nada suaranya kembali tegas. Ia mengetuk layar. “Bagian analisis terlalu singkat. Tambahkan proyeksi minimal lima tahun ke depan. Klien Malaysia biasanya memperhatikan detail itu.”
Aku buru-buru mencatat. “Baik, Pak. Akan saya tambahkan.”
“Dan untuk penutup,” ia menatapku sekilas, “jangan terlalu formal. Buat lebih meyakinkan. Anggap saja kita bukan sekadar menawarkan kerja sama, tapi memberi solusi.”
Aku mengangguk. “Mengerti, Pak.”
Setelah mengucapkan terima kasih, aku berdiri dan melangkah keluar. Namun baru dua langkah, suara beratnya kembali memanggil.
“Akira.”
Aku menoleh cepat. “Ya, Pak? Ada yang lain?” tanyaku hati-hati.
Dia hanya menatapku. Diam. Ekspresinya sulit kutebak, antara serius atau… iba. Sekilas aku teringat, mungkin ini ada hubungannya dengan kondisiku yang terlanjur ia ketahui.
Beberapa detik kemudian, akhirnya ia bertanya, sederhana tapi membuatku kaku.
“Kamu sudah makan?”
Dahiku berkerut. “Sudah, Pak,” jawabku singkat, entah kenapa terasa canggung.
Dia mengangguk pelan, lalu kembali menatap berkas-berkas di mejanya. “Baik. Silakan kembali bekerja.”
Aku terdiam sejenak lalu membungkuk hormat sebelum benar-benar meninggalkan ruangan itu.
Jam pulang kerja sudah lewat, tapi aku masih duduk di kursi kerjaku. Melirik jam tangan, lalu kembali menatap layar ponsel. Jari-jariku sibuk menekan tombol game sederhana yang biasanya dimainkan anak-anak.
Saat suasana kantor semakin lengang, aku akhirnya beranjak dari kursi. Langkahku pelan, seolah setiap ayunan kaki ditahan oleh rasa waswas. Aku memang sengaja menunggu hingga kantor benar-benar sepi, hanya karena takut bertemu Pak Adrian di dalam lift.
Ya, aku takut jika harus satu lift lagi dengannya. Takut jika aku tidak bisa mengendalikan delusiku. Lalu dihantam serangan panik di ruang sempit itu. Sekadar membayangkan saja sudah membuat telapak tanganku dingin dan napasku terasa berat.
TING. Suara lift terbuka. Dan seketika nafasku tercekat.
Pak Adrian ada di sana.
Aku refleks mematung, mata membelalak. Degup jantungku langsung kacau. Namun, suara tawanya memecah suasana yang tegang. Ringan, tapi cukup untuk meruntuhkan kekakuanku.
"Saya pikir pulang belakangan tidak akan bertemu denganmu, Akira. Tapi tetap bertemu."
Aku masih terdiam, bingung harus menanggapi apa.
Ia menghela napas, lalu melangkah keluar dari lift. “Pakailah. Saya bisa lewat tangga.”
Aku menoleh, refleks. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Lalu ia melangkah pergi dengan tenang.
Entah kenapa, pandanganku tak bisa lepas. Mataku terus mengikuti punggungnya yang perlahan menjauh, hingga sosoknya benar-benar hilang dari pandangan.
“Kalau kencan tuh bilang-bilang napa, Ra!”
“Ya Allah, sumpah kita udah kepikiran mau lapor polisi, tahu nggak!”
Aku terbahak, meski sisa air mata masih terasa hangat di pipi. Dua sahabatku, Henny dan Moana, memandangku dengan wajah campur aduk antara lega dan kesal.
“Tadi ada kerjaan mendadak, maaf nggak sempat ngabarin,” jelasku cepat.
Moana mencubit lenganku gemas. “Ih, bilang aja kencan, Ra.”
“Enggak!” aku membela diri.
“Jawab iya aja napa, biar gampang,” Henny ikut menggoda sambil menggoyang-goyangkan tanganku.
Aku tertawa bersama mereka, rasa hangat kembali mengisi dada.
“Udah deh, buruan cerita, kalian dari mana aja?” desak Moana.
“Dih, kepo,” balasku sambil nyengir lalu merangkul keduanya masuk ke apartemen.
"Eh eh, tunggu anakku ketinggalan di ruang tunggu." Sontak Henny menghentikan langkah dan ngacir keruang tunggu.
Aku dan Moana saling pandang lalu tertawa. Dasar, Henny. Kami melangkah mengikuti Henny. Lalu membantu menggendong anak-anaknya yang sudah terlelap.
“Suami kalian bakalan nyariin nggak?” tanyaku begitu kami sampai di unitku. Alan dan Abel tidur lelap di kasur. Sementara kami di depan televisi. Aku langsung memesan beberapa makanan lewat lewat aplikasi.
“Aku udah ngabarin Mas Aditya,” jawab Moana santai sambil merebahkan diri di sofa. “Dia malah seneng aku keluar rumah, katanya biar nggak stres di rumah terus."
Kami terkekeh.
“Kalau Bang Sandi sih…” Henny menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya. “Kayaknya bodo amat ya sama aku.” Ia menoleh sebentar pada kami, senyum tipis di bibirnya tapi matanya nggak benar-benar tersenyum. “Eh, tapi ya, dia bakalan nyariin sih kalau lagi butuh bikin kopi.” Dia terdiam sepersekian detik, lalu melanjutkan, “Dan bikin…”
Moana langsung menyahut, “Anak.”
Sejenak hening, lalu tawa kami pecah bersamaan. Meledak, riuh, menutupi getir yang sempat menyelinap di ruangan.
Henny pun akhirnya ikut tertawa sampai menepuk pahanya. “Dasar kalian berdua, selalu aja bisa bikin aku ketawa padahal lagi pengen nangis, inget kalau Bang Sandy nggak perduli sama aku."
Aku meraih tangannya dan menggenggamnya sebentar. “Itu fungsi sahabat, Hen. Biar kamu nggak gila sendirian.”
Moana mengangguk setuju. “Tenang aja, kita bertiga udah kayak trio tangguh. Nggak bakal ada yang bisa bikin kita tumbang.”
“Eh eh, buruan cerita, siapa tadi yang nganter kamu? Cieee…,” seru Moana sambil menyenggol lenganku penuh goda, matanya menyipit nakal.
Aku berusaha tetap tenang. “Beliau atasan aku. Kami ada rapat mendadak di kantor.”
“Di kantor?” ulang Henny, keningnya terangkat tinggi seolah tak percaya.
Aku mengangguk mantap, mencoba meyakinkan. “Iya, beneran.”
Tapi Henny cepat sekali menangkap kejanggalan. “Kalau rapat di kantor, kenapa bisa pulangnya dianterin atasan? Bukannya kamu biasanya bawa mobil sendiri?” tanyanya penuh analisa, sambil melipat tangan di dada.
Aku membeku. Mata berkedip cepat, mencari celah jawaban. Iya juga ya… terus aku harus alasan apa sekarang?
Moana yang dari tadi memperhatikan ekspresi gugupku langsung bersorak. “Nah, kan ketahuan, cieee!” Ia menepuk-nepuk pundakku sambil ngakak, lalu refleks mengulurkan tangan ke Henny. Tanpa pikir panjang, Henny menepuknya balik. Toss mereka mendarat dengan bunyi keras, menandai keberhasilan mereka meledekku.
Aku hanya bisa menunduk sambil menghembuskan napas, pipi terasa panas terbakar malu.
** @ **
Pagi ini aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Baru saja jam kerja mulai, Roni datang dengan map di tangannya.
“Selamat pagi, Bu,” sapanya ramah. “Ini beberapa dokumen dari Pak Adrian. Hasil meeting kemarin. Beliau minta Ibu merapikannya jadi satu file.”
Aku tersenyum kecil, menerima map itu. “Baik, akan segera saya kerjakan.”
“Oh ya, satu lagi,” Roni menambahkan sambil menyesuaikan posisi kacamatanya. “Pak Adrian juga meminta Ibu menyiapkan bahan presentasi untuk pertemuan dengan klien dari Malaysia, dua hari lagi.”
Aku mengangguk lagi. “Baik.”
“Setelah jam istirahat, beliau minta Ibu datang ke ruangannya.”
“Baik, terima kasih.”
Begitu Roni pergi, aku langsung tenggelam dalam pekerjaan, berusaha menyelesaikan dengan rapi.
Siang hari, tepat setelah jam istirahat, aku berdiri di depan pintu ruang direktur. Nafasku kutahan sebentar, lalu ku ketuk pelan.
“Masuk,” suara berat itu terdengar jelas.
Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Rasanya seperti pertama kali masuk ke ruangan ini, seolah baru pertama kali berhadapan dengan Pak Adrian. Entah kenapa, grogi yang tak seharusnya ada malah menyerang.
“Silakan duduk,” ucapnya sopan namun tetap tegas.
Aku mengangguk, meletakkan tablet yang sudah penuh file di meja depannya, lalu duduk berhadapan.
“Semua sudah dikerjakan?” tanyanya sambil mulai membuka file dengan tangannya yang sigap.
“Sudah, Pak,” jawabku pelan.
“Baik. Saya periksa sebentar. Jika ada yang tidak tepat, revisi segera.” Suaranya tenang, tapi ada tekanan halus yang membuatku refleks menegakkan punggung.
Aku hanya bisa mengangguk lagi, sambil menunggu ia meneliti hasil kerjaku dengan jantung berdegup lebih kencang dari seharusnya.
“Semuanya rapi, tapi ada yang perlu diperbaiki,” katanya setelah selesai memeriksa file. Nada suaranya kembali tegas. Ia mengetuk layar. “Bagian analisis terlalu singkat. Tambahkan proyeksi minimal lima tahun ke depan. Klien Malaysia biasanya memperhatikan detail itu.”
Aku buru-buru mencatat. “Baik, Pak. Akan saya tambahkan.”
“Dan untuk penutup,” ia menatapku sekilas, “jangan terlalu formal. Buat lebih meyakinkan. Anggap saja kita bukan sekadar menawarkan kerja sama, tapi memberi solusi.”
Aku mengangguk. “Mengerti, Pak.”
Setelah mengucapkan terima kasih, aku berdiri dan melangkah keluar. Namun baru dua langkah, suara beratnya kembali memanggil.
“Akira.”
Aku menoleh cepat. “Ya, Pak? Ada yang lain?” tanyaku hati-hati.
Dia hanya menatapku. Diam. Ekspresinya sulit kutebak, antara serius atau… iba. Sekilas aku teringat, mungkin ini ada hubungannya dengan kondisiku yang terlanjur ia ketahui.
Beberapa detik kemudian, akhirnya ia bertanya, sederhana tapi membuatku kaku.
“Kamu sudah makan?”
Dahiku berkerut. “Sudah, Pak,” jawabku singkat, entah kenapa terasa canggung.
Dia mengangguk pelan, lalu kembali menatap berkas-berkas di mejanya. “Baik. Silakan kembali bekerja.”
Aku terdiam sejenak lalu membungkuk hormat sebelum benar-benar meninggalkan ruangan itu.
Jam pulang kerja sudah lewat, tapi aku masih duduk di kursi kerjaku. Melirik jam tangan, lalu kembali menatap layar ponsel. Jari-jariku sibuk menekan tombol game sederhana yang biasanya dimainkan anak-anak.
Saat suasana kantor semakin lengang, aku akhirnya beranjak dari kursi. Langkahku pelan, seolah setiap ayunan kaki ditahan oleh rasa waswas. Aku memang sengaja menunggu hingga kantor benar-benar sepi, hanya karena takut bertemu Pak Adrian di dalam lift.
Ya, aku takut jika harus satu lift lagi dengannya. Takut jika aku tidak bisa mengendalikan delusiku. Lalu dihantam serangan panik di ruang sempit itu. Sekadar membayangkan saja sudah membuat telapak tanganku dingin dan napasku terasa berat.
TING. Suara lift terbuka. Dan seketika nafasku tercekat.
Pak Adrian ada di sana.
Aku refleks mematung, mata membelalak. Degup jantungku langsung kacau. Namun, suara tawanya memecah suasana yang tegang. Ringan, tapi cukup untuk meruntuhkan kekakuanku.
"Saya pikir pulang belakangan tidak akan bertemu denganmu, Akira. Tapi tetap bertemu."
Aku masih terdiam, bingung harus menanggapi apa.
Ia menghela napas, lalu melangkah keluar dari lift. “Pakailah. Saya bisa lewat tangga.”
Aku menoleh, refleks. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Lalu ia melangkah pergi dengan tenang.
Entah kenapa, pandanganku tak bisa lepas. Mataku terus mengikuti punggungnya yang perlahan menjauh, hingga sosoknya benar-benar hilang dari pandangan.
Other Stories
Senja Terakhir Bunda
Sejak suaminya pergi merantau, Siska harus bertahan sendiri. Surat dan kiriman uang sempat ...
Blind
Ketika dunia gelap, seorang hampir kehilangan harapan. Tapi di tengah kegelapan, cinta dar ...
Ayudiah Dan Kantini
Waktu terasa lambat karena pahitnya hidup, namun rasa syukur atas persahabatan Ayudyah dan ...
Kala Cinta Di Dermaga
Saat hatimu patah, di mana kamu akan berlabuh? Bagi Gisel, jawabannya adalah dermaga tua y ...
Setinggi Awan
Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Awan tumbuh dengan mimpi besar. Ia i ...
Jika Nanti
Adalah sebuah Novel yang dibuat untuk sebuah konten ...