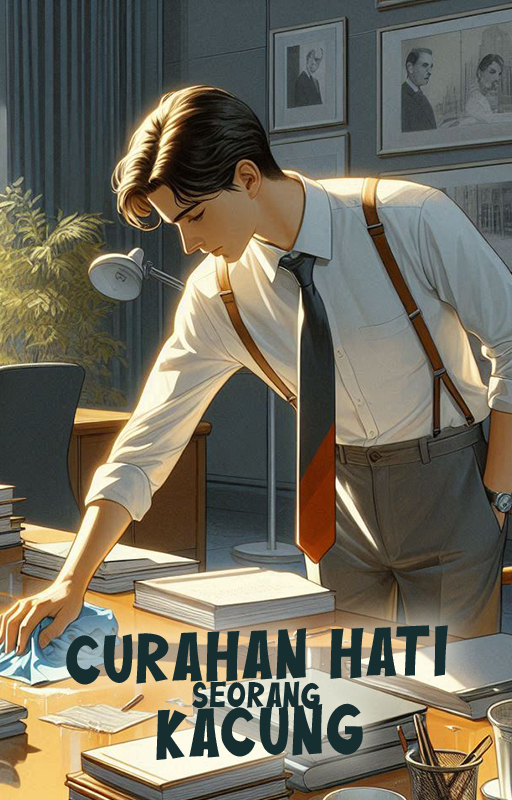Prolog
Kata orang, saat ada yang meninggal langit akan menghujani bumi
Ikut bersedih atasnya
Namun pagi itu langit begitu cerah
Matahari tanpa malu menatap Sekar
Yang berharap ia bersembunyi di balik kelabu awan
Yang tak kunjung datang
***
Sekar diam tak berkutik, mengabaikan sengatan matahari yang menerobos tajam kedalam kulitnya. Keringat yang menguap tak ia hiraukan—raganya seolah menolak semua rangsang dari luar. Hanya tertuju pada papan persegi panjang yang di kedua belah ujungnya cenderung runcing, salah satunya menyerupai atap rumah.
Sedangkan sisi lainnya menukik tajam. Terukir indah–seolah menyindir–nama Panji Erlangga lengkap dengan tanggal lahir dan wafat.
Selaput bening mata Sekar berganti adegan, memantulkan kotak besi hitam logam mulia mewah berlapis emas, yang tengah diturunkan enam lelaki lintas usia. Suara tanah jatuh satu genggam demi satu genggam. Seperti gemericik hujan yang salah tempat.
Sekar tidak menangis.
Tidak juga menjerit.
Bahkan ketika papan yang menarik perhatiannya, tegak memaku bumi.
Dia hanya berdiri, kaku, sementara orang-orang berkerumun di belakangnya dengan gelisah.
Mereka mencoba mendekat, menyentuh bahunya, memanggil namanya dengan suara hati-hati, tapi rasanya percuma. Satu per satu orang pergi, menyerah pada kesunyian yang menolak dipecahkan.
Tinggallah Arya, lelaki dipenghujung dua puluh—yang sejak tadi berusaha menahan cemasnya agar tidak tumpah. Ia terlihat seperti seseorang yang memaksa diri berdiri di tepi jurang, pura-pura tak gentar pada angin yang berhembus.
Betullah perkataan guru bahasa Indonesia—bangkai akan tercium juga. Cemas Arya tak lagi terelakkan. Langkah sedikit terseret kaku, menciptakan gemuruh kecil dari bebatuan dan tanah yang kakinya pijak.
Tak mungkin ia mematung saja saat menyaksikan istri Panji, sahabatnya sendiri, tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya.
Tanpa aba-aba, apalagi pengumuman.
Momen setelahnya, Arya kembali bergeming. Tak acuh pada posisi berdirinya yang canggung. Wajahnya kembali menolak cemas, ketika Sekar tertatih merayap–menghampiri gundukan tanah. Mencoba disisa tenaganya meraih gumpalah merah kecokelatan, kemudian digerusnya geram.
Arya menghelas napas panjang.
Menyaksikan pundak Sekar naik turun dengan tempo yang tak beraturan, beriringan dengan sorakan derita yang melengking.
Arya tak dapat mengelak gundahnya.
Berusaha menahan diri, tapi rasa takutnya mulai menetes sedikit demi sedikit ke dalam dada. Perlahan ia bergerak, menempatkan diri di belakang Sekar. Tangannya terulur, ragu. Sekali. Dua kali. Pada percobaan ketiga, ujung jarinya menyentuh bahu Sekar.
Tak ada reaksi.
Arya menggenggam sedikit lebih kuat.
Barulah Sekar menoleh.
Pelan sekali, seolah lehernya terbuat dari besi karatan.
Pandangan mereka bertemu. Mata Sekar gelap, pupilnya menyempit, memerangkap bayangan Arya di sana. Philtrum bibir atas Sekar–yang lebih kecil dibanding bibir bawahnya bergidik, lalu terlipat ke dalam, beberapa kali, seolah menguji rasa kata yang akan ia keluarkan.
“Kamu yang membunuhnya!”
Kata-kata itu jatuh seperti jarum di tengah sunyi.
Arya menegak, melepas genggaman.
Matanya terbuka lebih lebar, napasnya patah-patah. Alisnya yang menyerupai segitiga tak beraturan saling mendekat, bibir tebal dengan rambut tipis yang mengelilinginya terbuka lalu terkatup, berganti sayu seolah memahami tuduhan itu.
Tapi dia tidak membantah.
Hanya menatap Sekar dengan sorot yang tak bisa dipahami—entah pengakuan, entah penyangkalan yang terlalu lelah. Setelahnya, hanya mengulurkan tangan. Sekar menatapnya sesaat, lalu menerima uluran itu. Arya membantunya berdiri, memapah tubuh Sekar yang limbung menjauh dari pusara. Tak tahu apa yang akan terjadi di bawah sana, dalam perut bumi, sesuatu mulai bergerak.
Langkah pertama Sekar terayun, memicu kelopak Panji terbuka serentak. Bola mata terbalik, urat ungu merambat di sana seperti akar mati. Mulutnya ternganga patah-patah ke kiri dan kanan. Bergerak perlahan, menimbulkan suara gemeretak kayu.
Langkah kedua—tubuhnya melengkung, perlahan merayap pelan bagai ular. Lehernya bergerak ke belakang, berputar–menghasilkan suara derak yang tajam. Seakan sendi-sendinya menolak dihidupkan lagi. Wajahnya mengacuhkan bantal yang menjadi sandaran kepalanya. Mengambil alih, seolah bantal memang tercipta sebagai sandaran wajah.
Langkah ketiga—perutnya mengembang seperti balon, merobek jas hitam yang dipakaikan padanya dengan hormat. Menekan hebat perutnya—menampakkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana.
Sekar terus melangkah, dipapah Arya.
Tak tahu di kedalaman tanah, sesuatu yang seharusnya mati seolah-olah sedang berusaha bangkit.
Dan langit yang terlalu cerah, tetap menonton, tanpa berkedip.
Ikut bersedih atasnya
Namun pagi itu langit begitu cerah
Matahari tanpa malu menatap Sekar
Yang berharap ia bersembunyi di balik kelabu awan
Yang tak kunjung datang
***
Sekar diam tak berkutik, mengabaikan sengatan matahari yang menerobos tajam kedalam kulitnya. Keringat yang menguap tak ia hiraukan—raganya seolah menolak semua rangsang dari luar. Hanya tertuju pada papan persegi panjang yang di kedua belah ujungnya cenderung runcing, salah satunya menyerupai atap rumah.
Sedangkan sisi lainnya menukik tajam. Terukir indah–seolah menyindir–nama Panji Erlangga lengkap dengan tanggal lahir dan wafat.
Selaput bening mata Sekar berganti adegan, memantulkan kotak besi hitam logam mulia mewah berlapis emas, yang tengah diturunkan enam lelaki lintas usia. Suara tanah jatuh satu genggam demi satu genggam. Seperti gemericik hujan yang salah tempat.
Sekar tidak menangis.
Tidak juga menjerit.
Bahkan ketika papan yang menarik perhatiannya, tegak memaku bumi.
Dia hanya berdiri, kaku, sementara orang-orang berkerumun di belakangnya dengan gelisah.
Mereka mencoba mendekat, menyentuh bahunya, memanggil namanya dengan suara hati-hati, tapi rasanya percuma. Satu per satu orang pergi, menyerah pada kesunyian yang menolak dipecahkan.
Tinggallah Arya, lelaki dipenghujung dua puluh—yang sejak tadi berusaha menahan cemasnya agar tidak tumpah. Ia terlihat seperti seseorang yang memaksa diri berdiri di tepi jurang, pura-pura tak gentar pada angin yang berhembus.
Betullah perkataan guru bahasa Indonesia—bangkai akan tercium juga. Cemas Arya tak lagi terelakkan. Langkah sedikit terseret kaku, menciptakan gemuruh kecil dari bebatuan dan tanah yang kakinya pijak.
Tak mungkin ia mematung saja saat menyaksikan istri Panji, sahabatnya sendiri, tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya.
Tanpa aba-aba, apalagi pengumuman.
Momen setelahnya, Arya kembali bergeming. Tak acuh pada posisi berdirinya yang canggung. Wajahnya kembali menolak cemas, ketika Sekar tertatih merayap–menghampiri gundukan tanah. Mencoba disisa tenaganya meraih gumpalah merah kecokelatan, kemudian digerusnya geram.
Arya menghelas napas panjang.
Menyaksikan pundak Sekar naik turun dengan tempo yang tak beraturan, beriringan dengan sorakan derita yang melengking.
Arya tak dapat mengelak gundahnya.
Berusaha menahan diri, tapi rasa takutnya mulai menetes sedikit demi sedikit ke dalam dada. Perlahan ia bergerak, menempatkan diri di belakang Sekar. Tangannya terulur, ragu. Sekali. Dua kali. Pada percobaan ketiga, ujung jarinya menyentuh bahu Sekar.
Tak ada reaksi.
Arya menggenggam sedikit lebih kuat.
Barulah Sekar menoleh.
Pelan sekali, seolah lehernya terbuat dari besi karatan.
Pandangan mereka bertemu. Mata Sekar gelap, pupilnya menyempit, memerangkap bayangan Arya di sana. Philtrum bibir atas Sekar–yang lebih kecil dibanding bibir bawahnya bergidik, lalu terlipat ke dalam, beberapa kali, seolah menguji rasa kata yang akan ia keluarkan.
“Kamu yang membunuhnya!”
Kata-kata itu jatuh seperti jarum di tengah sunyi.
Arya menegak, melepas genggaman.
Matanya terbuka lebih lebar, napasnya patah-patah. Alisnya yang menyerupai segitiga tak beraturan saling mendekat, bibir tebal dengan rambut tipis yang mengelilinginya terbuka lalu terkatup, berganti sayu seolah memahami tuduhan itu.
Tapi dia tidak membantah.
Hanya menatap Sekar dengan sorot yang tak bisa dipahami—entah pengakuan, entah penyangkalan yang terlalu lelah. Setelahnya, hanya mengulurkan tangan. Sekar menatapnya sesaat, lalu menerima uluran itu. Arya membantunya berdiri, memapah tubuh Sekar yang limbung menjauh dari pusara. Tak tahu apa yang akan terjadi di bawah sana, dalam perut bumi, sesuatu mulai bergerak.
Langkah pertama Sekar terayun, memicu kelopak Panji terbuka serentak. Bola mata terbalik, urat ungu merambat di sana seperti akar mati. Mulutnya ternganga patah-patah ke kiri dan kanan. Bergerak perlahan, menimbulkan suara gemeretak kayu.
Langkah kedua—tubuhnya melengkung, perlahan merayap pelan bagai ular. Lehernya bergerak ke belakang, berputar–menghasilkan suara derak yang tajam. Seakan sendi-sendinya menolak dihidupkan lagi. Wajahnya mengacuhkan bantal yang menjadi sandaran kepalanya. Mengambil alih, seolah bantal memang tercipta sebagai sandaran wajah.
Langkah ketiga—perutnya mengembang seperti balon, merobek jas hitam yang dipakaikan padanya dengan hormat. Menekan hebat perutnya—menampakkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana.
Sekar terus melangkah, dipapah Arya.
Tak tahu di kedalaman tanah, sesuatu yang seharusnya mati seolah-olah sedang berusaha bangkit.
Dan langit yang terlalu cerah, tetap menonton, tanpa berkedip.
Other Stories
Testing
testing ...
Test
Test ...
The Ridle
Gema dan Mala selalu kompak bersama dan susah untuk dipisahkan. Gema selalu melindungi Mal ...
Kabinet Boneka
Seorang presiden wanita muda, karismatik di depan publik, ternyata seorang psikopat yang m ...
Curahan Hati Seorang Kacung
Saat sekolah kita berharap nantinya setelah lulus akan dapat kerjaan yang bagus. Kerjaan ...
Hati Yang Terbatas
Kinanti mempertahankan cintanya meski hanya membawa bahagia sesaat, ketakutan, dan luka. I ...