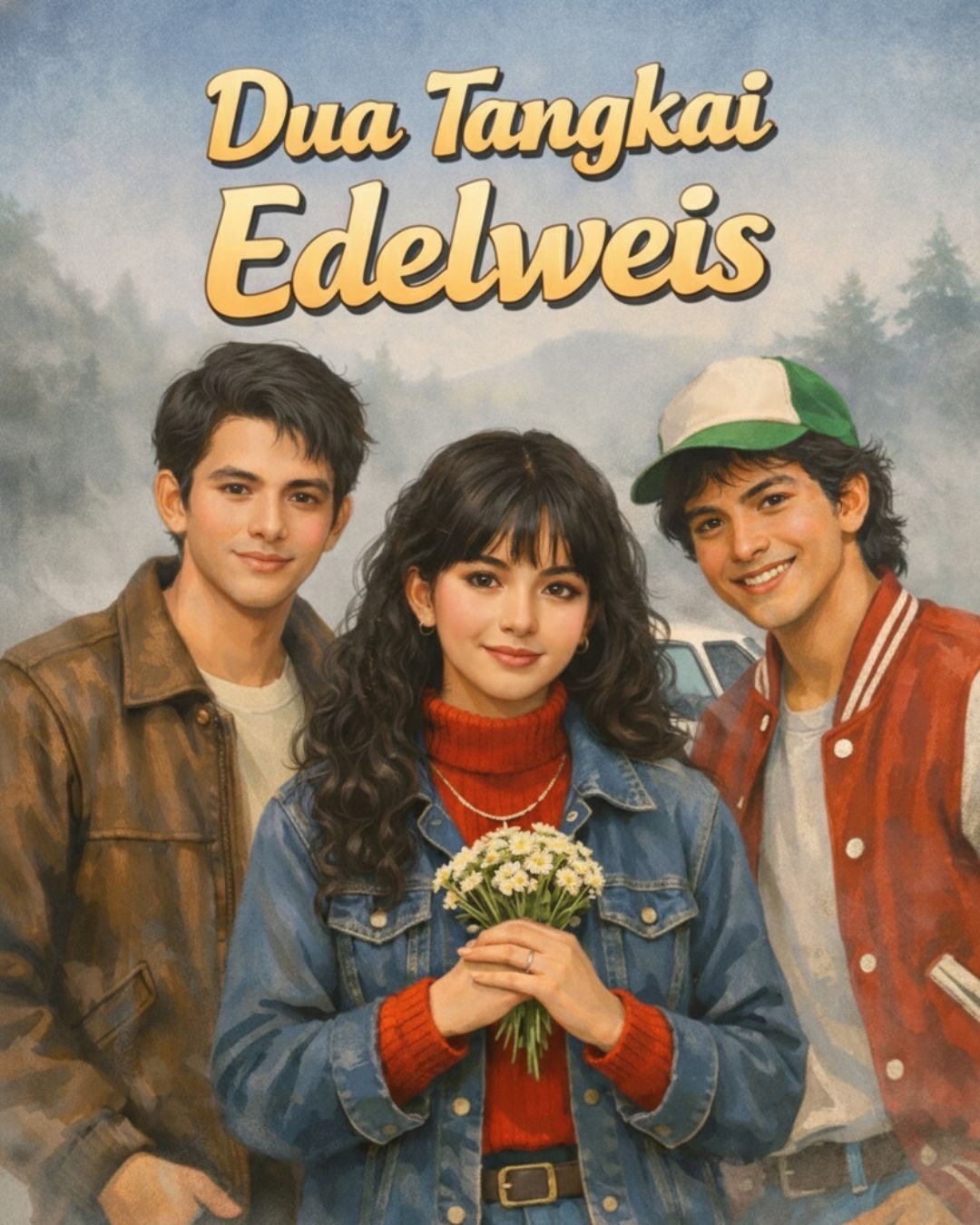TELEPON DARI CIANJUR
Beberapa bulan setelah Bagas dan keluarganya pulang ke Cianjur, hidup Rani kembali dipenuhi rutinitas.
Ia sudah duduk di bangku SMA.
Hari-harinya padat: sekolah, latihan, rapat, lomba, tugas, dan ekskul yang membuat waktunya terasa selalu kurang.
Ia jarang memikirkan Cianjur.
Bukan karena lupa—
tapi karena hidupnya terlalu ramai untuk memberi ruang pada satu kota kecil yang pernah begitu sunyi di hatinya.
Sore itu, hujan turun tipis di Cirebon.
Rani sedang mengerjakan tugas di kamar ketika telepon rumah berdering.
“Ibu!” panggil Ayah dari ruang tengah.
Ibu mengangkat.
Rani mendengar suara lirih Ibu dari balik pintu.
“Iya, Neng…”
“Iya…”
“Ya Allah…”
Ada jeda panjang.
Lalu langkah kaki Ibu mendekat ke kamar Rani.
“Ran…”
Nada itu membuat Rani berdiri.
“Ada apa, Bu?”
Ibu menatapnya. Matanya basah.
“Itu Bi Nadin.”
Rani menelan ludah.
“Kinkin… meninggal.”
Rani seperti tak mengerti arti kata itu.
“Meninggal?”
Ibu mengangguk pelan.
“Kata Bi Nadin, Kinkin kena demam berdarah. Telat dibawa ke rumah sakit… karena nggak punya cukup biaya.”
Kalimat itu seperti palu.
Dada Rani sesak.
Ia mundur selangkah, lalu duduk di tepi ranjang.
Dunia terasa terlalu sunyi.
Tanpa suara, Rani masuk ke lemari.
Menarik jaketnya.
Dan menemukan edelweis itu.
Ia memeluknya.
Dan tangisnya pecah.
Tangis yang selama ini ia simpan—tentang Cianjur, tentang Kinkin, tentang pagi berkabut dan janji kecil.
Dalam pelukan bunga kering itu, Rani belajar satu hal yang paling berat:
ikhlas.
Bukan karena ia siap,
tapi karena hidup memaksanya.
Ia sudah duduk di bangku SMA.
Hari-harinya padat: sekolah, latihan, rapat, lomba, tugas, dan ekskul yang membuat waktunya terasa selalu kurang.
Ia jarang memikirkan Cianjur.
Bukan karena lupa—
tapi karena hidupnya terlalu ramai untuk memberi ruang pada satu kota kecil yang pernah begitu sunyi di hatinya.
Sore itu, hujan turun tipis di Cirebon.
Rani sedang mengerjakan tugas di kamar ketika telepon rumah berdering.
“Ibu!” panggil Ayah dari ruang tengah.
Ibu mengangkat.
Rani mendengar suara lirih Ibu dari balik pintu.
“Iya, Neng…”
“Iya…”
“Ya Allah…”
Ada jeda panjang.
Lalu langkah kaki Ibu mendekat ke kamar Rani.
“Ran…”
Nada itu membuat Rani berdiri.
“Ada apa, Bu?”
Ibu menatapnya. Matanya basah.
“Itu Bi Nadin.”
Rani menelan ludah.
“Kinkin… meninggal.”
Rani seperti tak mengerti arti kata itu.
“Meninggal?”
Ibu mengangguk pelan.
“Kata Bi Nadin, Kinkin kena demam berdarah. Telat dibawa ke rumah sakit… karena nggak punya cukup biaya.”
Kalimat itu seperti palu.
Dada Rani sesak.
Ia mundur selangkah, lalu duduk di tepi ranjang.
Dunia terasa terlalu sunyi.
Tanpa suara, Rani masuk ke lemari.
Menarik jaketnya.
Dan menemukan edelweis itu.
Ia memeluknya.
Dan tangisnya pecah.
Tangis yang selama ini ia simpan—tentang Cianjur, tentang Kinkin, tentang pagi berkabut dan janji kecil.
Dalam pelukan bunga kering itu, Rani belajar satu hal yang paling berat:
ikhlas.
Bukan karena ia siap,
tapi karena hidup memaksanya.
Other Stories
Cerita Pendekku
Pada saat jatuh cinta, terdapat dua tipe orang dalam merespon perasaan tersebut. Ada yang ...
Hafidz Cerdik
Jarum jam menunjuk di angka 4 kurang beberapa menit ketika Adnan terbangun dari tidurnya ...
Senja Terakhir Bunda
Sejak suaminya pergi merantau, Siska harus bertahan sendiri. Surat dan kiriman uang sempat ...
Metafora Diri
Cerita ini berkisah tentang seorang wanita yang mengalami metafora sejenak ia masih kanak- ...
Kota Ini
Plak! Terdengar tamparan keras yang membuat Jesse terperanjat dari tempat tidurnya. "S ...
Rahasia Ikal
Ikal, bocah yang lahir dari sebuah keluarga nelayan miskin di pesisir Pulau Bangka. Ia tin ...