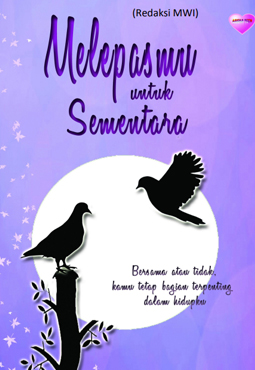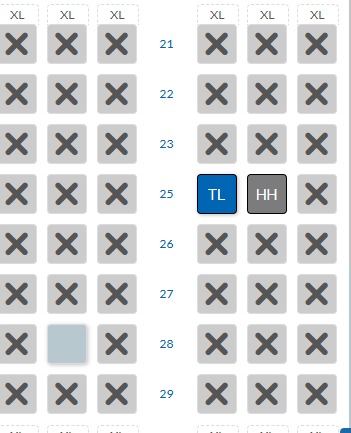Masalah Utama Manusia Berkepala Tiga: Tidak Peduli Seberapa Banyak Uang Di Rekening, Tak Akan Berguna Bila Belum Menikah
Masalah Utama Manusia Berkepala Tiga: Tidak Peduli Seberapa Banyak Uang di Rekening, Tak Akan Berguna Bila Belum Menikah
“Mau sampai kapan kamu akan sendiri terus?”
Pertanyaan sang mama membuat pria kepala tiga, berkacamata, dan sedang duduk di depan laptop hitam tersebut menghela napas panjang. Seolah-olah dia sudah menduga kalau cepat atau lambat mamanya akan mengeluarkan kalimat tersebut.
“Mama ini semakin hari tidak semakin muda lho, Ga. Mama ingin sekali sebelum meninggal bisa melihat kamu menikah, punya anak dan hidup bahagia.”
Sambil memutar-mutar cangkir putih berisi kopi di atas meja, Arga menjawab seadanya, “Aku bahagia kok, Ma.”
“Dengan tinggal sendirian di dalam apartemen sempit yang nyaris tidak pernah kamu bersihkan itu? Yang seperti kapal pecah itu?” ulang Bu Fatimah, terdengar seperti tikaman langsung di dada Arga.
Namun, mamanya benar, karena begitu Arga menoleh ke sekeliling ..., suasana apartemennya memang kotor –meski tidak sampai bisa dibilang kapal pecah juga.
Pakaian berserakan di mana-mana, tumpukan piring dan gelas kotor di atas meja, serta bunga-bunga layu yang tertata di dalam pot-pot kecil yang berjejer di rak gantung.
Astaga! Arga bahkan tidak ingat jika dia memiliki mereka di rumahnya.
“Makanya, kamu itu sesekali keluarlah dari rumah,” lanjut Bu Fatimah dengan nada masih penuh omel. “Bagaimana kamu bisa punya pacar kalau setiap hari di rumah melulu? Masa kamu kalah sama si David?”
Arga menelan ludah, kecut. “Ma, ini bukan soal menang atau kalah. Lagian nggak ada yang berkompetisi di sini.”
“Itu, kan! Membantah terus kalau dibilangi orang tua,” gerutu Bu Fatimah. Wanita berjilbab panjang tersebut tampak mengacungkan sutil yang dia gunakan untuk menumis ke arah kamera, seakan mengancam sang putra. “Umurmu lho sudah berapa, Ga? Lihat itu si Rangga, dia menikah hampir delapan tahun.”
“Terus?”
“Kok malah terus?” Fatimah berkacak pinggang, matanya tertuju lurus ke kamera, tanda intimidasi. “Dengan menikah Rangga bisa punya kehidupan yang stabil. Setiap hari ada yang masakin, ada yang menemani dan yang paling penting ..., rumahnya tidak kempros seperti apartemenmu yang mirip kandang babi itu.”
Arga mendesis, kesal tetapi tidak bisa menjawab. Lebih tepatnya dia paham betul kalau apa pun yang keluar dari mulutnya sekarang akan selalu salah, dan alih-alih menyelesaikan masalah, malah akan membuatnya dapat balasan berkali-kali lipat dari wanita yang telah menyebabkan dia ada di dunia ini.
“Memang kamu tidak mau kalau malam ada teman cerita? Teman berbagi keluh?” Nada bicara Fatimah kembali menurun, serius tetapi karena sambil memasak, wajah wanita itu kini tidak kelihatan.
“Kalau cuma berbagi cerita sih aku nggak butuh ya, Ma. Kan aku bisa menyalurkan semuanya ke novel-novelku. Dibayar pula.”
Bu Fatimah mengulang ancamannya, kali itu menggunakan pisau dapur. “Anak ini, ada saja alasannya! Ya pasti beda tho, Mas Argantara Ramadhani. Menulis kan untuk publik, sementara pasangan cuma buat dirimu sendiri. Bisa kasih masukan. Bisa merawat kamu kalau sakit. Dan yang paling penting ..., memang kamu nggak mau punya anak?”
BOOM!
Arga kembali meletakkan punggungnya ke sofa, lalu memutar bola matanya malas. Bukan apa, karena dia lebih khatam lagi akan dibawa ke mana obrolan ini oleh sang bunda.
“Mama kan juga ingin seperti Bu Nur. Pagi-pagi merawat cucu, gendong cucu, ajak main cucu. Padahal si Ferdi jauh lebih muda dari kamu, tapi dia sudah jadi bapak anak satu, sementara kamu?“
“Ya kan aku belum ada pasangan, Ma. Masa mau buat anak?”
“Makanya, cari dong!” Bu Fatimah memasang air muka sedih, bahkan agar lebih meyakinkan wanita itu berpura-pura menyeka air mata. Yang sayangnya, langsung Arga sadari sebagai drama minggu pagi rutin ala mamanya.
Bukannya Arga jahat apalagi menuduh tanpa bukti, tetapi sebaliknya, pria tiga puluh tahun itu paham benar betapa hebat kemampuan akting wanita kepala enam tersebut. Toh, omong-omong cucu ..., mamanya telah mendapatkan itu belasan tahun lalu.
“Keponakanmu kan sudah besar semua. Nggak bisa digendong-gendong.” Begitulah alasan Bu Fatimah.
Yang akan Arga balas dengan, “Ya sudah, Mama tunggu saja anak dari David.”
“Ya bukan cucu dong namanya.”
“Sama saja, Ma. Cucu sama buyut.”
♥♥♥
Apakah Arga tidak mau menikah?
Jawabannya, tentu saja ingin. Hanya saja, tidak bisa.
Bukan karena dia memiliki orientasi seksual berbeda sehingga tidak bisa menikah legal di negara tercinta, atau karena dia takut berumah tangga, atau malah tidak ada wanita yang mau dia nikahi –untuk poin terakhir bisa dibilang sebaliknya. Ada banyak perempuan muda, terutama yang menjadi pembacanya, tidak hanya menyukai Arga sebagai seniman tetapi juga secara romantis.
Sayang seribu sayang, cinta Arga telah berakhir. Habis pada sosok perempuan yang fotonya terpajang di dinding apartemennya.
Bella punya mata yang sangat indah, tubuh mungil dan kulit sawo matang khas perempuan Jawa.
Di dalam potret yang Arga pajang, Bella tampil sempurna dalam balutan seragam putih abu-abu penuh coretan warna-warni, rambut basah oleh hujan dan membiarkan Arga merangkul pundaknya. Tubuh mungil itu, terlalu pendek untuk Arga yang punya tinggi seratus delapan puluh dua senti, tetapi entah mengapa terasa pas dan hangat untuk dipeluk.
“Mau sampai kapan kamu terus begini?” Ucapan Bu Fatimah lagi-lagi membuyarkan lamunan Arga. Kali itu, sang mama mendelik di depan kamera, membuat ponsel pintar Arga penuh dengan wajah keriput wanita bermata sipit tersebut. Yang hampir membuat Arga jantungan saking kagetnya. Yang apesnya, saat dia mengeluh alih-alih dapat ucapan maaf malah dibalas oleh Bu Fatimah dengan, “Salah sendiri kenapa bengong! Masih untung tidak kesambet setan penunggu apartemen.”
♥♥♥
Omong-omong setan apartemen, Arga terkadang membayangkan alangkah indah hidupnya andai saja mendadak muncul arwah penasaran di unitnya, tetapi bukan hantu seram melainkan gadis cantik seperti di film dan novel romansa yang dia baca, lalu tak perlu jatuh cinta, tak perlu pendekatan. Kemudian dengan keajaiban makhluk itu berubah menjadi manusia dan hidup bahagia selamanya bersama dirinya.
“Premis yang terlalu pasaran.” Mbak Indah, editor sekaligus sahabat Arga, yang sudah menemani karier menulisnya lima belas tahun terakhir menolak mentah-mentah ide tersebut, bahkan sebelum Arga menyelesaikan ceritanya. “Lo sudah pernah tulis cerita kayak gini sepuluh tahun lalu.”
“Ya kan itu sepuluh tahun lalu, sekarang kita bikin beda di eksekusinya.”
Mbak Indah menggeleng, tegas. “Jangan aneh-aneh, Arga. Pembaca lo itu bukan pembaca yang suka mengulang. Mereka akan langsung tahu. Novel terakhir lo saja dapat kritikan pedas gara-gara dianggap merombak novel lama. Mau berapa kali lo membuat ulang cerita bagus buat jadi cerita yang –ya kalau lebih bagus, kalau lebih jelek? Mau jadi Disney lo?”
Arga berdecak, pelan. “Nggak separah itu juga kali, Mbak.”
“Memang, tapi ini sangat buruk buat karier menulis lo.” Indah meralat, penuh tekanan di setiap kata yang dia ucapkan, menandakan seberapa besar kekecewaan yang dia rasakan, dan itu cukup untuk membikin Arga seketika terdiam. “Lo sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tulisan lo terasa ..., hampa?”
“Hampa apanya sih, Mbak?” kilah Arga sembari membetulkan kaca mata yang nangkring di hidung mancungnya. “Gue nggak menulis, salah. Gue menulis, masih salah.”
“Ini bukan hanya soal menulis, Ga!” tegas Indah, sebal. “Gue mendampingi lo bukan sehari atau dua hari. Gue paham betul tulisan lo ..., cara bertutur, pilihan diksi sampai rasa yang lo berikan ke dalam cerita.
“Cerita lo memang masih laris, gue akui itu. Lo punya nama besar, basis penggemar dan orang-orang yang percaya sama tulisan lo. Tapi mau sampai kapan lo membohongi mereka dengan menjejalkan tulisan-tulisan yang kosong?”
Arga bergeming. Karena dia pun tak bisa mengelak. Pernyataan Mbak Indah seratus persen benar.
“Kita semua memang di masa yang sulit sekarang,” lanjut Mbak Indah, penuh empati. “Setahun ini semua menjadi sangat sulit. Nggak bisa keluar rumah, banyak keluarga dan teman yang meninggal dunia, tapi bukan berarti hidup berhenti.”
Untuk perkara keluar rumah, sebenarnya tidak perlu ada yang dicemaskan. Toh, sejak sebelum pandemi pun Arga memang sudah jarang keluar rumah. Dia terlalu nyaman dengan kursi kayu, meja makan dan laptop hitam miliknya, ditemani secangkir kopi hitam tanpa gula, yang sesekali dipadukan dengan camilan buatan rumah, yang dikirimkan oleh mama dan teman-temannya.
♥♥♥
“Anggap saja itu cara yang bisa kami gunakan untuk memastikan bahwa lo masih hidup,” kata Rian, sahabatnya, saat mereka tersambung di panggilan bersama. Malam yang sama setelah sebungkus biskuit cokelat dan makanan lainnya datang ke apartemen Arga, yang langsung dia nikmati sebagai teman ngopi di balkon apartemen yang tinggi dan ditemani angin dingin pandemi yang kering nun dipenuhi duka.
“Jujur, kami takut kalau lo mendadak ditemukan mati di apartemen.” Rangga, cowok berpenampilan kalem yang muncul dengan baju koko warna cokelat tua menyambung dengan nada tak kalah dramatis. “Tahu-tahu, begitu ditemukan sudah membusuk atau malah jadi kerangka tanpa bisa dikenali.”
“Hsst!” Annisa, istri Rangga tampak memukul bahu suaminya, meminta pria itu tidak melanjutkan ucapannya, lalu menoleh ke kamera. “Mas Arga, sudah! Nggak usah didengarkan! Mulut dia memang nggak bisa dikontrol.”
“Bohong dia, Mas! Beneran itu!” Rian, yang sibuk membuat makan malam, mendadak muncul di depan kamera yang sebelumnya hanya menyorot meja dapur, lengkap dengan celemek merah muda bergambar Mickey and Minnie Mouse serta mangkuk besar yang dipinggirnya terdapat adukan kue. “Wah, parah banget nyumpahin orang mati lo, Ngga!”
“Astagfirullah, bukan nyumpahin, Ian. Cuma antisipasi.”
“Alah! Masa?” canda Rian, meyakinkan. “Iya, Sayang! Apa?” Dia berkata ke arah lain, menyusul suara lembut bocah tiga tahun yang memanggil namanya. “Sini! Ada Om dan Tante.”
Benar saja, tidak lama muncul bocah mungil berambut hitam tebal yang dihiasi pita merah muda di tampilan layar, melambaikan tangan untuk menyapa mereka.
“Halo, Om Aga, Om Angga, Om Fledi dan Ate Ica!” sapa si bocah, cukup lancar meski belum begitu jelas. “Ia, mamam.” Dia memamerkan buah tomat segar ke kamera, lalu memasukkannya ke dalam mulut, membuat semua orang dewasa di panggilan otomatis tersenyum.
“Enak, Sayang?” tanya Annisa, dijawab anggukan penuh keyakinan oleh Daniar. “Tante minta, boleh?”
“Idak.” Daniar menggeleng. “Ini cudah acu mamam.” Lalu, menoleh pada ayahnya. “Ambi balu uat Ate Ica, Ayah?”
“Pintarnya!” puji Ferdi, pria lain dalam panggilan yang juga sedang menggendong bayi merah, satu dari dua manusia bergelar ayah di grup mereka. “Kalau Om boleh minta, Niar? Adik bayi boleh minta?”
Daniar kecil kembali menggeleng. “Idak. Dedek ayi kecil. Idak boleh mamam omat. Om Aga, mamam? Om aga, Ia angen! Cini!”
Arga yang sejak tadi menonton sontak mengembangkan senyum tatkala namanya disebut. “Iya, Sayang. Besok ya. Om masih belum bisa keluar.”
“Tenapa?” Si bocah terlihat kecewa.
Terdengar suara lain tanpa sosok dari komputer. “Kan masih pandemi. Nanti, kalau sudah selesai isolasi, Om Arga pasti ke sini. Ya kan, Om?” Yang dimaksud muncul ke kamera, mencubit pipi Daniar sebelum duduk di depan kamera. Bella tersenyum lebar, menampilkan tawa khasnya. Seketika, Arga merasa dunianya berhenti. “Bagaimana, Mas? Sudah keluar hasilnya? Sudah negatif?” lanjut Bella, serius dan penuh kekhawatiran. “Mas Arga? Mas? Mas melamun ya?”
Arga menggeleng, cepat. “Eh, sorry, Bell. Belum. Cuma gejalanya sudah sangat mendingan.”
“Oh, syukurlah kalau begitu. Mau aku kirimi makanan, nggak? Biar semakin cepat pulih.”
“Boleh?”
“Kenapa, nggak?” Bella tersenyum, lagi. Dan sialnya, berhasil membuat jantung Arga berdegup tak karuan.
Tak peduli berapa lama pun Arga berusaha membunuh perasaan ini, dia selalu gagal. Hanya butuh satu senyuman, maka seluruh pertahanan yang sudah Arga bangun dalam setahun akan hancur berkeping-keping. Meski begitu, dia paham posisinya, terlebih baik Bella maupun Rian, keduanya sama-sama sahabatnya.
“Oh iya, Bell, ternyata sudah berapa minggu?” tanya Annisa.
Yang ditanya tersenyum malu-malu, tidak langsung menjawab.
“Apanya?” Arga ikut bertanya, bingung. Akan tetapi, begitu dia menyadari semua orang di layar tersenyum, dia langsung mengarahkan pandangannya ke arah Bella. “Kamu hamil, Bell?”
Hanya anggukan kecil yang Bella berikan.
Namun Rian dengan bangga menambahkan. “Yup. Tiga minggu. Sebesar biji kacang hijau.”
“Acang ijo?” Daniar menempelkan tangan kotornya ke pipi Rian, yang langsung dilap oleh ayah dua anak itu menggunakan tisu.
“Iya, Sayang. Adik kamu sebesar kacang hijau.”
“Dedek bayi? Cepelti Adik Aden?”
Rian mengangguk, mencium pipi buah hatinya. Lalu, membawa bocah itu menjauhi kamera, menggendongnya ke wastafel untuk mencuci tangan. Arga tahu dari suaranya, suara air yang mengalir juga canda tawa ayah dan anak yang terdengar begitu renyah, juga indah.
Namun, alih-alih bahagia, jantung Arga malah terasa sangat nyeri. Seperti ada pedang panjang yang baru saja dihunuskan di sana. Sayangnya, tidak ada luka terbuka. Tidak ada yang tahu cara menambalnya.
Andai ..., andai saja dulu dia lebih berani. Mungkinkah tempat itu harusnya dia yang isi?
Other Stories
Testing
testing ...
Bunga Untuk Istriku (21+)
Laras merasa pernikahannya dengan Rendra telah mencapai titik jenuh yang aman namun hambar ...
Melepasmu Untuk Sementara
Menetapkan tujuan adalah langkah pertama mencapai kesuksesanmu. Seperti halnya aku, tahu ...
Kasih Ibu #1 ( Hhalusinada )
pengorbanan seorang ibu untuk putranya, Angga, yang memiliki penyakit skizofrenia. Ibu rel ...
Diary Anak Pertama
Sejak ibunya meninggal saat usianya baru menginjak delapan tahun, Alira harus mengurus adi ...
Jjjjjj
ghjjjj ...