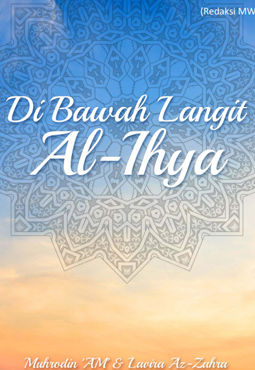Bab 3: Debu-Debu Fatih
Pagi di distrik Fatih selalu terasa berbeda. Jika Uskudar adalah ketenangan Asia, maka Fatih adalah denyut nadi sejarah Eropa yang konservatif. Aroma roti Simit yang baru keluar dari pemanggangan bercampur dengan bau kopi Turki yang pekat, menciptakan simfoni aroma yang menggugah selera. Namun, Fatimah tidak punya waktu untuk mampir ke kedai roti mana pun. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 08.45. Ia punya waktu lima belas menit sebelum "hukuman" keterlambatan dari Emir Arslan jatuh padanya.
Lokasi restorasi itu berada di sebuah madrasah peninggalan abad ke-16 yang tersembunyi di gang sempit di belakang Masjid Fatih. Bangunan itu tampak ringkih, dengan perancah besi yang memeluk dinding-dinding batunya yang mulai keropos.
Fatimah merapikan jilbabnya, mengenakan helm proyek putih yang terasa agak kebesaran di kepalanya, dan melangkah masuk. Di dalam, debu kapur beterbangan di bawah sorot lampu kerja yang temaram. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria yang sedang menatap serius ke sebuah dinding yang setengah hancur.
"Kurang dari delapan menit. Kau belajar dengan cepat, Fatimah," ucap Emir tanpa menoleh.
Pendengarannya tajam, atau mungkin ia sudah hafal dengan langkah kaki Fatimah yang ragu-ragu.
Fatimah mengatur napasnya. "Saya tidak ingin memberikan kesan buruk pada hari pertama kerja lapangan, Emir Bey."
Emir berbalik. Kali ini ia tidak memakai mantel panjangnya, melainkan kemeja flanel kotak-kotak dengan lengan yang digulung hingga siku, menampakkan jam tangan kulit yang tampak klasik. "Bagus. Ambil buku catatanmu. Hari ini kita tidak menggambar. Kita mendengarkan dinding ini bicara."
Selama tiga jam berikutnya, Fatimah menyadari bahwa Emir Arslan bukan sekadar arsitek; ia adalah seorang tabib bagi bangunan tua. Emir menunjukkan celah-celah kecil pada fondasi, menjelaskan bagaimana kelembapan Istanbul selama ratusan tahun perlahan-lahan memakan struktur bangunan tersebut.
"Lihat ini," Emir menunjuk ke arah hiasan muqarnas (ornamen sarang lebah) di sudut langit-langit. "Seseorang mencoba memperbaikinya tahun 1980-an dengan semen modern. Itu adalah kesalahan fatal. Semen tidak bernapas. Ia justru mencekik batu aslinya."
Fatimah mencatat setiap kata dengan tekun. "Jadi, kita harus membongkarnya dan menggantinya dengan mortar tradisional?"
"Tepat. Kita menggunakan campuran kapur, pasir, dan telur putih—seperti yang dilakukan para leluhur. Kita tidak sedang membangun yang baru, Fatimah. Kita sedang menyembuhkan yang lama agar ia bisa bertahan seratus tahun lagi."
"Tepat. Kita menggunakan campuran kapur, pasir, dan telur putih—seperti yang dilakukan para leluhur. Kita tidak sedang membangun yang baru, Fatimah. Kita sedang menyembuhkan yang lama agar ia bisa bertahan seratus tahun lagi."
Fatimah menatap Emir dengan kagum yang tak sengaja terpancar dari matanya. Cara pria itu menyentuh permukaan batu dengan ujung jarinya seolah-olah ia sedang menyentuh sesuatu yang bernyawa. Ada rasa hormat yang mendalam terhadap sejarah.
"Mengapa Anda begitu peduli pada hal-hal yang hampir runtuh seperti ini?" tanya Fatimah pelan, saat mereka beristirahat sejenak di pelataran madrasah.
Emir mengambil botol air mineral, meminumnya sedikit, lalu menatap ke langit Fatih yang biru cerah. "Karena dunia ini sudah terlalu penuh dengan hal-hal baru yang tidak punya jiwa. Orang-orang membangun gedung tinggi dari kaca dan baja hanya untuk pamer kekuatan. Tapi bangunan tua ini... mereka punya doa di setiap susunan batunya. Madrasah ini dulu tempat orang belajar Al-Qur'an dan sains. Jika kita membiarkannya runtuh, kita juga membiarkan sebagian dari identitas kita hilang."
Ia kemudian menatap Fatimah. "Sama seperti manusia, Fatimah. Kadang kita harus melihat ke belakang untuk tahu ke mana kita harus melangkah ke depan."
Suasana yang hangat itu tiba-tiba berubah ketika seorang mandor bangunan datang dengan wajah panik. Ia berbicara dalam bahasa Turki yang sangat cepat kepada Emir. Fatimah hanya menangkap kata "Problem" dan "Tehlike" (bahaya).
Emir segera bangkit dan berlari menuju bagian belakang madrasah. Fatimah mengikuti dari belakang dengan perasaan waswas. Di sana, sebuah bagian dinding penyangga tampak retak lebih lebar setelah para pekerja mencoba memindahkan puing-puing di bawahnya. Suara gemertak batu yang bergeser terdengar mengerikan.
"Semua keluar! Dışarı!" teriak Emir kepada para pekerja.
Keadaan menjadi kacau. Dalam kepanikan itu, seorang pekerja muda tersandung kabel lampu dan terjatuh tepat di bawah retakan dinding yang tampak akan runtuh. Tanpa berpikir panjang, Fatimah berlari mendekat, mencoba membantu pekerja itu berdiri.
"Fatimah! Jangan!" teriak Emir.
Brak!
Beberapa bongkah batu kecil jatuh dari atas. Fatimah berhasil menarik lengan pekerja itu tepat sebelum tumpukan debu dan kerikil menimbun tempat mereka berdiri tadi. Namun, kaki Fatimah terkilir saat ia mencoba melompat menghindar. Ia terduduk di tanah, meringis kesakitan, debu menutupi jilbab marunnya yang bersih tadi pagi.
Emir segera menghampirinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak pucat dan penuh amarah yang tertahan. Ia meraih bahu Fatimah, memastikan gadis itu masih utuh.
"Apa kau gila?!" suara Emir meninggi, menggema di ruangan yang berdebu itu. "Kau bisa tertimbun! Arsitek itu menggunakan otak, bukan hanya keberanian yang ceroboh!"
Fatimah tertegun. Ia belum pernah melihat Emir seemosional ini. Mata cokelat itu tidak lagi teduh, melainkan berkilat tajam. "Saya... saya hanya ingin membantu, Bey. Orang itu dalam bahaya."
"Dan kau hampir membuat dirimu sendiri berada dalam bahaya yang lebih besar!" Emir memejamkan mata, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia menyadari suaranya terlalu keras. "Jangan pernah... jangan pernah lakukan itu lagi tanpa instruksi saya."
Emir kemudian berjongkok, melihat pergelangan kaki Fatimah yang mulai membiru. Tanpa permisi, ia memanggil salah satu asistennya untuk membawakan kompres es dan air.
Karena kaki Fatimah yang cedera, Emir bersikeras untuk mengantarnya pulang ke Uskudar. Awalnya Fatimah menolak karena merasa tidak enak, namun tatapan tajam Emir membuatnya bungkam.
Mereka duduk di dalam mobil Volvo tua milik Emir yang bersih dan beraroma kayu cendana. Perjalanan dari Fatih menuju Uskudar melewati Jembatan Galata terasa sangat sunyi. Fatimah menunduk, memainkan ujung jilbabnya yang kotor.
"Maafkan saya," bisik Fatimah akhirnya.
Emir yang sedang menyetir tetap menatap lurus ke depan. "Untuk apa?"
"Karena sudah ceroboh. Dan membuat Anda marah."
Emir menghela napas. Keheningan kembali menyelimuti mereka sampai mobil berhenti di depan gerbang asrama Fatimah. Emir tidak langsung membiarkannya turun. Ia mematikan mesin mobil.
"Tadi itu... saya tidak marah padamu, Fatimah," ucap Emir dengan nada yang jauh lebih lembut. "Saya hanya... takut. Istanbul sudah terlalu banyak mengambil hal-hal yang berharga dari hidup saya. Saya tidak ingin melihat hal buruk terjadi pada seseorang yang baru saja mulai mencintai kota ini."
Fatimah menatap profil samping wajah Emir. Di bawah cahaya lampu jalan, pria itu tampak begitu rapuh. "Apa yang diambil Istanbul dari Anda, Emir Bey?"
Emir menoleh. Untuk pertama kalinya, ia memberikan senyuman yang sangat tipis, senyuman yang penuh luka. "Mungkin suatu hari nanti, saat kau sudah bisa menyebut nama 'Istanbul' tanpa merasa asing, aku akan menceritakannya padamu."
Ia turun dari mobil dan membantu Fatimah keluar, meskipun Fatimah bersikeras bisa berjalan sendiri dengan tertatih.
"Terima kasih atas segalanya, Emir Bey," ucap Fatimah saat mereka sampai di depan pintu masuk.
"Obati kakimu. Besok jangan ke lokasi dulu. Kerjakan laporan risetmu di perpustakaan asrama saja," perintah Emir, kembali ke mode bosnya yang disiplin. "Dan Fatimah?"
"Ya?"
"Warna marun cocok untukmu. Tapi mungkin besok pakailah warna yang lebih gelap, agar debu tidak terlalu terlihat."
Fatimah merasakan wajahnya memanas. Ia segera berbalik dan masuk ke dalam gedung asrama tanpa berani menoleh lagi. Di dalam kamarnya, ia menyandarkan punggung di balik pintu, jantungnya berdebu—sama seperti pakaiannya. Bukan karena debu bangunan, tapi karena getaran aneh yang mulai merayap di hatinya.
Di sisi lain, di dalam mobilnya yang masih terparkir sebentar, Emir Arslan memegang kemudi dengan erat. Ia melihat ke arah jendela asrama lantai tiga yang lampunya baru saja menyala.
"Gadis Indonesia itu... dia punya mata yang sama dengan Ibuku," gumam Emir pelan sebelum menginjak gas dan menghilang di kegelapan malam Uskudar.
Malam itu, Fatimah menulis di buku hariannya, tepat di bawah sketsa pintu Masjid Suleymaniye:
Istanbul bukan hanya tentang menara yang tinggi. Istanbul adalah tentang fondasi yang tersembunyi. Hari ini aku belajar bahwa luka di masa lalu bisa membuat seseorang membangun dinding yang sangat tebal di sekeliling hatinya. Ya Allah, jaga hatiku agar tidak lancang memasuki ruang yang belum diizinkan-Mu.
Ia menutup bukunya, lalu melakukan sujud syukur. Di tanah dua benua ini, ia mulai menyadari bahwa setiap bata yang ia pelajari memiliki cerita, dan setiap pertemuan memiliki makna yang telah digariskan oleh Al-Khaliq.
Lokasi restorasi itu berada di sebuah madrasah peninggalan abad ke-16 yang tersembunyi di gang sempit di belakang Masjid Fatih. Bangunan itu tampak ringkih, dengan perancah besi yang memeluk dinding-dinding batunya yang mulai keropos.
Fatimah merapikan jilbabnya, mengenakan helm proyek putih yang terasa agak kebesaran di kepalanya, dan melangkah masuk. Di dalam, debu kapur beterbangan di bawah sorot lampu kerja yang temaram. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria yang sedang menatap serius ke sebuah dinding yang setengah hancur.
"Kurang dari delapan menit. Kau belajar dengan cepat, Fatimah," ucap Emir tanpa menoleh.
Pendengarannya tajam, atau mungkin ia sudah hafal dengan langkah kaki Fatimah yang ragu-ragu.
Fatimah mengatur napasnya. "Saya tidak ingin memberikan kesan buruk pada hari pertama kerja lapangan, Emir Bey."
Emir berbalik. Kali ini ia tidak memakai mantel panjangnya, melainkan kemeja flanel kotak-kotak dengan lengan yang digulung hingga siku, menampakkan jam tangan kulit yang tampak klasik. "Bagus. Ambil buku catatanmu. Hari ini kita tidak menggambar. Kita mendengarkan dinding ini bicara."
Selama tiga jam berikutnya, Fatimah menyadari bahwa Emir Arslan bukan sekadar arsitek; ia adalah seorang tabib bagi bangunan tua. Emir menunjukkan celah-celah kecil pada fondasi, menjelaskan bagaimana kelembapan Istanbul selama ratusan tahun perlahan-lahan memakan struktur bangunan tersebut.
"Lihat ini," Emir menunjuk ke arah hiasan muqarnas (ornamen sarang lebah) di sudut langit-langit. "Seseorang mencoba memperbaikinya tahun 1980-an dengan semen modern. Itu adalah kesalahan fatal. Semen tidak bernapas. Ia justru mencekik batu aslinya."
Fatimah mencatat setiap kata dengan tekun. "Jadi, kita harus membongkarnya dan menggantinya dengan mortar tradisional?"
"Tepat. Kita menggunakan campuran kapur, pasir, dan telur putih—seperti yang dilakukan para leluhur. Kita tidak sedang membangun yang baru, Fatimah. Kita sedang menyembuhkan yang lama agar ia bisa bertahan seratus tahun lagi."
"Tepat. Kita menggunakan campuran kapur, pasir, dan telur putih—seperti yang dilakukan para leluhur. Kita tidak sedang membangun yang baru, Fatimah. Kita sedang menyembuhkan yang lama agar ia bisa bertahan seratus tahun lagi."
Fatimah menatap Emir dengan kagum yang tak sengaja terpancar dari matanya. Cara pria itu menyentuh permukaan batu dengan ujung jarinya seolah-olah ia sedang menyentuh sesuatu yang bernyawa. Ada rasa hormat yang mendalam terhadap sejarah.
"Mengapa Anda begitu peduli pada hal-hal yang hampir runtuh seperti ini?" tanya Fatimah pelan, saat mereka beristirahat sejenak di pelataran madrasah.
Emir mengambil botol air mineral, meminumnya sedikit, lalu menatap ke langit Fatih yang biru cerah. "Karena dunia ini sudah terlalu penuh dengan hal-hal baru yang tidak punya jiwa. Orang-orang membangun gedung tinggi dari kaca dan baja hanya untuk pamer kekuatan. Tapi bangunan tua ini... mereka punya doa di setiap susunan batunya. Madrasah ini dulu tempat orang belajar Al-Qur'an dan sains. Jika kita membiarkannya runtuh, kita juga membiarkan sebagian dari identitas kita hilang."
Ia kemudian menatap Fatimah. "Sama seperti manusia, Fatimah. Kadang kita harus melihat ke belakang untuk tahu ke mana kita harus melangkah ke depan."
Suasana yang hangat itu tiba-tiba berubah ketika seorang mandor bangunan datang dengan wajah panik. Ia berbicara dalam bahasa Turki yang sangat cepat kepada Emir. Fatimah hanya menangkap kata "Problem" dan "Tehlike" (bahaya).
Emir segera bangkit dan berlari menuju bagian belakang madrasah. Fatimah mengikuti dari belakang dengan perasaan waswas. Di sana, sebuah bagian dinding penyangga tampak retak lebih lebar setelah para pekerja mencoba memindahkan puing-puing di bawahnya. Suara gemertak batu yang bergeser terdengar mengerikan.
"Semua keluar! Dışarı!" teriak Emir kepada para pekerja.
Keadaan menjadi kacau. Dalam kepanikan itu, seorang pekerja muda tersandung kabel lampu dan terjatuh tepat di bawah retakan dinding yang tampak akan runtuh. Tanpa berpikir panjang, Fatimah berlari mendekat, mencoba membantu pekerja itu berdiri.
"Fatimah! Jangan!" teriak Emir.
Brak!
Beberapa bongkah batu kecil jatuh dari atas. Fatimah berhasil menarik lengan pekerja itu tepat sebelum tumpukan debu dan kerikil menimbun tempat mereka berdiri tadi. Namun, kaki Fatimah terkilir saat ia mencoba melompat menghindar. Ia terduduk di tanah, meringis kesakitan, debu menutupi jilbab marunnya yang bersih tadi pagi.
Emir segera menghampirinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak pucat dan penuh amarah yang tertahan. Ia meraih bahu Fatimah, memastikan gadis itu masih utuh.
"Apa kau gila?!" suara Emir meninggi, menggema di ruangan yang berdebu itu. "Kau bisa tertimbun! Arsitek itu menggunakan otak, bukan hanya keberanian yang ceroboh!"
Fatimah tertegun. Ia belum pernah melihat Emir seemosional ini. Mata cokelat itu tidak lagi teduh, melainkan berkilat tajam. "Saya... saya hanya ingin membantu, Bey. Orang itu dalam bahaya."
"Dan kau hampir membuat dirimu sendiri berada dalam bahaya yang lebih besar!" Emir memejamkan mata, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia menyadari suaranya terlalu keras. "Jangan pernah... jangan pernah lakukan itu lagi tanpa instruksi saya."
Emir kemudian berjongkok, melihat pergelangan kaki Fatimah yang mulai membiru. Tanpa permisi, ia memanggil salah satu asistennya untuk membawakan kompres es dan air.
Karena kaki Fatimah yang cedera, Emir bersikeras untuk mengantarnya pulang ke Uskudar. Awalnya Fatimah menolak karena merasa tidak enak, namun tatapan tajam Emir membuatnya bungkam.
Mereka duduk di dalam mobil Volvo tua milik Emir yang bersih dan beraroma kayu cendana. Perjalanan dari Fatih menuju Uskudar melewati Jembatan Galata terasa sangat sunyi. Fatimah menunduk, memainkan ujung jilbabnya yang kotor.
"Maafkan saya," bisik Fatimah akhirnya.
Emir yang sedang menyetir tetap menatap lurus ke depan. "Untuk apa?"
"Karena sudah ceroboh. Dan membuat Anda marah."
Emir menghela napas. Keheningan kembali menyelimuti mereka sampai mobil berhenti di depan gerbang asrama Fatimah. Emir tidak langsung membiarkannya turun. Ia mematikan mesin mobil.
"Tadi itu... saya tidak marah padamu, Fatimah," ucap Emir dengan nada yang jauh lebih lembut. "Saya hanya... takut. Istanbul sudah terlalu banyak mengambil hal-hal yang berharga dari hidup saya. Saya tidak ingin melihat hal buruk terjadi pada seseorang yang baru saja mulai mencintai kota ini."
Fatimah menatap profil samping wajah Emir. Di bawah cahaya lampu jalan, pria itu tampak begitu rapuh. "Apa yang diambil Istanbul dari Anda, Emir Bey?"
Emir menoleh. Untuk pertama kalinya, ia memberikan senyuman yang sangat tipis, senyuman yang penuh luka. "Mungkin suatu hari nanti, saat kau sudah bisa menyebut nama 'Istanbul' tanpa merasa asing, aku akan menceritakannya padamu."
Ia turun dari mobil dan membantu Fatimah keluar, meskipun Fatimah bersikeras bisa berjalan sendiri dengan tertatih.
"Terima kasih atas segalanya, Emir Bey," ucap Fatimah saat mereka sampai di depan pintu masuk.
"Obati kakimu. Besok jangan ke lokasi dulu. Kerjakan laporan risetmu di perpustakaan asrama saja," perintah Emir, kembali ke mode bosnya yang disiplin. "Dan Fatimah?"
"Ya?"
"Warna marun cocok untukmu. Tapi mungkin besok pakailah warna yang lebih gelap, agar debu tidak terlalu terlihat."
Fatimah merasakan wajahnya memanas. Ia segera berbalik dan masuk ke dalam gedung asrama tanpa berani menoleh lagi. Di dalam kamarnya, ia menyandarkan punggung di balik pintu, jantungnya berdebu—sama seperti pakaiannya. Bukan karena debu bangunan, tapi karena getaran aneh yang mulai merayap di hatinya.
Di sisi lain, di dalam mobilnya yang masih terparkir sebentar, Emir Arslan memegang kemudi dengan erat. Ia melihat ke arah jendela asrama lantai tiga yang lampunya baru saja menyala.
"Gadis Indonesia itu... dia punya mata yang sama dengan Ibuku," gumam Emir pelan sebelum menginjak gas dan menghilang di kegelapan malam Uskudar.
Malam itu, Fatimah menulis di buku hariannya, tepat di bawah sketsa pintu Masjid Suleymaniye:
Istanbul bukan hanya tentang menara yang tinggi. Istanbul adalah tentang fondasi yang tersembunyi. Hari ini aku belajar bahwa luka di masa lalu bisa membuat seseorang membangun dinding yang sangat tebal di sekeliling hatinya. Ya Allah, jaga hatiku agar tidak lancang memasuki ruang yang belum diizinkan-Mu.
Ia menutup bukunya, lalu melakukan sujud syukur. Di tanah dua benua ini, ia mulai menyadari bahwa setiap bata yang ia pelajari memiliki cerita, dan setiap pertemuan memiliki makna yang telah digariskan oleh Al-Khaliq.
Other Stories
Dante Fairy Tale
“Dante! Ayo bangun, Sayang. Kamu bisa terlambat ke sekolah!” kata seorang wanita gemu ...
Senja Terakhir Bunda
Sejak suaminya pergi merantau, Siska harus bertahan sendiri. Surat dan kiriman uang sempat ...
Di Bawah Langit Al-ihya
Tertulis kisah ini dengan melafazkan nama-Mu juga terbingkailah namanya. Berharap mega t ...
Hantu Dan Hati
Di tengah duka dan rutinitasnya berjualan bunga, seorang pemuda menyadari bahwa ia tidak s ...
KEDUNG
aku adalah dia yang tertutup ...
Pra Wedding Escape
Nastiti yakin menikah dengan Bram karena pekerjaan, finansial, dan restu keluarga sudah me ...