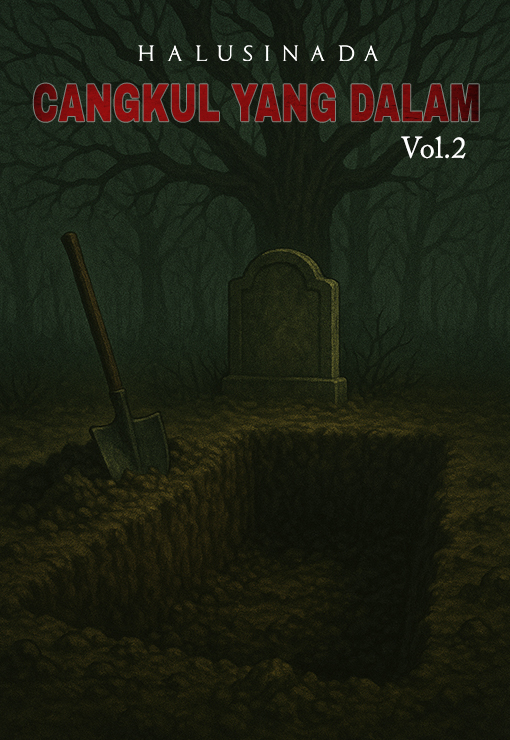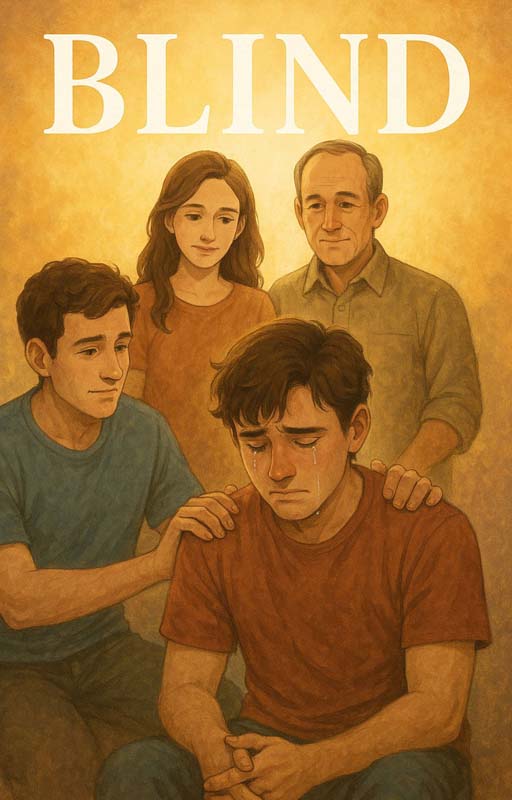15. Pendakian Gunung Fuji
Gunung Fuji atau Fujiyama merupakan gunung kebanggaan bangsa Jepang. Bangsa Jepang menyebutnya Fuji San sebagai bentuk penghormatan atas gunung berapi yang tingginya mencapai 3.776 meter itu. Rupanya yang cantik dan anggun menawan saat musim dingin, menjadikannya incaran pemburu foto tak hanya dari wisatawan luar negeri, tetapi juga wisatawan dalam negeri sendiri. Ya, bangsa Jepang memang terkenal sangat bisa menghargai keindahan alam dan budaya negerinya. Saat musim panas tiba, sekitar bulan Juli-Agustus, adalah waktu yang ditunggu-tunggu ribuan pengagumnya untuk bisa mencapai puncak Fuji San. Tentu saja karena hanya pada waktu musim panaslah Fuji San dibuka untuk umum sebagai objek wisata pendakian. Selain es yang menutupi puncaknya telah mencair, udara hangat di musim panas sangat mendukung proses pendakian ke puncak yang dinginnya menggigit.
Aku merupakan salah satu penggagum Fuji San yang merasa penting untuk bisa mencapai puncaknya. Dalam harap ada kebanggaan tersendiri bila berhasil mencapai puncak gunung yang mashyur di dunia dan akrab kudengar meski dalam bait lagu di masa kecilku. Yaa… aku memang mengabaikan usia dan menjadi terlalu yakin bisa menjalani pendakian gunung itu. Seorang sahabatku yang tengah study di Tokyo, Azra, telah berhasil memprovokasiku.
“Mba May kenapa ngga jadi ikut naik? Asyik lho Mba… katanya pengin naik Gunung Fuji?” sambil terkekeh khas Azra mencoba memengaruhiku.
“Iih... ya pengin bangeet… tapi kan itu pas aku deffend ujian tesisku! Btw… medannya susah ngga? Lagian kamu sudah pergi duluan... trus nanti aku sama siapa ke sananya?”
“Ngga usah takut Mba, jalannya luas dan landai. Banyak lho Mba nenek-nenek yang ndaki Fuji San. Masa Mba kalah sama nenek-nenek… heheheh,\" suara tawanya pecah. Sepertinya puas sekali bisa meledekku.
Azra dan beberapa teman pelajar Indonesia di Tokyo memang sudah melakukan pendakian Fuji San beberapa hari sebelumnya sehingga melihat sendiri apa dan bagaimana situasi dan kondisi yang dialami saat pendakian. Foto-foto aksinya di puncak Fuji San dengan latar belakang awan putih berada di bawah, sungguh telah membuatku tak bisa menahan keinginan untuk bisa merasakan kebanggaan serupa.
“Pergilah Mba... kabarnya rombongan Grips dan Keio juga mau naik... cuma belum tahu kapan pastinya. Nah, Mba tanya Hermes saja!\" Azra tampak serius menyampaikan kabar yang semakin menggairahkanku.
“Emang Hermes mau ikut naik?” sambutku cepat. Antara harap dan ragu. “Sepertinya dia bukan tipe yang hobi naik gunung?”
“Coba Mba hubungi dia saja... nanti nyesel lho Mba, kalo ketinggalan lagii... heheheh.”
***
Akhirnya bulatlah rencanaku menuju puncak Fuji. Terlebih setelah menghubungi Hermes bahwa benar rombongan yang terdiri dari gabungan mahasiswa Indonesia yang studi di GRIPS Tokyo dan Keio University Yokohama akan melakukan pendakian, dan Hermes ada dalam rombongan. Maka bertambah kuat niatku untuk menggapai puncak Fuji.
Persiapan sudah dilakukan. Tidak terlalu sulit buatku karena sudah beberapa kali melakukan kegiatan pendakian gunung “kecil-kecilan” ketika masih studi S1 di Bogor dulu bersama teman-teman korps palang merah mahasiswa. Ada beberapa gunung yang sempat kujajaki saat berada di Bogor, yaitu Gunung Gede dan Gunung Salak, meski hanya di kakinya. Ada juga Gunung Papandayan di Garut.
Gunung Papandayan Garut track-nya terbilang cukup mudah. Dengan melalui Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, setelah melewati kawah, dilanjutkan naik ke arah puncak maka akan sampai di Pondok Selada tempat di mana terdapat hamparan padang edelweis. Kala itu aku dan empat orang temanku berhasil membawa segenggam bunga abadi itu dari Pondok Salada, meski turunnya harus kucing-kucingan dengan petugas jaga. Mereka adalah anak-anak rimbawan dari Akademi Ilmu Kehutanan (AIK) Jatinangor, Bandung yang kemudian bertransformasi menjadi Universitas Winaya Mukti Bandung.
Demi bunga edelweis itu aku harus rela turun melalui jalan memutar dengan jarak tempuh lebih jauh, yaitu dari sisi arah Pangalengan Bandung Selatan. Track-nya tidak biasa dilewati pendaki dan harus melalui jalan yang terbentuk dari aliran air hujan.
Sesekali aku berhenti berjalan mengambil napas dan memandang ke arah bawah. Hamparan kebun teh terlihat bagai permadani hijau yang membentang luas. Sangat menggemaskan. Senyum terkembang dari bibir-bibir kami yang kering pucat oleh udara dingin. Rasanya ingin segera bisa mencapainya untuk berbaring meluruskan punggung yang pegal dan berat oleh ransel yang bergelayut sedari pagi. Atau sekadar mengusapnya lembut.
Segala harap dan lamunan indah tentang permadani hijau pudar setelah sampai di areal kebun teh. Aku menghentikan langkah yang setengah berlari menuruni jalan menuju kebun teh dan menjerit. Ulat bulu berwarna merah-hitam mencolok mondar-mandir berjalan cepat di jalanan tanah atau nangkring di tangkai dan dahan teh pada jalur yang akan kami lewati. Geli, aku bergidik. Menjerit dan menjerit setiap kali melihat ulat-ulat itu. Ternyata apa yang terlihat indah dari jauh belum tentu demikian adanya kala kita dekati.
Lama-lama aku tidak tahan dan ingin segera keluar dari areal perkebunan teh itu. Namun, luasnya lahan kebun membuat kami justru tersesat. Bukannya mendekati permukiman penduduk agar bisa segera menemukan angkutan umum yang bisa membawa kami menuju Kota Pangalengan, malah sebaliknya semakin menjauh. Bagaimanapun kenangan suka-duka perjalanan itu tak akan terlupakan.
Kembali ke persiapan rencana pendakian Gunung Fuji. Ransel Eiger hitam yang kubawa dari tanah air itu kuisi beberapa helai pakaian. Kuperkirakan cukup untuk empat hari pulang pergi Kyoto-Tokyo. Tiket kereta api murah Jyu hachi kippu dari Japan Railway (JR) sudah ada di tangan. Aku sudah membelinya beberapa hari lalu di sebuah etalase penjualan tiket kereta jyu hachi kippu di pertokoan dekat Minami Kusatsu Eki.
Seperti rencana, rombongan bertemu di titik start di sebuah stasiun di Tokyo. Rombongan berjumlah 15 orang, terdiri dari 7 orang perempuan dan 8 orang laki laki. Dalam rombongan itu ikut juga 4 orang warga negara lain, yaitu 1 orang laki-laki dari Laos, 1 orang perempuan dari Mongolia, 1 orang perempuan dari Vietnam dan 1 orang perempuan dari Pakistan. Belakangan selama perjalanan pendakian aku lebih sering berjalan bersama dengan teman asal Pakistan bernama Aisyah.
Perjalanan dari Tokyo menuju Gunung Fuji ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 jam menggunakan kereta api dan bus kota. Jalur yang kami tempuh adalah Jalur Yoshida di Prefecture Yamanashi. Rute ini merupakan rute yang paling poluler. Stasiun terakhir kereta menuju Fuji San adalah stasiun Kawaguchiko yang berada di kaki gunung Fuji. Dari stasiun tersebut perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan bus kota Fuji Express yang membawa rombongan kami sampai ke Stasiun 5. Selama perjalanan itu, rombongan kami asyik bercanda ria dengan semangat yang masih full tank. Hanya beberapa saja yang terlihat diam dan sesekali tersenyum mendengar guyonan mereka, termasuk teman-teman warga negara lain yang tidak mengerti bahasa Indonesia.
Sampai stasiun 5 pendakian Gunung Fuji, waktu sudah menunjukkan jam 4 sore waktu setempat. Stasiun 5 merupakan stasiun terendah yang menjadi titik start pendakian dengan berjalan kaki. Di stasiun ini berdiri bangunan seperti ruko tempat menjual makanan dan minuman, souvenir serta peralatan pendakian dengan halaman parkir yang luas bisa menampung banyak bus kota yang membawa pengunjung. Tak heran bila tempat ini ramai dengan pengunjung, baik yang akan melakukan pendakian ke puncak Gunung Fuji ataupun yang sekadar berkunjung sampai stasiun ini saja. Mereka berfoto-foto dan membeli souvenir bertema Fuji San sebagai bukti sudah sampai di stasiun ini. Rombongan kami pun tak bedanya dengan pengunjung lain, segera ambil posisi masing-masing dan jeprat-jepret.
Setelah dirasa cukup sesi foto-fotonya, ketua rombongan segera mengumpulkan kami untuk briefing sejenak guna menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pendakian. Informasi yang disampaikan antara lain kondisi cuaca yang diprediksi akan segera turun hujan dan pesan-pesan berkaitan dengan hal-hal yang perlu atau malah tidak boleh dilakukan selama pendakian, terutama memupuk kekompakan dan saling menjaga teman satu rombongan. Ketua mempersilakan kami untuk salat, mengisi perut dan membeli peralatan pendakian lalu berkumpul lagi satu jam kemudian.
Selesai briefing, rombongan kami segera menghambur ke dalam deretan toko untuk mencari keperluan masing-masing, yaitu makanan dan minuman untuk bekal pendakian serta peralatan pendakian, seperti tongkat kayu berkerincing, mantel plastik dan lain-lain. Aku dan beberapa teman mengisi perut dengan udon (semacam mie kuah khas Jepang), lumayan untuk menghangatkan badan meskipun rasanya tidak senikmat seperti di Hana no Mae dekat Minami Kusatsu Eki. Untuk bekal perjalanan pendakian, aku membeli tongkat kayu berkerincing, sepasang lonceng kecil, senter kecil, cokelat dan sebotol air mineral.
Seperti waktu yang telah ditentukan, kami berkumpul lagi untuk memulai pendakian. Hari sudah hampir gelap, jarum jam di tangan menunjukkan sudah 30 menit berlalu dari jam 5 petang dan gerimis mulai turun rintik-rintik. Kami berjalan perlahan menuju stasiun 6 sambil berdoa agar rintik hujan segera reda sehingga perjalanan kami menjadi lebih ringan dan asyik. Jalan menuju stasiun 6 ini kondisinya mudah dilalui dengan lebar sekitar 4 meter sehingga barisan dua berbanjar masih bisa lewat dan sisi lain masih bisa untuk dilewati pejalan lain yang ingin mendahului.
Dalam perjalanan kami sempat melewati barisan pendaki warga negara Jepang yang bergerak perlahan. Barisan mereka rapi dua banjar dengan langkah kaki pendek-pendek teratur dipimpin seorang pemandu. Ini berguna untuk mengatur pernapasan agar tidak mudah lelah dan kelak akan sangat membantu meraka untuk mampu mencapai puncak. Sebagian dari mereka sudah tidak muda lagi, bisa dikatakan lansia. Persis seperti yang digambarkan Azra waktu itu. Dalam hati bergumam kagum dengan para kakek dan nenek dalam rombongan itu. Mereka terlihat masih semangat meski raga sudah tak lagi sekuat kami. Kami juga melewati rombongan keluarga yang mengajak serta anak-anak umur 5 tahunan turut dalam pendakian.
Pemandangan di sisi sebelah kanan atas kami adalah rimbunan pepohonan hutan yang terlihat asri alami. Pohon-pohon yang besar dan tinggi itu sebagian besar ditumbuhi lumut dan paku-pakuan. Memberi petunjuk bahwa ia telah lama tumbuh pada kondisi lingkungan yang dingin. Sementara di sisi sebelah kiri adalah jurang cukup dalam yang pada sisi bawahnya juga ditumbuhi pepohonan besar dan rimbun.
Kurang lebih 30 menit berjalan, kami tiba di stasiun 6. Di stasiun ini rombongan kami berhenti sejenak untuk melaksanakan salat magrib. Alhamdulillah rintik hujan mulai mereda dan cuaca gunung tampak bersahabat. Usai salat magrib, seperti biasa kami yang masih penuh energi segera menuju beberapa spot menarik untuk pengambilan foto.
Sekitar jam 7 malam kami melanjutkan perjalanan menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun 7. Medan perjalanan mulai sedikit terjal mendaki meskipun jalannya masih agak luas. Bagi pemula perjalanan ini sudah mulai terasa sulit, apalagi rintik hujan masih turun meski rinai saja. Beberapa teman wanita yang baru pertama kalinya mendaki gunung mulai melambat jalannya, sebentar-sebentar berhenti. Dalam keadaan lelah akhirnya kami semua sampai juga di stasiun 7, di mana ada Torii, atau gerbang merah menyambut kami. Kami berhenti untuk istirahat, berbagi bekal biskuit dan cokelat, serta mencari toilet umum. Di stasiun ini kami masih sempat mengabadikan foto meski dengan bantuan cahaya di kamera.
Istirahat di stasiun ini cukup lama sehingga aku punya kesempatan untuk membuka Iphone-ku. Handphone terbaru produk Apple pada zaman itu yang cicilannya masih diangsur setiap bulan sekaligus tagihan pemakaian pulsanya. Tidak ada sinyal. Hanya terbaca beberapa pesan yang belum sempat kubuka dari mulai pendakian di stasiun 5 tadi. Salah satunya dari suamiku tercinta yang menanyakan kabarku. Satu lagi dari Azra sahabatku menanyakan hal senada. Sepertinya mereka mengkhawatirkan perjalanan pendakianku.
Setelah dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan kembali menuju stasiun 8. Medan pendakian semakin terjal dan curam sehingga sangat menguras tenaga. Belum lagi ditambah dengan berkurangnya oksigen di udara. Setelah berjalan mendaki sekitar 1 jam, tiba-tiba seorang teman wanita, Elda, mengalami hysteria. Bicaranya ngelantur tidak jelas dan menjerit-jerit, “Ibu... ibu... aku mau pulang! Lina, teman wanita yang berada di dekatnya berusaha menenangkan. Aku dan beberapa orang teman pendakian yang sudah lebih dulu sampai di stasiun 8, berhenti untuk istirahat sambil menunggu kedatangan Elda dan beberapa teman yang masih berada di bawah.
Elda tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan harus tinggal beristirahat di stasiun 8 dengan menyewa sebuah hat (penginapan) yang hangat. Lina menemani dan merawatnya tinggal di dalam hat. Sementara Hermes dan seorang teman lelaki yang aku belum kenal namanya, memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan dengan alasan menjaga Elda dan tinggal di luar hat.
Aku sempat kecewa dengan keputusan Hermes untuk berhenti mendaki karena di dalam rombongan pendakian itu hanya Hermes yang aku kenal. Sedangkan yang lain masih asing semua karena baru ketemu sesaat sebelum berangkat pendakian. Tapi aku tidak menyerah dan masih terus semangat untuk melanjutkan perjalanan.
Rombongan kami melanjutkan pendakian dengan personil berkurang 4 orang, tinggal 11 orang. Saat itu sudah jam 9 malam, suasana semakin gelap dan rintik hujan mulai rapat, namun kami tetap semangat mengejar waktu agar jam 2 malam bisa sampai di puncak Fuji San. Harapan terbesar kami adalah dapat menyaksikan detik-detik matahari terbit di puncak Fuji San.
Medan pendakian menuju stasiun 9 semakin terjal dan menukik. Kondisi ini diperparah oleh air hujan yang membuat licin batu-batu besar yang menjadi pijakan kaki dan pegangan tangan kami, sehingga kami bergerak lambat. Perjalanan menuju stasiun 8 ini terasa berat. Beberapa kali aku berhenti mengambil napas dan menatap kilauan cahaya dari arah atas sambil berkata dalam hati. “Itu stasiun 9 sudah dekat... ayo semangat... sedikit lagi sampai.” Kalimat untuk menyemangati diri untuk tetap semangat dan tidak putus asa karena langkah tak boleh berhenti. Saat itu tak ada pilihan lain selain harus terus mendaki.
Jam 11 malam, rombongan kami sampai juga di stasiun 9. Alhamdulillah, lega dan senangnya hati sampai juga di satu stasiun lagi menuju puncak. Beberapa teman terlihat kepayahan, tak bedanya dengan keadaanku. Kami berusaha mencari tempat untuk melepas letih berteduh dari hujan yang turun semakin deras. Badan kami sudah basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sementara menunggu ketua rombongan mencari tempat untuk beristirahat, kami berteduh di bawah emperan sebuah restoran. Beberapa kali angin bertiup kencang menerpa kami dari arah depan sehingga badan kami terguyur air hujan.
Stasiun 9 terlihat paling ramai bila dibandingkan dengan stasiun-stasiun sebelumnya. Stasiun ini berada di ketinggian sekitar 3.400 M. Artinya, tidak jauh lagi kami akan sampai di puncak Fuji San. Ada beberapa hat dan dua bangunan yang kalau tidak bisa dikatakan restoran sederhana ya warung makan. Dalam hati bersyukur ada tempat untuk membeli makan dan minuman untuk menghangatkan badan. Meskipun terlihat sangat ramai dan penuh oleh pengunjung, tapi tak apalah bisa gantian, nanti pasti ada yang keluar.
Dalam kedinginan menggigil dan penuh harap bisa masuk ke dalam salah satu warung makan itu, tiba-tiba ketua rombongan mendatangi kami dengan wajah lesu. Ketua menyampaikan kabar buruk bahwa malam itu tidak ada seorang pun diperbolehkan melakukan pendakian sampai ke puncak. Penjaga keamanan Fuji San, dengan alasan keamanan akibat adanya hujan badai, telah menutup semua jalur menuju puncak.
Berita buruk berikutnya, tak ada lagi tempat tersisa untuk kami berteduh. Semua hat (penginapan) dan warung makan telah penuh oleh pengunjung yang telah lebih dahulu datang dan bahkan sudah reserve jauh hari sebelumnya. Dikarenakan di luar hujan deras dan udara sangat dingin, maka tidak ada satu pun pengunjung warung makan yang beranjak dari duduknya. Mereka terus menetap di dalam ruangan yang hangat dan tersedia makanan dan minuman. Duuuh... masa kami harus terus kedinginan berteduh di emperan bangunan? Wajah harap kami menunggu jawab ketua yang tak dapat berbuat apa-apa.
Tak mau diam menyerah, seorang teman wanita dari Mongol yang menguasai bahasa Jepang dengan cukup bagus mengajakku, dan dua teman wanita yang wajahnya sudah terlihat pucat mendatangai sebuah warung. Dengan memelas, kami mengetuk pintu warung yang ditutup dari dalam dengan harapan bisa masuk ke dalam warung. Pintu warung berbentuk seperti pagar sehingga penjaga warung bisa melihat kami dari dalam. Melihat kami, penjaga warung menghampiri dan menanyakan maksud kami. Teman wanita kami memohon dalam bahasa Jepang bahwa kami memerlukan tempat untuk berteduh karena ada teman kami yang sakit dan kedinginan. Mendengar maksud kedatangan kami. Penjaga dengan cepat berkata, “Muri... Muri...” yang artinya tidak bisa.
“Waah kejam sekali”, bisik hatiku. Padahal kami bisa melihat dari jendela kaca warung itu sebenarnya masih ada sedikit ruang di dalam untuk bisa menampung kami, meskipun kami harus berdesak-desakan. Apakah mungkin karena kondisi kami sudah basah kuyup sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan pengunjung yang sudah ada di dalam! Aku tidak pernah mendapat jawaban dari pertanyaan yang hanya kusimpan sendiri. Dengan masygul, kami pun kembali ke rombongan berteduh di bawah emperan bangunan penginapan.
Aku menggigil kedinginan dan hampir putus asa. Kami satu rombongan bersebelas berdiri saling mendekat dengan tangan bersedekap agar lebih hangat dan saling memberi dukungan semangat. Aku tak henti berdoa agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Tiba-tiba seorang teman dari Mongolia yang tampak paling tegar berinisiatif mengajak bernyanyi dan menggerakkan badan ke kiri dan kanan dengan maksud agar kami tetap hangat dan bertahan dari dingin yang seperti meyergap sampai ke jantung.
Sambil bernyanyi, aku dan juga mereka, tak dapat menyembunyikan kegelisahan saat itu. Apalagi lagu yang kami nyanyikan bersama adalah lagu Go With The Wind, sound track-nya film Titanic. Seakan-akan kematian sedang mendekat dan kami semua akan mati kedinginan. Dengan bibir pucat bergetar dan mata sesekali terpejam, kami terus bernyanyi dan bergerak.
Sampai akhirnya aku dan seorang teman memutuskan pindah untuk berteduh ke dalam bangunan toilet umum. Tempat ini juga sudah dipadati oleh pendaki lain. Di sana aku dan teman dari Pakistan, Aisyah mendapatkan harapan untuk hidup kembali. Dengan berpura-pura seakan sudah tidak tahan untuk buang hajat, kami masuk menerobos pendaki lain yang hanya bergerombol di depan. Tentu saja karena tak tahan oleh aroma menyengat dari bilik-bilik toilet.
“Sumimasen… Sumimasen.” kataku mengucapkan permisi agar diberi jalan lewat untuk masuk ke bagian dalam bangunan toilet.
Sampai di dekat bilik toilet, hidungku sangat terganggu oleh aroma yang semakin menyengat. Aku dan Aisyah berhenti sesaat. Berdiri di belakang kerumunan pendaki lain sambil mengamati susunan ruang dalam bangunan itu.
Bangunan toilet umum khusus wanita ini cukup besar. Di dalamnya ada 4 bilik toilet dengan ukuran 1,5 x 2 meter persegi. Toilet ini merupakan toilet kering, tidak ada air untuk cebok melainkan hanya tersedia tissue gulung untuk mengelap seusai buang hajat. Cairan untuk menyiram/flushing yang kemudian menggenang di dasar toilet jongkok itu sepertinya diberi bahan kimia pengharum untuk mengurangi bau tidak sedap yang ada. Antara pintu bilik toilet dan dinding bangunan utama terdapat ruang memanjang kurang lebih 1 x 6 meter persegi. Aku langsung menuju ruang di depan bilik paling ujung yang nampak kosong. Aisyah mengikuti di belakangku.
Sambil menutup hidung, aku jongkok diam di sudut ruang itu mencari kehangatan dari dinding bangunan. Kulepas jaket bulu angsa tebal yang membungkus tubuhku. Jaket yang dipinjami oleh Asra dari apato-nya di Gyotoku, sesaat sebelum berangkat.
“Mba, kok bawa jaket tipis begitu?” tanyanya heran.
“Lhaa... katamu ngga usah bawa jaket terlalu tebal... mberat-mberatin aja! Yaa sudah aku bawa yang ini. Adanya ini,\" sergahku.
Sebelum berangkat aku memang terus berkomunikasi dengan Azra melalui telepon untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan rencana keberangkatan ke Fuji San.
“Sudah, pake jaketku aja Mba!\" setengah memaksa dia menyodorkan jaket berwarna cokelat susu tebal berisi bulu angsa miliknya kepadaku.
“Lhaah.. gede banget.. Ngga ada feminimnya. Ngga ah... jadi kelihatan ndut aku ntar kalo difoto!” aku mengulurkan lagi jaket tebal itu ke arahnya.
Ngga Mba... Mba harus pake jaket yang ini. Itu bukan jaket buat ke gunung!” dengan tegas dia menyodorkan lagi jaketnya sambil matanya menatap ke arah jaketku yang tergeletak di lantai apato-nya.
Sesaat badan terasa lebih ringan dan sedikit hangat. “Ternyata ini juga bukan jaket yang tepat untuk kondisi saat hujan, Sra...” kata hatiku. Bagian luar jaket tidak tahan air sehingga bulu-bulu angsa di dalamnya basah dan jaket menjadi berat. Kututupkan jaket di depan lututku.
Kulepas sepatu kets dan kaos kaki yang melindungi kakiku selama perjalanan. Sepatu berwarna kecokelatan senada jaket tebal itu kini sudah basah digenangi air. Kucoba menegakkan dan mengibaskannya untuk mengeluarkan air yang meresap ke dalamnya. Lalu kuinjak untuk alas kaki.
Sepatu itu milik Nita, sahabat satu apato-ku di Kasayama. Aku masih ingat saat dimintai pendapat ketika dia akan memilih sepatu olahraga di sebuah departemen store di Yogya sebelum berangkat ke Jepang.
Dia meminjamkan sepatunya saat aku akan berangkat dan berpamitan. Menurutnya sepatu yang kupakai tidak cocok untuk naik gunung. Kebetulan juga ukuran sepatu kami sama.
“Pake sepatuku aja Mba... itu ringan lho, kayak’e lebih cocok pake punyaku,” Nita meyakinkanku dengan logat Jawa medoknya.
“Ngga apa-apa kalo aku pake Nit? Aku takut nanti rusak,” aku ragu-ragu dan khawatir, meski dalam hati sepakat dengan kata-kata Nita.
“Wiss ngga apa-apa... pake ajaa! Di sini aku juga jarang pake!\"
Nita termasuk wanita yang kurang menyukai petualangan di alam. Oleh karenanya dia sama sekali tidak tertarik untuk naik gunung.
“Nggalah Mba... aku ngga kepengin. Nanti capek... aku mau lihat puncak Fuji dari bawah saja nanti,” jawab Nita saat kutawari naik Fuji San. Dia memang ada rencana untuk pergi ke Shizuoka. Teman wanitanya asli Jepang yang satu ruangan dan satu bimbingan di laboratorium arsitektur mengajak Nita untuk berkunjung ke rumahnya tengah September nanti. Puncak Fuji San memang tampak indah dilihat dari arah Kota Shizuoka yang berada di kakinya.
Sejenak aku tersenyum sendiri. Barang-barang ini, jaket dan sepatu, milik sahabat-sahabat dekatku selama di Jepang yang peduli dan sayang padaku. Betapa beruntungnya aku memiliki mereka. Dan tiba-tiba aku merasa konyol karena naik gunung dengan modal jaket dan sepatu pinjaman. Aku tertawa sendiri.
Aku memeriksa isi ranselku. Ya ampun, ternyata pakaian gantiku sudah basah semua. Aku tidak tahu kenapa bisa lupa untuk membungkus pakaian dengan kantong plastik sebelum dimasukkan ke dalam ransel. Sesuatu yang biasa kukerjakan ketika hendak berangkat praktikum ke laut, pun saat hendak berangkat mengikuti kegiatan korps palang merah mahasiswa kamping ke alam terbuka saat kuliah S1 dulu di Bogor. Ya sudah. Aku harus terima akibat dari kelalaianku sendiri. Terpaksa kubiarkan panas badanku mengeringkan sendiri baju kaos plus dalaman yang kupakai.
Perlahan aroma menyengat dari dalam bilik toilet mulai bisa kuabaikan tanpa harus menutupi hidung. Apalagi sejak aku jongkok di sudut ruang itu tidak ada satu pun orang memasuki bilik paling pojok tepat di depanku jongkok. Mungkin mereka sungkan melihatku ada di depan pintu. Dan sesungguhnya, berada di dalam gedung toilet ini jauh lebih baik ketimbang di luar terkena terpaan angin dan air hujan langsung. Apalagi di depan pintu masuk toilet sudah dibentengi rapat oleh pendaki yang ikut berteduh, tetapi tidak tahan dengan aroma dari dalam. Maka bagian dalam gedung menjadi lebih hangat.
Kuamati Aisyah yang sedari tadi hanya berdiri merapatkan badan dan menyandarkan kepala ke dinding bangunan toilet dan berada satu meter saja di depanku. Dia tampak sangat mengantuk. Sesekali matanya terpejam tidur dan badannya bergoyang hendak jatuh... lalu terbangun lagi.
Jongkok cukup lama membuat kakiku terasa pegal. Ingin sekali duduk, tapi lantai bangunan toilet ini pasti dingin. Aku menengok ke arah kanan ke pintu bilik toilet sambil mengingat benda apa saja yang ada di dalamnya yang bisa kupakai duduk. Aku berdiri membuka pintu toilet dan “Yaa... ini bisa dipake,” bisik hatiku. Aku mengambil sebuah stok tisu gulung yang belum dipakai dan diletakkan di bagian atas dinding bilik toilet. Kutegakkan tisu gulung di tempatku jongkok tadi lalu kududuki. Alhamdulillah... kedua kakiku bisa beristirahat sekarang. Aku meluruskan kedua kakiku yang menggunakan sepatu basah sebagai alas pijakan lalu menutupi bagian paha dengan jaket.
Kulihat lagi Aisyah yang tampak kepayahan dan gelisah tidak nyaman. Kukatakan padanya untuk tidur saja beristirahat sambil duduk di bawah di dekatku. Namun, dia menolak. Dia tidak ingin tertidur. Dia takut tidak bisa bangun lagi bila tertidur. Dia tidak ingin mati di sini.
“Aisyah, you look so tired and sleepy.. come here, just sit and sleep near me.”
“No... I’m so scared. I’m afraid I’ll die if I fall asleep. I don’t wanna die here.” Aisyah terlihat sangat putus asa dan ketakutan. Dia memilih untuk terus berdiri menyandarkan kepalanya ke dinding bangunan toilet.
Kata-kata Aisyah membuatku merasa takut. Tidak! Aku juga tidak ingin mati sia-sia di sini. Aku harus tetap hidup. Aku tak ingin tertidur.
Sejenak pikiranku melayang pada keluargaku di kampung halaman. Tergambar jelas wajah suami, anak-anak, ibu, ayah. Orang-orang yang kucintai dan kusayangi. Ingin sekali rasanya pulang dan berkumpul bersama mereka dalam kehangatan. Terbayang wajah si kecil Neto yang lucu. Mba Khansa yang gendut menggemaskan. Kak Wildan yang kreatif namun suka jahil terhadap adik-adiknya. Satu-satu mereka melintas di benakku. Ah... rindunya aku.
Apa yang aku cari di sini? Pertanyaan yang dulu dilontarkan suamiku ketika aku hendak mengajukan surat lamaran beasiswa pendidikan. Aku rapuh dan seketika timbul rasa penyesalan atas apa yang telah kulakukan dengan meninggalkan mereka.
“Astaghfirullah hal’adziim... berkali-kali aku istighfar memohon ampun kepada Allah.
“Ya Allah… tolong jangan ambil nyawaku di sini. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali pada keluargaku. Aku sangat rindu mereka.”
Aku terus istighfar dan berdoa... memohon kepada Sang Pencipta. Tuhan Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Penyayang, Maha Mendengar doa hamba-Nya. Entah sampai berapa lama hingga tak sadar aku tertidur oleh letih dan kantuk yang amat sangat. Tidur dalam posisi duduk dan kepala ditopang di atas dengkul berbantal kedua tangan dilipat.
Aku terbangun saat mendengar suara ribut-ribut. Perlahan aku membuka mata dan ternyata ada seorang wanita petugas kebersihan toilet datang membangunkan dan mengusir kami. Kulihat Aisyah sudah terbaring di lantai di depanku. Jantungku berdegup kencang. Aisyah tidur atau mati yaa? Belum sempat untuk mengeceknya. Petugas kebersihan sudah berada di depanku dan berkata dengan keras dan cepat, “Koko de nemurenai!”
Kata-kata itu saja yang sempat tertangkap telinga dan kucerna. Dia melarang kami untuk tidur di dalam toilet. Aisyah pun terbangun. Dia terlihat kaget mendapati dirinya tertidur di lantai. Lalu bergegas bangun berdiri merapikan pakaian dan rambutnya.
Aku segera memakai sepatu, mengambil ransel dan jaket lalu berdiri meluruskan badan. Kusingkap lengan kiri bajuku mengintip arloji. Ah, sudah jam 4 pagi. Pendaki yang semalam ramai berdiri di pintu toilet sudah tidak ada lagi. Aku dan Aisyah bergerak keluar dari bangunan toilet. Ternyata di luar hujan sudah reda dan langit mulai terang tanda fajar segera datang. Pantaslah! Kami yang kesiangan rupanya.
Aku dan Aisyah berjalan melewati warung makan yang tadi malam ramai sesak dan tidak bisa menerima kami. Kali ini suasana di dalam warung tidak lagi penuh. Satu per satu anggota rombongan pendaki yang berteduh semalaman mulai keluar dari dalam warung. Mereka segera beranjak menuju puncak Fuji San yang sudah tidak jauh lagi.
Kulihat teman-teman rombongan sudah berada di dalam warung. Aku dan Aisyah segera masuk ke dalam warung yang sama. Melepas sepatu di depan pintu lalu mengambil posisi duduk di bale-bale dengan meluruskan kedua kaki. Alhamdulilaah... betapa nikmatnya. Akhirnya kami bisa mendapat tempat berteduh yang layak dan hangat. Kami segera memesan makanan dan minuman untuk menghangatkan badan.
Sambil menunggu pesanan datang, kami melaksanakan salat subuh. Aku bertayamum. Lalu salat duduk dengan pakaian yang melekat di badan dan jaket kututupkan di kedua kakiku. Tidak yakin kondisiku bersih. Namun, aku sangat ingin sekali bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena aku dan semua anggota rombongan selamat... meskipun tidak bisa dikatakan sehat. Seorang teman wanita yang sedari tadi malam sudah terlihat pucat, pagi itu terlihat lemah sekali dan kondisi kesehatannya makin memburuk. Kami berlama-lama di dalam warung. Pesan dan pesan lagi makanan atau minuman sehingga kami punya alasan untuk tetap tinggal di dalam warung.
Selesai mengisi perut di warung sekitar jam 6 pagi. Matahari sudah terbit. Sinarnya menerobos dari balik celah dinding warung yang terbuat dari kayu. Aku masih berharap bisa melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tidak apalah tidak bisa menyaksikan matahari terbit di puncak Fuji San. Tapi setidaknya bisa menginjakkan kaki di sana. Memandang alam Jepang dari ketinggian puncak Fuji. Namun, ketua rombongan memutuskan untuk mengambil jalan turun dan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Hal ini dikarenakan beberapa teman kondisinya sudah tidak fit lagi, terutama teman wanita dari Jakarta itu.
Pupus sudah harapanku untuk bisa sampai ke puncak Fuji San. Sambil berjalan turun kupandangi jalan berbatu menuju puncak. Tidak jauh lagii... setengah jam sepertinya sampai. Duuh sayangnya. Kecewa sekali, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin aku berjalan sendiri berpisah dari rombongan. Di mana rasa kebersamaanku? Baiklah, aku harus akhiri sampai di sini saja. Setidaknya aku pernah hampir mencapainya.
Perjalanan menuruni puncak Gunung Fuji seperti mengajak berlari, menggelundung. Jalanan turun yang merupakan butiran pasir kasar itu sangat licin. Beberapa pendaki yang juga berjalan turun bersama kami tampak sesekali terjatuh. Tak luput, aku pun terperosot jatuh. Sudah pasti sebabnya bagian bawah sepatu yang kupakai tidak bisa mencengkeram tanah berpasir kasar yang kupijak. Ini memang bukan sepatu yang cocok untuk pendakian.
Beberapa kali kami berhenti beristirahat selama dalam perjalanan turun untuk kembali ke stasiun 5. Kami berpatokan pada peta penunjuk jalan yang dicetak pada brosur promosi pariwisata Gunung Fuji yang kami dapat di stasiun 6. Sekitar jam 1 siang kami tiba di stasiun 5 tempat memulai pendakian kemarin sore. Segera saja kami menuju bangunan pertokoan mencari air bersih untuk membasuh muka, membersihkan pakaian dari lumpur, dan berwudu untuk melaksanakan salat zuhur. Tak lupa makan siang dan menambah souvenir berupa pelat cetakan dari kuningan dan gantungan kunci bertemakan Fuji San.
Alhamdulillah! Sungguh perjalanan yang sangat berkesan dan tidak akan terlupakan seumur hidupku. Betapa Allah SWT telah memberikan pelajaran yang tak terhingga buatku. Allah telah membuatku sadar betapa aku sangat mencintai keluargaku dan aku tidak ingin jauh dari mereka. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan hidup dan waktuku bersama mereka, sekembalinya aku kepada mereka nanti.
***
Other Stories
Devils Bait
Berawal dari permainan kartu tarot, Lanasha meramal kalau Adara, Emily, Alody, Kwan Min He ...
Cangkul Yang Dalam ( Halusinada )
Alya sendirian di dapur. Dia terlihat masih kesal. Matanya tertuju ke satu set pisau yang ...
Blind
Ketika dunia gelap, seorang hampir kehilangan harapan. Tapi di tengah kegelapan, cinta dar ...
Haura
Apa aku hidup sendiri? Ke mana orang-orang? Apa mereka pergi, atau aku yang sudah berbe ...
Petualangan Di Negri Awan
seorang anak kecil menemukan negeri ajaib di balik awan dan berusaha menyelamatkan dari ke ...
Deru Suara Kagum
Perlahan keadaan mulai berubah. Pertemuan-pertemuan sederhana, duduk berdekatan , atau sek ...