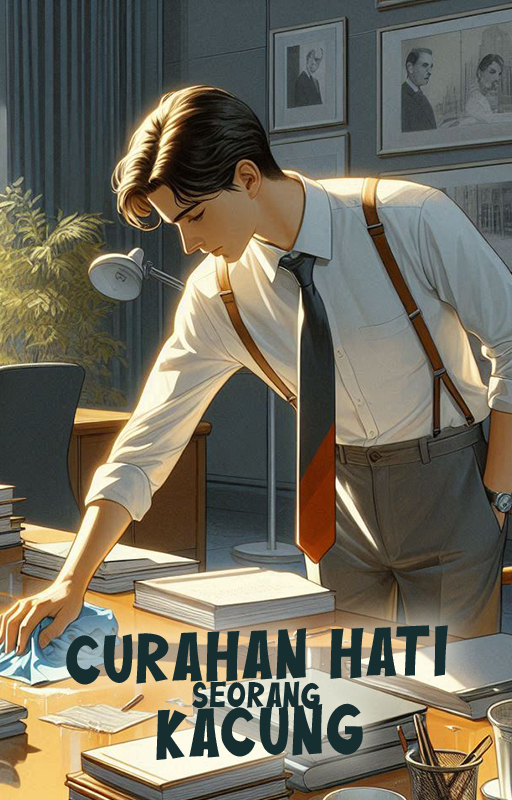2. Satu Bintang Di Langit Kelam
BINTANG
Semesta akhirnya berpihak pada gue. Dengan semua perjuangan yang gue lakukan bersama Petra, Raihan, dan Raja. Jatuh bangun berkali-kali hingga hampir putus asa. Pada akhirnya kami mencoba bangkit kembali tanpa berpikir macam-macam. And it work! Kami berhasil memenangkan kompetisi tahunan bergengsi itu. Saat itu gue mulai sadar. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menepati janjinya. Meski kita pikir itu terlambat, tapi perhitungan Tuhan tak pernah meleset.
Kemenangan itu memang harus dibayar mahal. Demi mimpi kami, jadwal latihan terpaksa diperketat, terus mencoba fokus mengasah kemampuan, dan mengikuti lomba-lomba berskala kecil. Tak jarang semua itu bertabrakan dengan kepentingan masing-masing, seperti masalah kuliah, keluarga, dan pacar. Pertengkaran? Jangan ditanya. Kami pernah melewati malam yang buruk, saat kami mabuk dan berkelahi tanpa sebab. Yang gue ingat, waktu itu gue sedang kesal gara-gara kalah lagi di Dream Band. Gue menuduh teman-teman tidak berguna, bahkan berpikir sebaiknya band bubar saja. Rupanya pendapat gue menyinggung mereka. Ya, kami berkelahi sekaligus tertawa pada akhirnya. Tepat di tengah derasnya hujan yang membasahi Kota Bandung.
Suatu ketika, Om Christ—bokap Petra—pemilik café bernama Petrapucino, meminta kami untuk tampil di café-nya setiap malam Minggu. Tentunya tawaran itu kami sambut dengan suka cita. Lumayan untuk mengasah kemampuan dan membiasakan diri bersosialisasi dengan penonton. Gue sedikit cemburu dengan Petra, hobinya didukung seratus persen oleh bokapnya. Beda sama gue. Bokap sudah wanti-wanti gue belajar tekun supaya lulus kuliah dan jadi pengacara kelak.
“Ya nggak gitu juga kali Bro. Lo gak tau sih apa tuntutan bokap ke gue,” celoteh Petra saat kami berkumpul santai di salah satu sudut Petrapucino. “Sebagai anak cowok pertama. Gue disuruh belajar bisnis supaya bisa lanjutin usaha bokap. Makanya meski beliau mendukung hobi nge-band gue, harus ada timbal baliknya kelak. Gue harus mampu bantu beliau beresin semua hal yang berhubungan dengan café.”
“Keren. Enak ya jadi elo. Lulus kuliah langsung dapet jabatan bos café,” celetuk Raja.
“Ya enak gak enak lah. Elo tau kan cita-cita gue sebenernya?”
“Fotografer?” tebak Raihan. Petra mengangguk. “Ya gak apa-apa kali. Jadiin kerjaan sampingan aja. Motret aja sesekali, ikut lomba-lomba. Lama-lama kan terasah. Jadi dah fotografer sekaligus pengusaha.”
“Gimana nih sama elo, calon pengacara terkenal,” celetuk Raja. Semua perhatian tertuju pada gue.
“Gue gak minat jadi pengacara,” gue bangkit segera menuju wastafel. Mendengar paparan mereka tentang cita-cita malah bikin telinga gue semakin panas. Kayaknya gue aja anak yang cita-citanya diatur sedemikian rupa sama bokap-nyokap. Jadi pengacara? It suck! Gue gak pernah punya mimpi jadi pengacara.
Tiba-tiba saja gue ingat Kirana. Damn! Kenapa ya akhir-akhir ini gue kangen banget sama tuh cewek? Ini gara-gara Langit—si penyiar nocturnal itu. Tiba-tiba aja dia dekati gue dan mengenalkan Kirana yang katanya sobat dia. Hm… anaknya manis sih. Gue suka aja sama penampilannya yang cuek waktu itu. Rambut diiket seadanya, t-shirt biru tipis yang nyaris seksi, plus celana jins pendeknya yang aduhai. Gak kuat kalau terlalu lama lihat kakinya yang putih mulus.
Waktu itu alasan Langit kenalin Kirana karena mau wawancara gitu. And guess what? Itu cewek malah gak tau apa yang mau ditanyain. Masa iya grogi sama gue? Pantesnya kan grogi kalau wawancara sama Geisha atau Armada yang kebetulan jadi bintang tamu Dream Band.
Pada akhirnya, gue mutusin ajak dia makan mie ayam gerobak yang kebetulan lewat. Gue laper. Gila, siang bolong panitia belum juga kasih konsumsi. Lucunya, Kirana mau aja gue ajak makan. Nah baru setelah itu proses wawancara berjalan lancar, lewat obrolan ringan seputar band gue—belakangan gue baru nyadar, tuh cewek kelaparan juga kayak gue. Satu lagi. Kayaknya itu kamera SLR yang melingkar di lehernya sama sekali gak berguna. Ujung-ujungnya dia foto gue pake kamera handphone. Alasan dia sederhana, lupa cara makenya. Hah?
Pertemuan manis itu ternyata meninggalkan sedikit kesan di hati gue. Banyak yang bilang kalau gue sok cool ke cewek. Tapi suer. Untuk kali ini gue gak bisa bersikap dingin kayak biasanya. Maunya pingin ketawa aja. Atau sedikit-sedikit candain dia. Dan gue suka cara dia menanggapi candaan gue. Gak kampungan kayak cewek-cewek yang gue kenal.
Terakhir kami ketemu lagi pas di final Dream Band. Ternyata tuh cewek bawa pasukannya sambil bawa spanduk gede bertuliskan nama band kami. Jelas gue terharulah. Band gue dielu-elu sama segerombolan cewek manis kayak mereka. Gue yakin personil Armada juga jealeous sama kami—mereka gitu bintang sebenarnya.
Gue seneng saat band kami jadi juara. Saking senengnya, spontan gue ajak traktir makan Kirana di Petrapucino. Ini tindakan terberani gue selama deketin cewek. Padahal biasanya gue ogah-ogahan ajak cewek buat jalan. Feeling gue selalu nggak bener, dan pada akhirnya malah kacau gak jelas. Tapi kali ini malah sebaliknya. Sisi hati gue berkata, She is the right one. Seseorang yang dikenalkan oleh lelaki gak jelas seperti Langit.
Ngomong-ngomong soal Langit. Kenapa ya gue sama dia gak deket? Padahal kami satu jurusan. Apa dia emang sombong? Atau jangan-jangan gue kali yang kelewat cuek, jadinya terkesan sombong? Gue butuh anak itu buat melancarkan aksi pendekatan gue. Cari tahu semua hal tentang cewek bernama Kirana.
***
Pagi yang suntuk. Gue ogah-ogahan masuk ke kelas. Ini juga terpaksa karena denger-denger mau ada kuis dadakan. Hadeuh, mana minggu lalu gue bolos. Gak punya catatan sama sekali. Gue duduk di deretan paling kiri. Salah satu posisi favorit gue karena terdapat jendela menghadap ke arah luar. Kalau misalkan ngantuk atau bosan, gue bisa nengok ke arah luar sekedar meneduhkan mata.
Selang beberapa waktu kemudian, Langit datang dengan tampang yang lebih parah dari gue. Anak itu pasti kurang tidur gara-gara keseringan jadi penyiar nocturnal.
“Lang! Langit!” seru gue. Mungkin ini waktunya gue mulai dekati cowok itu. Tuh kan benar. Ekspresinya datar sekali waktu dipanggil. Perlahan dia menghampiri gue. “Elo kenapa? kusut bener tampangnya.”
“Aku susah tidur semalam,” balasnya setelah duduk di samping gue. “Hari ini ada kuis ya?” Gue mengangguk. “Damn!” umpatnya pelan, lalu mengeluarkan catatan dari ranselnya.
“Eh, apa kabar si Kirana?” tiba-tiba nama cewek itu malah terucap begitu saja.
Spontan Langit menoleh ke arah gue. “Kirana? Hm… she ok. Kenapa?” ujarnya seraya memperbaiki posisi kacamata. Dari nada suaranya kelihatan dia tidak suka gue nanyain Kirana. Atau jangan-jangan dia juga naksir sama itu cewek?
Gue melebarkan senyuman. “Nggak. Senang aja bisa kenalan sama cewek asyik kayak dia,” alasan gue. “Kalau gue dekati dia, gak ada masalah kan?” lirih gue. “Ma… maksud gue elo gak lagi PDKT kan sama Kirana?” kok malah gue yang nervous sendiri.
Langit malah menyeringai. “Aku sama dia cuma sahabatan.”
“Nice. Berarti elo bisa bantu gue dong ya?” seru gue setengah bercanda.
“Maksudnya? Bantuin kamu PDKT sama Kirana?” dahi Langit mengerut. “Gak nyangka. Cowok keren kayak kamu masih grogi juga deketin cewek.”
“Yaelah gak gitu juga kali. Masalahnya gue kan gak tau apa-apa soal Kirana. Dan kebetulan elo sahabatnya. Gak apa-apa kan gue minta informasi dari elo? Lagian ini gara-gara elo juga, ngenalin cewek cakep ke gue.”
Kali ini Langit melebarkan senyumannya. “Lah Kirana sendiri yang minta. Buat bahan wawancara, katanya.”
It work! Obrolan kami melebar hingga soal hobi dan aktivitas masing-masing. Hingga akhirnya berlanjut di kantin belakang kampus dengan sepiring ketoprak pedas. Pembawaan Langit yang ramah bikin gue enak bicara apapun sama dia. Bisa jadi itu bawaan seorang penyiar radio mungkin ya? Selalu ada topik yang asyik untuk dibahas.
“Apa sih yang kamu lihat dari sosok Kirana? Bukannya selama ini kamu dikelilingi para perempuan cantik?”
“Pertanyaan elo kayak nanya seleb yang baru jadian sama model,” gue terkekeh.
“Oya? Kebiasaan wawancara orang kali ya?” ujarnya seraya menyeruput teh manisnya. Gue malah ikut mengulum senyum. “Kamu gak usah khawatir. Selama kamu punya niat baik sama Kirana, aku bantu. Tapi kalau mulai ada indikasi gak bener. Sorry, it’s better for you to go away from her.”
“Wow, gak nyangka Si Kirana punya bodyguard yang galak ya?”
Langit tertawa. It’s ok. Lagian gue gak punya niat terselubung dekati si Kirana. Cuma pingin kenal lebih dekat. Itu aja.
***
Barusan gue udah titip salam ke Kirana lewat Langit. Sial! Kok kayak cerita film Indonesia tahun 80-an ya? Sok-sok kirim salam gak jelas—jangan sampai besok malah titip surat juga. Mati gue kalau ketahuan anak-anak. Mau ditaruh di mana muka ganteng gue?
Sebenarnya gue simpan sih nomor ponsel Kirana. Yang jadi masalah gue gak ada alasan yang tepat buat hubungi dia. Tengsin banget gue telepon dia dan bilang “Miss you, babe!” Pokoknya harus punya alasan yang logis.
Tanya aja hasil wawancara kemarin, batin gue berbicara. Gue menjentikkan jari. Benar juga. Wajar kan gue tanya begituan? Gak pikir panjang gue rogoh iPhone di saku kanan.
“Halo, Kirana. Apa kabar?”
“Hei, Bin. Dikira siapa…”
“Iya. Cuma mau say hello aja, sekalian tanya soal wawancara waktu itu. Ada masalah, gak?”
“Masalah? Maksudnya?”
“Maksud aku kali aja materinya kurang, jadi bisa wawancara ulang,” sial! Kok bisa sih kalimat gue gak masuk akal kayak gini.
Kirana malah tertawa di seberang sana. “Mau wawancara gimana? Majalahnya sudah keluar kok. Nanti deh aku kasih satu biji buat kamu.”
“Wah… cepet banget,” ujar gue basa basi—faktanya wawancara itu dilakukan satu bulan yang lalu. “Ya udah kita ketemu yuk, sekalian bawa majalahnya. Aku pingin baca.”
“Ketemu di mana? Petrapucino?”
Gue menggelengkan kepala. Sangat tidak setuju. Bisa-bisa si Petra mengendus-endus kedekatan gue sama Kirana. “How about other place? Tempat yang cozy gitu,” saran gue.
“Di mana?” payah. Kirana sepertinya gak punya ide apa-apa.
“Ya udah. Di Ngopi Doeloe aja kali ya?” tiba-tiba aja gue inget kafe yang letaknya gak jauh di belakang kampus.
“Hm… aku tahu tempatnya. Di DU[1] kan?”
“Bener,” ujar gue girang. “Gimana kalau jam tujuh malam ini?”
“Malam ini aku ada janji sama Langit,” lirihnya. “Tapi, ya udah deh. Lagian ketemu Langit bisa kapan aja,” ujar Kirana beberapa saat kemudian.
“Yakin? Gak bakal marah Si Langit?”
Lagi-lagi Kirana tertawa. “Ya nggaklah. Kayak ke siapa aja. Langit itu sudah kayak kakak sendiri. Aku bisa datang kapan aja ke rumahnya.”
***
Akhirnya dengan perjuangan panjang di seputar Jalan Merdeka dan Dago. Jeep gue berhasil masuk ke jalan kecil di sekitaran Dipati Ukur, tepatnya Jalan Hasanudin. Sambil mencari lokasi parkiran yang enak, gue coba telepon si Kirana. Tuh cewek udah nyampe di Ngopdoel[2] belum ya?
“Kirana? Kamu udah nyampe?”
“Belum. Masih di angkot,” waduh, doi malah pake angkot. Bodoh banget sih gue!? Kenapa gak gue jemput aja kali tadi di rumahnya? batin gue seraya menepuk jidat. “Bentar lagi nyampe kok. Ini sebentar lagi deket-deket Rumah Sakit Borromeus. Nanti aku turun di sana.”
“Oke,” balas gue. Niatnya sih pingin muter balik buat jemput dia. Tapi susah nembus jalan ke arah Dago. Macet banget. Lagian gue udah dapet tempat parkir. Nanti malah susah lagi dapet parkiran.
Beres markirin Jeep gue yang rada jauh dari lokasi Ngopdoel. Gue inisiatif jalan dulu ke arah jalan besar buat nungguin Kirana. Tepatnya di samping Rumah Sakit Borromeus. Sekalian mau ambil duit di ATM.
Baru aja gue keluar dari selasar rumah sakit, sosok cewek yang gue kenal akhirnya muncul di depan mata. Perempuan itu kelihatan cantik dengan rambut yang digerai bebas. Kadang kibasan angin yang mempermainkan rambutnya nampak seperti Dian Sastro di iklan sampo merek terkenal itu. Dan tentu saja itu didukung dengan selera fashion-nya yang gak kampungan. Sederhana sih, cuma celana jeans dan t-shirt putih polos, lalu dipermanis dengan syal berwarna pink yang melilit lehernya.
“Loh kok kamu ada di depan rumah sakit? Abis ngapain?” tepat sekali Kirana mergoki gue yang baru keluar dari pintu gerbang rumah sakit gede itu.
“Nggak dari mana-mana. Cuma abis ambil uang di ATM,” jawab gue jujur. “Sorry ya, Mustinya tadi aku jemput kamu di rumah. Jadi gak perlu macet-macetan di jalan.”
Perempuan itu malah tertawa. “Sama aja kali. Mau dijemput atau nggak. Ya, tetep bakal macet-macetan. Kecuali kalo kafenya deket rumahku.”
Iya ya? Bener juga. Gue cuma meringis.
Seperti yang dijanjikan. Kirana membawa satu eksemplar majalah terbitan kampusnya yang di dalamnya ada hasil wawancara kemarin plus foto gue berdua sama doi. Berasa lagi pacaran gitu.
“Makasih ya. Aku ngerasa kayak superstar masuk majalah gituan,” garing banget ya? Whatever! Gue bingung aja mau ngomong apa. Gue terlalu terpesona melihat Kirana dalam keremangan lampu di teras café ini.
“Ah, kamu ini. Cuma majalah kampus doangan. Aku yakin sebentar lagi kalian bisa diwawancara sama majalah nasional,” ujarnya seraya memainkan sendok di cangkir Cappucino-nya.
“Aaminn… doain Angkasa Band masuk dapur rekaman dulu kali ya? Baru bisa diwawancara,” komentar gue.
***
Keren! Langkah pertama gue deketin Kirana berjalan mulus. Selama hampir dua jam kita seru-seruan ngobrol di Ngopdoel sampai akhirnya dia mau gue anter balik ke rumahnya. Cuma sempet sih ada kejadian yang bikin gue gak enak. Tadi waktu ketawa-ketawa, tiba-tiba aja Blackberry Kirana berbunyi. Dan ternyata orang yang hubungi dia adalah Langit.
“Lang, sorry ya aku gak jadi dateng. Soalnya tadi ada keperluan mendadak sama Bintang,” gue curi-curi denger meski Kirana mencoba bangkit dan menjaga jarak agar suaranya tak terdengar. “Ih, kok ampe marah gitu, sih? Besok-besok kenapa? Kayak gak ada waktu aja,” suaranya merajuk. Hingga beberapa saat dia terdiam. Mungkin Si Langit lagi nyerocos ala-ala penyiar Dream FM. “Lang! Kamu kenapa sih? Kok tumben-tumbenan marah gak jelas? Ada masalah apa sih di radio? Atau masalah di kampus?” kali ini suaranya mulai keras. “Ya kamu gak bisa kayak gitu dong, atur-atur sama siapa aku pergi. Aku bebas mau berteman sama siapa juga!” seketika itu dia menutup ponselnya.
Takut dikira ikut campur, gue pura-pura lagi mainin iPhone. “Kenapa Kir? Kok keliatan kesel gitu.”
“Tau nih Si Langit. Lagi datang bulan, kali!” dengusnya. Gue gak tega lihat wajahnya yang mulai bersemu merah. Apalagi di sudut matanya mulai terlihat gejala pingin menangis. Nah, kan bener. Perempuan itu akhirnya menangis juga. Sialan Si Langit! Sukses bikin gue gak enak hati gara-gara kelakuannya.
“Hei, kok malah nangis?” dengan sigap gue menawari sapu tangan yang selalu setia tersimpan di saku belakang celana jeans.
‘Maaf,” perempuan itu meringis malu-malu seraya mengusap air matanya. “Abis Langit jengkelin. Masa gara-gara hal sepele marahnya sampai kayak gitu,” ujarnya manja.
“Kali aja dia lagi ada masalah,” ujar gue sok bijak. “Kadang aku juga suka lepas kendali kalau sedang dapat masalah.”
“Masalahnya ini Langit, Bin! Dia gak pernah sekasar itu sama aku.”
Kali ini gue gak mampu berkata-kata. Sialan! Kenapa si Langit dibawa-bawa ke urusan gue sama Kirana.
Masih di perjalanan menuju Pasteur—tempat tinggal Kirana. Jeep gue meluncur mulus melalui bentangan jembatan Pasupati. Tempat favorit gue. Lampu-lampu yang menghiasi sepanjang fly over itu membawa kesan tersendiri. Gue seakan berada di suatu tempat yang berbeda. Kadang kalau lagi suntuk, gue suka menepikan jeep gue dan duduk di ruas sisi jembatan itu, menikmati suasana Bandung di malam hari. Gak jarang gue dapat inspirasi lagu yang datang tiba-tiba.
“Mau nongkrong dulu di sini?”
Kirana yang dari tadi melamun, menoleh padaku. “Hm? Ngapain?”
“Ya sekedar menikmati Bandung dari atas lah,” timpal gue.
Sedikit ragu ia menganggukkan kepala, “Boleh.”
“Tenang aja, Kirana. Aku cowok baik-baik. Gak bakal nyakitin kamu,” khawatir saja dia berpikir macam-macam hanya karena gue mengajak dia ke tempat yang jauh dari keramaian.
Jeep gue berhenti tepat di Cable Stayed yang di bawahnya terbentang kawasan perumahan sekitar Cikapundung. Semilir angin malamnya lebih terasa membuat Kirana yang kebetulan tidak memakai jaket harus mengelus-elus lengannya. Spontan gue melepas jaket dan memakaikannya pada tubuh perempuan itu.
“Udah pake aja,” kukuh gue saat dia mencoba melepaskannya kembali. Kami bersandar pada sisi jembatan menyaksikan Bandung dalam balutan lampu warna-warni. “Kamu tahu, ini tempat pribadiku. Setiap kali pingin sendiri atau sedang kesal. Pasti larinya kemari.”
Kirana menoleh seraya mengaitkan helaian rambut yang terkibas angin ke telinganya. “Terus kamu ngapain aja di sini?”
Gue hanya mengulum senyum. “Banyaklah, ngerokok ditemani sekaleng bir, main gitar, atau sekedar diem aja menatap langit Kota Bandung,” seketika gue nggak mampu bereaksi. Sialan! Cewek ini terlihat cantik di bawah pancaran lampu tiang-tiang serupa harpa itu. Dan napas gue terasa tertahan saat tersungging senyuman dari bibir ranumnya. God! jantung gue berdetak kencang sekali.
Setelah beberapa saat saling tatap, akhirnya kami malah tertawa sendiri. Nervous kali ya? Dan gue yakin dia pun merasakan hal yang sama saat rona wajahnya mulai bersemu merah.
Mengenyahkan kekakuan di antara kami, kembali Kirana mengalihkan pandangan ke langit Kota Bandung. “Akhir-akhir ini langit selalu mendung. Kita gak bisa melihat taburan bintang di atas sana.”
Aku mengangguk seraya ikut memperhatikan langit yang kelam seperti malam-malam sebelumnya. “Untung masih tersisa satu bintang di sini,” gumam gue.
“Mana?” Kirana mencari-cari di mana gerangan bintang yang gue maksud.
“Di samping kamu. Bintang Praja Nugraha,” eh, perempuan itu malah tersenyum seraya menepuk halus bahu gue.
“Bener juga ya? Meski cuma satu. Jadilah bintang sederhana yang bisa menghibur malam kelabu. Meski kilauannya tak mampu menerangi malam, setidaknya bisa menjadi harapan bagi yang melihatnya.”
Seketika gue menoleh. Satu pujian yang sangat mengena di hati gue. Dan dia? Perempuan itu tanpa dosa menyunggingkan senyumnya untuk yang ke sekian kali.
Setelah puas berlama-lama di Jembatan Pasupati, kami memutuskan melanjutkan perjalanan. Waktu hampir menunjukkan pukul 12 malam. Gue khawatir bokap-nyokapnya marah.
“Langit tak pernah mendendam pada bintang. Meski pada suatu ketika keduanya tak pernah bersatu merangkai pesona malam. Karena kenyataaannya langit selalu menyuguhkan keajaiban lain di balik itu. Masih bersama Langit Putra Begawan, kita tunggu atensi kamu di line telepon, twitter atau WA.”
Suara renyah Langit dari car stereo gue seolah menambah keromantisan perjalanan kami. Sengaja gue buat pelan kemudi kendaraan yang ternyata tak Kirana hiraukan. Tak lama satu lagu indah mengalun di sana. Thanks Langit, elo buat malam ini semakin sempurna.
Angkasa tanpa pesan, merengkuh semakin dalam
Berselimut debu waktu, kumenanti… cemas
Kau datang dengan sederhana, satu bintang di langit kelam
Sinarmu rimba pesona, dan kutahu telah tersesat
(Satu Bintang di Langit Kelam-Rida, Sita, Dewi)
[1] Singkatan Dipati Ukur, salah satu jalan terkenal di Bandung
[2] Istilah anak muda Bandung untuk kafe Ngopi Doeloe
Other Stories
Breast Beneath The Spotlight
Di tengah mimpi menjadi idol K-Pop yang semakin langka dan brutal, delapan gadis muda dari ...
Melepasmu Dalam Senja
Cinta pertama yang melukis warna Namun, mengapa ada warna-warna kelabu yang mengikuti? M ...
First Snow At Laiden
Bunda Diftri mendidik Naomi dengan keras demi disiplin renang. Naomi sayang padanya, tapi ...
Petualangan Di Negri Awan
seorang anak kecil menemukan negeri ajaib di balik awan dan berusaha menyelamatkan dari ke ...
Curahan Hati Seorang Kacung
Saat sekolah kita berharap nantinya setelah lulus akan dapat kerjaan yang bagus. Kerjaan ...
Kita Pantas Kan?
Bukan soal berapa uangmu atau seberapa cantik dirimu tapi, bagaimana cara dirimu berdiri m ...