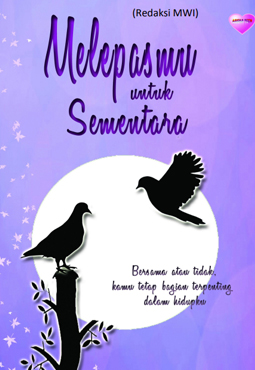New Beginning
Langit Jogja sore itu kelabu, seperti menggambarkan hati Okan yang tak bisa lagi tinggal. Stasiun Tugu dipenuhi suara pengumuman keberangkatan, langkah-langkah terburu, dan deru kereta yang tak pernah benar-benar berhenti. Tapi di tengah riuh itu, Okan berdiri sendiri, menatap rel panjang yang akan membawanya menjauh dari kota yang pernah ia cintai dan dari seseorang yang bahkan lebih ia cintai lagi.
Stella.
Dari balik jaketnya, Okan menggenggam erat sebuah kotak kecil yang masih tertutup. Benda yang tak sempat ia serahkan, seperti perasaannya yang tak sempat selesai. Ia membuka sedikit tutup kotak itu, memandang kalung perak sederhana dengan inisial O dan huruf S di dalamnya. Sebentuk simbol dari masa muda, dari janji yang tak pernah terucap, dari mimpi yang tak sempat tumbuh.
“Udah cukup,” bisiknya pada dirinya sendiri.
Okan lalu meraih ponselnya. Memanggil kontak seseorang. Tama.
Dering pertama
Kedua
“Halo, Mas Okan”, jawab Tama di ujung sana.
“Hey, Tam. Gimana, Stella udah siuman?”
“Eh udah Mas ini”
“Syukurlah. Sampaiin salamku ya. Aku juga minta maaf sama mau pamit. Hari ini berangkat ke Jakarta. Aku ada tawaran kerja di sana”
“Oh iya Mas, nanti aku sampaiin ke Kak Lala”
Panggilan berakhir.
Okan menatap langit Jogja untuk terakhir kali sebelum naik ke gerbong. Di pikirannya, potongan-potongan kenangan berputar seperti slide film lama, tawa Stella saat kehujanan bersamanya, suara biola dari panggung konser, senyum Stella di hari kelulusan, dan akhirnya… Stella dalam balutan kebaya, tersenyum untuk orang lain.
Untuk Fandi.
Saat kereta mulai bergerak, Okan menyandarkan kepalanya ke jendela. Hujan mulai turun perlahan. Ia tak menangis. Tapi dadanya terasa sesak, seperti kota ini menolak melepaskannya, seperti separuh dirinya tertinggal di antara kafe, kelas, laboratorium, dan RSGM Prof Soedomo yang dulu pernah mempertemukannya dengan Stella.
Jogja kini hanya kota.
Dan kenangan itu, akan ia bawa ke Jakarta… untuk perlahan-lahan ia lupakan, atau mungkin… hanya untuk dikenang, diam-diam.
--
Suara denting sendok yang membentur gelas kopi terdengar pelan di sebuah kafe kecil di rumah sakit. Fandi duduk di pojok ruangan, wajahnya lelah tapi matanya masih menyimpan kepedihan yang belum bisa ia sembunyikan. Di depannya, Reiza duduk sambil memegang cangkir kopinya, memperhatikan sahabatnya dengan tenang.
“Rasanya baru kemarin gue liat dia senyum tiap pagi, nyambut gue pulang, ngambek-ngambek manja kalau gue telat balas chat,” ucap Fandi lirih. “Sekarang... dia ngeliat gue kayak musuh. Kayak balik lagi ke masa dia masih benci-bencinya sama gue.”
Reiza hanya mengangguk pelan, membiarkan Fandi mengalirkan perasaannya.
“Gue ngerti ini bukan salah dia. Salah gue malah. Dia lupa, gue ngerti. Tapi sakit, Za. Banget. Gue ngerasa kehilangan padahal orangnya ada di depan gue. Rumah yang harusnya hangat, sekarang kayak ruang asing.”
Fandi tertawa pahit lalu menatap kosong ke luar jendela.
“Gue cuma pengen bisa peluk dia, kayak dulu. Tapi sekarang gue mesti nunggu... sabar... nyesuaiin diri lagi, kayak orang yang baru kenalan. Harus PDKT lagi tapi sama cewek yang benci sama gue”
Reiza menaruh cangkirnya. Ia menyandarkan badan ke kursi dan menatap Fandi penuh empati.
“Ya gue tahu ini berat, Fan. Tapi sabar ya. Jatah pasti bakalan berkurang.”
Fandi menoleh.
“Maksud lo?”
“Mmm mak.. maksudnya jatah sabar lo,” jawab Reiza sambil tersenyum jahil. “Itu pasti berkurang tiap hari lo lewatin bareng dia. Tiap pagi dia lihat lo tetap di sampingnya. Tiap malam lo tetap jagain dia. Lama-lama, hatinya bakal ingat, bahkan kalau pun otaknya lupa.”
Fandi menunduk, menggenggam gelas kopinya lebih erat.
“Gue harap lo bener, Za. Karena yang gue perjuangin itu bukan cuma ingatan Stella. Tapi cinta kita.”
--
Stella berdiri di ambang pintu rumah masa kecilnya. Udara hangat Jogja menyapa wajahnya, tapi tak bisa mengusir rasa asing yang merayap di dada. Rumah ini penuh kenangan—dari masa kecil hingga remaja. Tapi hari ini, semua terasa... janggal.
Di belakangnya, Fandi membawa koper kecil dan tas tangan Stella. Lelaki itu diam, seperti biasa, menahan semua guncangan di dalam dada.
Begitu masuk ke ruang tamu, Mama langsung menyambut dengan senyum penuh syukur. “Alhamdulillah akhirnya pulang juga, Nak. Bisa istirahat tenang di rumah.”
Papa menyusul, menepuk pelan pundak Fandi. “Terima kasih ya, Fandi.”
Fandi hanya mengangguk kecil, matanya sesekali melirik Stella yang tak menyentuh satu pun orang. Ia hanya berdiri, matanya menyapu ruangan dan berhenti di foto besar di dinding. Foto dirinya dan Fandi, mengenakan busana pengantin. Stella terpaku.
“…itu apa?” suaranya pelan, tapi tajam.
Mama dan Papa saling berpandangan. Fandi melangkah mendekat. “Itu… foto kita. Waktu nikah.”
Stella menoleh cepat. “Nikah?” Nadanya naik satu oktaf. “Sama kamu?”
Fandi hanya mengangguk.
“Jadi semua orang yakin aku nikah sama..” Stella menunjuk Fandi dengan nada sinis, “asdos killer yang dulu hampir bikin aku nangis waktu presentasi?”
Mama mencoba menenangkan. “Nak, kamu memang sempat hilang ingatan sebagian. Tapi percayalah, kalian udah saling sayang…”
“Sayang?” Stella tertawa miris. “Lucu ya, semua orang bilang gitu. Padahal aku nggak ingat satu momen pun bahagia sama dia.”
Fandi menunduk, tak berani menatap mata Stella.
“Aku bahkan masih ingat kamu tuh ngeselin, songong, suka sok benar. Dan sekarang tiba-tiba semua orang bilang kamu suamiku? Gila.”
Fandi masih diam. Ia tahu, bukan waktunya membela diri.
Stella melangkah cepat ke kamarnya. Sebelum masuk, ia menoleh sebentar, matanya tajam menusuk.
“Aku mungkin lupa banyak hal. Tapi perasaan nggak bisa dipaksa. Dan sekarang... aku cuma ngerasa asing. Sama kamu, sama semuanya. Bahkan... aku iri.”
Mama pelan bertanya, “Iri, Nak?”
Stella mengangguk. “Iri sama diriku yang katanya pernah bahagia sama dia. Karena aku yang sekarang... nggak lihat kebahagiaan itu di mataku sendiri.”
“Mama udah beresin kamar kalian kalau mau istirahat”, ucap Mama.
“Kamar kalian? Maksudnya kamarku?”, tanya Stella sambil melirik Fandi sinis.
Stella langsung naik ke lantai atas. Lalu pintu kamar tertutup. Fandi berdiri di depan tangga, masih memegang koper Stella. Tak ada yang berkata apa-apa.
Dan sore itu, rumah yang dulu hangat kini dihuni dua hati yang sama-sama luka, satu karena lupa, satu karena terlalu ingat.
Malam turun perlahan di rumah itu. Di dalam kamar, Stella berbaring dengan mata terbuka, memandangi langit-langit. Pikirannya tak tenang. Suara detik jam dinding terdengar begitu nyaring di antara keheningan.
Sementara itu, di ruang tamu, Fandi tidur meringkuk di sofa. Badannya yang tinggi besar tampak kurang nyaman di permukaan sempit itu. Selimut tipis menutupi setengah badannya. Sesekali ia membalikkan badan, tapi tetap terjaga.
Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Mama datang sambil membawa segelas susu hangat.
“Fandi, kamu ngapain tidur di sini? Masuk kamar dong. Kasur kan luas.”
Fandi buru-buru duduk, canggung. “Nggak apa-apa, Ma. Stella masih belum nyaman…”
Mama menatapnya lembut tapi tegas. “Kamu itu suaminya, Fan. Kalau kamu terus-terusan jaga jarak, kapan Stella terbiasa? Ayo naik”
Fandi menunduk, lalu mengangguk pelan. “Iya, Ma.”
Ia bangkit, mengambil selimut dan berjalan pelan menuju kamar Stella mengikuti Mama. Di depan pintu, ia menghela napas panjang sebelum Mama mengetuk pelan.
Tok. Tok.
Pintu terbuka sedikit. Wajah Stella muncul dari balik daun pintu. “Kenapa, Ma?”
Mama menghela nafas. “Kamu gimana sih, La. Masa suami kamu suruh tidur di sofa?”
Stella menghela napas kesal. “Aku gak nyuruh kok. Orang itu ide dia sendiri.”
Fandi tersenyum miris. “Kalau itu bisa bikin kamu lebih nyaman, ya udah.”
Stella membuka pintu lebar. “Masuk. Tapi jangan ngorok.”
Mama lalu meninggalkan mereka berdua. Fandi berjalan masuk dengan langkah hati-hati, lalu duduk di sisi kasur yang paling pinggir. Stella kembali ke tempat tidurnya, mengambil posisi membelakangi Fandi. Kamar itu terasa dingin, tapi bukan karena suhu.
Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu Stella bersuara, pelan. “Kamu tidur aja. Aku nggak bakal gigit.”
Fandi tertawa kecil. “Nggak takut kamu ngamuk kayak dulu?”
Akhirnya lampu kamar dimatikan. Dalam gelap, hanya suara napas mereka yang terdengar. Masih canggung, tapi ada sedikit ketenangan di antara dua hati yang sedang mencari jalan untuk saling menemukan kembali.
Pagi menjelang. Cahaya matahari menerobos masuk lewat celah tirai, menyinari kamar perlahan. Stella membuka mata lebih dulu. Ia terdiam beberapa detik, butuh waktu untuk menyadari di mana dirinya berada.
Lalu, pandangannya jatuh ke sisi lain tempat tidur, di sana, Fandi masih terlelap, rambut sedikit berantakan, wajahnya tenang. Stella sontak bergeser sedikit menjauh, lalu buru-buru duduk dan menyibak selimut.
Tak lama kemudian, suara pintu kamar diketuk pelan.
Tok. Tok.
“Pagi, sayang-sayang mama!” suara mama menggoda dari luar.
Stella langsung tersentak. “M-ma! Astaga…” Ia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Mama berdiri di sana dengan senyum lebar, diikuti papa yang ikut melongok dari ruang makan.
“Wah, udah bangun dua-duanya?” tanya papa, pura-pura polos.
Fandi yang mulai sadar pun ikut duduk, masih berusaha menyesuaikan diri dengan situasi.
“Tumben kalian nggak rebutan bantal kayak dulu ya?” celetuk mama sambil tertawa kecil.
Stella menutup mukanya dengan kedua tangan. “Ma, jangan gitu dong…”
“Lho, mama seneng loh ngeliat kalian akhirnya bisa tidur sekamar juga. Kalau tiap malam Fandi-nya di sofa, mama jadi mikir, ini nikah beneran apa nikah-nikahan,” kata mama lagi, makin menggoda.
Papa ikut menimpali, “Kalau kamu hamil cepet, nanti cucu papa bisa barengan sama panen mangga di halaman.”
Stella makin malu, wajahnya memerah. “Aduh, paaa…!”
Fandi cuma terkekeh sambil mengusap tengkuknya yang mulai hangat. “Hehe… pagi yang seru ya…”
Stella melirik tajam ke arahnya. “Seru dari mana?!”
“Tuh kan… udah mulai marah. Ini baru Stella yang aku kenal,” goda Fandi santai.
Semua tertawa. Meski masih kikuk, tapi pagi itu seperti menghapus sedikit sekat di antara mereka. Sedikit demi sedikit, jarak yang dulu terasa lebar mulai terisi dengan kehangatan yang sederhana.
Di meja makan, aroma nasi goreng buatan mama memenuhi ruangan. Stella duduk di antara Fandi dan Tama, berusaha tenang meski hatinya masih canggung. Tapi suasana hangat keluarga pagi itu membuatnya sedikit lebih rileks.
Tama melirik kakaknya dengan senyum jahil. “Kak, semalem tidur nyenyak nggak? Soalnya kamar sebelah nggak kedengeran apa-apa tuh.”
Stella hampir tersedak air putihnya. “Tama!”
Mama dan papa tertawa bersamaan. Fandi hanya tersenyum sambil mengelus lengan Stella pelan, mencoba menenangkan.
Tama pura-pura polos. “Lho, aku cuma nanya…”
“Udah jangan gengsi gitu sih sama suaminya, La. Kalau jual mahal gini ati-ati, besok anak kalian tau-tau banyak lho” goda Papa lagi.
“Ish, Papa apaan sih!”, protes Stella nyaris teriak.
Semua tertawa. Termasuk Fandi.
Selesai sarapan, mereka kembali ke kamar. Stella menutup pintu dan langsung duduk di pinggir ranjang sambil memeluk bantal. Wajahnya masih merah, tapi kini lebih karena rasa penasaran.
Ia menoleh ke Fandi yang sedang menyusun kertas-kertas dokumen medisnya.
“Mas…” panggilnya pelan.
Fandi menoleh, “Hm?”
“Berarti… aku punya mertua dong ya?” tanyanya hati-hati.
Fandi tersenyum. “Iya dong. Mama udah nggak sabar pengen ketemu kamu lagi, by the way.”
Stella mengangguk pelan. “Terus… berarti aku udah sah jadi istri kamu. Sah banget. Di KUA gitu kan?”
Fandi tertawa pelan, “Iya, sah banget. Ada bukti dan saksinya juga. Reiza jadi saksi dulu”
Stella menggigit bibir, ragu-ragu sebelum bertanya lagi. “Terus… eh, yaudah lah ya… berarti kita… udah pernah…” Ia menunduk, suara makin pelan, “...tidur bareng?”
Fandi tertawa, lalu duduk di sampingnya. “Kalau maksudnya literally tidur bareng satu ranjang, iya. Tapi kamu juga sering dorong aku sampai jatuh dari kasur pas tengah malam. Kalau yang gak literally ya.. Ya jelas lah Stel. Kan kita udah nikah. Dua bulan masa gak ngapa-ngapain”
Stella membelalakkan mata. “Serius?”
“Serius. Kamu bahkan pernah ngomel-ngomel waktu mimpi. Katanya aku ngambil guling kamu.”
Stella langsung menutup wajah dengan bantal, gemas dan malu. “Duh... aku tuh siapa sebenernya…”
Fandi menatapnya dengan lembut. “Kamu istri aku. Dan aku nggak akan capek sabar nunggu kamu ingat semuanya lagi.”
Stella menyingkap sedikit bantal, matanya menatap Fandi. Perlahan, senyumnya muncul—masih malu, masih belum yakin sepenuhnya, tapi ada hangat yang ia rasakan di hatinya.
--
Suara samar terdengar dari ruang tamu. Stella yang sedang di kamar hendak tidur tiba-tiba terjaga saat mendengar nama dirinya disebut-sebut. Ia duduk di tepi ranjang, menajamkan telinga.
Suara papa.
"Fandi, saya tahu kamu sayang sama Stella. Tapi kamu juga harus tahu, saya merestui kalian menikah bukan cuma karena kamu dokter atau karena keluarga kamu baik. Saya merestui karena kamu satu-satunya orang yang bisa bikin Stella hidup lagi waktu dia jatuh."
Hening sebentar.
"Tapi kamu bertengkar sama dia di hari dia kecelakaan. Kamu bikin dia pergi dengan hati yang kacau. Kamu tahu betapa menyesalnya saya sekarang? Kalau hari itu lebih parah, saya bisa kehilangan dia... dan kamu salah satu penyebabnya."
Fandi tidak langsung menjawab. Tapi dari nada suaranya, terdengar berat.
"Saya tahu, Pa... Saya menyesal. Saya marah, tapi saya nggak seharusnya nyakitin dia, secara emosi atau apa pun. Waktu itu saya kehilangan kendali."
Stella menahan napas. Hatinya mencelos mendengar semua itu. Ia berdiri perlahan dan kembali ke ranjang, pura-pura tidur saat suara langkah Fandi mendekat ke kamar.
Tak lama setelah itu, Fandi masuk. Ia diam beberapa saat di ambang pintu, lalu menutup pelan dan duduk di kursi dekat meja kerja.
Stella membuka mata perlahan.
“Mas...”
Fandi menoleh, terkejut. “Belum tidur?”
Stella menggeleng. Ia duduk perlahan dan menatap Fandi dari balik selimut.
“Tadi aku dengar... Papa marah ya sama kamu?”
Fandi menunduk. “Kamu denger?”
“Aku nggak sengaja. Tapi sekarang aku pengen tahu. Emang waktu aku kecelakaan… kita habis bertengkar?”
Fandi diam cukup lama. Ia tampak berjuang memilih kata.
“Iya. Kita habis bertengkar. Soal Okan.”
Stella menatapnya, bingung. “Okan?”
“Iya. Tapi bukan cuma karena itu. Aku marah karena... aku takut. Aku ngerasa gagal jadi suami kamu. Aku cemburu. Aku tersinggung. Tapi aku juga sadar, harusnya aku nggak ninggalin kamu dengan perasaan seberat itu.”
Fandi membuka ponselnya. Menunjukkan rekaman yang sempat dikirim Stella di hari kecelakaan itu.
“Waktu itu kamu ketemu Okan. Trus dia nemuin aku, nunjukin foto kalian pelukan. Ngomong yang enggak-enggak soal kamu. Dan bodohnya aku marah banget waktu itu”
Stella menunduk. Ada perasaan sesak yang ia sendiri tak bisa jelaskan.
“Papa bilang... kamu bikin aku hidup lagi, ya?”
Fandi tersenyum tipis. “Aku nggak tahu, tapi aku pengin jadi alasan kamu bahagia. Dulu, sekarang, nanti. Dan aku janji... nggak akan bikin kamu pergi dengan hati yang berat.”
--
Rumah Sakit Sardjito tampak ramai pagi itu. Pasien lalu lalang, beberapa perawat tampak tergesa. Fandi memarkir mobil dan bergegas membukakan pintu untuk Stella.
“Nanti kasih tahu aku ya kalau udah selesai, ruang dokternya sebelah kanan, nomor empat,” kata Fandi sambil membantu Stella turun dari mobil.
“Sendiri aja?” tanya Stella sambil menenteng map kontrol.
“Bentar lagi aku ada diskusi kasus, tapi nanti aku jemput. WA aja kalau udah selesai, oke?”
“Mas..”, Stella menarik tangan Fandi, lalu segera ia lepaskan dengan perasaan canggung.
“Kenapa?”
“Aku takut ketemu dokter”, jawab Stella ragu.
Fandi tertawa kecil, “Kamu kan juga dokter, tiap hari juga ketemu aku. Masa takut sih?”
“Iya, maksud aku, kalau aku jadi pasiennya”
“Semoga diskusinya cepet selesai ya, nanti aku segera ke kesini”.
Stella mengangguk pelan. Fandi pun berjalan menuju arah gedung belakang, sedangkan Stella masuk ke ruang tunggu. Sekitar satu jam kemudian, Stella keluar dari ruang periksa. Ia membuka ponsel dan mengetik pesan singkat:
Udah selesai. Kamu di mana?
Balasan dari Fandi muncul tak lama:
Aku baru selesai. Otw ke situ.
Stella:
Gak usah. Ketemu di kantin aja.
Stella melangkah ke arah kantin. Matanya segera menangkap sosok Fandi dan Reiza yang duduk di pojok, masing-masing dengan gelas kopi di tangan. Mereka tampak santai dan tertawa kecil membicarakan sesuatu. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Stella.
Dua orang berseragam dokter baru saja berdiri dari meja sebelah mereka. Salah satunya perempuan muda berambut panjang dan rapi. Ia tersenyum manis pada Fandi dan Reiza.
“Duluan, ya!” ucap Jena sambil melambaikan tangan.
“Yo,” jawab Reiza.
Stella yang baru tiba, berhenti sejenak beberapa langkah dari meja. Ia menatap Jena yang berlalu, lalu kembali memandang Fandi. Ia menarik kursi dan duduk tanpa berkata apa-apa. Reiza menyadari perubahan ekspresi Stella dan langsung tertawa pelan.
“Wah wah, Mas Fandi kayaknya perlu klarifikasi nih,” goda Reiza.
Stella melirik Fandi dengan ekspresi datar. “Dokternya cantik ya. Bikin betah di rumah sakit”.
Fandi tampak kikuk sejenak. “Enggak gitu, Stel. Aku tetep betah di rumah lah liat kamu kalau bisa milih”
“Oh gitu...” jawab Stella sambil menyeruput teh hangatnya, nadanya jelas menyindir.
Reiza tertawa makin keras. “Emang bener ya. Cewek tuh bisa menyembunyikan cintanya, tapi gak bisa nyembunyiin kalau dia lagi cemburu”
“Dih siapa juga yang cemburu”
Fandi tersenyum kecil. “Kalau cemburu juga nggak apa-apa. Lebih baik kamu inget aku siapa, daripada terus-terusan nganggep aku cuma orang asing.”
Stella menunduk, menahan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Ia masih belum bisa menerima sepenuhnya, tapi hatinya… mungkin sedang pelan-pelan membuka pintu lagi.
Mobil melaju tenang di tengah senja yang mulai turun. Stella menyandarkan kepala ke jendela, menikmati semilir angin dari celah kaca. Fandi meliriknya sekilas, lalu membuka suara.
“Kita mampir ke apartemen dulu, ya. Aku mau ambil buku dan jas.”
Stella hanya mengangguk tanpa menoleh. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah apartemen yang tampak rapi dan tenang. Fandi membuka pintu dan mempersilakan Stella masuk lebih dulu.
Stella melangkah pelan, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Nuansa hangat menyambut, tapi juga ada sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Ia berjalan ke arah meja makan, jemarinya menyentuh permukaan kayu itu secara perlahan.
Tiba-tiba, tubuhnya menegang.
Kilasan samar datang. Suara keras. Nada tinggi. Tatapan kecewa. Ia sendiri—berdiri sambil menangis. Suara Fandi membentak. Suaranya sendiri membalas dengan getir. Semua berputar seperti kabut yang menyelimuti ingatan.
Napasnya memburu. Stella memegang pinggiran meja untuk menjaga keseimbangan.
Fandi yang baru keluar dari kamar melihat ekspresi Stella dan langsung menghampiri. “Stel? Kamu kenapa?”
Stella menggeleng pelan.
“Hey?”
Matanya menatap kosong ke meja itu. “Kita bertengkar di sini, ya?”
Fandi menghela napas dan mengangguk. “Iya. Aku salah. Aku emosi.”
Stella menoleh perlahan, wajahnya masih pucat. “Aku inget... aku capek banget waktu itu. Rasanya... semua marah ke aku. Okan habis marah ke aku, habis itu kamu…”
Ia melipat tangannya di dada, langkahnya mundur menjauh dari Fandi. “Aku takut... waktu kamu marah. Aku nggak tahu harus ke siapa.”
Fandi mendekat, tapi langkahnya tertahan saat melihat tubuh Stella yang menegang lagi.
“Aku cuma ingat bagian itu,” lanjut Stella lirih. “Yang lain… masih gelap. Aku baru aja mau percaya sama kamu. Tapi ingatan itu… bikin aku ngeri.”
Fandi menunduk, merasa tertampar oleh kenangan itu. “Maaf, Stel. Aku nyesel banget.”
Stella terdiam. Ia berjalan menjauh, duduk di sofa dengan pandangan kosong. Fandi mendekat perlahan tapi tak berani duduk di sampingnya.
Mobil kembali melaju dalam diam. Fandi menyetir dengan tenang, sesekali melirik Stella yang duduk di sebelahnya, menatap ke luar jendela dengan wajah tanpa ekspresi. Tak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara pelan dari radio yang mengisi ruang hampa. Lagu lawas mengalun lembut, tapi tidak cukup menghangatkan suasana yang membeku.
Fandi mencoba membuka suara, hati-hati, seperti berjalan di atas pecahan kaca.
“Kamu lapar? Mau mampir makan dulu?”
Stella menggeleng pelan. “Nggak usah.”
Suara Stella datar, dingin. Bukan marah, bukan kesal, tapi… kosong. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Fandi kembali diam, menggenggam setir lebih erat. Setibanya di rumah,. Stella turun lebih dulu, membuka pintu rumah dengan kunci duplikat yang disimpannya. Fandi menyusul pelan di belakangnya.
Di ruang tamu, suasana rumah yang biasanya hangat terasa berbeda malam itu. Stella meletakkan tasnya di meja lalu langsung berjalan ke arah kamarnya tanpa menoleh sedikit pun.
“Stella…” panggil Fandi pelan.
Stella menoleh, hanya sebentar. “Makasih udah nganterin.”
Fandi ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Stella sudah menutup pintu kamarnya.
Fandi berdiri mematung di ruang tengah. Pandangannya tertuju ke pintu yang kini menutup rapat. Rasanya seperti kembali ke awal—ke masa saat Stella belum pernah mencintainya. Ke masa saat ia hanyalah seseorang yang tak diinginkan di dekat gadis itu.
--
Langit malam begitu tenang, hanya suara jangkrik dan gemericik air dari kolam kecil di belakang rumah yang terdengar. Stella membuka pintu kamar perlahan, matanya yang mengantuk baru saja terbuka karena haus—atau mungkin perasaan tak tenang yang tak bisa dijelaskan.
Menuruni anak tangga pelan, ia melihat cahaya lampu taman menerpa siluet seseorang di dekat kolam. Fandi. Masih mengenakan kemeja yang sedikit kusut, dan tubuh bersandar ke bangku kayu di sisi kolam. Pandangannya kosong, lelah, tapi damai.
Stella melangkah pelan, duduk di sampingnya.
“Baru pulang dari RS?”
Fandi menoleh, tersenyum kecil. “Iya. Kamu kok belum tidur?”
Stella menatap wajah suaminya itu dalam diam, lalu bertanya lirih,
“Berat ya, jadi residen?”
Fandi tertawa pelan. “Ya lumayan. Tapi lebih berat ninggalin kamu tidur sendirian setiap malam.”
Stella menunduk, memeluk lutut.
“Aku ngerepotin ya?”
Fandi menggeleng. “Nggak. Kamu nggak pernah ngerepotin. Bahkan waktu kamu lupa semuanya... aku tetap senang bisa jagain kamu.”
Hening sebentar. Angin malam menyapu rambut Stella yang tergerai. Ia menarik napas dalam-dalam.
“Mas...”
Fandi menoleh.
“Aku pengin mulai semuanya lagi.”
Mata Fandi menajam. “Maksudnya?”
Stella tersenyum kecil, menatap wajah Fandi dengan sorot ragu tapi hangat.
“Aku tahu aku masih belum inget semuanya, tapi... aku pengen coba lagi. Sama kamu. Dari awal. Kayak... kita baru mulai. Mau jatuh cinta lagi sama kamu”
Wajah Fandi perlahan melunak, lalu tersenyum lembut.
“Beneran?”
Stella mengangguk. “Kok aku deg-degan gini ya...”
Fandi terkekeh, lalu dengan nada menggoda mendekatkan wajahnya.
“Mau yang lebih deg-degan lagi? Yuk, ke kamar.”
Stella mencubit lengan Fandi pelan sambil menahan tawa. “Mas!”
Tanpa mereka sadari, dari balik tirai jendela lantai atas, tiga pasang mata—Mama, Papa, dan Tama—mengintip sambil berusaha menahan napas dan tawa.
Begitu mendengar celetukan Fandi, ketiganya langsung buru-buru menjauh.
Tama berbisik pelan, “Fix, Mas Fandi udah balik formasi.”
Mama hanya menggeleng-geleng sambil senyum malu. Papa berdehem.
“Udah, udah. Balik kamar. Jangan ganggu yang lagi mesra.”
Sementara itu di bawah, Stella dan Fandi masih tertawa kecil. Di tengah dinginnya malam, percakapan itu menghangatkan hati mereka—dan menjadi awal baru bagi kisah yang belum selesai.
--
Pagi itu langit Jogja cerah. Di halaman rumah keluarga Reiza, tenda putih sudah berdiri sejak subuh. Ornamen bunga, lampu gantung kecil, dan alunan musik lembut mengisi udara penuh harap. Hari ini adalah pertunangan Tama dan Rana—adik Stella dan Reiza.
Di sudut halaman, Fandi duduk di bangku taman. Di sampingnya, seorang bocah laki-laki dengan rambut legam dan mata berbinar menatap ke arah hidangan di meja.
“Boleh ambil satu, Pa?” si kecil bertanya sambil menunjuk kue lapis.
Fandi tertawa pelan. “Tunggu Mama datang, ya. Nanti dimarahi Mama kalau makan duluan.”
“Ah, Mama lama. Aku laper.”
Fandi mengacak rambut anaknya. “Kamu anak siapa sih cerewet banget?”
Dari arah belakang, suara tertawa Dewi dan Reiza menyahut.
“Anaknya kamu itu, Fan. Dulu kamu juga begitu. Baru lima bulan nikah langsung pamer kabar gembira. Sekarang udah jalan dua… rajin bener bikinnya,” goda Dewi sambil mengedip ke arah perut Stella yang sudah besar.
Reiza menambahkan sambil menggendong salah satu dari anak kembarnya, “Cuma kamu yang cepet dua kali. Kami aja baru kelar ngurus dua anak kembar, ini kalian udah mau nambah lagi. Salut sih.”
Stella datang pelan-pelan, mengenakan dress biru muda longgar. Wajahnya teduh, tubuhnya membesar, tapi senyumnya justru makin cantik. Ia menatap Fandi yang sudah sigap menyambutnya, menggandeng tangannya ke bangku.
“Perutnya makin berat ya?” bisik Fandi.
“Berat karena isinya mungkin kembar juga,” sahut Stella, geli.
Fandi menoleh cepat. “Serius?”
Stella pura-pura serius. “Ya enggak lah. Kan kemarin udah dicek”
Reiza langsung heboh. “Wah, bener-bener”
Fandi hanya nyengir. Tangannya tak lepas dari Stella. Di dadanya, rasa tenang. Seolah badai yang pernah menimpa mereka—amnesia, kehilangan, marah, kecewa—semua itu sudah menjelma jadi kenangan yang mendewasakan.
Di tengah kebahagiaan itu, Rana dan Tama akhirnya muncul, mengenakan busana senada. Semua orang bersorak kecil, menyambut dua insan yang hari itu resmi bertunangan. Di seberang, tampak Papa Stella dan Ayah Reiza bersalaman akrab.
“Mas Purnomo. Akhirnya kita bakalan jadi besan beneran”, ucap Papa Stella sambil menepuk bahu Ayah Reiza.
“Hahaha. Bener Mas Chandra, emang udah takdir”, balas Ayah Reiza.
Stella dan Reiza saling pandang. Keduanya tersenyum penuh makna.
“Plot twist banget, kita beneran jadi saudara jalur mereka, ya,” kata Stella pelan.
“Saudara ipar, partner manggung, partner ngasuh anak juga,” balas Reiza.
Fandi ikut menyahut, “Kalau Roni bisa lihat ini semua…”
Stella menunduk sejenak, lalu tersenyum. “Dia pasti ikut senang.”
Reiza mengangguk. “Dia pasti ikut tepuk tangan.”
Dan di tengah hiruk pikuk tawa, musik, dan makanan, Stella menggenggam tangan Fandi. Anak mereka tertidur di pangkuannya. Di perutnya, satu kehidupan lagi menunggu hadir. Di sekitarnya, orang-orang yang dulu hanya bagian cerita kini menjadi keluarga.
Kisah mereka tak lagi penuh luka, tapi dipenuhi harapan.
Karena cinta, seperti City of Dreams yang pernah mereka nyanyikan bersama, pada akhirnya selalu menemukan rumah untuk pulang.
Other Stories
Dari 0 Hingga 0
Tentang Rima dan Faldi yang menikah ketika baru saja lulus sekolah dengan komitmen ingin m ...
Melepasmu Untuk Sementara
Menetapkan tujuan adalah langkah pertama mencapai kesuksesanmu. Seperti halnya aku, tahu ...
Death Cafe
Sakti terdiam sejenak. Baginya hantu gentayangan tidak ada. Itu hanya ulah manusia usil ...
Seribu Wajah Venus
Kisah-kisah kehidupan manusia yang kuat, mandiri, dan tegar dalam menghadapi persoalan hid ...
Kelabu
Cinta? Apakah aku mencintai Samuel? Pertanyaan yang sulit kujawab. Perasaanku padanya sepe ...
Pasti Ada Jalan
Sebagai ibu tunggal di usia muda, Sari, perempuan cerdas yang bernasib malang itu, selalu ...