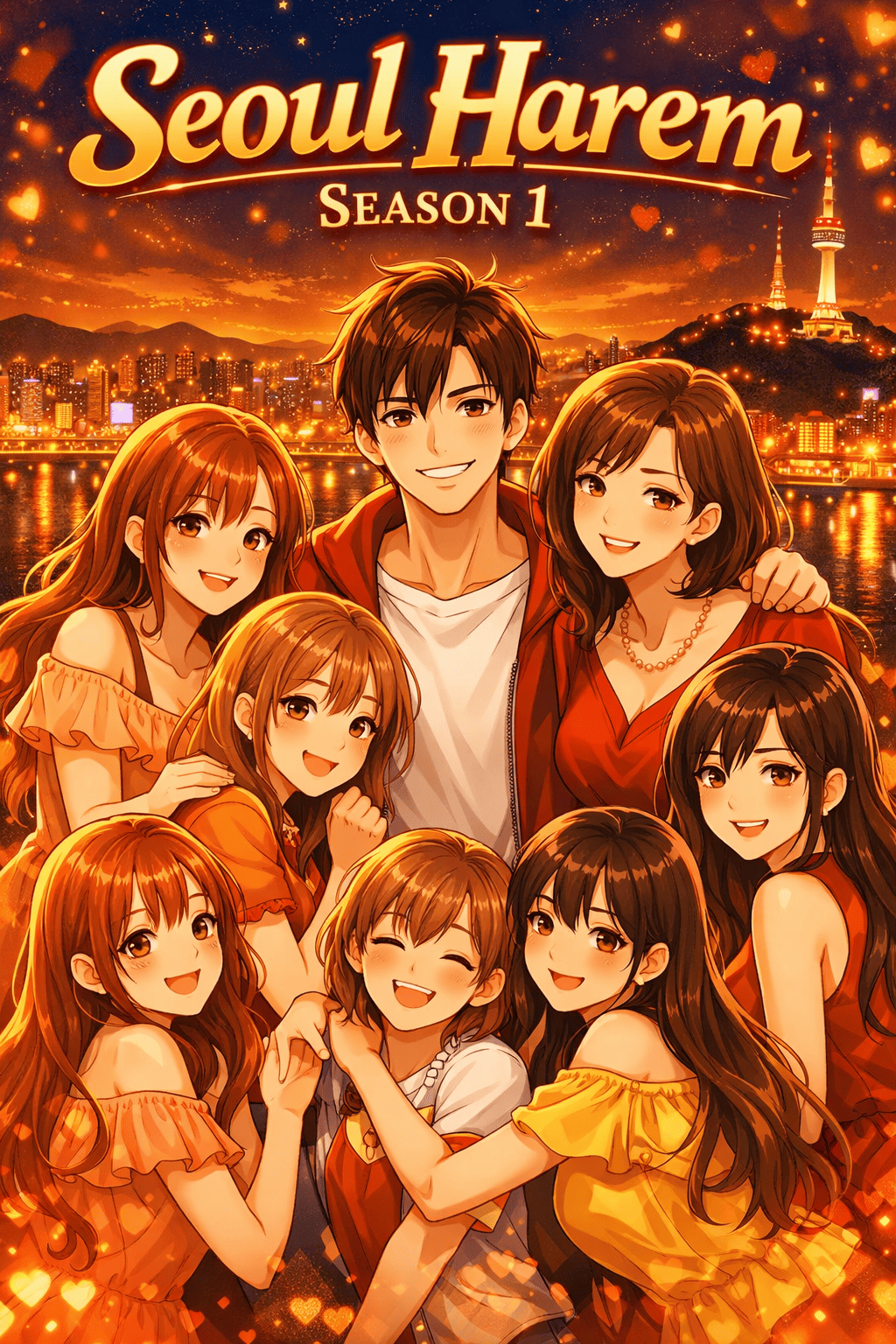Bab 26 Gelombang Pertama Di Barat
Bab 26
Gelombang Pertama di Barat
Pemancar buatan Albert yang kami pasang. berkat bantuan teknologi tenaga mana stone milik bangsa dwarf, akhirnya pemancar radio berdengung. Suaranya pecah-pecah di awal, lalu perlahan jernih.
"Handoyo di sini....apakah Terdengar, Dina dan Agus sudah di puncak memasang pemancar"
"Halo... ini Albert, kalian bisa dengar?"
"Jelas," jawab Dina sambil memutar tombol frekuensi. "Sinyalnya kuat, posisi kami di puncak gunung Stromcoast."
Dari pemancar terdengar suara Miau, masih dengan nada cepat dan cemas seperti biasa.
"Miau melaporkan, Bangsa Elf mulai menyerang, dari barat! Sihir mereka hujan dari langit, tapi kami balas dengan peluru. Jual beli anak panah dan sihir. Mereka belum tahu kita punya senjata plasma!"
Aku, Fredy, dan Chintya langsung saling pandang. Raja Gorn yang berdiri di sampingku mengangguk tegas. Janggut peraknya bergoyang pelan ditiup angin gunung.
"Waktunya kita balas. Kami, para dwarf, bukan hanya pemalu yang tinggal di gua."
Kami turun dari puncak menuju perkemahan. Di sana, pasukan dwarf sudah bersiap. Mereka mengenakan armor tempa tangan, dengan palu, kapak, dan beberapa alat baru dari blueprint Albert. berkat kerja sama dengan Albert, kini mereka membawa senapan canggih rakitan yang disesuaikan untuk tangan dwarf.
Fredy menyulut rokoknya, lalu menatapku.
"Gas, Yo."
Aku mengangguk.
"Dari utara ke barat gunung. Kita bantu pertahanan barat dan tekan balik pasukan elf. Mereka pikir kita hanya akan bertahan, padahal kita datang bawa bonus, teknologi plasma dan pasukan berkumis."
Dwarf di belakang tertawa serempak. Mereka menyukai guyonan bodoh.
Perjalanan menuju barat tak semudah kelihatannya. Tebing curam, kabut sihir, dan jalur tanah longsor membuat kami harus memotong rute lewat jalur tambang tua. Agus yang membawa peta membimbing kami.
Di tengah jalan, Chintya menatap kabut di kejauhan.
"Aku bisa merasakan tekanan mana dari sana. Pasukan elf menggunakan semacam sihir gelap untuk menyelimuti langit, membuat anak panah mereka tak terlihat.
"Kita punya pelacak panas. Mereka nggak tahu siapa yang mereka hadapi," timpal Dina setelah ia balik dari puncak gunung, sambil memeriksa monitor kecil di tangannya
Setelah tiga jam berjalan cepat, kami sampai di bibir bukit. Di bawah sana, barat Stromcoast yang dulu hening, kini berubah jadi medan tempur. Panah menyala beterbangan, sihir es dan api bertabrakan di udara. Pasukan Stromcoast bertahan di balik barikade batu dan karung pasir, membalas dengan panah dan beberapa senapan plasma. Tapi jelas mereka kewalahan.
"Sekarang," kataku.
Raja Gorn mengangkat kapaknya dan berteriak dalam bahasa dwarf yang penuh ledakan konsonan.
"BAGI TANAH DAN NAMA LELUHUR KAMI!"
Pasukan dwarf menyerbu dari atas bukit. Suara sepatu baja dan pekikan perang bergema di lembah.
Aku, Fredy, dan Chintya melompat paling depan.
Aku menebas panah yang mengarah ke arah kami dengan pedang perobek portal. meski belum bisa membuka portal, pedang itu cukup kuat memotong sihir.
Fredy menembakkan pistol plasma ke langit, menciptakan ledakan cahaya sebagai tanda, bahwa sudah saatnya menyerang. Lalu dari balik bukit, suara menggema. Selagi pasukan Dwarf menyerang kami bergerak ke arah Kota Stromcoast.
"Bersiap! Tembakan gelombang dua!" Suara Albert dari radio pemancar kami.
Lalu—BZZZZZT—barisan menara pemancar yang tersembunyi di antara batu aktif. Plasma hijau menyala dan menembak lurus ke arah kabut sihir.
Kabut buyar. Matahari menembus celah. Pasukan elf terlihat jelas. Panik mulai menjalari mereka.
Terlihat Miau muncul dari belakang karung pasir sambil membawa senapan yang dua kali lebih besar dari tubuhnya. "Selamat datang di barat, Pak Handoyo. Mau saya siapkan teh dulu, atau kita ratakan musuh?"
Aku tertawa. Masih bisanya Miau melucu.
"Teh belakangan. Sekarang, waktunya mereka tahu artinya teknologi dan persatuan."
Dan kami pun menyerbu.
Medan perang barat kini menjadi arena unjuk kekuatan. sihir vs teknologi, dendam vs persatuan, Kasta dan persamaan hak. Dan ini baru permulaan.
Sayap, Sihir, dan Seribu Panah
Aku, Chintya, Fredy, Dina, dan Agus terbang ke angkasa dengan tunggangan kami masing-masing.
Aku di atas bebek. ya, kamu tidak salah dengar, bebek yang bisa terbang. Dan jangan tertawa, karena ia bisa menembakkan lendir lengket dari paruhnya, yang entah darimana ia mempelajarinya.
Chintya lebih elegan, menunggang kuda terbang bersayap perak yang tampak seperti baru keluar dari legenda Dewa-dewa. Fredy? Tentu saja Griffin. Setengah elang, setengah singa, sepenuhnya penuh gaya. Dina dan Agus berbagi tunggangan di atas elang raksasa berlapis armor ringan.
Di udara, kami menyebar, terbang rendah sambil memancarkan sinyal radio komunikasi. Dan melaporkan kondisi perang dari atas.
Dengan suara tegas, aku berbicara melalui mikrofon di helmku. "Komando Handoyo kepada seluruh sekutu. Kondisi darurat. Bangsa elf telah membentuk benteng sihir. Dinding es menjulang di sisi Gunung Stromcoast. Mereka mulai menyerang."
Dari langit, kami menyaksikan sendiri.
Benteng es itu ... seperti tembok raksasa yang berkilau memantulkan cahaya. Magis dan megah. Lalu dari balik dinding, panah dilepaskan.
Satu. Lalu membelah jadi sepuluh. Kemudian jadi seribu.
ZRRRRRRAAAANG!
Hujan panah menyapu angin, seperti badai besi yang bersiul ganas. Tapi ini bukan besi biasa, ini panah sihir yang bisa membelah diri. Dari langit seperti hujan yang mematikan.
Di tanah, Dedy, penjaga alam yang selalu tenang, bergerak cepat. Dengan perisai sihirnya, dia menancapkannya ke tanah dan berteriak.
"Rimbunlah, wahai penjaga hijau!"
Akar-akar pohon muncul dari tanah dan saling melilit, menciptakan dinding akar yang tebal dan kokoh. Panah-panah sihir mulai menancap di akar itu, beberapa terpental, beberapa menembus tapi terhambat.
Pasukan aliansi di baliknya terselamatkan. Untuk sementara. Tapi bangsa elf belum selesai. Dari atas benteng es, para pemanah bersiap lagi. Kali ini anak panahnya menyala merah.
"Panah api," bisik Chintya dari udara.
Dan benar saja, begitu dilepaskan, panah-panah itu berubah jadi hujan kobaran api. Dinding akar terbakar.
FWOOSH!
Api menjalar dengan cepat. Akar yang tadinya hidup kini hangus. Beberapa pasukan aliansi panik dan mulai mundur.
"Semua unit, tarik ke kota! Fokus evakuasi pasukan terluka!" seruku melalui radio.
Fredy menukik dengan Griffinnya, menembakkan peluru asap yang sudah disiapkan di tas Dwarf perangnya, kini asap itu menutupi gerakan pasikan yang mundur untuk menyelamatkan diri.
Dina dan Agus melemparkan bom asap kecil dari atas elang mereka, memperlambat penyebaran api. Bom buatan Albert yang berguna untuk memadamkan api.
Kami, tim langit, tetap mengudara, mengawasi. Tapi jelas... ini baru permulaan.
Aku melihat ke arah benteng es bangsa elf. Dinding itu kuat. Sihir mereka tua dan mengakar. Tapi bukan berarti tak bisa ditembus.
"Kita belum kalah," kataku, separuh untuk diriku sendiri, separuh ke seluruh tim. Di balik semua ini, aku tahu... pertempuran belum dimulai sepenuhnya.
Pertarungan Langit
Angin menggila di langit barat Stromcoast. Dari kejauhan, kami melihat mereka sepuluh pasukan udara bangsa Elf menembus kabut pagi, sayap kuda mereka mengepak kuat, bulu putihnya memantulkan cahaya mentari, wajah-wajah dingin bersenjata lengkap.
"Mereka tahu kita mengintai dari udara," gumam Fredy, sambil mengecek senapan serbunya.
Aku menggenggam erat kendali bebek terbangku—jangan tanya kenapa bebek, yang jelas dia cepat, bisa menghindar, dan... suka ngambek kalau kecepatannya diremehkan.
Chintya mengarahkan kudanya lebih tinggi. "Kita harus pisahkan mereka. Bikin bingung formasi mereka!"
Fredy menembakkan beberapa tembakan kearah mereka yang semua ditangkis dengan sihir. Namun lima elf bersenjata panah membalas. Panah mereka melesat ke udara dan—BRRAAK—terbelah jadi ribuan anak panah sihir yang menyala hijau terang.
Aku berteriak, "HINDAR!"
Kami berputar di udara. Kulihat elang Dina menukik tajam bersama elangnya, Agus di belakang Dina berteriak sambil melepas anak panah ke depan, panah itu tak jatuh ke tanah. Ia malah terbang dan membelah diri jadi sulur-sulur tanaman melayang, makhluk menyerupai tanaman karnivora terbang, dengan rahang dari bunga yang bergigi dan duri yang menggigit. Ratingnya yang berdaun lebar jadi sayap layaknya burung. Yang kini mulai mengejar para Elf.
"Aku... gak tahu itu tanaman apa," kata Agus dari punggung elangnya, "tapi dia kelaparan!"
Tanaman-tanaman itu melesat seperti hiu terbang ke arah pasukan elf, satu menggigit sayap kuda terbang hingga oleng, yang lain memagut busur dari tangan musuh, melelehkannya dalam cairan getah lengket yang keluar dari mulutnya.
Fredy, yang kini berada di sisi kanan formasi, memanfaatkan momen itu. Ia merapatkan bidikan—dan BRRRRRTT!, senapan serbunya memberondong musuh. Peluru plasma menembus udara seperti kilatan petir, mengejutkan pasukan elf yang belum pernah melihat teknologi seperti ini.
Satu demi satu, kuda-kuda terbang mereka lepas kendali. Beberapa pasukan elf terpaksa jatuh mundur, mengepak menjauh dengan luka di lengan dan bahu. Namun yang bersenjata tombak dan pedang masih bertahan, kini mendekati Chintya.
"COVER CHINTYA!" aku berteriak.
Dina menerbangkan elangnya ke jalur tabrakan, lalu melempar bom asap buatan Albert. Ledakan kecil menimbulkan awan ungu yang membuat elf-elf kehilangan arah.
Chintya mengangkat tangannya dan melepaskan semburan cahaya dari kalungnya, BLAASSHH!, seberkas sinar membentuk perisai yang menahan serangan pedang dari elf penyerang.
Pertarungan udara itu seperti tarian maut. elf pengkhianat (Chintya), pembunuh senyap (Dina) pemanah tanaman (Agus), pembawa senapan plasma (Fredy), dan si pengendara bebek (aku)—melawan pasukan udara kerajaan elf yang tak pernah mengenal kekalahan. Namun satu hal yang kini mereka sadari, zaman mereka mendominasi telah berubah.
Udara berdesir cepat. Sayap kuda terbang berkibar liar, menciptakan pusaran angin yang membuat daun-daun dari akar terbang dan debu mengepul hingga ke atas langit. Di tengah pertempuran udara yang memusingkan, Dina bagaikan bayangan yang menari di angkasa.
Belati elf hutan yang dimilikinya bukan sekadar senjata. Ia adalah anugerah sihir yang menyatu dengan tubuh dan jiwa penggunanya. Saat belati dilemparkan dan ditangkis oleh tombak elf penjaga, seharusnya belati itu jatuh... tapi tidak. Ia lenyap dalam seberkas cahaya, dan saat elf musuh masih mencari-cari ke mana belati itu pergi—ia muncul kembali di genggaman tangan Dina.
Elf itu sempat terdiam. Ragu. Tapi terlalu terlambat.
Dengan satu hentakan kaki, Dina seperti menjejak lantai tak terlihat di langit. Ia melompat memutar, berlari di udara, mengitari kuda terbang musuh seperti angin puting beliung yang hidup. Tangan kanannya memutar belati, tangan kirinya menyiapkan serangan susulan. Gerakannya membuat elf itu kebingungan, tak bisa membidik panah, tak sempat menusuk dengan tombak.
"Bagaimana bisa... dia berjalan di udara?" teriak elf itu dalam bahasa mereka. tapi jawabannya adalah belati itu sendiri.
Dengan gerakan lincah, Dina memutar tubuhnya di atas punggung kuda terbang, lalu menyelinap ke belakang elf itu. Suara desing angin ditelan oleh suara detak jantung. Dan dalam sepersekian detik, belati Dina menembus punggung elf itu—tepat di antara pelindung punggung yang terbuka.
Kuda terbang itu meringkik liar. Tubuh si elf melayang jatuh, lalu menghilang ke balik awan. Dina mendarat kembali ke punggung kuda terbang itu, lalu menguasainya seolah telah biasa menungganginya sejak kecil.
Di kejauhan, Fredy bersorak lewat radio.
"Mantap, Dina! Satu jatuh. Masih ada sembilan lagi!"
Dina hanya tersenyum. Tak menjawab. Tapi kini, wajahnya menatap langit yang semakin ramai. Pertarungan udara belum selesai. Tapi dia sudah siap—dan tak ada yang lebih menakutkan daripada prajurit yang telah menaklukkan udara.
Gelombang Pertama di Barat
Pemancar buatan Albert yang kami pasang. berkat bantuan teknologi tenaga mana stone milik bangsa dwarf, akhirnya pemancar radio berdengung. Suaranya pecah-pecah di awal, lalu perlahan jernih.
"Handoyo di sini....apakah Terdengar, Dina dan Agus sudah di puncak memasang pemancar"
"Halo... ini Albert, kalian bisa dengar?"
"Jelas," jawab Dina sambil memutar tombol frekuensi. "Sinyalnya kuat, posisi kami di puncak gunung Stromcoast."
Dari pemancar terdengar suara Miau, masih dengan nada cepat dan cemas seperti biasa.
"Miau melaporkan, Bangsa Elf mulai menyerang, dari barat! Sihir mereka hujan dari langit, tapi kami balas dengan peluru. Jual beli anak panah dan sihir. Mereka belum tahu kita punya senjata plasma!"
Aku, Fredy, dan Chintya langsung saling pandang. Raja Gorn yang berdiri di sampingku mengangguk tegas. Janggut peraknya bergoyang pelan ditiup angin gunung.
"Waktunya kita balas. Kami, para dwarf, bukan hanya pemalu yang tinggal di gua."
Kami turun dari puncak menuju perkemahan. Di sana, pasukan dwarf sudah bersiap. Mereka mengenakan armor tempa tangan, dengan palu, kapak, dan beberapa alat baru dari blueprint Albert. berkat kerja sama dengan Albert, kini mereka membawa senapan canggih rakitan yang disesuaikan untuk tangan dwarf.
Fredy menyulut rokoknya, lalu menatapku.
"Gas, Yo."
Aku mengangguk.
"Dari utara ke barat gunung. Kita bantu pertahanan barat dan tekan balik pasukan elf. Mereka pikir kita hanya akan bertahan, padahal kita datang bawa bonus, teknologi plasma dan pasukan berkumis."
Dwarf di belakang tertawa serempak. Mereka menyukai guyonan bodoh.
Perjalanan menuju barat tak semudah kelihatannya. Tebing curam, kabut sihir, dan jalur tanah longsor membuat kami harus memotong rute lewat jalur tambang tua. Agus yang membawa peta membimbing kami.
Di tengah jalan, Chintya menatap kabut di kejauhan.
"Aku bisa merasakan tekanan mana dari sana. Pasukan elf menggunakan semacam sihir gelap untuk menyelimuti langit, membuat anak panah mereka tak terlihat.
"Kita punya pelacak panas. Mereka nggak tahu siapa yang mereka hadapi," timpal Dina setelah ia balik dari puncak gunung, sambil memeriksa monitor kecil di tangannya
Setelah tiga jam berjalan cepat, kami sampai di bibir bukit. Di bawah sana, barat Stromcoast yang dulu hening, kini berubah jadi medan tempur. Panah menyala beterbangan, sihir es dan api bertabrakan di udara. Pasukan Stromcoast bertahan di balik barikade batu dan karung pasir, membalas dengan panah dan beberapa senapan plasma. Tapi jelas mereka kewalahan.
"Sekarang," kataku.
Raja Gorn mengangkat kapaknya dan berteriak dalam bahasa dwarf yang penuh ledakan konsonan.
"BAGI TANAH DAN NAMA LELUHUR KAMI!"
Pasukan dwarf menyerbu dari atas bukit. Suara sepatu baja dan pekikan perang bergema di lembah.
Aku, Fredy, dan Chintya melompat paling depan.
Aku menebas panah yang mengarah ke arah kami dengan pedang perobek portal. meski belum bisa membuka portal, pedang itu cukup kuat memotong sihir.
Fredy menembakkan pistol plasma ke langit, menciptakan ledakan cahaya sebagai tanda, bahwa sudah saatnya menyerang. Lalu dari balik bukit, suara menggema. Selagi pasukan Dwarf menyerang kami bergerak ke arah Kota Stromcoast.
"Bersiap! Tembakan gelombang dua!" Suara Albert dari radio pemancar kami.
Lalu—BZZZZZT—barisan menara pemancar yang tersembunyi di antara batu aktif. Plasma hijau menyala dan menembak lurus ke arah kabut sihir.
Kabut buyar. Matahari menembus celah. Pasukan elf terlihat jelas. Panik mulai menjalari mereka.
Terlihat Miau muncul dari belakang karung pasir sambil membawa senapan yang dua kali lebih besar dari tubuhnya. "Selamat datang di barat, Pak Handoyo. Mau saya siapkan teh dulu, atau kita ratakan musuh?"
Aku tertawa. Masih bisanya Miau melucu.
"Teh belakangan. Sekarang, waktunya mereka tahu artinya teknologi dan persatuan."
Dan kami pun menyerbu.
Medan perang barat kini menjadi arena unjuk kekuatan. sihir vs teknologi, dendam vs persatuan, Kasta dan persamaan hak. Dan ini baru permulaan.
Sayap, Sihir, dan Seribu Panah
Aku, Chintya, Fredy, Dina, dan Agus terbang ke angkasa dengan tunggangan kami masing-masing.
Aku di atas bebek. ya, kamu tidak salah dengar, bebek yang bisa terbang. Dan jangan tertawa, karena ia bisa menembakkan lendir lengket dari paruhnya, yang entah darimana ia mempelajarinya.
Chintya lebih elegan, menunggang kuda terbang bersayap perak yang tampak seperti baru keluar dari legenda Dewa-dewa. Fredy? Tentu saja Griffin. Setengah elang, setengah singa, sepenuhnya penuh gaya. Dina dan Agus berbagi tunggangan di atas elang raksasa berlapis armor ringan.
Di udara, kami menyebar, terbang rendah sambil memancarkan sinyal radio komunikasi. Dan melaporkan kondisi perang dari atas.
Dengan suara tegas, aku berbicara melalui mikrofon di helmku. "Komando Handoyo kepada seluruh sekutu. Kondisi darurat. Bangsa elf telah membentuk benteng sihir. Dinding es menjulang di sisi Gunung Stromcoast. Mereka mulai menyerang."
Dari langit, kami menyaksikan sendiri.
Benteng es itu ... seperti tembok raksasa yang berkilau memantulkan cahaya. Magis dan megah. Lalu dari balik dinding, panah dilepaskan.
Satu. Lalu membelah jadi sepuluh. Kemudian jadi seribu.
ZRRRRRRAAAANG!
Hujan panah menyapu angin, seperti badai besi yang bersiul ganas. Tapi ini bukan besi biasa, ini panah sihir yang bisa membelah diri. Dari langit seperti hujan yang mematikan.
Di tanah, Dedy, penjaga alam yang selalu tenang, bergerak cepat. Dengan perisai sihirnya, dia menancapkannya ke tanah dan berteriak.
"Rimbunlah, wahai penjaga hijau!"
Akar-akar pohon muncul dari tanah dan saling melilit, menciptakan dinding akar yang tebal dan kokoh. Panah-panah sihir mulai menancap di akar itu, beberapa terpental, beberapa menembus tapi terhambat.
Pasukan aliansi di baliknya terselamatkan. Untuk sementara. Tapi bangsa elf belum selesai. Dari atas benteng es, para pemanah bersiap lagi. Kali ini anak panahnya menyala merah.
"Panah api," bisik Chintya dari udara.
Dan benar saja, begitu dilepaskan, panah-panah itu berubah jadi hujan kobaran api. Dinding akar terbakar.
FWOOSH!
Api menjalar dengan cepat. Akar yang tadinya hidup kini hangus. Beberapa pasukan aliansi panik dan mulai mundur.
"Semua unit, tarik ke kota! Fokus evakuasi pasukan terluka!" seruku melalui radio.
Fredy menukik dengan Griffinnya, menembakkan peluru asap yang sudah disiapkan di tas Dwarf perangnya, kini asap itu menutupi gerakan pasikan yang mundur untuk menyelamatkan diri.
Dina dan Agus melemparkan bom asap kecil dari atas elang mereka, memperlambat penyebaran api. Bom buatan Albert yang berguna untuk memadamkan api.
Kami, tim langit, tetap mengudara, mengawasi. Tapi jelas... ini baru permulaan.
Aku melihat ke arah benteng es bangsa elf. Dinding itu kuat. Sihir mereka tua dan mengakar. Tapi bukan berarti tak bisa ditembus.
"Kita belum kalah," kataku, separuh untuk diriku sendiri, separuh ke seluruh tim. Di balik semua ini, aku tahu... pertempuran belum dimulai sepenuhnya.
Pertarungan Langit
Angin menggila di langit barat Stromcoast. Dari kejauhan, kami melihat mereka sepuluh pasukan udara bangsa Elf menembus kabut pagi, sayap kuda mereka mengepak kuat, bulu putihnya memantulkan cahaya mentari, wajah-wajah dingin bersenjata lengkap.
"Mereka tahu kita mengintai dari udara," gumam Fredy, sambil mengecek senapan serbunya.
Aku menggenggam erat kendali bebek terbangku—jangan tanya kenapa bebek, yang jelas dia cepat, bisa menghindar, dan... suka ngambek kalau kecepatannya diremehkan.
Chintya mengarahkan kudanya lebih tinggi. "Kita harus pisahkan mereka. Bikin bingung formasi mereka!"
Fredy menembakkan beberapa tembakan kearah mereka yang semua ditangkis dengan sihir. Namun lima elf bersenjata panah membalas. Panah mereka melesat ke udara dan—BRRAAK—terbelah jadi ribuan anak panah sihir yang menyala hijau terang.
Aku berteriak, "HINDAR!"
Kami berputar di udara. Kulihat elang Dina menukik tajam bersama elangnya, Agus di belakang Dina berteriak sambil melepas anak panah ke depan, panah itu tak jatuh ke tanah. Ia malah terbang dan membelah diri jadi sulur-sulur tanaman melayang, makhluk menyerupai tanaman karnivora terbang, dengan rahang dari bunga yang bergigi dan duri yang menggigit. Ratingnya yang berdaun lebar jadi sayap layaknya burung. Yang kini mulai mengejar para Elf.
"Aku... gak tahu itu tanaman apa," kata Agus dari punggung elangnya, "tapi dia kelaparan!"
Tanaman-tanaman itu melesat seperti hiu terbang ke arah pasukan elf, satu menggigit sayap kuda terbang hingga oleng, yang lain memagut busur dari tangan musuh, melelehkannya dalam cairan getah lengket yang keluar dari mulutnya.
Fredy, yang kini berada di sisi kanan formasi, memanfaatkan momen itu. Ia merapatkan bidikan—dan BRRRRRTT!, senapan serbunya memberondong musuh. Peluru plasma menembus udara seperti kilatan petir, mengejutkan pasukan elf yang belum pernah melihat teknologi seperti ini.
Satu demi satu, kuda-kuda terbang mereka lepas kendali. Beberapa pasukan elf terpaksa jatuh mundur, mengepak menjauh dengan luka di lengan dan bahu. Namun yang bersenjata tombak dan pedang masih bertahan, kini mendekati Chintya.
"COVER CHINTYA!" aku berteriak.
Dina menerbangkan elangnya ke jalur tabrakan, lalu melempar bom asap buatan Albert. Ledakan kecil menimbulkan awan ungu yang membuat elf-elf kehilangan arah.
Chintya mengangkat tangannya dan melepaskan semburan cahaya dari kalungnya, BLAASSHH!, seberkas sinar membentuk perisai yang menahan serangan pedang dari elf penyerang.
Pertarungan udara itu seperti tarian maut. elf pengkhianat (Chintya), pembunuh senyap (Dina) pemanah tanaman (Agus), pembawa senapan plasma (Fredy), dan si pengendara bebek (aku)—melawan pasukan udara kerajaan elf yang tak pernah mengenal kekalahan. Namun satu hal yang kini mereka sadari, zaman mereka mendominasi telah berubah.
Udara berdesir cepat. Sayap kuda terbang berkibar liar, menciptakan pusaran angin yang membuat daun-daun dari akar terbang dan debu mengepul hingga ke atas langit. Di tengah pertempuran udara yang memusingkan, Dina bagaikan bayangan yang menari di angkasa.
Belati elf hutan yang dimilikinya bukan sekadar senjata. Ia adalah anugerah sihir yang menyatu dengan tubuh dan jiwa penggunanya. Saat belati dilemparkan dan ditangkis oleh tombak elf penjaga, seharusnya belati itu jatuh... tapi tidak. Ia lenyap dalam seberkas cahaya, dan saat elf musuh masih mencari-cari ke mana belati itu pergi—ia muncul kembali di genggaman tangan Dina.
Elf itu sempat terdiam. Ragu. Tapi terlalu terlambat.
Dengan satu hentakan kaki, Dina seperti menjejak lantai tak terlihat di langit. Ia melompat memutar, berlari di udara, mengitari kuda terbang musuh seperti angin puting beliung yang hidup. Tangan kanannya memutar belati, tangan kirinya menyiapkan serangan susulan. Gerakannya membuat elf itu kebingungan, tak bisa membidik panah, tak sempat menusuk dengan tombak.
"Bagaimana bisa... dia berjalan di udara?" teriak elf itu dalam bahasa mereka. tapi jawabannya adalah belati itu sendiri.
Dengan gerakan lincah, Dina memutar tubuhnya di atas punggung kuda terbang, lalu menyelinap ke belakang elf itu. Suara desing angin ditelan oleh suara detak jantung. Dan dalam sepersekian detik, belati Dina menembus punggung elf itu—tepat di antara pelindung punggung yang terbuka.
Kuda terbang itu meringkik liar. Tubuh si elf melayang jatuh, lalu menghilang ke balik awan. Dina mendarat kembali ke punggung kuda terbang itu, lalu menguasainya seolah telah biasa menungganginya sejak kecil.
Di kejauhan, Fredy bersorak lewat radio.
"Mantap, Dina! Satu jatuh. Masih ada sembilan lagi!"
Dina hanya tersenyum. Tak menjawab. Tapi kini, wajahnya menatap langit yang semakin ramai. Pertarungan udara belum selesai. Tapi dia sudah siap—dan tak ada yang lebih menakutkan daripada prajurit yang telah menaklukkan udara.
Other Stories
Seoul Harem
Raka Aditya, pemuda tangguh dari Indonesia, memimpin keluarganya memulai hidup baru di gem ...
Dengan Ini Saya Terima Nikahnya
Hubungan Dara dan Erik diuji setelah Erik dipilih oleh perusahaannya sebagai perwakilan ma ...
Mission Escape
Apa yang akan lo lakukan jika Nyokap lo menjadikan lo sebagai ‘bahan gosip’ ke tetangg ...
Kucing Emas
Kara Swandara, siswi cerdas, mendadak terjebak di panggung istana Kerajaan Kucing, terikat ...
Rumah Malaikat
Alex, guru pengganti di panti Rumah Malaikat, diteror kejadian misterius dan menemukan aja ...
DI BAWAH PANJI DIPONEGORO
Damar, seorang petani terpanggil jiwanya untuk berjuang mengusir penjajah Belanda di bawah ...