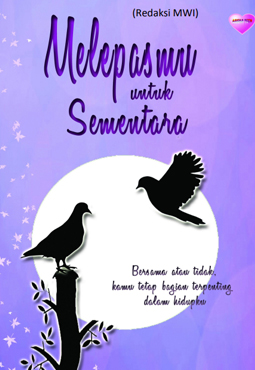Chapter 2 - Kaleng Biskuit Harapan
Keheningan yang mengikuti pertanyaan itu adalah jawaban yang paling jujur. Mimpi yang baru saja meledak setinggi langit, kini terancam jatuh kembali ke bumi, pecah berkeping-keping. Mereka saling pandang. Adi yang biasanya paling berisik kini hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Rina menunduk, memainkan ujung bajunya.
“Kereta,” jawab Bayu pelan, memecah kesunyian.
“Kereta ekonomi PP cah lima, durung penginapan, durung mangan…,” Gilang, si bendahara tim, mulai menghitung dengan jarinya, wajahnya semakin kusut. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya dan mulai menulis angka-angka. “Totalnya… paling sedikit kita butuh lima juta, Bay. Itu sudah makan paling irit, penginapan paling murah, lho.” Ia menunjukkan hitungannya pada yang lain. Angka itu, bagi mereka, terasa seperti jarak ke bulan. “Duit kas kita nggak akan cukup, Bay. Buat tiketnya aja kurang, kok.”
“Aku sih punya sedikit tabungan,” kata Rina lirih. “Dari jualan online kemarin. Mungkin ada tiga ratus ribu.”
“Aku juga ada,” sahut Dodi. “Tapi yo nggak banyak. Cuma seratus lima puluh.”
Bayu menatap teman-temannya. Ia melihat keraguan yang sama yang sering ia rasakan saat menatap ayahnya. Tapi di sini, di antara teman-temannya, keraguan itu terasa berbeda. Itu bukan cemoohan, melainkan sebuah pertanyaan tulus: apakah kita bisa?
“Kita coba,” kata Bayu, suaranya lebih tegas dari yang ia duga. “Kita cari cara. Dua minggu. Pokoke, apapun caranya.”
Dan begitulah perjuangan mereka di dunia nyata dimulai. Dua minggu sebelum keberangkatan, desa kecil mereka di pinggiran Klaten menjadi saksi bisu kegigihan lima anak muda. Kehidupan mereka berjalan begitu cepat. Pagi hari, Bayu dan Adi membantu Pak Purnomo di sawah, bukan lagi karena terpaksa, tapi demi upah harian yang mereka kumpulkan di dalam sebuah kaleng biskuit bekas. Mereka belajar mencangkul, menanam bibit, merasakan punggung yang pegal dan telapak tangan yang melepuh. Pak Purnomo tidak berkomentar, hanya mengawasi dalam diam, mungkin bingung melihat anaknya yang pemalas tiba-tiba bekerja sekeras itu. Sesekali ia melihat Bayu berhenti sejenak, mengusap keringat, lalu kembali bekerja dengan determinasi yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Rina, dibantu ibunya, setiap sore menggoreng mendoan dan bakwan, menjualnya di depan rumah kepada orang-orang yang pulang kerja. Aroma gurih masakan berpadu dengan debu jalanan. Ia belajar pembukuan sederhana, menghitung setiap rupiah keuntungan. Dodi dan Gilang menawarkan jasa cuci motor di halaman warnet, terkadang diselingi candaan dari para pelanggan yang tidak percaya mereka sedang mengumpulkan dana untuk menjadi “atlet”. “Atlet kok kurus-kurus begini?” ledek seorang bapak. “Atlet pencet HP, Pak,” jawab Dodi sambil tersenyum, menyembunyikan rasa lelahnya.
Satu minggu setelah email undangan itu datang, kaleng di markas mereka baru terisi seperempatnya. Uang hasil kerja serabutan dan menjual gorengan terasa seperti tetesan air di ember yang bocor. Siang itu, di tengah kepulan asap rokok dan keheningan yang putus asa di JayaNet, Gilang membanting buku catatannya ke meja.
“Ora iso ngene terus,” katanya. “Kalau cuma ngandelin tenaga, sampai lebaran monyet pun kita nggak akan berangkat.”
“Terus piye maneh?” sahut Adi, pasrah.
“Kita cari sponsor,” kata Gilang mantap. “Proposal. Kita buat proposal, kita ajukan ke orang paling penting di desa ini.”
Semua mata tertuju pada Gilang, lalu saling pandang. Ide itu terdengar begitu dewasa, begitu profesional, dan begitu… mustahil. Tapi mereka tidak punya pilihan lain.
Sore harinya, Bayu dan Gilang sudah berdiri di depan Balai Desa yang lengang. Di tangan Gilang tergenggam sebuah map plastik tipis berisi tiga lembar kertas HVS yang diketik di warnet: sebuah proposal singkat yang menjelaskan apa itu e-sport, prestasi tim “Anak Singkong”, dan rincian dana yang mereka butuhkan, lengkap dengan janji akan memasang logo “Desa Maju Sejahtera” di kaus mereka. Jantung Bayu berdebar lebih kencang daripada saat menghadapi team fight penentuan.
Pak Lurah Rahmat, seorang pria paruh baya berkumis tebal dengan kemeja safari yang rapi, menerima mereka di ruangannya yang sejuk oleh kipas angin. Ia menatap kedua anak muda di hadapannya dengan tatapan ramah namun penuh selidik.
“Dadi, wonten nopo niki, Le?” tanyanya, suaranya berat dan berwibawa.
Gilang, dengan tangan yang sedikit gemetar, menyodorkan proposal itu. “Ngeten, Pak Lurah. Kami… tim kami, namanya Anak Singkong, mendapat undangan untuk ikut turnamen nasional di Jakarta.”
“Turnamen?” Pak Lurah mengangkat alis. “Turnamen voli? Atau sepak bola?”
“E-sport, Pak,” sahut Bayu pelan. “Olahraga elektronik. Nggih, game, Pak.”
Pak Lurah mengangguk-angguk pelan, meskipun raut wajahnya menunjukkan ia tidak benar-benar paham. Ia membaca proposal itu, matanya menyipit saat melihat rincian anggaran. Lima juta rupiah.
“Lha terus, kalian mau minta dana desa untuk ini?” tanyanya, nadanya mulai berubah.
“Bukan minta, Pak. Anggap saja sponsor,” Gilang menyodorkan proposal itu, mencoba terdengar profesional seperti para manajer tim yang ia tonton di YouTube. “Nanti kami promosikan nama desa kita di Jakarta. Sebagai... uhm... sebagai return on investment-nya, Pak.”
Pak Lurah tertawa kecil, sebuah tawa yang tidak terdengar lucu. Ia meletakkan proposal itu di meja, lalu bersandar di kursinya.
“Bayu, Gilang,” katanya sambil menatap mereka bergantian. “Bapak ini bangga, lho, kalau anak-anak desa sini punya prestasi. Tapi, yo, coba dipikir pakai akal sehat.”
Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. “Dana desa itu sudah ada pos-nya masing-masing. Buat perbaikan irigasi, buat posyandu, buat bayar guru ngaji. Kamu lihat jalan di depan itu? Masih banyak yang berlubang.”
Ia menatap lurus ke arah mereka, kali ini tanpa senyum sama sekali.
“Terus, kalian datang ke sini, minta uang lima juta untuk pergi ke Jakarta… main game? Ngapain saya kasih uang buat kalian main game? Mending buat benerin jalan, jelas manfaatnya buat semua warga.”
Bayu dan Gilang terdiam. Semua argumen yang sudah mereka siapkan di kepala terasa menguap. Logika Pak Lurah adalah logika dunia nyata, dunia tempat cangkul lebih berharga dari mouse gaming.
“Nggih, Pak. Kulo ngertos,” akhirnya Bayu yang angkat bicara, suaranya nyaris tak terdengar. “Maaf sudah mengganggu waktunya.”
Mereka pamit dengan sopan, meninggalkan proposal yang bahkan tidak dilirik lagi oleh Pak Lurah. Di luar kantor, di bawah terik matahari sore, mereka berjalan dalam diam. Gilang meremas map plastik di tangannya hingga kusut.
“Kan, wis tak duga,” desisnya penuh kekecewaan.
Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap jalanan berlubang di depannya. Untuk pertama kalinya, ia setuju dengan ayahnya. Mimpi mereka memang terasa tidak nyata di dunia ini.
Mereka kembali ke JayaNet bukan sebagai calon juara, tapi sebagai dua prajurit yang kalah perang. Rina, Adi, dan Dodi yang sudah menunggu dengan cemas, langsung tahu jawabannya hanya dari cara mereka berdua berjalan masuk. Gilang melempar map yang sudah kusut itu ke atas meja dengan kasar. Tak ada kata yang terucap. Hanya helaan napas berat dan suara kursi plastik yang digeser gontai.
Selama satu jam berikutnya, mereka tidak bermain. Mereka hanya duduk dalam diam di sudut langganan mereka, menatap layar ponsel yang mati. Aura kekalahan itu begitu pekat, bahkan para pemain lain di warnet yang biasanya berisik pun seolah ikut merasakannya. Dari balik meja kasirnya, Bang Udin mengamati mereka. Ia melihat bukan lagi sekumpulan anak berisik, tapi lima anak muda yang mimpinya baru saja dipatahkan.
Kabar tentang kegagalan mereka di kantor lurah dan semangat mereka yang padam menyebar dari mulut ke mulut di dalam warnet. Suatu sore, saat kaleng biskuit itu baru terisi sepertiganya, Bang Udin memanggil mereka.
“Kalian ini, bikin repot wae,” gerutunya seperti biasa. Tapi kemudian ia menunjuk sebuah kardus mi instan di atas meja kasirnya. Di atasnya tertulis spidol hitam: “DANA BANTUAN UNTUK TIM ANAK SINGKONG MENUJU IBU KOTA”. Kardus itu sudah terisi beberapa lembar uang sepuluh ribuan dan dua puluh ribuan yang lecek. “Itu dari anak-anak warnet. Katanya, biar nama JayaNet ikut nampang di TV.”
Mata mereka berlima berkaca-kaca. Dukungan itu, dari komunitas yang selama ini menjadi saksi bisu mimpi mereka, terasa lebih berharga dari hadiah turnamen manapun.
Malam itu, tas ransel kelima anak muda itu sudah siap di sudut kamar masing-masing. Uang yang terkumpul, berkat kebaikan komunitas warnet, akhirnya cukup. Kereta ekonomi menuju Jakarta akan berangkat esok subuh. Tapi bagi Bayu, ada satu gunung lagi yang harus ia daki, atau setidaknya, ia lewati dalam diam.
Ia mencoba tidur, namun matanya terus terbuka, menatap langit-langit kamarnya yang retak. Ia tahu ia tidak bisa pergi begitu saja.
Subuh menjelang, saat ayam jantan baru mulai bersahutan, Bayu keluar dari kamarnya, sudah rapi dengan jaket satu-satunya. Ia berniat untuk pamit pada ibunya diam-diam. Namun, di ruang tengah yang remang-remang, ia menemukan ayahnya sudah duduk sendirian di kursi kayu, menatap kosong ke arah pintu depan. Secangkir kopi hitam mengepul di meja di sebelahnya.
Hening.
Pak Purnomo tidak menoleh. Ia berbicara ke arah pintu. “Dadi, bener omongane uwong-uwong. Kowe arep neng Jakarta.” (Jadi, benar omongan orang-orang. Kamu mau ke Jakarta.)
Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah konfirmasi dingin bahwa ia tahu, dan ia tahu bukan dari Bayu. Jantung Bayu terasa mencelos.
“Nggih, Pak,” jawab Bayu pelan, berdiri canggung di ambang pintu kamarnya.
Pak Purnomo akhirnya menoleh. Tatapannya tidak marah, justru itu yang lebih menakutkan. Tatapannya datar, lelah. “Duite seko ngendi?” (Uangnya dari mana?)
“Dari… dari teman-teman, Pak. Ada tabungan juga.” Bayu tidak berani menyebut donasi dari warnet.
Pak Purnomo menghela napas panjang, sebuah suara yang sarat akan kekecewaan. “Uang hasil kerja di sawah kemarin kamu pakai juga?”
Bayu mengangguk pelan.
“Bapak kira uang itu untuk beli buku sekolah. Ternyata untuk mengejar angan-anganmu itu,” kata Pak Purnomo, lebih pada dirinya sendiri. Ia menyesap kopinya. “Sudah Bapak bilang, Bayu. Dunia itu tidak nyata. Hari ini kamu dipuja, besok kamu dilupakan. Apa yang kamu pegang setelahnya?”
“Ini kesempatan, Pak,” Bayu memberanikan diri. “Kesempatan yang belum tentu datang lagi.”
“Kesempatan untuk apa?” balas Pak Purnomo cepat. “Kesempatan untuk jadi bahan tertawaan orang-orang kota? Untuk pulang dengan tangan hampa dan utang?”
Ibu Ratna muncul dari dalam, membawa tas bekal untuk Bayu. Wajahnya tegang melihat interaksi suami dan anaknya.
Pak Purnomo bangkit. Ia berjalan mendekati Bayu, berhenti tepat di depannya. Ia menatap wajah anaknya dalam-dalam.
“Yo wes, mangkat o.” (Ya sudah, berangkatlah.)
Bayu terkejut mendengar izin itu, namun nadanya terasa salah.
“Tapi dengarkan Bapak baik-baik,” lanjut Pak Purnomo, suaranya kini sangat pelan namun menusuk. “Kalau kamu gagal… jangan pulang bawa angan-angan kosong lagi. Pulanglah sebagai anak laki-laki yang siap kerja beneran. Mengerti?”
Itu bukan izin. Itu adalah sebuah ultimatum. Sebuah garis yang ditarik di atas tanah.
Bayu hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat.
Pak Purnomo mengambil cangkulnya yang bersandar di dinding dan berjalan keluar menuju sawah yang masih gelap, seolah hari itu adalah hari biasa. Ia melewati Bayu tanpa menoleh lagi.
Di tengah keheningan dingin yang ditinggalkan ayahnya, Ibu Ratna mendekat. Matanya berkaca-kaca. Ia menyerahkan tas bekal yang sudah ia siapkan. Saat Bayu menerimanya, tangan Ibu Ratna dengan cepat menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang terlipat rapi ke dalam saku tas ransel Bayu, uang simpanannya.
“Jaga diri baik-baik, Le,” bisiknya, suaranya bergetar. “Jangan dimasukkan ke hati omongan Bapakmu. Dia cuma khawatir.” Ia memeluk Bayu erat. “Buktikan kalau kamu bisa.”
Bayu mengangguk lagi, kali ini dengan tekad yang membara. Pelukan ibunya adalah restu, dan ultimatum ayahnya adalah bahan bakar. Ia tidak lagi pergi hanya untuk bermimpi. Ia pergi untuk bertarung.
Perjalanan mereka ke Jakarta dengan kereta ekonomi adalah sebuah ziarah. Meninggalkan hijaunya sawah Klaten, mereka menatap lanskap yang perlahan berubah menjadi hutan beton. Selama dua belas jam perjalanan, mereka hampir tidak tidur. Mereka berdiskusi strategi, menonton ulang pertandingan tim-tim besar di satu layar HP yang mereka pegang bergantian, dan mencoba menghafal nama-nama pahlawan yang sedang meta. Di dalam gerbong yang sesak, di antara obrolan teman-teman yang penuh semangat dan cemas, Bayu hanya menatap keluar jendela. Ia tidak hanya sedang menuju sebuah turnamen. Ia sedang menuju sebuah pembuktian.
Other Stories
Haura
Apa aku hidup sendiri? Ke mana orang-orang? Apa mereka pergi, atau aku yang sudah berbe ...
Losmen Kembang Kuning
Rumah bordil berkedok losmen, mau tak mau Winarti tinggal di sana. Bapaknya gay, ibunya pe ...
Melepasmu Untuk Sementara
Menetapkan tujuan adalah langkah pertama mencapai kesuksesanmu. Seperti halnya aku, tahu ...
Cinta Dibalik Rasa
Cukup lama menunggu, akhirnya pramusaji kekar itu datang mengantar kopi pesananku tadi. ...
Gm.
menakutkan. ...
Setinggi Awan
Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Awan tumbuh dengan mimpi besar. Ia i ...