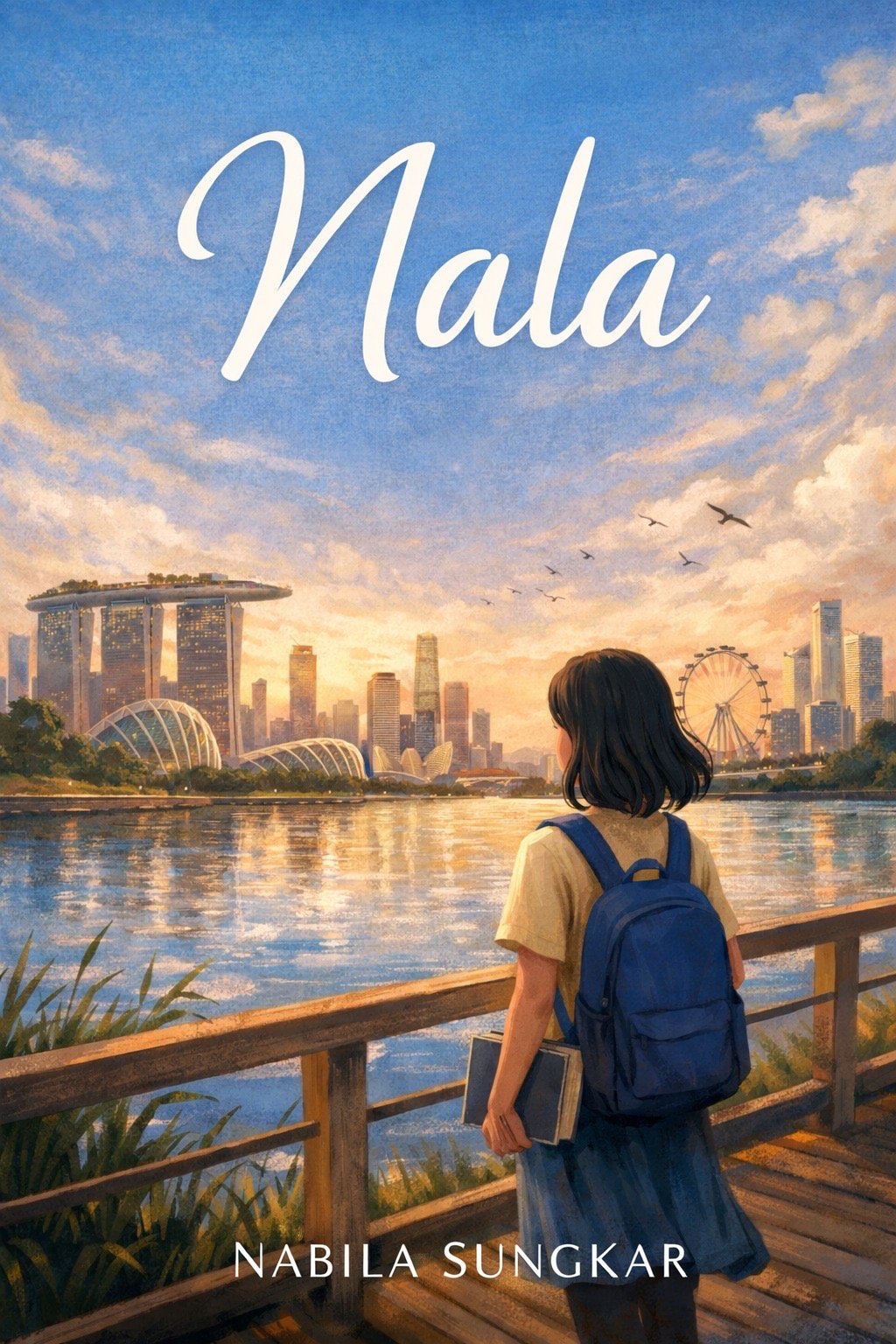Buku Menjadi Tempat Sembunyi
Kriiinggg… bel istirahat berbunyi. Pelajaran sains selesai hari itu. Suasana kelas mendadak riuh, murid-murid berhamburan keluar seperti lebah keluar dari sarangnya.
Seperti biasa, Nala mengeluarkan bekalnya dan makan di mejanya.
“Nala,” panggil Pak Husein, tepat saat Nala hampir menyuap ayam bumbu lengkuas dan nasi buatan Mama.
Nala langsung berdiri dan melangkah ke depan.
“Kamu terus belajar yang giat, ya. Kita bisa coba lagi tahun depan. Tetap semangat,” kata Pak Husein. Kalimat penyemangat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa sangat bermakna.
“Iya, Pak.”
Dua kata yang selalu sama ‘Iya dan Pak’. Tapi kali ini Nala mengucapkannya lebih kencang, lebih yakin, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri.
Sejak hari itu, Nala memberi porsi lebih untuk pelajaran sains. Bukan berarti pelajaran lain ditinggalkan, tapi sains menjadi dunianya sendiri.
Tanpa sadar, sepulang sekolah ia langsung masuk kamar, membuka buku, dan belajar.
“Nala, lagi apa?” tanya Gala yang menyelonong masuk.
“Lagi belajar.”
Tiga puluh menit kemudian—
“Nala lagi apa?” tanya Mila.
“Lagi belajar.”
Satu jam setelahnya—
“Nala?” panggil Mama dari pintu.
“Lagi belajar, Mah,” jawab Nala tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya.
“Makan malam dulu, yuk,” ajak Mama, matanya sempat menyapu meja Nala yang penuh buku.
Nala keluar dari kamarnya. Keluar dari kepompong kecil yang nyaman itu.
Mila dan Gala sudah duduk di meja makan. Tempe goreng, tumis kangkung, dan telur dadar tersaji rapi. Nala langsung tersenyum, melihat makanan Nala langsung menyadari bahwa dirinya lapar.
Malam itu mereka tertawa, berbincang, dan bermain tebak-tebakan.
“Buah apa yang suka main tembak-tembakan?” tanya Gala.
Semua terdiam.
“Doorrrr-ian!”
“Jayussss banget,” sahut Mila dan Nala kompak.
Mama hanya tertawa melihat tingkah anak-anaknya.
Setelah makan dan mencuci piring masing-masing, Nala kembali ke kamarnya.
Belajar.
Belajar.
Ia melakukannya setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tanpa paksaan. Namun, karena memang ia senang.
.
.
.
Di sekolah—
“Nala, ke kantin yuk,” ajak Ipeh.
“Mulai sekarang aku nggak mau sering jajan. Aku makan bekal aja.”
Ipeh menoleh bingung. “Kenapa, Nal?”
“Aku mau nabung. Entah buat apa. Tapi aku pengin di dompetku selalu ada uang.”
Nala sendiri belum tahu. Tapi ia ingin siap kalau suatu hari Mama butuh.
“Aku juga mau nabung deh. Buat beli komik,” kata Ipeh nyengir.
Nala mengeluarkan dompetnya.
“Peh, uangku udah segini. Dua puluh ribu!”
Ipeh ikut menghitung uangnya dengan wajah lesu.
“Peh, kenapa ngitung uangnya kayak gitu?” tanya Nala.
“Terus gimana?”
“Kalau ngitung uang itu harus sambil senyum. Kayak gini,” kata Nala, memperagakan.
“Seribu… dua ribu… tiga ribu…”
Mereka tertawa.
Seperti biasa, Nala mengeluarkan bekalnya dan makan di mejanya.
“Nala,” panggil Pak Husein, tepat saat Nala hampir menyuap ayam bumbu lengkuas dan nasi buatan Mama.
Nala langsung berdiri dan melangkah ke depan.
“Kamu terus belajar yang giat, ya. Kita bisa coba lagi tahun depan. Tetap semangat,” kata Pak Husein. Kalimat penyemangat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa sangat bermakna.
“Iya, Pak.”
Dua kata yang selalu sama ‘Iya dan Pak’. Tapi kali ini Nala mengucapkannya lebih kencang, lebih yakin, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri.
Sejak hari itu, Nala memberi porsi lebih untuk pelajaran sains. Bukan berarti pelajaran lain ditinggalkan, tapi sains menjadi dunianya sendiri.
Tanpa sadar, sepulang sekolah ia langsung masuk kamar, membuka buku, dan belajar.
“Nala, lagi apa?” tanya Gala yang menyelonong masuk.
“Lagi belajar.”
Tiga puluh menit kemudian—
“Nala lagi apa?” tanya Mila.
“Lagi belajar.”
Satu jam setelahnya—
“Nala?” panggil Mama dari pintu.
“Lagi belajar, Mah,” jawab Nala tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya.
“Makan malam dulu, yuk,” ajak Mama, matanya sempat menyapu meja Nala yang penuh buku.
Nala keluar dari kamarnya. Keluar dari kepompong kecil yang nyaman itu.
Mila dan Gala sudah duduk di meja makan. Tempe goreng, tumis kangkung, dan telur dadar tersaji rapi. Nala langsung tersenyum, melihat makanan Nala langsung menyadari bahwa dirinya lapar.
Malam itu mereka tertawa, berbincang, dan bermain tebak-tebakan.
“Buah apa yang suka main tembak-tembakan?” tanya Gala.
Semua terdiam.
“Doorrrr-ian!”
“Jayussss banget,” sahut Mila dan Nala kompak.
Mama hanya tertawa melihat tingkah anak-anaknya.
Setelah makan dan mencuci piring masing-masing, Nala kembali ke kamarnya.
Belajar.
Belajar.
Ia melakukannya setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tanpa paksaan. Namun, karena memang ia senang.
.
.
.
Di sekolah—
“Nala, ke kantin yuk,” ajak Ipeh.
“Mulai sekarang aku nggak mau sering jajan. Aku makan bekal aja.”
Ipeh menoleh bingung. “Kenapa, Nal?”
“Aku mau nabung. Entah buat apa. Tapi aku pengin di dompetku selalu ada uang.”
Nala sendiri belum tahu. Tapi ia ingin siap kalau suatu hari Mama butuh.
“Aku juga mau nabung deh. Buat beli komik,” kata Ipeh nyengir.
Nala mengeluarkan dompetnya.
“Peh, uangku udah segini. Dua puluh ribu!”
Ipeh ikut menghitung uangnya dengan wajah lesu.
“Peh, kenapa ngitung uangnya kayak gitu?” tanya Nala.
“Terus gimana?”
“Kalau ngitung uang itu harus sambil senyum. Kayak gini,” kata Nala, memperagakan.
“Seribu… dua ribu… tiga ribu…”
Mereka tertawa.
Other Stories
DI BAWAH PANJI DIPONEGORO
Damar, seorang Petani, terpanggil untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari tanah airn ...
Negeri Bawah Laut Porkah: Cakra Di Samudra Hindia
Cakra Abiyoga adalah remaja yang tak pernah mengenal kata cukup. Rupawan, jenius, bertalen ...
Cinta Rasa Kopi
Kesalahan langkah Joylin dalam membina bahtera rumah tangga menjadi titik kulminasi bagi t ...
Hold Me Closer
Pertanyaan yang paling kuhindari di dunia ini bukanlah pertanyaan polos dari anak-anak y ...
Separuh Dzarrah
Dzarrah berarti sesuatu yang kecil, namun kebaikan atau keburukan sekecil apapun jangan di ...
Tugas Akhir Vs Tugas Akhirat
Skripsi itu ibarat mantan toxic: ditinggal sakit, dideketin bikin stres. Allan, mahasiswa ...