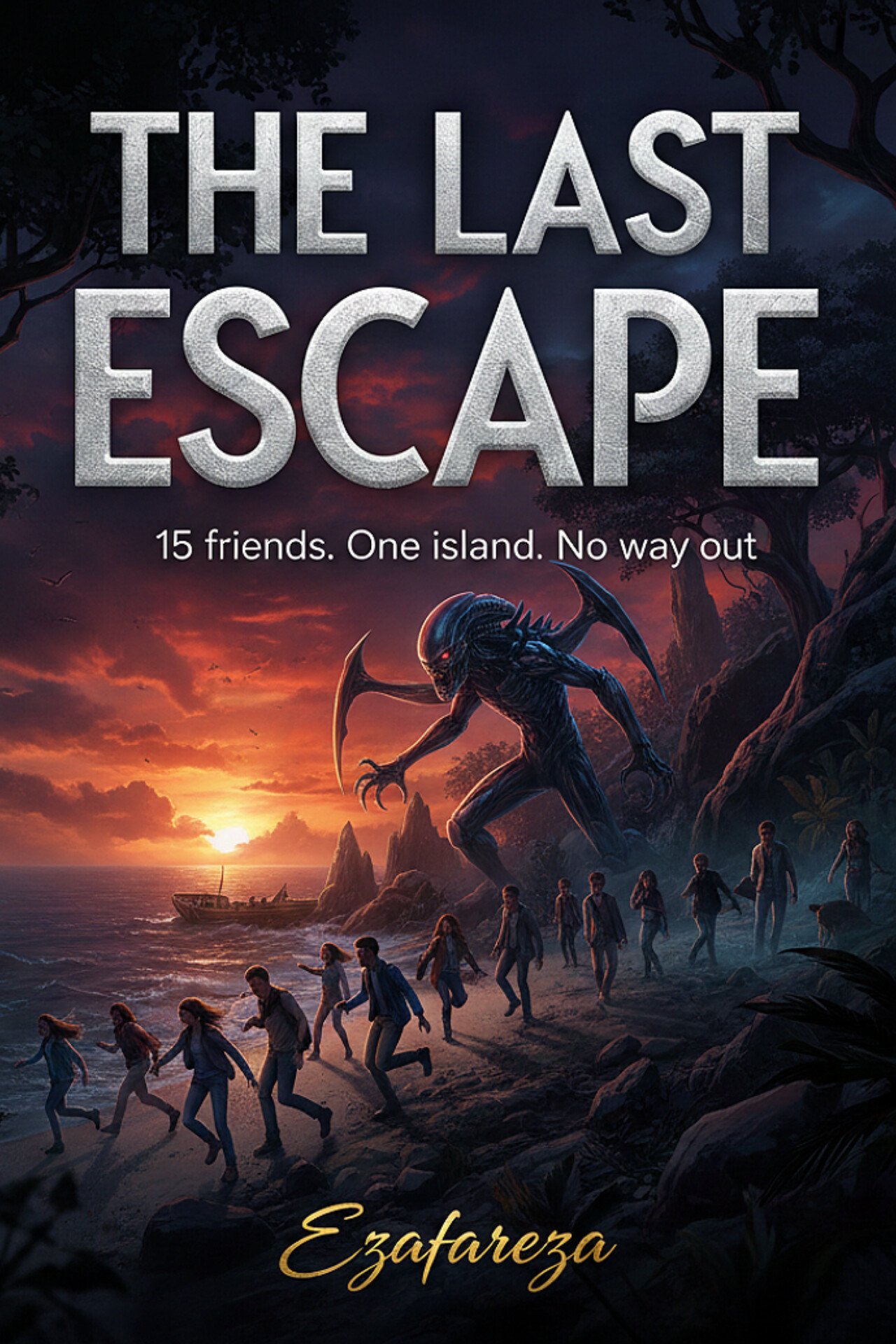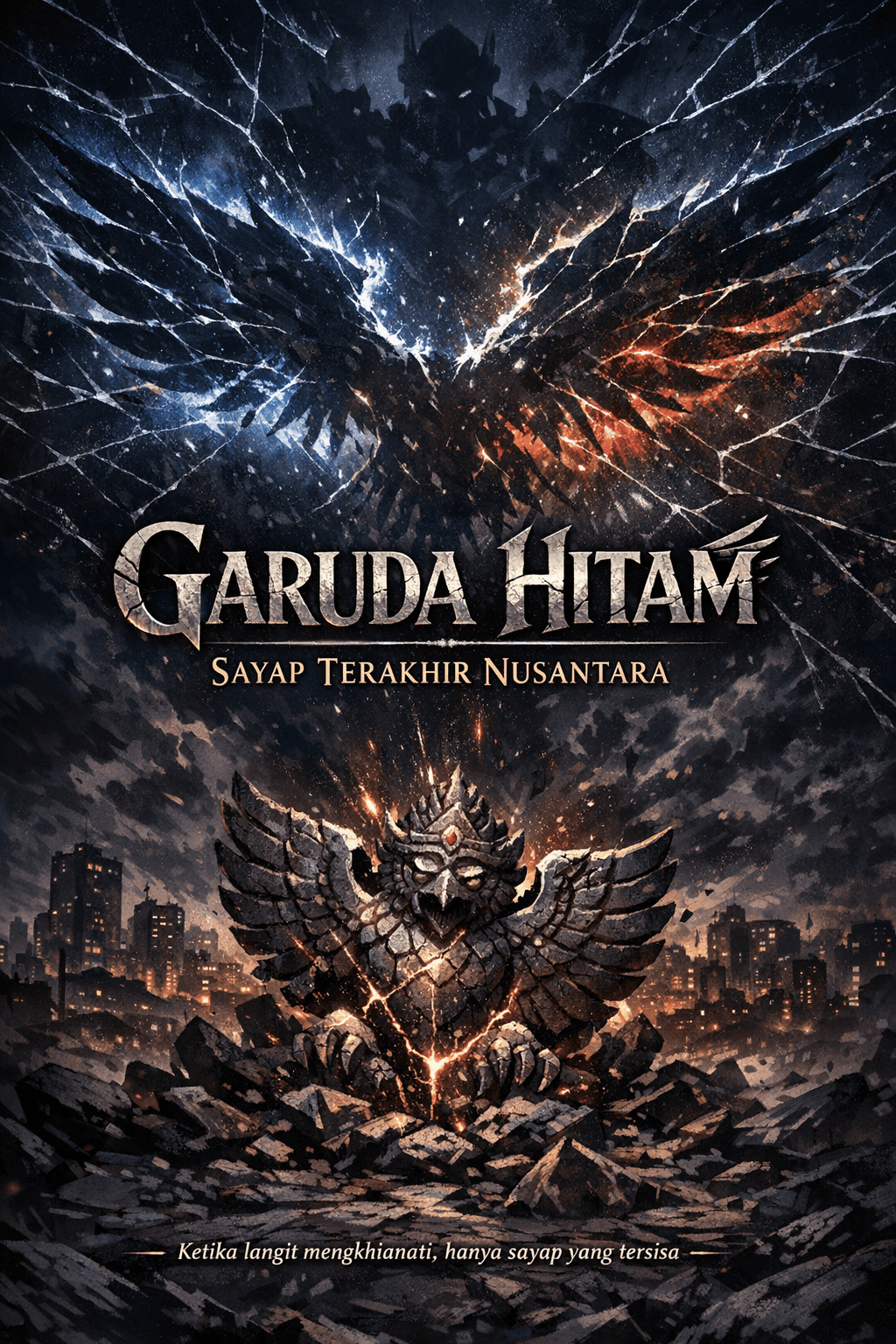BAB 3 | "Jejak Yang Tak Dikenal"
Fajar menyingsing di ufuk timur Pulau Seribu Hening dengan warna yang sulit dilukiskan kata-kata. Bukan sekadar kuning atau merah, tapi gradasi ungu muda yang perlahan meleleh menjadi jingga keemasan. Udara pagi itu sangat bersih, jenis udara yang membuat paru-paru terasa seperti baru saja dicuci bersih dari segala debu kota. Suara deburan ombak yang semalam terdengar menderu, kini berubah menjadi bisikan halus yang menyapu tepian pantai.
Bab 3: Jejak yang Tak Dikenal
Adit adalah yang pertama bangun. Kebiasaannya sebagai ketua rombongan membuatnya sulit untuk tidur terlalu lama. Ia keluar dari pondok cowok dengan langkah berjinjit, tidak ingin membangunkan Bram yang tidur mendengkur dengan posisi tangan yang aneh, atau Bimo yang kakinya menjuntai keluar kasur karena tempat tidurnya tidak cukup panjang untuk ukuran tubuh atletisnya.
Di luar, Adit menarik napas dalam-dalam. Ia melihat Gilang sudah berdiri di tepi pantai dengan tripod-nya. Lensa kameranya diarahkan tepat ke arah matahari yang mulai mengintip.
"Udah dari tadi, Lang?" tanya Adit pelan sambil menghampiri sahabatnya itu.
Gilang menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke bidikannya. "Sekitar lima belas menit yang lalu. Gila, Dit. Gue udah keliling banyak pantai, tapi nggak ada yang birunya sedalam ini. Lu liat tuh, gradasinya kayak nggak nyata."
Adit berdiri di samping Gilang, keduanya terdiam dalam kekaguman yang sama. Tak lama kemudian, pintu pondok cewek terbuka. Maya keluar dengan kain pantai melilit bahunya, disusul oleh Lala yang rambutnya masih berantakan namun matanya sudah berbinar-binar.
"Pagi, Bapak-Bapak fotografer!" seru Lala dengan suara seraknya yang khas bangun tidur. "Kopi mana kopi? Janjinya tadi malam ada kopi pagi sambil liat *sunrise* kan?"
"Sabar, La. Si Aris lagi nyiapin kompor portable-nya di dalam," jawab Adit sambil tertawa.
Satu per satu, penghuni pulau itu mulai bermunculan. Dina keluar dengan kacamata hitam besarnya, meski matahari belum sepenuhnya terik.
Ia tampak cantik meski tanpa riasan tebal, sesuatu yang jarang dilihat teman-temannya di kampus. Rio dan Jaka keluar sambil saling dorong, masih memperebutkan siapa yang semalam mengambil selimut paling banyak.
"Sumpah ya, si Rio ini kalau tidur udah kayak baling-baling bambu. Gue ditendang sampai mepet tembok!" keluh Jaka sambil menguap lebar.
"Lu-nya aja yang tidurnya kayak papan seluncuran, kaku banget!" balas Rio tak mau kalah.
Nadia keluar membawa nampan berisi biskuit dan beberapa gelas plastik. "Udah, jangan ribut pagi-pagi. Mending bantuin gue tata ini. Kita sarapan di atas pasir aja yuk?"
Ide itu langsung disetujui. Mereka menghamparkan kain lebar di atas pasir putih yang masih terasa sejuk. Santi dan Rico duduk berdekatan, saling menyandarkan kepala, menikmati kedamaian yang jarang mereka dapatkan di tengah hiruk-pikuk jadwal kuliah kedokteran yang padat. Tora dan Eka juga tampak asyik mengobrol tentang sketsa yang dibuat Eka semalam.
"Dit," panggil Aris yang sejak tadi diam memperhatikan sekeliling dermaga. "Pak Bakri semalam bilang dia bakal balik lagi dua hari lagi buat anter logistik tambahan, kan?"
"Iya, kenapa Ris?" Adit menyesap kopi hitamnya yang masih mengepul.
Aris menunjuk ke arah dermaga kayu tempat kapal *Sinar Pagi* bersandar semalam. "Enggak, gue cuma mikir aja. Pulau ini beneran kosong ya? Tadi pas gue mau ambil air di sumur belakang pondok, gue ngerasa kayak ada yang baru aja lewat di antara pohon kelapa. Tapi pas gue liat, nggak ada siapa-siapa."
Bram yang baru saja bergabung sambil mengunyah biskuit menimpali, "Paling juga monyet atau burung besar, Ris. Namanya juga pulau nggak berpenghuni. Lu terlalu banyak nonton film horor kayaknya."
"Mungkin sih," gumam Aris, meski matanya tetap menatap tajam ke arah hutan di belakang mereka.
Percakapan beralih ke rencana hari itu. Mereka sangat bersemangat.
"Gimana kalau pagi ini kita *snorkeling* dulu di sekitar dermaga? Tadi malam kan kita liat airnya bening banget," usul Bimo.
"Boleh tuh! Gue bawa alatnya lengkap," sahut Tora. "Nanti si Gilang bisa foto kita dari bawah air pakai kamera antiairnya."
"Dina, lu ikut kan?" tanya Lala sambil menyenggol lengan temannya itu.
Dina tampak ragu. "Airnya dalam nggak? Gue nggak mau ya kalau ada ubur-ubur yang bikin kulit gue gatal."
"Aman, Din. Gue jagain," kata Rico menenangkan. "Lagian kita kan ramai-ramai. Kalau ada apa-apa tinggal teriak aja."
Setelah sarapan sederhana yang penuh tawa, mereka mulai bersiap-siap. Suasana di depan pondok sangat riuh. Ada yang sibuk mengoleskan tabir surya, ada yang mencoba memakai *fin* atau kaki katak sambil melompat-lompat lucu, dan ada yang sibuk menyiapkan pelampung.
Maya tidak langsung ikut masuk ke air. Ia berjalan agak menjauh menyusuri garis pantai, membiarkan kakinya dicumbu ombak kecil. Ia adalah tipe orang yang sangat menghargai kesendirian di tengah keramaian. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di atas pasir yang agak basah.
Ada deretan jejak kaki.
Maya berjongkok, mengamati jejak itu. Jejak itu besar, lebih besar dari kaki Bimo, dan bentuknya tidak seperti bekas telapak kaki orang yang memakai sandal atau sepatu pantai. Jejak itu telanjang, namun jari-jarinya tampak sedikit berbeda, lebih panjang dan dalam tekanannya.
"Maya! Ayo sini! Airnya seger banget!" teriak Lala dari kejauhan, sudah berada di dalam air setinggi pinggang.
Maya menoleh ke arah teman-temannya yang sedang bersenang-senang. Ia melihat Bram yang baru saja menjatuhkan Rio ke dalam air, disambut tawa ledakan dari yang lain. Ia melihat kebahagiaan yang begitu murni di wajah mereka.
*Mungkin ini jejak Pak Bakri pas tadi malam pamit?* pikir Maya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi arah jejak itu bukan menuju dermaga, melainkan mengarah masuk ke dalam rimbunnya hutan bakau di sisi barat pulau.
Maya memutuskan untuk tidak merusak suasana. Ia menghapus jejak itu dengan kakinya, lalu berlari menyusul teman-temannya. "Iya! Tungguin!"
Di dalam air, segala kekhawatiran seolah luruh. Dunia di bawah permukaan laut Pulau Seribu Hening benar-benar menakjubkan. Terumbu karang berwarna-warni berbentuk seperti kipas, otak manusia, dan tanduk rusa tersebar di mana-mana. Ikan-ikan kecil berwarna kuning, biru, dan garis-garis hitam berenang dengan tenang di antara kaki mereka, seolah-olah mereka adalah bagian dari alam itu sendiri.
"Gila! Bagus banget!" teriak Santi saat ia muncul ke permukaan setelah menyelam sebentar. "Rico, liat tadi ada bintang laut warna biru cerah banget!"
Rico tertawa, membetulkan kacamata renang Santi. "Iya, sayang. Aku liat. Sini, jangan jauh-jauh dari aku."
Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di dalam air. Jaka dan Rico bahkan membuat perlombaan siapa yang paling lama menahan napas di bawah air, yang tentu saja dimenangkan oleh Bimo sang atlet. Kehangatan matahari yang mulai menyengat tidak mereka pedulikan. Mereka merasa seperti anak kecil kembali, tanpa beban tugas akhir, tanpa tuntutan orang tua, tanpa ketakutan akan masa depan.
Siang harinya, mereka kembali ke darat dengan perut keroncongan dan kulit yang mulai memerah terbakar matahari.
"Duh, perih dikit ya," keluh Dina sambil mengamati bahunya.
Nadia langsung sigap mengeluarkan gel lidah buaya dari tas medisnya. "Sini, Din. Gue olesin. Makanya, tadi jangan kelamaan di tengah kalau nggak pakai baju renang panjang."
Sambil makan siang dengan nasi bungkus yang mereka siapkan tadi pagi, mereka mulai bercerita tentang keindahan yang mereka lihat di bawah air.
"Gue tadi liat ikan yang mukanya lucu banget, kayak lagi cemberut," cerita Lala sambil memperagakan wajah ikan tersebut, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak.
Namun, di tengah tawa itu, Aris kembali terlihat gelisah. Ia sejak tadi hanya diam dan tidak terlalu banyak makan.
"Ris, lu kenapa? Masih mikirin 'sesuatu' yang lewat tadi pagi?" tanya Adit dengan nada rendah agar tidak terdengar yang lain.
Aris menatap Adit, lalu menghela napas. "Bukan cuma itu, Dit. Gue tadi pas lagi nyelam agak jauh ke arah karang pembatas, gue liat ada sesuatu yang nyangkut di bawah sana. Kayak... kain atau tas gitu. Gue mau ambil tapi napas gue udah nggak kuat karena lumayan dalam."
"Mungkin sampah dari laut lepas yang kebawa arus, Ris," ujar Adit mencoba logis.
"Mungkin. Tapi warnanya merah terang, Dit. Kayak jaket almamater kampus kita," bisik Aris.
Adit terdiam sejenak. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang, namun ia segera menepis pikiran buruk itu. "Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita di sini cuma berlima belas. Dan kita semua lengkap di sini sekarang, kan?"
Adit menghitung satu per satu temannya di meja makan. Satu, dua, tiga... sampai lima belas. Semuanya ada. Semuanya sehat. Semuanya tertawa.
"Tuh kan, lengkap. Udah, makan yang banyak. Habis ini kita mau istirahat siang, sorenya kita jalan-jalan ke sisi lain pulau, oke?" perintah Adit dengan nada final.
Matahari siang itu sangat terik, membuat udara di atas pasir seolah bergetar karena panas.
Masa-masa senang ini terasa sangat berharga, dan Adit bertekad untuk menjaganya selama mungkin.
---
Siang itu, matahari seolah berhenti tepat di atas kepala, membakar pasir putih hingga mengeluarkan hawa hangat yang menggelitik telapak kaki. Namun, panas itu sama sekali tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah sesi *snorkeling* yang melelahkan namun memuaskan, area di depan pondok berubah menjadi semacam kamp pengungsian paling ceria di dunia.
Bram dan Bimo entah bagaimana caranya berhasil menemukan dua buah pohon kelapa yang letaknya sangat pas untuk memasang *hammock*. Dengan keahlian simpul pramuka yang entah kapan ia pelajari, Bram mengikat kain kuat itu dan langsung melompat ke atasnya.
"Gue nyatakan, kursi gantung ini adalah singgasana Raja Pulau hari ini!" seru Bram sambil berayun-ayun. "Bimo, ambilkan hamba kelapa muda!"
Bimo, yang sedang mencuci wajahnya dengan air tawar di ember, hanya melempar handuk basahnya ke arah wajah Bram. "Raja apaan? Raja kelapa busuk? Sini lu turun, gantian gue yang mau tidur siang!"
Di sisi lain pantai, Dina dan Lala sedang asyik melakukan eksperimen kecantikan alami. Mereka menemukan beberapa buah kelapa tua yang jatuh dan mencoba mengoleskan santannya ke ujung rambut mereka.
"Kata nyokap gue, ini rahasia rambut berkilau orang zaman dulu, La," ujar Dina sambil mengoleskan cairan putih itu dengan sangat hati-hati agar tidak mengenai bajunya yang bermerek. "Tapi ya ampun, bau kelapa banget ya. Gue jadi berasa kayak rendang berjalan."
Lala tertawa terbahak-bahak sampai tersedak air kelapa yang sedang ia minum. "Rendang berjalan? Hahaha! Tapi serius Din, liat deh kulit kita. Habis kena air laut terus kena matahari begini, warnanya jadi eksotis banget kan."
Sementara itu, Maya duduk di teras pondok kayu, kakinya menjuntai ke bawah sambil memperhatikan Eka yang sedang asyik dengan buku sketsanya. Eka tampak begitu fokus, tangannya bergerak lincah menarik garis-garis yang membentuk siluet teman-temannya yang sedang beraktivitas.
"Lu lagi gambar siapa, Ka?" tanya Maya lembut.
Eka menoleh, menunjukkan sketsa setengah jadi. Di sana ada gambar Rico dan Santi yang sedang duduk di batang pohon tumbang, saling berbagi satu buah kelapa dengan dua sedotan. "Gue mau kasih ini ke mereka pas hari terakhir nanti. Buat kado. Mereka tuh manis banget ya, May. Kayak nggak punya masalah sama sekali."
Maya tersenyum, meski matanya tetap tertuju pada hutan di belakang pondok yang tampak sangat rapat. "Semua orang punya masalah, Ka. Mungkin mereka cuma pintar menyembunyikannya di balik suara ombak ini."
Percakapan mereka terhenti saat suara musik akustik yang cukup kencang terdengar dari arah pondok cowok. Rupanya Rio telah mengeluarkan speaker bluetooth miliknya. Alunan gitar dan vokal yang santai mulai memenuhi udara, bercampur dengan suara angin laut.
"Nah, ini baru namanya liburan mewah!" teriak Rio sambil menari-nari kecil dengan gerakan yang sangat kaku, mengundang tawa dari siapa pun yang melihatnya. Jaka bergabung dengannya, mencoba meniru gerakan tari tradisional namun berakhir seperti orang yang sedang mengusir nyamuk.
"Ayo semuanya! Kita nge*games*!" ajak Adit yang baru saja keluar dari air setelah membersihkan peralatan *snorkeling*. "Yang kalah harus nyebur ke laut pakai baju lengkap!"
Tantangan itu disambut dengan sorakan setuju. Mereka berkumpul di tengah lapangan pasir, membentuk lingkaran. Permainannya sederhana: 'Gajah-Semut', tapi dengan aturan siapa yang salah sebut harus menceritakan rahasia paling memalukan dalam hidup mereka atau langsung lari ke dermaga dan terjun.
"Oke, mulai dari Aris!" tunjuk Adit.
Aris, yang biasanya sangat serius, tampak tertantang. Ia memperbaiki letak kacamatanya dengan gaya detektif. "Siapa takut. Ayok."
Permainan berlangsung sangat seru. Tawa pecah setiap kali ada yang salah sebut karena konsentrasi yang buyar akibat digoda oleh yang lain. Tora menjadi korban pertama. Ia salah menyebut 'Gajah' dengan tangan mengecil.
"Ayo Tor! Rahasia atau nyebur?" tagih Bram dengan mata berbinar jahil.
Tora menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Oke, oke. Rahasia aja. Jadi... sebenernya, gue itu pernah nggak sengaja masuk ke toilet cewek pas semester satu gara-gara gue lagi asyik dengerin musik pakai *headphone* dan nggak liat simbol di pintunya."
"Terus? Terus?" desak Nadia sambil menahan tawa.
"Terus ada dosen killer kita, Bu Mirna, lagi cuci tangan di sana. Dia cuma liat gue dengan tatapan maut, dan gue... gue cuma bilang 'Permisi Bu, saya salah masuk planet' terus lari," cerita Tora yang disambut ledakan tawa dari semua orang. Bahkan Santi sampai memegangi perutnya karena terlalu banyak tertawa.
Momen-momen seperti inilah yang membuat mereka merasa sangat dekat. Di bawah naungan langit biru Pulau Seribu Hening, mereka bukan lagi sekadar teman sekelas atau teman satu organisasi. Mereka merasa seperti keluarga yang dipilih sendiri.
Sore pun mulai menjelang. Udara yang tadinya panas kini berubah menjadi sejuk yang menenangkan. Nadia, si petugas kesehatan rombongan, mulai berkeliling membawa termos berisi teh hangat yang ia buat dengan bantuan kompor kecil.
"Nih, minum dulu. Jangan sampai ada yang masuk angin karena keasikan main air," ujar Nadia dengan empati yang selalu terpancar dari wajahnya. Ia berhenti di dekat Gilang yang sedang sibuk membersihkan lensa kameranya. "Lang, jangan lupa makan ya. Lu dari pagi cuma ngurusin foto doang."
Gilang menengadah, tersenyum lebar. "Iya Nad, makasih ya. Gue cuma pengen pastiin memori di kamera ini cukup buat seminggu. Gue mau ambil setiap ekspresi kalian di sini. Soalnya... gue ngerasa aura kalian di sini beda banget. Lebih lepas gitu."
Adit memperhatikan interaksi teman-temannya dari kejauhan. Ia merasa sangat puas. Semua rencananya berjalan dengan sangat baik. Biaya mahal yang mereka keluarkan untuk menyewa kapal pribadi dan izin tinggal di pulau terpencil ini terasa sangat sepadan. Tidak ada gangguan, tidak ada orang asing, hanya mereka dan alam.
Namun, di tengah kedamaian itu, Jaka tiba-tiba berteriak dari arah belakang pondok.
"Woy! Siapa yang mindahin sandal jepit gue?"
Semua orang menoleh. Jaka berdiri di sana dengan satu kaki telanjang. "Tadi gue taruh di bawah tangga pondok, sekarang cuma sisa yang kiri doang. Yang kanan ilang!"
"Paling kebawa anjing liar atau apa gitu, Jak," sahut Rio santai dari kejauhan.
"Anjing liar apaan? Dari kemarin kita nggak liat satu pun binatang kaki empat di sini kecuali cicak," balas Jaka sambil mengomel.
"Mungkin dibawa ombak pas tadi pasang?" usul Bimo.
Jaka mendengus. "Pondok kita jauh dari bibir pantai, Bimo. Masa ombaknya bisa jalan kaki ke sini cuma buat ambil sandal gue?"
Adit menghampiri Jaka. "Udah, nanti kita cari bareng-bareng pas mau api unggun. Paling kesenggol siapa gitu. Pakai sandal cadangan lu dulu aja."
Meskipun Jaka terus mengomel tentang 'pencuri sandal misterius', suasana kembali mencair saat matahari mulai bersiap untuk tenggelam. Mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri pantai ke arah barat, tempat di mana terdapat tumpukan batu karang besar yang menyerupai gua kecil.
Di sana, mereka duduk berjejer, melihat langit yang mulai berubah warna menjadi merah jambu dan emas. Tidak ada musik kali ini. Hanya ada suara nafas alam yang dalam.
"Dit," bisik Bram yang duduk di sebelah Adit. "Gue pengen kita tetep kayak begini ya. Sampai nanti kita tua, sampai kita punya anak masing-masing, kita harus tetep liburan bareng kayak gini."
Adit menatap sahabatnya itu, merasakan getaran emosi yang tulus. "Pasti, Bram. Gue janji. Kita bakal balik lagi ke sini lima atau sepuluh tahun lagi."
Mereka tidak tahu bahwa janji itu adalah janji yang paling berat untuk ditepati. Mereka tidak tahu bahwa keindahan senja hari itu adalah salah satu senja terakhir yang bisa mereka nikmati bersama secara lengkap. Di dalam kegelapan yang perlahan merayap naik, Pulau Seribu Hening mulai bersiap untuk menunjukkan wajah aslinya yang lain wajah yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi buruk sekalipun.
"Eh, liat tuh!" seru Lala sambil menunjuk ke arah tengah laut. "Ada lampu kelap-kelip! Itu kapal Pak Bakri bukan?"
Mereka semua menyipitkan mata, menatap ke arah garis cakrawala yang mulai gelap. Memang ada sebuah titik cahaya yang berkedip pelan, sangat jauh di tengah laut. Cahaya itu berwarna merah pucat, berdenyut pelan seperti detak jantung yang lemah.
"Bukan, itu terlalu jauh kalau kapal nelayan," gumam Aris dengan nada bingung. "Dan cahayanya... nggak bergerak. Kayak mercusuar, tapi di sana kan nggak ada pulau lagi."
"Sudahlah, paling juga pelampung navigasi atau kapal tanker besar yang lewat jauh di sana," sela Adit mencoba menjaga suasana tetap ringan. "Ayo balik ke pondok. Malam ini kita bakar ikan yang tadi dikasih Pak Bakri!"
Sorakan "Ikan Bakar!" pun menggema, mengalahkan rasa penasaran mereka akan cahaya merah di tengah laut.
•••
Bab 3: Jejak yang Tak Dikenal
Adit adalah yang pertama bangun. Kebiasaannya sebagai ketua rombongan membuatnya sulit untuk tidur terlalu lama. Ia keluar dari pondok cowok dengan langkah berjinjit, tidak ingin membangunkan Bram yang tidur mendengkur dengan posisi tangan yang aneh, atau Bimo yang kakinya menjuntai keluar kasur karena tempat tidurnya tidak cukup panjang untuk ukuran tubuh atletisnya.
Di luar, Adit menarik napas dalam-dalam. Ia melihat Gilang sudah berdiri di tepi pantai dengan tripod-nya. Lensa kameranya diarahkan tepat ke arah matahari yang mulai mengintip.
"Udah dari tadi, Lang?" tanya Adit pelan sambil menghampiri sahabatnya itu.
Gilang menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke bidikannya. "Sekitar lima belas menit yang lalu. Gila, Dit. Gue udah keliling banyak pantai, tapi nggak ada yang birunya sedalam ini. Lu liat tuh, gradasinya kayak nggak nyata."
Adit berdiri di samping Gilang, keduanya terdiam dalam kekaguman yang sama. Tak lama kemudian, pintu pondok cewek terbuka. Maya keluar dengan kain pantai melilit bahunya, disusul oleh Lala yang rambutnya masih berantakan namun matanya sudah berbinar-binar.
"Pagi, Bapak-Bapak fotografer!" seru Lala dengan suara seraknya yang khas bangun tidur. "Kopi mana kopi? Janjinya tadi malam ada kopi pagi sambil liat *sunrise* kan?"
"Sabar, La. Si Aris lagi nyiapin kompor portable-nya di dalam," jawab Adit sambil tertawa.
Satu per satu, penghuni pulau itu mulai bermunculan. Dina keluar dengan kacamata hitam besarnya, meski matahari belum sepenuhnya terik.
Ia tampak cantik meski tanpa riasan tebal, sesuatu yang jarang dilihat teman-temannya di kampus. Rio dan Jaka keluar sambil saling dorong, masih memperebutkan siapa yang semalam mengambil selimut paling banyak.
"Sumpah ya, si Rio ini kalau tidur udah kayak baling-baling bambu. Gue ditendang sampai mepet tembok!" keluh Jaka sambil menguap lebar.
"Lu-nya aja yang tidurnya kayak papan seluncuran, kaku banget!" balas Rio tak mau kalah.
Nadia keluar membawa nampan berisi biskuit dan beberapa gelas plastik. "Udah, jangan ribut pagi-pagi. Mending bantuin gue tata ini. Kita sarapan di atas pasir aja yuk?"
Ide itu langsung disetujui. Mereka menghamparkan kain lebar di atas pasir putih yang masih terasa sejuk. Santi dan Rico duduk berdekatan, saling menyandarkan kepala, menikmati kedamaian yang jarang mereka dapatkan di tengah hiruk-pikuk jadwal kuliah kedokteran yang padat. Tora dan Eka juga tampak asyik mengobrol tentang sketsa yang dibuat Eka semalam.
"Dit," panggil Aris yang sejak tadi diam memperhatikan sekeliling dermaga. "Pak Bakri semalam bilang dia bakal balik lagi dua hari lagi buat anter logistik tambahan, kan?"
"Iya, kenapa Ris?" Adit menyesap kopi hitamnya yang masih mengepul.
Aris menunjuk ke arah dermaga kayu tempat kapal *Sinar Pagi* bersandar semalam. "Enggak, gue cuma mikir aja. Pulau ini beneran kosong ya? Tadi pas gue mau ambil air di sumur belakang pondok, gue ngerasa kayak ada yang baru aja lewat di antara pohon kelapa. Tapi pas gue liat, nggak ada siapa-siapa."
Bram yang baru saja bergabung sambil mengunyah biskuit menimpali, "Paling juga monyet atau burung besar, Ris. Namanya juga pulau nggak berpenghuni. Lu terlalu banyak nonton film horor kayaknya."
"Mungkin sih," gumam Aris, meski matanya tetap menatap tajam ke arah hutan di belakang mereka.
Percakapan beralih ke rencana hari itu. Mereka sangat bersemangat.
"Gimana kalau pagi ini kita *snorkeling* dulu di sekitar dermaga? Tadi malam kan kita liat airnya bening banget," usul Bimo.
"Boleh tuh! Gue bawa alatnya lengkap," sahut Tora. "Nanti si Gilang bisa foto kita dari bawah air pakai kamera antiairnya."
"Dina, lu ikut kan?" tanya Lala sambil menyenggol lengan temannya itu.
Dina tampak ragu. "Airnya dalam nggak? Gue nggak mau ya kalau ada ubur-ubur yang bikin kulit gue gatal."
"Aman, Din. Gue jagain," kata Rico menenangkan. "Lagian kita kan ramai-ramai. Kalau ada apa-apa tinggal teriak aja."
Setelah sarapan sederhana yang penuh tawa, mereka mulai bersiap-siap. Suasana di depan pondok sangat riuh. Ada yang sibuk mengoleskan tabir surya, ada yang mencoba memakai *fin* atau kaki katak sambil melompat-lompat lucu, dan ada yang sibuk menyiapkan pelampung.
Maya tidak langsung ikut masuk ke air. Ia berjalan agak menjauh menyusuri garis pantai, membiarkan kakinya dicumbu ombak kecil. Ia adalah tipe orang yang sangat menghargai kesendirian di tengah keramaian. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di atas pasir yang agak basah.
Ada deretan jejak kaki.
Maya berjongkok, mengamati jejak itu. Jejak itu besar, lebih besar dari kaki Bimo, dan bentuknya tidak seperti bekas telapak kaki orang yang memakai sandal atau sepatu pantai. Jejak itu telanjang, namun jari-jarinya tampak sedikit berbeda, lebih panjang dan dalam tekanannya.
"Maya! Ayo sini! Airnya seger banget!" teriak Lala dari kejauhan, sudah berada di dalam air setinggi pinggang.
Maya menoleh ke arah teman-temannya yang sedang bersenang-senang. Ia melihat Bram yang baru saja menjatuhkan Rio ke dalam air, disambut tawa ledakan dari yang lain. Ia melihat kebahagiaan yang begitu murni di wajah mereka.
*Mungkin ini jejak Pak Bakri pas tadi malam pamit?* pikir Maya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi arah jejak itu bukan menuju dermaga, melainkan mengarah masuk ke dalam rimbunnya hutan bakau di sisi barat pulau.
Maya memutuskan untuk tidak merusak suasana. Ia menghapus jejak itu dengan kakinya, lalu berlari menyusul teman-temannya. "Iya! Tungguin!"
Di dalam air, segala kekhawatiran seolah luruh. Dunia di bawah permukaan laut Pulau Seribu Hening benar-benar menakjubkan. Terumbu karang berwarna-warni berbentuk seperti kipas, otak manusia, dan tanduk rusa tersebar di mana-mana. Ikan-ikan kecil berwarna kuning, biru, dan garis-garis hitam berenang dengan tenang di antara kaki mereka, seolah-olah mereka adalah bagian dari alam itu sendiri.
"Gila! Bagus banget!" teriak Santi saat ia muncul ke permukaan setelah menyelam sebentar. "Rico, liat tadi ada bintang laut warna biru cerah banget!"
Rico tertawa, membetulkan kacamata renang Santi. "Iya, sayang. Aku liat. Sini, jangan jauh-jauh dari aku."
Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di dalam air. Jaka dan Rico bahkan membuat perlombaan siapa yang paling lama menahan napas di bawah air, yang tentu saja dimenangkan oleh Bimo sang atlet. Kehangatan matahari yang mulai menyengat tidak mereka pedulikan. Mereka merasa seperti anak kecil kembali, tanpa beban tugas akhir, tanpa tuntutan orang tua, tanpa ketakutan akan masa depan.
Siang harinya, mereka kembali ke darat dengan perut keroncongan dan kulit yang mulai memerah terbakar matahari.
"Duh, perih dikit ya," keluh Dina sambil mengamati bahunya.
Nadia langsung sigap mengeluarkan gel lidah buaya dari tas medisnya. "Sini, Din. Gue olesin. Makanya, tadi jangan kelamaan di tengah kalau nggak pakai baju renang panjang."
Sambil makan siang dengan nasi bungkus yang mereka siapkan tadi pagi, mereka mulai bercerita tentang keindahan yang mereka lihat di bawah air.
"Gue tadi liat ikan yang mukanya lucu banget, kayak lagi cemberut," cerita Lala sambil memperagakan wajah ikan tersebut, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak.
Namun, di tengah tawa itu, Aris kembali terlihat gelisah. Ia sejak tadi hanya diam dan tidak terlalu banyak makan.
"Ris, lu kenapa? Masih mikirin 'sesuatu' yang lewat tadi pagi?" tanya Adit dengan nada rendah agar tidak terdengar yang lain.
Aris menatap Adit, lalu menghela napas. "Bukan cuma itu, Dit. Gue tadi pas lagi nyelam agak jauh ke arah karang pembatas, gue liat ada sesuatu yang nyangkut di bawah sana. Kayak... kain atau tas gitu. Gue mau ambil tapi napas gue udah nggak kuat karena lumayan dalam."
"Mungkin sampah dari laut lepas yang kebawa arus, Ris," ujar Adit mencoba logis.
"Mungkin. Tapi warnanya merah terang, Dit. Kayak jaket almamater kampus kita," bisik Aris.
Adit terdiam sejenak. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang, namun ia segera menepis pikiran buruk itu. "Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita di sini cuma berlima belas. Dan kita semua lengkap di sini sekarang, kan?"
Adit menghitung satu per satu temannya di meja makan. Satu, dua, tiga... sampai lima belas. Semuanya ada. Semuanya sehat. Semuanya tertawa.
"Tuh kan, lengkap. Udah, makan yang banyak. Habis ini kita mau istirahat siang, sorenya kita jalan-jalan ke sisi lain pulau, oke?" perintah Adit dengan nada final.
Matahari siang itu sangat terik, membuat udara di atas pasir seolah bergetar karena panas.
Masa-masa senang ini terasa sangat berharga, dan Adit bertekad untuk menjaganya selama mungkin.
---
Siang itu, matahari seolah berhenti tepat di atas kepala, membakar pasir putih hingga mengeluarkan hawa hangat yang menggelitik telapak kaki. Namun, panas itu sama sekali tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah sesi *snorkeling* yang melelahkan namun memuaskan, area di depan pondok berubah menjadi semacam kamp pengungsian paling ceria di dunia.
Bram dan Bimo entah bagaimana caranya berhasil menemukan dua buah pohon kelapa yang letaknya sangat pas untuk memasang *hammock*. Dengan keahlian simpul pramuka yang entah kapan ia pelajari, Bram mengikat kain kuat itu dan langsung melompat ke atasnya.
"Gue nyatakan, kursi gantung ini adalah singgasana Raja Pulau hari ini!" seru Bram sambil berayun-ayun. "Bimo, ambilkan hamba kelapa muda!"
Bimo, yang sedang mencuci wajahnya dengan air tawar di ember, hanya melempar handuk basahnya ke arah wajah Bram. "Raja apaan? Raja kelapa busuk? Sini lu turun, gantian gue yang mau tidur siang!"
Di sisi lain pantai, Dina dan Lala sedang asyik melakukan eksperimen kecantikan alami. Mereka menemukan beberapa buah kelapa tua yang jatuh dan mencoba mengoleskan santannya ke ujung rambut mereka.
"Kata nyokap gue, ini rahasia rambut berkilau orang zaman dulu, La," ujar Dina sambil mengoleskan cairan putih itu dengan sangat hati-hati agar tidak mengenai bajunya yang bermerek. "Tapi ya ampun, bau kelapa banget ya. Gue jadi berasa kayak rendang berjalan."
Lala tertawa terbahak-bahak sampai tersedak air kelapa yang sedang ia minum. "Rendang berjalan? Hahaha! Tapi serius Din, liat deh kulit kita. Habis kena air laut terus kena matahari begini, warnanya jadi eksotis banget kan."
Sementara itu, Maya duduk di teras pondok kayu, kakinya menjuntai ke bawah sambil memperhatikan Eka yang sedang asyik dengan buku sketsanya. Eka tampak begitu fokus, tangannya bergerak lincah menarik garis-garis yang membentuk siluet teman-temannya yang sedang beraktivitas.
"Lu lagi gambar siapa, Ka?" tanya Maya lembut.
Eka menoleh, menunjukkan sketsa setengah jadi. Di sana ada gambar Rico dan Santi yang sedang duduk di batang pohon tumbang, saling berbagi satu buah kelapa dengan dua sedotan. "Gue mau kasih ini ke mereka pas hari terakhir nanti. Buat kado. Mereka tuh manis banget ya, May. Kayak nggak punya masalah sama sekali."
Maya tersenyum, meski matanya tetap tertuju pada hutan di belakang pondok yang tampak sangat rapat. "Semua orang punya masalah, Ka. Mungkin mereka cuma pintar menyembunyikannya di balik suara ombak ini."
Percakapan mereka terhenti saat suara musik akustik yang cukup kencang terdengar dari arah pondok cowok. Rupanya Rio telah mengeluarkan speaker bluetooth miliknya. Alunan gitar dan vokal yang santai mulai memenuhi udara, bercampur dengan suara angin laut.
"Nah, ini baru namanya liburan mewah!" teriak Rio sambil menari-nari kecil dengan gerakan yang sangat kaku, mengundang tawa dari siapa pun yang melihatnya. Jaka bergabung dengannya, mencoba meniru gerakan tari tradisional namun berakhir seperti orang yang sedang mengusir nyamuk.
"Ayo semuanya! Kita nge*games*!" ajak Adit yang baru saja keluar dari air setelah membersihkan peralatan *snorkeling*. "Yang kalah harus nyebur ke laut pakai baju lengkap!"
Tantangan itu disambut dengan sorakan setuju. Mereka berkumpul di tengah lapangan pasir, membentuk lingkaran. Permainannya sederhana: 'Gajah-Semut', tapi dengan aturan siapa yang salah sebut harus menceritakan rahasia paling memalukan dalam hidup mereka atau langsung lari ke dermaga dan terjun.
"Oke, mulai dari Aris!" tunjuk Adit.
Aris, yang biasanya sangat serius, tampak tertantang. Ia memperbaiki letak kacamatanya dengan gaya detektif. "Siapa takut. Ayok."
Permainan berlangsung sangat seru. Tawa pecah setiap kali ada yang salah sebut karena konsentrasi yang buyar akibat digoda oleh yang lain. Tora menjadi korban pertama. Ia salah menyebut 'Gajah' dengan tangan mengecil.
"Ayo Tor! Rahasia atau nyebur?" tagih Bram dengan mata berbinar jahil.
Tora menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Oke, oke. Rahasia aja. Jadi... sebenernya, gue itu pernah nggak sengaja masuk ke toilet cewek pas semester satu gara-gara gue lagi asyik dengerin musik pakai *headphone* dan nggak liat simbol di pintunya."
"Terus? Terus?" desak Nadia sambil menahan tawa.
"Terus ada dosen killer kita, Bu Mirna, lagi cuci tangan di sana. Dia cuma liat gue dengan tatapan maut, dan gue... gue cuma bilang 'Permisi Bu, saya salah masuk planet' terus lari," cerita Tora yang disambut ledakan tawa dari semua orang. Bahkan Santi sampai memegangi perutnya karena terlalu banyak tertawa.
Momen-momen seperti inilah yang membuat mereka merasa sangat dekat. Di bawah naungan langit biru Pulau Seribu Hening, mereka bukan lagi sekadar teman sekelas atau teman satu organisasi. Mereka merasa seperti keluarga yang dipilih sendiri.
Sore pun mulai menjelang. Udara yang tadinya panas kini berubah menjadi sejuk yang menenangkan. Nadia, si petugas kesehatan rombongan, mulai berkeliling membawa termos berisi teh hangat yang ia buat dengan bantuan kompor kecil.
"Nih, minum dulu. Jangan sampai ada yang masuk angin karena keasikan main air," ujar Nadia dengan empati yang selalu terpancar dari wajahnya. Ia berhenti di dekat Gilang yang sedang sibuk membersihkan lensa kameranya. "Lang, jangan lupa makan ya. Lu dari pagi cuma ngurusin foto doang."
Gilang menengadah, tersenyum lebar. "Iya Nad, makasih ya. Gue cuma pengen pastiin memori di kamera ini cukup buat seminggu. Gue mau ambil setiap ekspresi kalian di sini. Soalnya... gue ngerasa aura kalian di sini beda banget. Lebih lepas gitu."
Adit memperhatikan interaksi teman-temannya dari kejauhan. Ia merasa sangat puas. Semua rencananya berjalan dengan sangat baik. Biaya mahal yang mereka keluarkan untuk menyewa kapal pribadi dan izin tinggal di pulau terpencil ini terasa sangat sepadan. Tidak ada gangguan, tidak ada orang asing, hanya mereka dan alam.
Namun, di tengah kedamaian itu, Jaka tiba-tiba berteriak dari arah belakang pondok.
"Woy! Siapa yang mindahin sandal jepit gue?"
Semua orang menoleh. Jaka berdiri di sana dengan satu kaki telanjang. "Tadi gue taruh di bawah tangga pondok, sekarang cuma sisa yang kiri doang. Yang kanan ilang!"
"Paling kebawa anjing liar atau apa gitu, Jak," sahut Rio santai dari kejauhan.
"Anjing liar apaan? Dari kemarin kita nggak liat satu pun binatang kaki empat di sini kecuali cicak," balas Jaka sambil mengomel.
"Mungkin dibawa ombak pas tadi pasang?" usul Bimo.
Jaka mendengus. "Pondok kita jauh dari bibir pantai, Bimo. Masa ombaknya bisa jalan kaki ke sini cuma buat ambil sandal gue?"
Adit menghampiri Jaka. "Udah, nanti kita cari bareng-bareng pas mau api unggun. Paling kesenggol siapa gitu. Pakai sandal cadangan lu dulu aja."
Meskipun Jaka terus mengomel tentang 'pencuri sandal misterius', suasana kembali mencair saat matahari mulai bersiap untuk tenggelam. Mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri pantai ke arah barat, tempat di mana terdapat tumpukan batu karang besar yang menyerupai gua kecil.
Di sana, mereka duduk berjejer, melihat langit yang mulai berubah warna menjadi merah jambu dan emas. Tidak ada musik kali ini. Hanya ada suara nafas alam yang dalam.
"Dit," bisik Bram yang duduk di sebelah Adit. "Gue pengen kita tetep kayak begini ya. Sampai nanti kita tua, sampai kita punya anak masing-masing, kita harus tetep liburan bareng kayak gini."
Adit menatap sahabatnya itu, merasakan getaran emosi yang tulus. "Pasti, Bram. Gue janji. Kita bakal balik lagi ke sini lima atau sepuluh tahun lagi."
Mereka tidak tahu bahwa janji itu adalah janji yang paling berat untuk ditepati. Mereka tidak tahu bahwa keindahan senja hari itu adalah salah satu senja terakhir yang bisa mereka nikmati bersama secara lengkap. Di dalam kegelapan yang perlahan merayap naik, Pulau Seribu Hening mulai bersiap untuk menunjukkan wajah aslinya yang lain wajah yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi buruk sekalipun.
"Eh, liat tuh!" seru Lala sambil menunjuk ke arah tengah laut. "Ada lampu kelap-kelip! Itu kapal Pak Bakri bukan?"
Mereka semua menyipitkan mata, menatap ke arah garis cakrawala yang mulai gelap. Memang ada sebuah titik cahaya yang berkedip pelan, sangat jauh di tengah laut. Cahaya itu berwarna merah pucat, berdenyut pelan seperti detak jantung yang lemah.
"Bukan, itu terlalu jauh kalau kapal nelayan," gumam Aris dengan nada bingung. "Dan cahayanya... nggak bergerak. Kayak mercusuar, tapi di sana kan nggak ada pulau lagi."
"Sudahlah, paling juga pelampung navigasi atau kapal tanker besar yang lewat jauh di sana," sela Adit mencoba menjaga suasana tetap ringan. "Ayo balik ke pondok. Malam ini kita bakar ikan yang tadi dikasih Pak Bakri!"
Sorakan "Ikan Bakar!" pun menggema, mengalahkan rasa penasaran mereka akan cahaya merah di tengah laut.
•••
Other Stories
Koper Coklat Ibu
Bagi Arini, Yogyakarta bukan lagi tempat untuk pulang, melainkan ruang bawah tanah yang ia ...
After Meet You
kacamata hitam milik pria itu berkilat tertimpa cahaya keemasan, sang mata dewa nyaris t ...
Hellend ( Noni Belanda )
Sudah sering Pak Kasman bermimpi tentang hantu perempuan bergaun zaman kolonial yang terus ...
Permainan Mematikan: Narsistik
Delapan orang asing diculik dan dipaksa mengikuti serangkaian permainan mematikan. Tujuh d ...
Keeper Of Destiny
Kim Rangga Pradipta Sutisna, anak dari ayah Korea dan ibu Sunda, tumbuh di Bandung dengan ...
Garuda Hitam: Sayap Terakhir Nusantara
Aditya Pranawa adalah mantan pilot TNI AU yang seharusnya mati dalam sebuah misi rahasia. ...